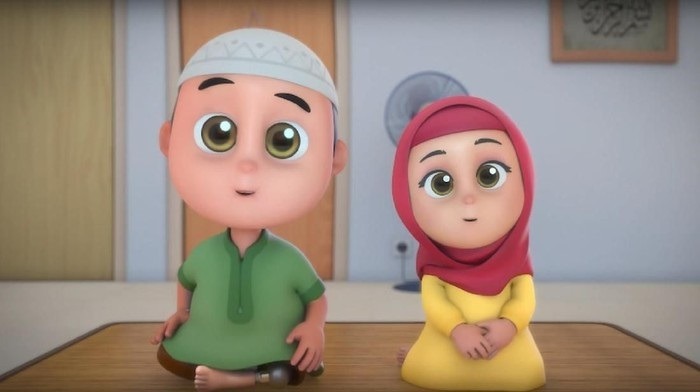
Saya sempat tidak menyangka esai saya terkait film kartun Nussa beberapa waktu lalu menarik perhatian publik. Walau tidak sempat menghitung secara pasti, berapa banyak uneg-uneg protes terhadap esai yang saya buat sejak awal Ramadan tersebut, tapi yang pasti baik cuitan balasan hingga retweet mencapai angka ribuan.
Satu esai bernada ‘bantahan’ muncul dalam waktu tidak sampai 24 jam setelah esai saya terbit.. Dari sekian ribu yang menanggapi tulisan saya, ada satu orang yang menuliskan sebuah sanggahan dengan serius, tentu alasan dia menuliskan keberatannya jelas tidak sembarangan.
Elam Sanurihim Ayatuna, menuliskan opini berjudul “Menjawab Kekakuan BerIslam Animasi Nussa-Rara: Bantahan Tulisan Supriansyah” dan saya punya beberap catatan atasnya. Sebenarnya, penulisan esai Nussa tersebut dimulai sejak awal bulan Ramadan. Alasannya, saya menulis karena ingin melanjutkan penelusuran terhadap tema “Islam Anak-Anak”, yang yang pernah saya tulis sebelumnya di laman islami.co dengan judul “Geliat Pasar Menangkap Islam Anak-anak”.
Apalagi, salah satu televisi swasta menayangkan kartun Nussa sebagai salah satu sajian mereka menyambut bulan Ramadan, hasrat saya menelisik lebih dalam naik. Jadi, yang perlu diketahui adalah esai Nussa kemarin bukan ujug-ujug hadi, tidak hanya untuk mengkritik konten belaka. Ia hadir karena dalam penelusuran, saya mendapati kerterkaitan antara kartun Nussa dengan dinamika keberislaman kelas menengah yang sedang menggelora di Indonesia.
Klaim tersebut bukan sekadar asumsi belaka. Hal itu berdasarkan survei Alvara Institute tahun 2019. Riset tersebut menjelaskan bahwa fenomena bermunculan model-model keberislaman yang baru, yang diinisiasi oleh kelas menengah. Kehadiran mereka cukup massif mewarnai dinamika keIslaman masyarakat Indonesia saat ini.
Bagaimana bisa kehadiran kelas menengah bisa mempengaruhi keberislaman, termasuk anak-anak?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu melihat bagaimana pertumbuhan pemakaian internet di masyarakat menjadi sumber perubahan dalam artikulasi keberislaman masyarakat Indonesia.
Pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya. Lihat data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada Mei 2019 kemarin, jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12%, dari tahun 2017 yang mencapai 54,85%, artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia sudah terpapar media sosial.
Adapun dari riset Alvara Institute menunjukkan, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet melalui Handphone (98,4%), dan laptop (12,3%). Menariknya, handphone menjadi perangkat yang paling banyak digunakan oleh semua generasi, baik Gen Z, Milenial, dan Gen X.
Pengaruh yang paling mudah kita deteksi atas kehadiran internet mempengaruhi keberislaman adalah kemunculan dinamika Youtube dan Facebook dalam mempengaruhi popularitas ulama di kalangan masyarakat.
Walau di bulan Desember tahun 2019, Alvara merilis hasil survei mereka yang menyebutkan Ustad/ulama dilingkungan tempat tinggal masih menjadi sumber informasi keagamaan utama bagi umat Islam di Indonesia.
Kemudian diikuti oleh orang tua, guru agama serta youtube. Hal yang menarik adalah munculnya youtube, web internet dan facebook sebagai rujukan informasi keagamaan bagi generasi muda. Gen Z (kelahiran 1998-2010), millennial (kelahiran 1981-1997) cukup banyak yang merujuk ke youtube, web internet dan facebook dibanding generasi sebelumnya atau sering disebut gen X (kelahiran di atas 1980).
Berangkat dari dinamika kehadiran layanan jejaring sosial tersebut, saya melihat irisan antara kelas menengah dengan kehadiran media sosial sebagai motor penggerak, adalah faktor penting yang mewarnai keberislaman masyarakat Indonesia sekarang.
Sejak meningkatnya kesadaran kelas menengah atas eksistensi dan pentingnya simbol-simbol Islam, tentu hal ini berefek pada kebutuhan akan ketersediaan ruang keagamaan dalam lanskap perkotaan, terutama di kota-kota besar. Kehadiran pusat-pusat Keislaman atau Islamic Centre bertebaran di kota-kota besar adalah salah satu faktanya.
Masih dalam pengaruh kondisi di atas, Islam Indonesia akhirnya mengalami apa yang disebut dengan gentrifikasi atau kenaikan status, yang lebih mendukung teknologi tinggi global dan cita rasa Islam yang konsumtif (Abaza, 2004). Dalam hal ini juga bermunculan berbagai program dakwah yang inovatif untuk kepentingan kelas menengah.
Di titik inilah sebenarnya posisi kartun Nussa dalam diskursus keberislaman sekarang. Kehadirannya adalah efek dari kondisi di atas, di mana saat semakin meningkatnya tuntutan kelas menengah terhadap simbol Islam sebagai ekspresi budaya modern di ruang publik, yang diwakili dengan penggunaan media eletronik dan media sosial dalam proses produksinya.
Saat informasi keislaman yang hadir di media sosial dijadikan rujukan informasi keagamaan, maka diharuskan ada penyesuaian dengan selera kelas menengah. Sebenarnya fenomena ini dilatarbelakangi oleh kebangkitan Islam yang terjadi di tahun 1980-an yang telah menyapu seluruh Indonesia, menurut catatan Noorhaidi Hasan, dosen asal Yogyakarta.
Efek dominonya adalah pergeseran keberislaman di kalangan anak-anak. Mereka yang sebelumnya hanya terfokus pada interaksi dengan pengetahuan keislaman belaka. Sebagaimana yang dijalani generasi baby boomers (baca: kelahiran sebelum 1981) atau minimal generasi milenial, di mana keislaman anak-anak saat itu hanya berkisar pada dua hal yakni kultural dan pendidikan.
Sehingga saat kebutuhan masyarakat Islam akan kehadiran akan simbol-simbol Islam di ruang publik, sebagaimana digambarkan di atas, tentu transmisi ilmu agama dalam kehidupan anak-anak akhirnya juga turut berubah.
Semuanya disesuaikan dengan pasar, monetisasi dan kreativitas, akibatnya bermunculan artikulasi dan model keislaman untuk anak-anak yang juga turut disesuaikan dengan gaya yang sama dengan kelas menengah, seperti bermunculannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang sangat memanjakan kebutuhan kelas menengah, seperti mencetak anak yang saleh (memiliki hapalan Al-Quran, hadis dan memilik akhlak yang bagus)
Kalau di media sosial maka kehadiran kartun Nussa adalah model artikulasi keberislaman masyarakat yang hadir dengan selera kelas menengah. Kelahiran kartun Nussa yang dibidani oleh kanal Youtube bernama “Nussa Official”, telah banyak menjelaskan perubahan yang terkait fenomena selera kelas menengah tersebut.
Sebenarnya minimal ada dua perubahan yang bisa kita rasakan yaitu konten dan pergeseran otoritas keagamaan, walau yang terakhir ini tidak saya telisik mendalam di opini kemarin. Perubahan dua hal tersebut tentu memiliki efek domino yang sebagian besarnya telah saya ulas.
Yang paling awal terasa adalah genre. Saat kartun Nussa hadir di media sosial dan media televisi, maka genre hiburan juga turut disematkan walau yang tertera hanya pendidikan.
Adapun kritik Elam lainnya adalah terkait Nussa ingin menggeser imaji anak-anak Indonesia soal nilai kehidupan. Jawaban singkat saya adalah lihat saja pernyataan dari Felix Siauw yang ditayangkan secara langsung oleh kanal ‘Nussa Official’ pertanggal 19 November 2018. Di sana ia menjelaskan apa yang saya tulis tersebut, termasuk soal cerita ‘Kancil’ dan ‘Jaka Tarub’.
Terkait dengan hal di atas, saya sekaligus menjawab persoalan dengan kartun Ipin-Upin. Saya ingin menegaskan kembali apa yang saya tulis kemarin, kartun Ipin-Upin bukan tanpa kekurangan, namun di dalam kartun tersebut memiliki keunggulan yang bisa dijadikan bahan bercermin bagi tim Nussa, diantaranya persoalan representasi ras, suku dan agama.
Selain itu, Ipin-Upin juga unggul menampilkan kehidupan anak-anak secara natural dengan segala kejailan dan kegembiraannya. Pemirsa anak-anak diajak belajar dari kehidupan yang beragam dan segala denyut dinamika di masyarakat, termasuk persoalan-persoalan yang mereka hadapi bersama dalam satu lokus, bernama kampung Durian Runtuh.
Sehingga, anak-anak bisa menyerap semua nilai kehidupan, seperti moralitas, interaksi dengan alam atau manusia hingga ajaran agama, yang terekam dalam memori masyarakat secara utuh, namun kesemuanya ditampilkan tanpa ada kesan menggurui.
Karena representasi dalam kartun Nussa ini sejak awal bermasalah sehingga tim Nussa perlu mendapatkan masukan atau kritikan. Bagi saya, permasalahan bermula kegagalan mereka memvisualisasi keragaman kehidupan secara utuh, atau minimal mendekati dari keadaan yang sebenarnya.
Mungkin yang paling mudah disoroti adalah ketika kartun Nussa bermasalah dalam visualisasi keberagaman hukum fiqih yang hidup di masyarakat. Diantaranya adegan Nussa dan Rara yang enggan bersalaman dengan orang non-mahram mereka.
Bagi saya, saat tim Nussa menampilkan ke persoalan fiqih yang beragam secara lugas dalam episode “Bukan Mahram” adalah keputusan tersebut tergolong berani. Mungkin saja bagi sebagian orang dengan mudah mengajukan alasan genre pendidikan yang melekat pada kartun Nussa sebagai alasan, sekaligus melegetimasi pilihan tim Nussa hanya menampilkan satu representasi saja dari mazhab fiqih yang ada.
Padahal di saat yang sama mereka malah mengabaikan keragaman hukum salaman non-mahram di dalam Islam, mungkin untuk memahami lebih ringkas bisa membaca tulisan Ustadz Alhafiz Kurniawan tentang ini.
Ketika kita belajar fiqih dengan guru atau ustad secara langsung maka dengan mudah bisa saja bertanya atau dijelaskan segala permasalahannya secara mendalam. Kondisi ini mengalami pergeseran akibat kehadiran media sosial dan internet.
Sayangnya, tim Nussa terjebak dalam dinamika pergeseran otoritas yang terjadi karena kehadiran media, baik internet dan media sosial. Memang model transmisi pengetahuan soal keislaman tradisional ditampilkan oleh tim Nussa, dengan memunculkan diksi “Kata ustad”, jadi Nussa tidak bisa dianggap menghilangkan peran otoritas keagamaan.
Namun, ketika mereka hanya menampilkan satu ajaran dalam persoalan fiqih yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan pendapat, di sinilah mereka mulai terjebak dalam pergeseran otoritas tersebut. Diksi “Kata Ustad” tidak cukup menampilkan keseluruhan perbedaan pendapat tersebut, akibatnya mereka hanya menampilkan apa yang dipercaya oleh tim Nussa sendiri.
Akibat dari saat mereka lakukan di atas adalah film tersebut telah mengabaikan fungsinya sendiri sebagai pengajaran bagi anak-anak, namun yang terjadi malah indoktrinasi hukum fiqih pada anak-anak. Persoalan ini baru saja ditulis dengan apik dengan tajuk Nussa Rara: Menarik, tapi Rawan Reduksi
Kalau Anwar Kurniawan meminjam apa yang disebut ‘wacana’ oleh Michel Foucault, filsuf asal Prancis, untuk menunjukkan segala bentuk dari praktik sosial yang dilakukan secara verbal (tutur kata) atau non-verbal (teks). Sebagai pembentukan wacana persoalan fiqih tunggal yang ditampilkan oleh tim Nussa.
Saya akan sedikit menambahkan bagaimana perubahan keberislaman di dunia media teknologi dan media sosial ini. Ketika Nussa dihadirkan dari dunia siber, maka ia akan masuk pada proses penandaan yang bisa saja tidak lagi menunjuk pada realitas di luar dirinya -sebagaimana umumnya representasi- tetapi menunjuk pada dirinya sendiri sebagai tanda. Sehingga antara tanda dan objek yang ditandai adalah entitas yang sama.
Jean Baudrillard, filsuf asal Prancis, menyebut kondisi self-reference di atas dengan “simulasi”. Di saat yang sama karakter dari dunia siber sebagai ruang konstruksi teknologis bersifat artifisial, di mana memiliki kemampuan menciptakan ruang semiotik yang juga dicirikan oleh sifat artifisial, simulasi dan virtualitas.
Imbasnya, teknologi mampu memunculkan, atau dalam bahasa Baudrillard melakukan simulasi, realitas sendiri yang dibangun dari tanda-tanda yang terputus dari realitas dunia nyata. Jika kita hubungkan dengan Nussa, maka konten enggan salaman terhadap non-mahram tidak bisa hanya dilihat sebagai salah satu dari ajaran Islam belaka, namun di saat yang sama tanda yang coba dibangun tim Nussa adalah realitas baru yakni Nussa yang “Islami” menurut role model yang mereka inginkan.
Tim Nussa membangun realitas sendiri yang menurut mereka sebagai representasi Islam yang benar. Di titik inilah saya akhirnya menyadari apa yang dilakukan oleh tim Nussa terlalu jauh atau terlalu berani masuk ke wilayah hukum yang beragam, apalagi diamalkan oleh sebagian masyarakat, rupanya saya sadari ada hubungan dengan konstruksi dari tim Nussa membangun realitas “Islam” yang mereka anggap benar.
Jika kita kembalikan kartun Nussa sebagai simbol Islam yang tampil di ruang publik sebagai bagian dari menggeloranya keislaman kelas menengah, maka di saat yang sama tim Nussa membangun realitas “Islam” sendiri yang masuk ke ranah pertarungan keislaman di Indonesia yang belum digarap baik oleh organisasi otoritatif, seperti NU dan Muhammadiyah, terutama dengan hadirnya teknologi media yaitu dunia anak-anak.
Persoalan Islam anak-anak masih terlalu bergantung pada model pendidikan saja, padahal dengan kemajuan teknologi sekarang memungkinkan penanaman nilai-nilai kehidupan, termasuk doktrin kekerasan, justru semakin mudah. Kondisi ini sering dikeluhkan saja tapi jarang beraksi untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut.
Fatahallahu alaihi futuh al-arifin
Anda bisa membaca perdebatan Nussa Rara ini di bawah ini:
Sisi Lain Nussa Rara: Menyaksikan Islam Kaku Disiarkan via Layar Televisi Kita
Menjawab Kekakuan BerIslam Animasi Nussa-Rara
Menengahi Polemik Islam Kaku Animasi Nussaa Rara: Apresiasi Islami.co, Suprinyah & Ayatuna
Nussa Rara dan Islam yang Beragam
Nussa Rara Episode Bukan Mahram; Menarik, tapi Rawan Reduksi
*Analisis ini kerja sama Islami.co & RumahKitaB*



