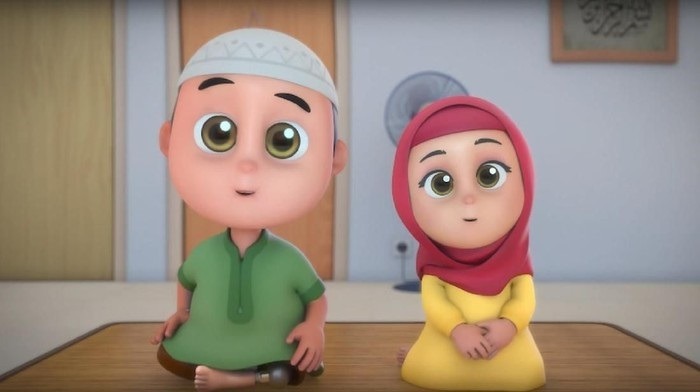
Perang opini ‘Islam kaku’ film animasi Nussa-Rara antara artikel Supriansyah dan Ayatuna menjadi warna tersendiri di tengah banyaknya media yang hanya memberi satu sudut pandang. Saya harus apresiasi tim redaksi Islami.co yang tetap menjaga ‘kewarasannya’ dengan memberi ‘hak jawab’ dari pihak yang berbeda. Belakangan cukup sulit menemukan terjadinya perang opini yang elegan di media online, terlebih di media yang mengatasnamakan dakwah.
Supriansyah, melalui tulisannya berjudul Sisi Lain Nussa-Rara, Menyaksikan ‘Islam Kaku’ Diajarkan via Layar Televisi Kita, mengkritik tayangan animasi Nussa-Rara yang sudah beberapa tahun terakhir tayang di YouTube. Pada Ramadhan tahun ini, sebuah televisi swasta menayangkan tayangan Nussa-Rara di saat sahur dan berbuka puasa. Hal ini yang menjadikan penulis artikel tersebut gelisah. Sebab, menurutnya, ada bagian-bagian yang mengusik dirinya, terutama soal ‘kakunya’ cara berislam yang ditayangkan oleh karakter animasi tersebut.
Supriansyah kemudian membawa persoalan semiotis tersebut ke ranah yang lebih besar, yaitu ekonomi politik. Di sebuah tayangan pasti ada ideologi cuan di baliknya. Dalam kajian ilmu komunikasi, ‘kecurigaan’ seperti ini dikupas oleh beberapa ilmuwan komunikasi seperti Vincent Mosco dan Anthony Giddens.
Perspektif ekonomi politik biasanya digunakan untuk membedah sesuatu yang invisible. Ia berusaha menganalisis hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang, tetapi merupakan kekuatan terbesar dari sebuah produksi budaya, termasuk film. Sedikit saja gagal mengunci data, penelitian tentang ekonomi politik akan menjadi bumerang bagi peneliti.
Apakah Supriansyah mengalami kegagalan ini? Wallahua’lam. Yang jelas, artikel tersebut ditanggapi oleh banyak netizen yang ‘tidak terima’ apabila tayangan kesayangannya disebut mengajarkan Islam yang kaku. Sayangnya, di Twitter banyak akun-akun yang hanya menghujat tanpa memberi tanggapan yang apple to apple.
Hingga muncul tulisan dari seorang penggemar animasi Nussa-Rara, Elam Sanurihim Ayatuna, seorang pendidik anak yang bekerja sebagai ASN di Kementrian Keuangan. Ia menulis artikel berjudul Menjawab Kekakuan BerIslam Animasi Nussa-Rara: Bantahan Tulisan Supriansyah. Tulisan ini agaknya mewakili kegundahan para penikmat animasi tersebut.
Bagi Ayatuna, Nussa-Rara adalah oase di tengah banyaknya tayangan ‘kurang mendidik’ di Indonesia, terutama animasi. Eksploitasi drama percintaan dan perkelahian dewasa yang biasa jadi latar cerita animasi bisa diimbangi dengan tayangan sederhana berdurasi 2-3 menit. Tentu saja, bagi Ayatuna, Nussa-Rara ini merupakan animasi sangat ramah anak yang berkelas dengan grafis memukau. Saking takjubnya, ia menyebut sampai tidak percaya animasi ini dibuat oleh studio dalam negeri.
Saya mencoba melepaskan diri dari subjektivitas untuk mendukung salah satu di antaranya. Saya justru tertarik untuk menengahi perdebatan yang dijamin tidak akan pernah selesai. Apa pasalnya? Kedua penulis menggunakan perspektif yang sama sekali berbeda.
Supriansyah menggunakan pendekatan semiotik yang lahir dari tradisi strukturalisme. Tradisi ini melihat bahwa media (dan budayanya) memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk imajinasi dan realitas. Animasi yang seolah hanya hiburan semata ternyata memiliki ideologi yang tengah diinjeksi kepada audiens, yang akan memengaruhi cara pandang audiens terhadap nilai tertentu.
Sementara Ayatuna menggunakan perspektif kulturalisme yang lebih memihak pada kekuatan audiens dalam memilah isi tayangan. Ia menilai, pilihan fikih yang ditonjolkan dalam animasi tersebut merupakan bentuk pembelajaran bahwa memang ada fikih yang seperti itu. Untuk mendukung pendapatnya, ia menyebut dirinya bukan anti-salaman, tetapi juga tidak alergi dengan orang yang enggan bersalaman.
Tentu saja kedua argumen tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan Supriansyah sangat tepat jika membaca target audiens animasi tersebut adalah kalangan awam yang mudah percaya pada simbol-simbol yang dimunculkan dalam sebuah tayangan. Namun pendekatan ini mudah dipatahkan apabila membaca audiens yang terdidik dan melihat tontonan sebatas tontonan. Sementara preferensi pribadi dibentuk oleh pengalaman manusia seumur hidupnya.
Sebaliknya, pendekatan Ayatuna sangat tepat untuk mengatakan bahwa masyarakat kita sebagai agen sudah cerdas. Tidak perlu mengkhawatirkan sebuah tayangan bisa serta merta menanamkan ideologi tertentu. Kelemahannya, pendekatan ini rawan mengabaikan banyaknya audiens yang benar-benar menganggap tontonan sebagai tuntunan. Karena preferensi manusia bisa diawali dari satu tayangan yang memengaruhi pilihan-pilihan hidup selanjutnya.
Lalu bagaimana kita menyikapi pandangan kedua penulis tersebut dalam konteks Indonesia? Ya, biasa saja. Lha wong keduanya sama-sama memiliki argumen yang kuat. Saya justru tidak ingin pembaca menjadi tim hore yang hanya fanatik terhadap satu pendapat lalu menutup diri dari pendapat lain.
Sejak pertama kali kajian budaya dibicarakan dalam keilmuan Sosiologi berikut turunannya, para ilmuwan tidak pernah berhenti untuk menguji satu teori, mengkritiknya, lalu memberi tawaran baru. Kajian tentang budaya dan hal-hal terkait tentangnya sejak dulu sangat dinamis.
Komodifikasi: Sebuah Masalah?
Saya ingin coba mengurai hal-hal yang dipermasalahkan keduanya.
Pertama, kata ‘kaku’ yang disematkan dalam sebuah perilaku keagamaan. Bagi saya, tidak ada yang salah dengan pelabelan kaku. Dan tidak pula ada yang salah apabila orang memilih cara berislam yang kaku. Mengapa demikian?
Saya teringat pada sebuah forum diskusi bersama teman-teman Institut Fahmina, Cirebon. Mereka sedang melakukan penelitian di sebuah tempat dan mengemukakan adanya terminologi konservatif-toleran. Apa maksudnya? Di tempat yang diteliti, orang-orang berislam dengan cara yang kaku itu tadi. Meski begitu, mereka bisa hidup dengan warga yang berbeda agama.
Yang menjadi masalah adalah jika kekakuan itu sampai membuat orang bersikap eksklusif. Orang-orang yang berbeda dengannya dieksklusi dan dihambat hak-haknya sebagai warga negara.
Kedua, Supriansyah mengajak kita membahas sebuah produksi budaya dalam kacamata komodifikasi. Komodifikasi secara mudah dipahami sebagai penukaran barang, jasa, gagasan, dan lain-lain menjadi komoditas yang bisa diperjual-belikan. Dilihat dari prosesnya, jenis komodifikasi yang terjadi dalam animasi Nussa-Rara masuk dalam dua kategori, yaitu komodifikasi konten dan audiens.
Supriansyah mengutip populasi middle-class di Indonesia yang mencapai angka 141 juta jiwa. Tentu saja, ini adalah ceruk pasar yang sangat besar. Ditambah karakter middle-class muslim yang dermawan dan cenderung ingin tampil religius (Yuswohady, 2016), pasar ini tentu bermandikan rupiah.
Meningkatnya kelas menengah muslim tampaknya menjadi fenomena global. Shelina Janmohamed di tahun 2016 menulis Generation M: Young Muslims Changing the World yang memotret prilaku konsumerisme kalangan muslim urban yang luar biasa. Ada orang yang ingin tampil religius dengan memburu berbagai produk berlabel halal atau syariah. Tak mengherankan jika muncul sabun halal, kain syar’i, dll. Hal yang kurang lebih ditemukan juga oleh Yuswohady di Indonesia (Baca: Gen M #GenerationMuslim Islam Itu Keren, 2016).
Kegelisahan Supriansyah disadari oleh Ayatuna. Ia bahkan membela, memangnya kenapa jika produsen animasi tersebut mendapatkan cuan dari sini? Apakah ada yang salah? Begitu kira-kira pertanyaannya.
Komodifikasi di satu sisi memang jahat. Ia memberikan keuntungan materi pada satu pihak, di saat yang sama memproyeksikan pihak lain untuk mendukungnya tanpa imbalan berarti. Namun, baik Supriansyah dan Ayatuna sama-sama memiliki sikap yang jelas dalam praktik ini. Yang satu kritis, yang satu permisif. Kedua sikap tersebut menurut saya sah-sah saja.
Akhirnya, saya menikmati pertarungan wacana yang disampaikan dengan cara yang elegan. Sebuah praktik yang sudah sangat lama tidak terjadi di media online. Karena itu saya percaya, baik Supriansyah atau pun Ayatuna adalah orang-orang yang tidak anti kritik dan mengemukakan pendapat berdasar perjuangan nilai yang diyakini.
Yang mengkhawatirkan adalah orang yang enggan melawan wacana dengan wacana, tetapi melakukan penyerangan secara membabi-buta. Orang-orang tersebutlah yang merusak pergulatan pemikiran. Padahal, jika kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, salah satu cirinya adalah munculnya ragam pemikiran yang berbeda-beda.
Seseorang menulis, jika ada yang tidak sependapat, akan dibalas dengan tulisan. Kalau tulisan dibalas dengan hujatan, berarti orang tersebut ingin menjerumuskan Islam pada abad kegelapan. Semoga saja kita menjadi bagian yang berupaya membawa kejayaan bagi peradaban ini. Amin.
Wallahua’lam bisshawab.



