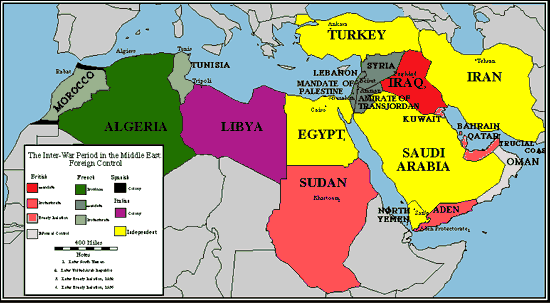
Membincang fenomena konflik di Timur Tengah dari kacamata Indonesia memiliki respon yang sangat beragam. Tidak sedikit dari masyarakat yang salah paham, gagal paham, bahkan menggunakan model untuk di copypaste secara serampangan, meski tak sedikit pula yang memiliki cara pandang yang clear atau proporsional.
Jika di Timur Tengah, negeri asalnya, terjadinya konflik yang memporak-porandakan negeri dilatari banyaknya kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Namun di Indonesia, konflik politik seperti di Timur Tengah itu bisa berubah menjadi sangat ideologis, dan sektarian antar agama, atau aliran keagamaan, semisal Sunni-Syi’ah atau muslim-kristen dan sekte serta kabilah-kabilah. Apakah ketika melihat konflik Timur Tengah harus menggunakan kacamata kuda begitu? Nampaknya perlu pembacaan lebih luas, sehingga kita bisa melihat banyak hal, yang pada gilirannya pandangan kita juga bukan hanya sektarian dan lebih jauh hanya hitam-putih.
Dari penelusuran KBBI, sektarian memiliki dua makna; 1) berkaitan dengan anggota (pendukung, penganut) suatu sekte atau mazhab; sementara makna ke-2) picik, terkungkung pada satu aliran saja. Nah, penyempitan makna menjadi sektarian dalam membaca konflik Timur Tengah inilah yang ingin kita bahas lebih dalam.
Dari sisi sejarah, kawasan Timur Tengah memiliki akar dan menjadi salah satu peradaban tua di dunia. Sejak dulu, kawasan ini memang selalu menjadi pusat perhatian, bahkan Adam dan Hawa bertemu setelah diturunkan ke bumi juga di Timur Tengah yang dikenal, Jabal Rahmah. Muncul peradaban kuno yang populer, antara lain kebudayaan dan peradaban Mesir kuno di lembah sungai Nil, Babilonia dan Assiria di Mesopotamia yang dialiri oleh sungai Tigris (Iraq) dan Eufrat (Persia), Pegunungan Armenia (Turki), Laut Mati/Sungai Yordan dan lain-lain.
Sistem-sistem sungai dan laut inilah yang memberikan nafas hidup kepada peradaban-peradaban besar itu jauh sebelum kedatangan Islam. Berikutnya ada banyak kisah yang muncul, selain Nabi dan Rasul, ada juga muncul nama-nama besar seperti Fir’aun, Namruj dan lainnya, atau versi berbeda menyebut Darius, Nebukadnezar, Sultan Saladin, dan lain-lain.
Jadi, ada banyak alasan mengapa kawasan ini dari dulu hingga kini menjadi penting, salah satunya adalah kawasan penghubung tiga benua, Asia, Afrika dan Eropa, terlebih setelah terbukanya terusan Suez. Dengan banyaknya peluang, termasuk sumberdaya, mineral, air, minyak, dan sumber transportasi serta lainnya, maka wilayah dan kawasan ini selalu menjadi perhatian.
Keberagaman penduduk dan latar belakang, termasuk aliran keagamaan dan ideologi juga menjadi bagian yang begitu mudah digerakkan untuk melahirkan konflik dan tarik-menarik kepentingan. Dan pemantik sebagai ‘bensin’ paling mudah dan mungkin juga murah, di Timur Tengah sendiri adalah sentimen agama dan aliran keagamaan. Jika di Timur Tengah sudah ‘meledak’, maka efek ledakannya bisa dengan mudah merembes ke kawasan lain, termasuk tanah air, Indonesia Raya tercinta ini.
Jalur laut yang menunjukkan superioritas militer, termasuk pengangkutan eksport minyak dari negara-negara Timur Tengah, juga menjadi cerita tambahan dari rentetan konflik. Jalur tersebut juga memberi pemasukan penghasilan negara karena hasil dari laut seperti ikan, mineral/gas, ataupun dari retribusi kapal-kapal asing yang melewati laut.
Faktor Pemicu Ketegangan
Dalam catatan Sidik Jatmika yang mengutip dari Gerald Blake soal Middle East, sebagian besar perbatasan darat di Timur Tengah sudah ditentukan sejak 1880 dan 1930, namun, soal perbatasan laut justru baru mulai ditentukan pada tahun 1960-an, dan hingga hari ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Berbagai perbedaan dan keragaman yang muncul, menyangkut perbatasan negara yang kecil dan besar, jalur laut yang kecil dan besar, kekayaan alam dan sumberdaya yang kecil dan besar, termasuk negara kaya-miskin, dan tingkat kemakmuran suatu negara, akan memiliki arah yang berbeda, baik secara politik maupun aspek lain dan tidak sedikit melahirkan ketegangan.
Ada banyak faktor yang menjadi pemicu ketegangan di kawasan Timur Tengah, baik secara internal kawasan, maupun pihak di luar kawasan yang juga berkepentingan. Dua poin utama bisa disebutkan: Pertama, posisi strategis kawasan ini yang menjadi penghubung bagi ekonomi, perdagangan, dan pertahanan global ketiga benua, yakni Asia, Afrika dan Eropa. Kedua, soal keanekaragaman yang memang dimiliki Timur Tengah. Beberapa keanekaragaman yang tergambar bisa disebut, antara lain:
- Geografis Timur Tengah yang melahirkan perbedaan wilayah, ada yang luas dan sempit sehingga menjadi pemicu dominasi, termasuk juga kedekatan regional yang tak jarang memicu ketegangan, seperti kawasan Arab inti (bulan sabit); Saudi Arabia, Mesir, Kuwait, Irak, Palestina, UEA, Bahrain, Qatar, Oman dan Yordania. Kawasan Arab periferal; Libya, Sudan, Yaman, Suriah dan Libanon. Kawasan Arab maghribi; Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Mauritania. Kawasan non-Arab; Turki, Iran, Siprus, Israel dan Afghanistan. Kawasan Asia Tengah yang merupakan eks Uni Soviet; Azarbaijan, Uzbekistan, Kazakstan dan Turkmenistan.
- Problem kepemilikan air, baik air tawar maupun air laut. Pemicunya bisa keterbatasan akses air, semisal perbatasan, potensi kekayaan air laut, mineral, pulau-pulau, dan pendapatan yang muncul dari kepemilikan laut. Sementara air tawar bisa berupa akses air bersih, irigasi untuk lahan, juga pembangkit listrik.
- Keanekaragaman agama, akar budaya dan suku atau kabilah. Ada warisan peradaban yang muncul di lembah sungai Nil, Tigris dan Eufrat, lalu muncul ras Semit yang melahirkan etnis Arab dan Yahudi, Aria dengan Persianya, dan Berber di Afrika Utara. Ada juga ras gabungan semisal Turki yang ada unsur Mongolia dan Kurdi yang Indo-Persia. Belum lagi pecahan dalam bentuk suku-suku dan kabilah yang juga beritu beragam. Dari sisi agama, ada Yahudi, Islam, dan Kristen, begitu juga aliran-aliran keagamaan lain. Keragaman yang bisa menjadi potensi baik sebagai sebuah kekayaan budaya ataupun sebaliknya, bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik.
- Keanekaragaman ekonomi dengan melihat tingkat kemakmuran suatu negara, kaya-miskin hingga kekayaan alam dan sumberdaya yang dimiliki, bisa melahirkan arah yang berbeda dan memicu ketegangan.
- Keanekaragaman ideologi juga hadir, ada Pan Islamisme, OKI dan juga Liga Arab yang merespon munculnya negara Israel. Ada sekularisme, liberalisme, komunisme, dan juga zionisme. Ada juga ideologi yang berbasis pada ajaran agama, semisal Islam, Kristen dan Yahudi dan aliran keagamaan, semisal Sunni-Syiah dan lainnya.
Nah, berbagai keragaman, termasuk letak geografis yang berujung pada perbatasan di atas, sangat mungkin menjadi salah satu faktor pemicu ketegangan, meskipun ujungnya juga soal beda kepentingan dan sudut pandang yang bermuara pada ekpresi politik, baik perorangan, kelompok, maupun atas nama negara. Maka melihatnya tidak hanya sektarian. Ada banyak model dan kamuflase yang mengemuka dalam ketegangan di kawasan ini yang musti dibaca secara mendalam dan dari berbagai aspek. Adakalanya tidak peduli dengan agama, asal kepentingannya sama. Adakalanya ideologi menjadi basis penyatuan kepentingan. Yang jelas basis kepentingan menjadi lebih penting dan menarik untuk dilihat, sementara pemicu dan ‘bahan bakar’ konflik dan ketegangan bisa bermacam-macam.
Baca juga: Sulitnya Mendamaikan Timur Tengah
Suasana batin atas perasaan ketidakadilan, diskriminasi atau peminggiran kelompok, ketimpangan ekonomi menjadi awal mula perasaan kecewa dengan situasi dan kondisi, dan akumulasinya bisa melahirkan protes, ketegangan dan konflik yang mencari sasaran dan target permusuhan. Dorongan pihak luar juga bisa menguatkan ketegangan, sehingga memperkeruh dan muncul pihak yang mengambil keuntungan dari situasi krisis.
Krisis Politik yang Berulang
Menurut Carl J Friedrich, politik merupakan suatu upaya atau cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan. Politik juga dapat diartikan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Kehidupan berpolitik tak pernah lepas dari kehidupan sosial suatu negara. Dan masyarakat di Timur Tengah dengan didominasi oleh bangsa Arab memiliki kultur pemerintahan yang sebagian besar adalah diktator. Salah satu faktor historis yang melatari karena di wilayah tersebut dulunya bersistem kekerajaan.
Arab Spring menjadi pintu masuk berbagai pihak melakukan koreksi terhadap kepemimpinan di Timur Tengah, mulai dari Tunisia hingga menyebar ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Beberapa tuntutan akibat reaksi ketidakpuasan publik Timur Tengah, ada yang menunjukkan hasil positif, namun tidak sedikit pula yang justru berakibat fatal dan melahirkan krisis dan konflik berkepanjangan. Kecepatan merespon dan kepiawaian negosiasi pemimpin di kawasan ini menjadi kunci, termasuk melihat berbagai efek dan dampak serta pengaruh para tokoh dan supporter yang menggerakkan aksi, baik secara internal maupun eksternal negara.
Tidak sedikit para pemimpin yang tumbang dan harus menyerahkan mandat kepada desakan publik, semisal Tunisia, Libya, Mesir dan Yaman. Namun ada juga yang hanya melakukan reformasi internal tanpa penggulingan kekuasaan, semisal Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan juga Syuriah meski mengalami pergolakan yang masih berlangsung hingga saat ini.
Di Mesir misalnya, pasca tumbangnya rezim Hosni Mubarak, rakyat Mesir justru terjerumus ke dalam konflik sektarian. Konflik sektarian tersebut terjadi antara warga muslim dan kristen. Dalam konflik yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tersebut, setidaknya terdapat beberapa orang yang menjadi korban akibat brutalnya aksi. Konflik sektarian di Mesir adalah satu contoh resistensi politik di kawasan Timur Tengah setelah revolusi berhasil dilakukan.
Pasca revolusi, umumnya tuntutan sederhana yang dikehendaki rakyat dan para elite politik adalah melangsungkan pemilihan umum secara demokratis untuk memilih kepemimpinan baru. Harapan baru tersebutlah yang menjadi suara mayoritas rakyat kawasan Timur Tengah, termasuk harapan kehidupan yang lebih baik dan demokratis.
Situasi yang sekarang terjadi di beberapa negara Timur Tengah ternyata juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi di berbagai negara lain seperti Indonesia. Ada dua dampak yang dirasakan oleh Indonesia -dampak langsung dan tidak langsung. Kehidupan ekonomi suatu negara memang tidak pernah lepas dari hubungan antar negara. Hubungan antar negara diwujudkan dalam hubungan keilmuan, sosial, politik, diplomatik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.
Krisis Timur Tengah juga melahirkan berbagai model dan varian yang juga sulit dibaca, kecuali pembacaan politik dan geopolitik yang melingkupi. Munculnya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) adalah bagian dari kerumitan krisis di kawasan ini. Sebelumnya persoalan sengketa Israel-Palestina, muncul juga Al-Qaeda, hingga berbagai kelompok separatis semisal kelompok Houthi di Yaman dan gerakan separatis lain menjadi bagian dari varian krisis yang rumit.
Gelombang Demokrasi dan Nasionalisme SARA
Harapan perubahan yang lebih baik adalah suara yang berdengung mengiringi gelombang revolusi yang bergulir di kawasan Timur Tengah. Pemerintahan yang demokratis diharapkan mampu memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas, meski dalam situasi transisi justru memiliki banyak kerentanan. Sebab, demokrasi yang berdampak positif membutuhkan prasyarat dan kondisi awal yang perlu diperhatikan.
Kondisi dan prasyarat bagi demokrasi yang dibutuhkan antara lain; pengetahuan dan ketrampilan politik yang memadai di antara penduduknya, dukungan elite politik terhadap demokrasi, tradisi rule of the law dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kuat, tingkat perkembangan ekonomi tertentu, kebudayaan yang menunjang dan sebagainya.
Nah, jika prasyarat ini tidak terpenuhi, justru akan melahirkan kerentanan yang dimaksud, meski kebebasan menyatakan pendapat, pemilihan umum langsung yang jurdil (jujur dan adil) dan luber (langsung, umum, bebas, rahasia) bisa diselenggarakan. Kerentanan pada proses politik awal dan masa transisi demokrasi seringkali melahirkan berbagai konflik kepentingan, terlebih di kalangan elit. Sebab, suara demokrasi ditentukan melalui suara mayoritas, sehingga pihak minoritas akan tersingkir. Dan kaum elit yang di periode sebelumnya berkuasa, bisa jadi punya peluang yang sama, menjadi tersingkir, maka elit tersebut akan menggunakan sentimen nasionalisme SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) untuk membangun kekuatan politik sesuai kepentingan elit. Dan cara-cara elit menarik sentimen SARA dalam proses pemenangan politik di era transisi demokrasi inilah yang mengganggu demokrasi yang diharapkan, bahkan tak sedikit melahirkan guncangan sosial-politik yang hebat.
Dalam bukunya, ‘From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict’, Jack Snyder mengungkapkan fakta keterkaitan antara demokratisasi dan konflik nasionalisme, dan itu banyak berhubungan dengan apa yang disebut nasionalisme SARA. Dasar legitimasinya diperoleh dengan cara benturan ras, agama, suku, golongan, bisa juga pengalaman sejarah, mitos dan seterusnya. SARA digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan orang dari term nasionalis, padahal ini bersifat rasis dan berangkat dari pemikiran yang sempit. Sementara perbedaan dan berbagai kesempitan dalam bentuk SARA tidak selayaknya menjadi basis demokrasi. Sebab demokrasi justru diharapkan melahirkan rasa nasionalisme yang tetap menghargai perbedaan dan tidak terkotak-kotak yang anti pluralisme.
Studi Snyder di atas menyebutkan, kebanyakan atau sebagian besar negara-negara yang tercebur dalam konflik SARA selama dasawarsa 1990-an adalah negara yaang sedang menuju tahapan transisi demokrasi. Lantas, bagi negara Indonesia yang dianggap sudah melampaui, tetapi masih menunjukkan situasi dan kondisi yang kurang lebih sama, adakah termasuk sebagian kecil dalam riset Snyder?
Ada maksud yang disampaikan Snyder, bahwa dua tahun sebelum pecahnya konflik dan pertikaian SARA, umumnya dimulai dengan pra kondisi dengan menguatnya kemajuan parsial dalam hal kebebasan politik atau kebebasan sipil. Parsialitas yang merusak, menyempit dan rasis inilah yang menjadi penyubur bagi lahirnya nasionalisme SARA.
Beberapa contoh negara yang mengalami pecah SARA, antara lain di bekas Yugoslavia, antara orang Armenia dan orang bekas Soviet Azerbaijan, begitu juga di Burundi dengan minoritas Tutsi dan mayoritas Hutu. Begitu juga yang terakhir kasus SARA di kawasan Timur Tengah, semisal Mesir.
Lantas bagaimana membuat nasionalisme SARA tidak muncul? Apakah demokrasi selalu melahirkan bahayanya yang juga semakin rumit dan membuat apriori?
Nasionalisme sipil musti dikuatkan. Para elit, baik di level pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif), maupun tokoh masyarakat dan ulama, bersama seluruh lapisan masyarakat saling menjaga situasi kondusif, tidak merasa terancam oleh proses demokratisasi, dan institusi politik (kelembagaan negara) yang ada juga saling menopang dan cukup kuat menampung proses ini.
Baca juga: Indonesia Bisa Jadi Juru Damai Timur Tengah
Penguatan nasionalisme sipil, seperti digagas Kim Holmes misalnya, adalah upaya untuk membangun basis pemersatu bangsa dan menciptakan kesetaraan warga negara tanpa melihat jenis suku, ras, warna kulit, keturunan dan agama, sehingga demokrasi yang dijalankan akan memberi dampak positif dan mencapai cita-cita bangsa yang diharapkan. Dengan cara yang setipe ini pula, pemahaman dan cara pandang sektarian, dengan sendirinya juga akan memudar. Berbagai perbedaan kepentingan dan konflik bisa dilihat secara lebih utuh dengan mempertimbangakan berbagai faktor dan penyebab yang menjadi pemicu konflik, dari berbagai aspek dan latar belakang secara menyeluruh.
Akhirnya kedewasaan setiap warga, kesadaran berdemokrasi yang semakin dipahami, akan berujung pada kondisi check and balances dan menjadi pupuk untuk terwujudnya proses demokrasi yang terus membaik dan saling menjaga melalui kritik-konstruktif, sehingga melahirkan kran demokrasi yang menyehatkan dan berujung pada kemakmuran negeri. []



