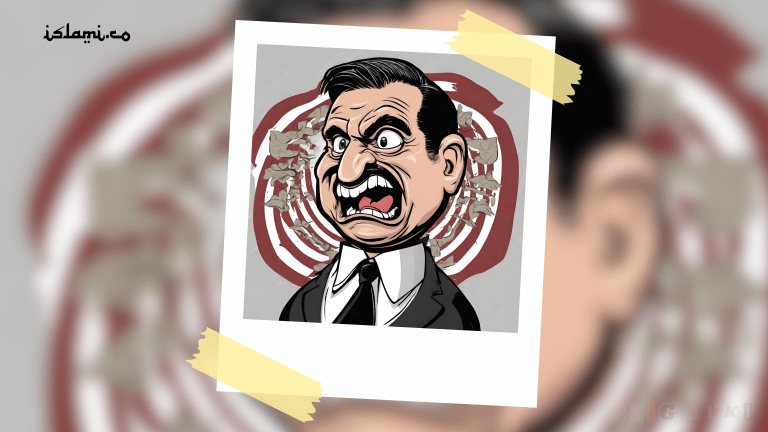
Konten-konten yang mengajak berteman lagi setelah pemilu perlu kita terjemahkan sebagai bersatunya kembali masyarakat untuk membentuk people power. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun kebelakang ini hilang. Karena siapapun yang terpilih, kita perlu turut andil mengawasi.
Kita tidak perlu terlena terlampau memuja, sampai tumpul kritisisme kita. Karena sejatinya kekuasaan memang melenakan, sehingga mereka patut untuk selalu diingatkan. Jangan sampai yang habis jadi kontestan pemilu berkawan lagi sementara pemilihnya masih cakar-cakaran.
Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah memastikan mereka selalu ada di dua jurang yang berbeda. Kita perlu melihat dan merasakan demokrasi di negara ini berjalan sebagaimana mestinya agar setiap elemen trias politica bekerja secara tupoksinya. Bukan malah makan siang untuk membicarakan jatah politik bancaan yang dijanjikan.
Mitos Hubungan Ideal
Lewat tulisan ini saya ingin berbagi sebuah konsep yang saya kenal medio 2016 lalu, yakni mitos hubungan ideal. Ada beberapa mitos dalam hubungan ideal, tapi di sini saya ingin menyampaikan satu saja, yakni hubungan ideal tidak pernah marahan.
Ya, hubungan yang ideal bukan berarti yang tidak pernah marahan. Karena marahan adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Setiap dari kita berbeda, pasti akan ada yang bertabrakan, dan kedewasaan kita menuntut kita meregulasi emosi itu.
Malah kita perlu curiga pada sebuah hubungan yang selalu adem ayem. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah memang benar-benar adem ayem karena kedamaian yang dialasi keadilan telah terjadi atau malah adem ayemnya karena ada salah satu manusia yang terpaksa selalu berada dalam situasi kalah kemudian bungkam.
Kalau yang terjadi adalah situasi kedua, saya ingin menyebut situasi ini dengan kedamaian semu. Seolah-olah damai, tapi sejatinya ada seseorang yang selalu dalam posisi kalah dan terpaksa ada di situasi itu. Ini semua dilakukan agar keluarganya terlihat damai.
Kita perlu akui bahwa sebagian dari kita menikmati situasi ini, demikian dengan negara kita. Yang penting terlihat adem ayem, guyup, dan rukun. Lalu dengan buru-buru menyimpulkan keadaannya baik-baik saja tanpa kroscek apa yang sejatinya terjadi. Sampai-sampai sengaja abai pada beragam riak fenomena yang berlawanan dari cita-cita adem ayem.
Kita mungkin tidak terbiasa dengan situasi berseberangan. Kita selalu membayangkan situasi damai adalah kondisi yang pola pikirnya, tingkah lakunya, sampai penerimaan atas tingkah laku semua orang adalah seragam. Adem ayem adalah ketika semua teriak “Setuju!”. Padahal dalam hidup, realita yang pasti adalah perbedaan-perbedaan antar manusia. Dan kita sebagai negara punya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Satu sama lain punya tolok ukur sendiri, dan ndak bisa atas dasar “terlihat” ayem seraya sesuara.
Mungkin kita tidak pernah membayangkan tetap damai tapi terbiasa dengan hidup saling kritik. Sekarang kita berada dalam situasi mengkritik berarti mengganggu stabilitas.
Padahal contoh situasi seperti itu mudah kita dapatkan. Salah satu yang paling masyhur adalah kisah “cekcok” pendapat antara Kiai Wahab dan Kiai Bisri. Beliau bersitegang argumen dalam sebuah forum ilmiah. Tapi saat forum pending karena jeda salat, satu di antara yang lain berusaha paling sibuk untuk menimbakan air wudhu untuk “musuh” debatnya. Karena satu dengan yang lain tetap rispek meskipun argumentasinya jauh berseberangan.
Kondisi seperti Kiai Wahab dan Kiai Bisri ini yang perlu kita dorong untuk hadir dalam demokrasi kita.
Pemerintah yang terpilih selalu memerlukan oposisi agar kerja-kerja yang dilakukan selalu ada yang mengevaluasi. Kita sebagai masyarakat juga perlu memperkuat people power.
People Power, Oposisi, dan Tumpulnya Kritisisme
Mari kita ingat-ingat seberapa sering rakyat tidak berdaya di depan hukum.
Beberapa bulan lalu ada seorang kakek di Bojonegoro terpaksa harus berurusan dengan meja hijau karena ayam yang ia beli mirip dengan ayam Bu Lurah, lalu kakek itu dituduh mencuri ayam milik Bu Lurah.
Selain itu, kita juga lebih sering mendengar plesetan Wakanda dan Konoha untuk mengganti kata Indonesia dalam setiap sajian komedi layar kaca.
Plesetan-plesetan ini dilakukan sejatinya karena kita malu-malu dalam mengkritik, atau karena takut?
Bukankah kejadian seperti ini lahir karena rakyat sejatinya tidak punya kekuatan apapun. Rakyat terlalu lemah, sementara di sisi lain pemerintah terlalu kuat. Hukum yang sejatinya berlaku setara, seperti pemilu kemarin, satu suara untuk satu orang, siapapun kita, tiba-tiba tinggal jadi konsep. Hukum hanya baik pada yang punya kuasa, pengikut, dan uang berlebih.
Sehingga dari sana, usaha agar kita memiliki kembali people power dengan bergotong royong jadi penting. Siapapun yang kemarin kamu pilih, kalau rakyat tetap lemah, sepertinya kita tinggal menunggu waktu untuk dikadali.
Terlebih, usaha untuk memperkuat people power muaranya untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan ke arah yang lebih baik. Lawong demokrasi aja demosnya berarti rakyat, kok rakyatnya tidak punya kuasa sama sekali. Sekali punya kuasa harganya cuma 50 ribu.
***
Selain soal people power, satu hal lagi yang perlu untuk didorong di demokrasi kita adalah oposisi yang kuat.
Saya jadi teringat sebuah pepeling menarik dari Abdul Gafar Karim, Akademisi Ilmu Politik UGM, tentang kenapa Indonesia gagal melahirkan oposisi.
Ia menjelaskan bahwa cara Jokowi menyelesaikan persoalan selama 10 tahun ini unik. Ia menamai sistem yang digunakan Jokowi adalah sistem otoritarianisme pangku.
Kalau ada yang berseberangan, kalau ada yang mengkritik, yang opininya beda dengan pemerintah, sekaligus mengganggu stabilitas publik dan pastinya mengganggu “kedamaian”, orang-orang itu akan dipangku, diajak masuk dalam pemerintahan. Lalu dengan sendirinya lawan yang berisik itu akan jinak.
Ironinya, sistem seperti inilah yang membuat kita sebagai negara yang memilih demokrasi sebagai jalan hidup tidak memiliki oposisi. Adapun lembaga legislatif yang bertugas menyeimbangkan kekuatan eksekutif, fungsinya belum maksimal.
Dan saat oposisi hilang dari tanah yang mengaku berdemokrasi, ia akan pincang. Tidak ada kekuatan penyeimbang. Eksekutif akan semakin sewenang-wenang, opini jadi tunggal, dan kita terjebak dalam kedamaian semu.
Atau jangan-jangan, kita selama bertahun-tahun ini membiarkan pemerintahan tanpa oposisi karena buaian yang penting hidup damai? Kita takut dipandang sebagai negara tidak ideal saat legislatif dan eksekutif tidak sejalan?
***
Ironinya, saat kita dibiasakan melihat bahwa damai harus sama adalah tumpulnya kritisisme. Kita terbiasa dengan keadaan kedamaian semu, sampai mengira bahwa ya yang semu ini paling ideal. Yang sama yang ideal, yang sesuara yang ideal. Sampai kita lupa bagaimana caranya mengkritik. Toh kalau mau mengkritik, harus lengkap dengan paket solusi. Wah berat.
Sehingga, selepas pemilu ini, bukan lagi siapa yang jadi, tetapi kita kembali pada cita-cita awal untuk bersama-sama menjaga demokrasi.
Kalau emang gak mau kekuatannya diseimbangkan, terlalu patronasi, dan opini harus satu atas dalih kedamaian, ya mari ngaku saja kalau kita memang umat monarki dengan pakaian demokrasi.



