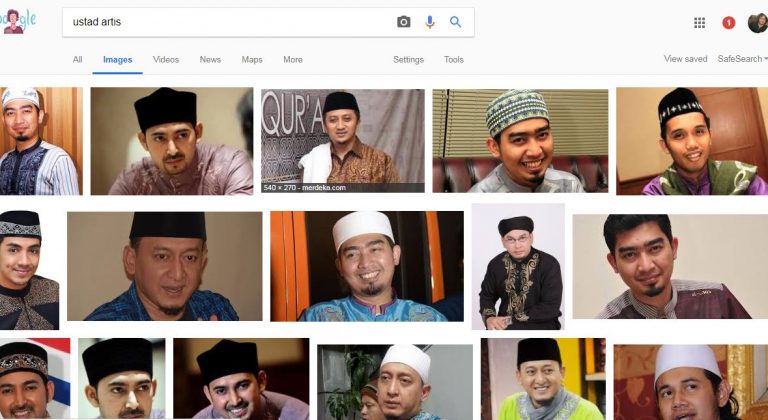
Pada bulan Ramadan tiap tahunnya, masyarakat urban Indonesia merasakan suasana bulan puasa yang lebih pekat karena ekspresi keislaman yang ditopang oleh industri. Sejak awal tahun 2000an, Islam semakin tampak di masyarakat urban Indonesia, dari legal-kebijakan sampai sektor perekonomian dan gaya hidup (lihat Fealy dan White [ed.], 2008). Hal ini terlihat dari perbankan syariah, kompleks perumahan Muslim, Islamic fashion week, hingga dakwah di televisi. Hal inilah yang membuat saya menekuni perkembangan komersialisasi Islam dalam konteks televisi terestrial Indonesia selama lima tahun terakhir.
Pada awalnya, terdapat dua alasan utama yang diargumenkan oleh sarjana Indonesia sebagai sebab meningkatnya keislaman di dalam konten televisi komersial di Indonesia. Yang pertama, pandangan bahwa industri televisi, dengan logika kapitalisme pasarnya, telah melakukan komodifikasi atas nilai-nilai Islam (Sasono, 2005). Hal ini mengarah ke reduksi ajaran agama, yang berpotensi membodohi penonton. Pandangan yang kedua, bahwa televisi komersial telah menyediakan ruang dakwah baru (Darmawan dan Armando, 2008). Sehingga, televisi memberikan kesempatan bagi sarjana Muslim untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan lingkungan pesantren yang merupakan basis jamaah primer mereka.
Ketika melakukan studi atas muatan tayangan bertema Islam, saya menemukan bahwa kedua pandangan ini tidaklah bertentangan. Dengan mengambil kasus sinetron religi misalnya, sejak tahun 2003 hingga 2005, penonton Indonesia dibanjiri gambar-gambar tokoh antagonis, yang juga merupakan Muslim yang kehilangan arah, yang tubuhnya dimakan belatung. Contohnya adalah sinetron Rahasia Ilahi (TPI, 2003) dan Hidayah (Trans TV, 2005). Ketika tren sinetron tersebut menurun, naiklah tren sinetron religi percintaan yang dipicu oleh keberhasilan film Ayat-ayat Cinta (MD Entertainment, 2008). Lazimnya sinetron percintaan merupakan kisah cinta dua tokoh menuju pelaminan. Kedua jenis sinetron religi ini menerima kritik dan pujiannya masing-masing. Sinetron Rahasia Ilahi dipuji oleh Hizbut Tahrir sebagai angin segar (Taufiqurrahman, 2005), dan film Ayat-ayat Cinta dipuji Din Syamsudin sebagai alternatif Islam damai, terutama karena isu terorisme pada saat itu (van Heeren, 2008). Meskipun secara umum keduanya dilihat sebagai upaya pihak industri televisi untuk menarik keuntungan dari perkembangan kesalehan Islam di masyarakat urban Indonesia, pihak-pihak ini merasa bahwa hal-hal baik terbawa bersama dengan naiknya popularitas tayangan bertema Islam di televisi.
Di tahun 2005, Citra Sinema, sebuah rumah produksi yang dipimpin oleh Dedy Mizwar, juga memproduksi sinetron religi. Berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya, Citra Sinema memiliki tujuan utama berdakwah melalui budaya popular. Pengembangan naskahnya sinetron Citra Sinema Para Pencari Tuhan (SCTV, 2007-2013), misalnya, melalui konsultasi dengan beberapa ahli fiqh. Tidak hanya itu, sinetron religi ini terus diproduksi selama tujuh tahun, serta selalu menduduki rating teratas selama bulan Ramadan sejak tahun 2005 hingga 2013.
Betapapun proses produksi tayangan bertema Islam harus meningkatkan rating, baik pihak stasiun maupun produser tayangan menyadari bahwa target pasar mereka adalah para penonton Muslim. Dalam perancangan dan produksi program, mereka peka bahwa penonton Muslim memiliki nilai-nilai yang ingin dijaga, sehingga secara terus-menerus terjadi swasensor dalam proses produksi (Rakhmani, 2014a).
Sensor juga terjadi melalui mekanisme kontrol yang disediakan Negara, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI; Rakhmani, 2014b). Dalam sepuluh tahun terakhir, KPI menerima protes dari masyarakat terkait penggambaran Islam. Dalam sinetron berbau gaib (2007), terdapat protes bahwa Islam tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Dalam sinetron percintaan yang bertemakan percintaan (2008), kritiknya adalah bahwa poligami tidak boleh digambarkan sebagai validasi syahwat lelaki. Dan, yang terkini, terdapat protes terhadap citra ustad dalam komedi religi, karena tokoh yang semestinya tinggi ilmu keislamannya digambarkan memiliki kekhilafan (2013).
Protes-protes inipun menjadi bahan pertimbangan bagi stasiun televisi untuk memperbaiki muatan sinetron religi, demi menghindari risiko kegagalan bisnis. Sehingga, dalam konteks tayangan bertema Islam, KPI turut membantu memberitahu pihak produser mana konten yang berpotensi tidak laku. Dengan kata lain, penggambaran yang sesuai moralitas Islam para penonton memberikan jaminan bahwa sebuah program televisi bertema Islam akan diterima dengan baik.
Yang telah terjadi selama satu dekade terakhir bukanlah semata-mata komodifikasi Islam, atau juga sekadar penggunaan televisi sebagai alat dakwah baru. Televisi komersial telah menjadi ruang dakwah baru, di mana program televisi dapat berperan sebagai khutbah, para penonton juga adalah jamaah, dan komersialisasi – atau penciptaan hubungan antara pengiklan dan audiens – sebuah ‘sistem baru’ yang mengizinkannya terjadi (lihat Rakhmani, 2014a, hal. 355).
Hal inilah yang menghubungkan komodifikasi Islam dengan televisi sebagai alat dakwah. Karena keduanya telah bercampur aduk, dan telah berbaur dalam sebuah hubungan saling menguntungkan – baik bagi para produser, penonton, maupun para pembuat kebijakan. Malah, ketiganya berada dalam simbiosis yang saling mempertahankan efektivitas peran satu sama lain. Para produser dapat terus memproduksi tayangan yang berhasil secara komersial, para penonton menikmati tayangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya, dan KPI memastikan bahwa muatan televisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun realita ini juga mengajukan sebuah pertanyaan penting: ‘Islam’ macam apa yang tengah ditayangkan di televisi Indonesia sekarang ini?
Berdasarkan kajian muatan, saya menemukan bahwa karena para produser acara bertema Islam berupaya menjaring audiens Islam seluas-luasnya, mereka melakukannya tanpa mengusik protes dari mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu, kelompok-kelompok Islam yang terpisah di masyarakat, apakah itu ‘tradisionalis’, ‘modernis’, ‘konservatif’, ‘liberal’, menjadi cair di dalam tayangan-tayangan bertema Islam. Dalam satu episode Para Pencari Tuhan, misalnya, sebuah hadith bisa diinterpretasi dengan beberapa cara berbeda di dalam naskah, dan tidak menghasilkan satu narasi dominan. Karena industri televisi terus hidup dari rating dan pemasukan iklan, posisinya tidak ditentukan secara absolut oleh satu kelompok Islam sebagaimana halnya dalam, misalnya, alat dakwah radio Rodja yang digunakan kelompok Salafi.
Penggambaran-penggambaran ini terus berjalan sendiri, dan bukan cerminan dari realita perdebatan maupun perkembangan pemikiran Islam di antara masyarakat arus utama Indonesia. Tayangan-tayangan tersebut adalah konstruksi Islam yang lahir karena adanya simbiosis antara komersialisasi dan dakwah. Pertanyaannya, apakah mereka yang terlibat dalam prosesnya berani menggunakannya sebagai kesempatan untuk membuka dialog antar organisasi, demi memikirkan ulang Islam seperti apa yang ingin dikembangkan bersama di Indonesia. []
Inaya Rakhmani; Ketua Pusat Kajian Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia dan seorang associate di Asia Research Centre, Murdoch University, Australia



