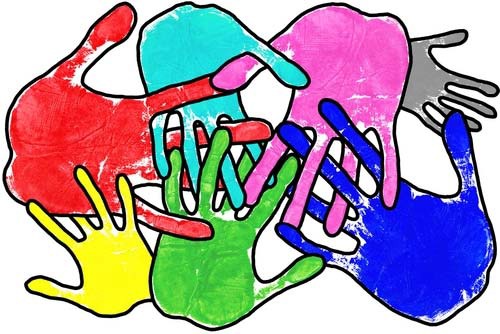
Istilah kebebasan beragama menurut David E. Apter pada mulanya mengacu kepada masyarakat-masyarakat yang majemuk. Menurut Musdah Mulia kebebasan beragama adalah suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima. Seorang sufi sekaligus ilmuwan Iran, Syed Hossein Nasr memilah dua bentuk kebebasan beragama:
Pertama, kebebasan menjadi (freedom to be), yang ditandai oleh pengalaman keberadaan-diri yang asali berkaitan dengan mistikisme yang kepedulian utamanya adalah kebebasan pribadi, bukan kebebasan politis. Kebebasan pribadi adalah kebebasan mutlak (absolute or infinite freedom), yang terdapat di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral (kebebasan menentukan sendiri tanpa hambatan sebab-sebab eksternal), atau kebebasan batin pada pikiran dan imaginasi. Kedua, kebebasan bertindak (freedom to act) yang ada dalam batas-batas yang dipaksakan oleh realitas eksternal kepada manusia.
Beberapa sarjana modern cukup dibuat kliyengan dengan persoalan hadis man baddala dinahu faqtuluhu. Beberapa berpendapat bahwa hadis man baddala dinahu faqtuluhu merupakan hadis ahad. Sebagai hadis ahad, dalam pandangan Abu Hanifah dalalatnya adalah dzanni (relatif). Dengan begitu, maka hadis tersebut tidak bisa menasakh ayat Al-Quran karena dalalatnya Al-Quran adalah qath’I.
Riwayat senada dengan redaksi berbeda, diriwayatkan Imam Malik, dari Zayd ibn Aslam bahwa Rasulullah bersabda, “Man ghayyar dinah fa ‘dribu unuqah” (barangsiapa mengubah agamanya, maka pukullah lehernya)”. Menurut Imam Malik, maksud dari hadis ini adalah barangsiapa keluar dari Islam dan berpindah ke yang lain, misalnya menjadi kafir zindiq, maka hukuman yang pantas baginya adalah hukum bunuh.
Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah mengirim Abu Musa ke Yaman. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirim Mu’adh ibn Jabal ke tempat yang sama. Sama di sana Mu’adh dipertemukan dengan seorang laki-laki. Mu’adh bertanya, “Siapa laki-laki itu?.” Dijelaskan, pada mulanya laki-laki itu beragama Yahudi, lalu masuk Islam namun beberapa waktu kemudian ia kembali masuk agama Yahudi. Mu’adh berkata, “Saya tidak akan turun dari pelana unta ini hingga ia dibunuh sebagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya”. Atas dasar itu maka dibunuhlah laki-laki tersebut setelah sebelumnya diberi kesempatan bertaubat selama dua puluh hari atau dalam dalam riwayat yang lain dua bulan.
Dalam riwayat lain, Al-Husaini menambahkan sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa pada Perang Uhud ada seseorang perempuan murtad. Nabi Muhammad memerintahkan agar orang yang bersangkutan disuruh bertaubat, sekiranya tidak mau, maka ia harus dibunuh. Cerita senada juga diriwayatkan Jabir sebagaimana dikutip Abu Ishaq Al-Syairazi. Bahwa pernah suatu ketika perempuan bernama Ummu Ruman murtad. Nabi memerintahkan agar perempuan tersebut bertaubat, sekiranya ia enggan kembali maka harus dibunuh.
Jamal Al-Banna mengajukan bukti lain. Menururtnya, pernah suatu ketika di zaman Nabi Saw. ada dua belas laki-laki Muslim yang keluar dari Islam, di antaranya adalah Al-Harits ibn Suwaid Al-Anshari. Dua belas orang itu kemudian keluar dari Madinah menuju Mekah. Sekalipun sudah keluar dari Islam, Nabi Saw. tidak membunuh mereka. Nabi Saw. tidak memerintahkan sahabat mengejar mereka untuk dibunuh.
Konon peristiwa kembalinya Al-Harits ibn Suwaid kepada agama yang dipeluk sebelum datangnya agama yang dibawa Muhammad S aw. menjadi sebab diturunkannya ayat wa mayyabtaghi ghairal islamadina. Cerita senada juga terdapat dalam Al-Sirat Al-Nabawiyah Ibn Hisyam. Ubaidillah ibn Jahsy setelah berpindah bersama istirnya (Ummu Habibah binti Abi Sufyan) ke Habasyah, ia kembali memeluk Kristen dan meninggal dalam keadaan Kristen.
Muhammad Husain Haikal dalam Hayatu Muhammad menjelaskan, semenjak awal sampai periode Madinah, Muhammad Saw. memang punya cita-cita politik memberikan kebebasan kepada setiap umat, baik Islam maupun Yahudi untuk menjalankan ajaran agamanya. Ini karena disadari, kebebasan merupakan sarana paling efektif mencapai kesatuan integral.
Berdasarkan penjelasan tersebut Abd Moqsith Ghazali menyimpulkan bahwa kebebasan beragama bukan hanya mendapatkan legitimasi normatif-teologis, melainkan dikukuhkan dari sudut pandang politik. Pendapat yang senada juga dikatakan Aisyah Abdurrahman bintu Al-Syāthi’. Menurutnya larangan pemaksaan beragama itu adalah untuk memastikan bahwa akidah itu benar-benar bersumber dari keyakinan hati, karena tidak ada iman yang benar kecuali bila berasal dari hati yang tulus, murni, tenang dan jujur. Pemaksaan hanya akan menghasilkan pengakuan di mulut, tetapi pengingkaran di dalam hati, dan itu adalah kemunafikan yang oleh Islam dianggap sebagai kekafiran yang paling jahat.
Jaminan atas kebebasan beragama menurut Abd Moqsith Ghazali juga diakui dalam Islam dengan didasarkan pada teks Q.S. Al-Baqarah ayat 256. Sekalipun hadis man baddala dinahu faqtuluhu benar datang dari Nabi, sebagaimana dikatakan Abd Moqsith Ghazali, dalam catatan sejarah Nabi sendiri tidak pernah menerapkan hadis tersebut. Lanjut, Abd Moqsith Ghazali berpendapat bahwa terkait persoalan itu setidaknya ada tiga kemungkinan.
Pertama, mungkin pada zaman Nabi, persisinya di Madinah, tidak ada orang Islam yang pindah agama ke agama lain sehingga hukum bunuh tidak perlu diterapkan. Kedua, mungkin saja pada zaman Nabi ada beberapa orang Islam yang pindah agama, tapi Nabi tidak menerapkan hukum yang demikian. Ketiga, mungkin pada zaman Nabi sudah ada beberapa orang pindah agama, tapi hadis tersebut sengaja tidak dilaksanakan karena ia dimaksudkan untuk menjaga ketentraman dan stabilitas umat Islam yang baru beberapa tahun memeluk agama Islam.
Menurut Ibn Rusyd penerapan hadis tersebut bukan kepada orang yang keluar dari Islam (pindah agama), tetapi kepada mereka yang murtad yang hendak memerangi kaum Muslimin. Senada dengan Ibn Rusyd, Maulana Muhammad Ali, menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadits man baddala dinahu faqtuluhu ialah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam, lalu bertempur melawan kaum muslimin.
Sementara sebagaimana dikatakan Yûsuf Qarad}âwî, Umar b. Khat}t}âb memahami hadis man baddal dînah faqtulûh adalah dalam kapasitas sebagai pemimpin umat sekaligus kepala negara. Bukan dalam kapasitasnya menyampaikan suatu fatwa atau menyampaikan wahyu dari Allah yang harus diikuti dalam segala situasi. Pada bagian lain, al-Bukhârî meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. menolak permintaan izin dari ‘Umar untuk membunuh ‘Abd Allâh ibn Ubay ibn Salûl, seorang munafk yang memprovokasi golongan Muhajirin dan Ansar agar saling berperang. Beliau bersabda: “Jangan, nanti orang akan berkata bahwa ia (Muhammad Saw.) membunuh sahabatnya sendiri”.
Dalam konteks dewasa ini, di mana kebebasan beragama telah diakui mayoritas negara-negara besar di dunia atau masyarakat dunia, bukan tidak mungkin polemik justru akan muncul ketika hukuman mati diterapkan kepada kaum Muslim yang menginginkan memeluk agama lain. Tidak saja haknya yang dijamin oleh negara sebagai warga negara yang sah, melainkan juga justru bertentangan dengan prinsip dasar Al-Quran sebagai syariat utama Islam. Nabi saw. sendiri sebagaimana tercantum dalam beberapa riwayat justru tidak pernah melakukan praktik sebagaimana tertuang dalam hadis tersebut melainkan justru sebaliknya.
Sebagaimana dikatakan Syed Hossein Nasr, pada dasarnya Nabi saw. adalah orang yang penuh kasih sayang dan kemurahan hati. Hal ini tampak jelas ketika Nabi saw. menundukkan kota Makkah, ketika Nabi Saw. telah berhasil menaklukkan orang-orang yang memusuhinya, tidak terpikir olehnya untuk mengadakan pembalasan bahwa sebaliknya Nabi Saw. mengampuni mereka.



