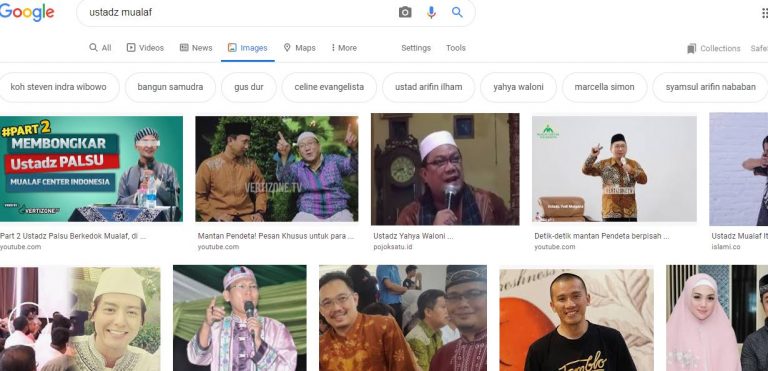
Pada setiap musim penerimaan santri baru seperti bulan Syawal sekarang ini, saya tebak tak sedikit adik-adik calon santri yang menjumpai pengalaman manis-menyebalkan sebagaimana dahulu saya alami.
Saat itu, sesaat setelah hasil kelulusan SD dibagikan, ibunya seorang teman tiba-tiba mendekati saya dan bertanya: “Nak, kamu mau lanjut ke SMP mana? Kalau daftar ke SMP anu, kamu bisa barengan lagi lho dengan anak saya.” Ibu itu lalu memasang emotikon senyum di wajahnya.
Saya pun tersenyum membalas. Sedetik kemudian, saya jawab pertanyaan sang ibu dengan mantap: “Sepertinya saya nggak lanjut ke SMP itu, Bu. Saya mau mondok.”
“Lho, maksudnya mondok di asrama? Di pesantren?”
“Hehe. Iya, Bu, di pesantren.”
“Lho, kenapa mondok? Padahal NEM kamu kan cukup buat masuk ke SMP negeri yang favorit. Kamu disuruh orang tua, ya?” Ibu itu setengah menggugat.
“Hehehe. Nggak, Bu.” Sambil berusaha tetap ramah, saya coba untuk menegaskan lagi keputusan saya: “Itu kemauan saya sendiri, kok. Hehehe.”
“Ooo gitu. Punya cita-cita jadi ustaz, ya?”
Hah???
Saya tercengang. Ternyata, begitu mudahnya bagi seorang ibu penanya itu untuk mengasosiasikan antara “memilih studi di pesantren” dengan “cita-cita menjadi seorang tokoh agama”.
Padahal, melanjutkan pendidikan di pondok pesantren sama sekali tak berarti mencalonkan diri menjadi tokoh agama ataupun kiai. Mendaftarkan diri menjadi seorang santri tak pernah mengandung makna lebih selain menjadi santri itu sendiri. Meski, tentu saja, berproses menapaki jalan pendidikan ala santri tak pernah sesederhana membayangkannya.
***
Sebagaimana telah saya duga, momen-momen menyebalkan memang tak pernah ada habisnya. Sepanjang umur menjadi santri di pesantren, dan barangkali hingga kini dan seterusnya, saya banyak menghadapi stereotip-stereotip sebagaimana tergambar pada pertanyaan ibu tadi.
Ibu itu tidak sendirian. Ia mewakili suara orang-orang secara umum. Mulai dari teman, tetangga, temannya tetangga, tetangganya teman, saudara dekat, saudara jauh, kenalan baru, dan mungkin juga Anda, rata-rata, di dalam pikiran orang-orang tersebut terdapat stereotip yang kurang lebih serupa dengan miliknya si-ibu-penanya-menyebalkan tadi itu.
Tapi di sisi lain, saya di sini juga tidak sendiri. Apa yang saya utarakan mewakili suara-suara teman santri kebanyakan. Ah, jika saya keliru mengatakan ini sebagai “suara kebanyakan santri” secara umum, minimalnya, tulisan ini mewakili lirihan batin kebanyakan teman-teman santri yang pernah keceplosan curhat soal ini kepada saya. Bhahaha.
Ini serius. Setelah bertahun-tahun nyantri, jejaring pertemanan kesantrian saya pun semakin meluas, referensi saya mengenai corak santri maupun tipe pesantren juga berkembang. Seiring dengan itu, jam nongkrong saya semakin tinggi. Di sela-sela nongkrong-ngopi itulah, biasanya, sesi curhat tak pernah terlewatkan.
Dari sesi curhatan bersama sobat sekamar, teman sekomplek pesantren, atau malah dengan sesama santri yang tak saling kenal, saya mendapati bahwa stereotip-stereotip itu ternyata sudah menjadi keluhan umum bagi kaum seperti kami.
Ooo, bukan. Tentu saja keluhan itu tidak berarti bahwa kami tak punya keinginan untuk mengabdi pada masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Tentu saja tidak demikian.
Kami, atau setidaknya saya, sebenarnya tidak lagi bermasalah ketika bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan semacam yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi. Sepanjang itu benar-benar dimaksudkan bertanya, atau ungkapan doa dan harapan, saya baik-baik saja. Yang menjadi titik keluh dan masalah adalah, ketika harapan itu bertransformasi pada tingkatannya yang lebih lanjut. Yaitu, ketika ia berubah menjadi tuntutan!
Tepat di titik itulah saya ngilu.
***
Saya sadar. Meski hubungan di antara santri dan kiai itu bukanlah hubungan sebab-akibat, tapi terma “santri” dan “kiai” memang tak pernah bisa dipisahkan.
Lebih jauh dari itu, saya malah sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa syarat mutlak menjadi kiai adalah pernah mengalami jadi santri. Sehingga, orang-orang hebat yang menyandang gelar “tokoh agama Islam”, seketika akan luntur ketokohannya itu di mata saya apabila ketahuan tak pernah nyantri.
Namun demikian, sebagaimana kukuhnya saya mengatakan bahwa seorang kiai itu harus merupakan alumnus pesantren, begitu pula saya kukuh dengan pendapat saya bahwa lulusan pesantren tak harus menjadi kiai.
Santri berhak menjadi apa saja. Segala stereotip yang diarahkan kepada santri, yang kemudian berlanjut menjadi tuntutan agar santri harus menjadi sosok kiai, jelas merupakan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam berpikir.
Khususnya pada konteks masa kini, ketika mencari sosok kiai di sebuah tempat tertentu bukan lagi pekerjaan yang sulit. Kiai, ustaz, ulama, tengku, ajengan, atau apapun itu sebutannya, sudah banyak tersebar di mana-mana. Apalagi di medsos. Eh.
Dengan kondisi demikian, maka menambah lagi jumlah kiai, menurut saya, tidak menjadi kebutuhan mendesak pada saat ini. Lagi pula, tidak semua santri punya minat dan kompetensi untuk menjadi tokoh agama.
Hal itu juga tak dapat dilepaskan dari corak pondok pesantren pada hari ini yang semakin beragam. Apabila kita amati, di sana terdapat corak pesantren yang memberikan pengajaran keagamaan dengan bobot yang lebih berat dan mendalam. Pesantren dengan corak seperti ini, biasanya memang bertujuan kaderisasi ulama.
Namun di samping itu, ada pula tipe pesantren yang fokus mendidik dasar-dasar keagamaan saja. Pesantren dengan corak seperti ini, rata-rata mencukupkan diri dengan materi-materi pengajaran keagamaan yang esensial, diseimbangkan dengan pendidikan umum yang memang sudah menghabiskan banyak waktu.
Nah, sependek pengamatan saya, justru pesantren dengan tipe kedua inilah yang mendominasi jagat raya hari ini. Persebaran alumninya juga lebih luas tersebar di mana-mana.
Dari alumni tipe pesantren yang dominan ini, jelas saja kita tak dapat memasang harapan yang muluk-muluk. Mampu menjadi pribadi yang saleh, bertanggung jawab, bermasyarakat dengan baik, serta konsisten melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan segala tata caranya yang benar, begitu saja sudah merupakan indikator keberhasilan pendidikan yang mereka tempuh di pesantren.
Malah, apabila kita renungkan kembali, bukankah keberadaan pesantren—secara mendasar—itu memiliki tujuan dan fungsi utama sebagai pengawal keberagamaan masyarakat?
Dari situ, kita lantas bisa mengetahui bahwa lulusan pesantren dengan corak “esensial” tadi itu saja, sebenarnya sudah cukup mengindikasikan terpenuhinya tujuan dan fungsi keberadaan pesantren. Pada saat yang bersamaan, kita juga akhirnya sadar bahwa menuntut semua lulusan pesantren menjadi tokoh agama merupakan tindakan yang naif, muluk-muluk, juga tidak relevan.
Nah, di titik ini, kita mungkin bisa mempertanyakan sesuatu: Apabila lulusan pesantren saja tidak semuanya bisa diharapkan menjadi kiai, lalu bagaimana dengan lulusan ekskul rohis? Apa kabarnya pelajar agama jalur internet? Apakah mereka bisa kita andalkan sebagai penyampai ajaran keagamaan yang otoritatif dan terpercaya?
Waduuuuuuuuhh!!



