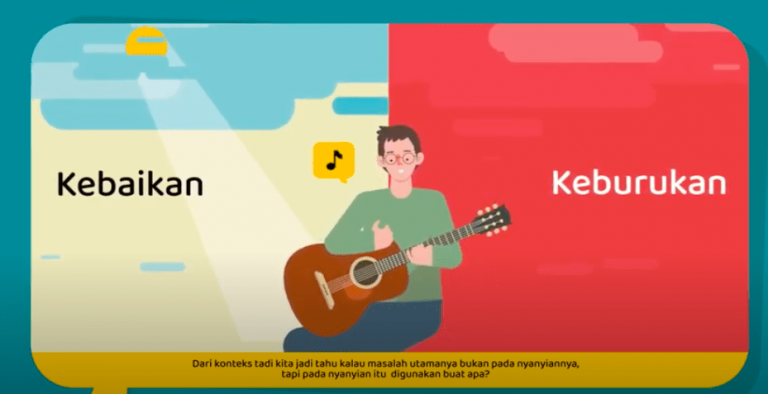
Saya tidak suka dengan konsep labelisasi halal di beragam benda. Dari awal kemunculannya saya memang tidak suka dengan konsep halal-haram yang dilakukan sangat agresif itu. Bukan karena status halal atau haram itu tidak penting, itu penting banget nget nget. Yang jadi problem adalah mengapa melibatkan pendekatan sains dalam penentuan makanan/benda/hal bersifat halal atau haram.
Semoga dugaan saya tentang pelibatan sains yang ditulis belakangan ini salah ya, soalnya akhir-akhir ini memang tidak cukup intens mengikuti regulasinya. Eh tapi kalau masih ada, begini alasan ketidaksukaan saya.
Domain objek pengamatan hal halal-haram dengan sains itu beda. Mudahnya, kalau kita buka saja sekilas keterangan yang diberikan Prof. Ahmad Tafsir di bukunya Filsafat Ilmu itu, kita akan mendapatkan keterangan bahwa sains itu mendekati objeknya dengan jalur empiris dan rasional. Nah sementara domain agama tidak memerlukan pendekatan empiris.
Dalam kita mempercayai Nabi Muhammad benar-benar pernah isra mi’raj, kita sebagai umat muslim ndak perlu secara langsung melihat bahwa Nabi Muhammad memang naik ke langit dan berkelana bersama burak. Kita juga tidak perlu tahu secara langsung pertemuan-pertemyan nabi dengan malaikat dalam menyampaikan wahyu. Tentu itu tidak dapat diwujudkan juga.
Sementara sains itu wajib pakai empiris, wajib terindra, ndak bisa kita tiba-tiba berkelakar tanpa bukti empiris. Hawong berkelakar menemukan vaksin tapi tidak pernah ada bukti publikasi risetnya saja bisa jadi problem. Apalagi basis penelitiannya jelas-jelas tidak empiris.
Sementara dulu saya pernah mendengar dari beberapa sumber kalau pendekatan dalam meninjau suatu makanan bersifat halal atau haram adalah dengan pendekatan empiris, tentu ini kontradiktif. Misalnya kita menilai minuman itu halal atau tidak adalah dengan memastikan minuman itu tidak mengandung alkohol, dideteksi dengan mencari beberapa gugus -OH. Lalu ada lagi, kita menilai makanan itu halal atau haram dari tidak ditemukannya spesies -dan turunanya- apapun yang mengandung hewan-hewan haram dimakan, misalnya babi, anjing, buaya, atau hewan-hewan haram lain.
Terma halal haram tidak sekaku itu. Lawong kita bisa lo makan babi di situasi tertentu. Babi tidak selalu hukumnya haram. Ya contoh paling common adalah kalau kita tersesat di hutan, satu-satunya makanan yang tersisa tinggal babi, dan kalau daging itu tidak dimakan, kita mati. Kita bisa lo makan daging itu untuk bertahan hidup, tentu tidak untuk membuat kenyang. Situasi seperti itu, kalau didekati dengan sains, ya akan tetap saja hasilnya adalah haram. Wong yang dites juga tetap mengandung babi.
Selain itu, yang bikin geleng-geleng kepala adalah maraknya halal yang disandingkan dengan sesuatu yang tidak kategori makanan. Seperti kerudung halal, kulkas halal, bahkan sampai mall halal.
Sejak kapan halal disandingkan pada sesuatu yang tidak dikonsumsi? Padahal sebenarnya islam sudah punya domain sendiri pada benda-benda yang tidak dikonsumsi, bukannya halal, tapi toyip atau bersih. Kan jelas tuh ayatnya, mengkonsumsilah yang halal dan baik.
Jadi penggunaan halal di kerudung, kulkas dan mall, itu untuk beneran mengedukasi warga soal status kehalalan atau memang kata toyib “belum laku” untuk dijadikan media promosi?
Sadar atau tidak sadar, kegemaran kita pada label halal-haram ini memiliki efek residu, yakni meningkatkan kebencian pada sebagian hewan yang dicap sebagai hewan haram.
Tidakkah kita ingat kejadian di depok beberapa bulan lalu dan di bekasi belakangan ini, ketika warga dengan beringaasnya berburu hewan babi yang diduga babi ngepet.
Nasib yang sama pun terjadi pada anjing. Berapa kali kita meyaksikan video viral beberapa warga menyiksa anjing. Ada yang mengikatnya dengan keras, ada yang meminuminya miras, ada yang membantingnya, sampai ada yang memburunya.
Sementara, kita juga tidak kurang-kurang anjuran dan cerita bahwa anjing adalah hewan yang dapat dijadikan wasilah untuk sampai ke surga atau mendapatkan pahala seperti hadits berikut:
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang pria sedang dalam perjalanan dan dia menderita kehausan yang sangat. Ia mendapat sebuah sumur, maka ia menuruninya dan mengambil minum. Lalu dia keluar dan melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan hingga menjilati tanah.
Pria itu berkata, ‘Sungguh anjing ini telah menderita kehausan seperti yang telah aku rasakan.’ Dia turun kembali ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, kemudian dia memberi anjing itu minum. Allah bersyukur (menghargai) atas perbuatan pria itu, lalu melimpahkan maghfirah padanya.” Mereka, para sahabat, lantas bertanya, “Ya Rasulullah, apakah terhitung pahala sedekah (sebab menolong) hewan?” Nabi berkata, “Ya. (Tindakan menolong) terhadap setiap makhluk dengan hati yang masih basah (hidup) itu, (maka) terdapat pahala amal.” (Sahih al-Bukhari hadits ke 5663 pada kitab Etika, bab mengasihi manusia dan binatang; Sahih Muslim hadits ke 2244 pada kitab tentang keselamatan, bab keutamaan memberi minum dan makan pada binatang muhtaromah)
Dalam beragam cerita, bahwa beberapa sahabat nabi juga berkawan dengan anjing, selain itu Gus Baha juga pernah bercerita bahwa anjing adalah hewan yang cerdas dan dipuji-puji. Ia hewan yang dapat dilatih dan memiliki manfaat.
Ada yang bilang “tapi anjing kan najis, menyentuhnya kita harus bersuci 7 kali dan salah satunya harus dengan debu”
Orang bijak sudah ada yang menjawab “memang, itulah bedanya orang yang tau cara bersuci dan cuma teori”
Namun, saya memang menduga betul bahwa ketidaksukaan kita pada hewan semacam babi atau anjing adalah karena stikma yang dilekatkan pada dua hewan ini. Stigma yang mengatakan bahwa mereka kotor dan najis. Diperparah dengan labelisasi yang membuat kisa semakin beringas pada mereka.
Sehingga pada akhirnya kita perlu mengurai betul apa sebenarnya yang menjadi cikal carut-marut yang terjadi. Kenapa kita jadi bengis pada sebagian hewan padahal banyak sahabat mencontohkan perbuatan yang baik-baik dengan semua hewan. Karena yang basah, tetap terdapat pahala saat disayangi.
Wallahu A’lam



