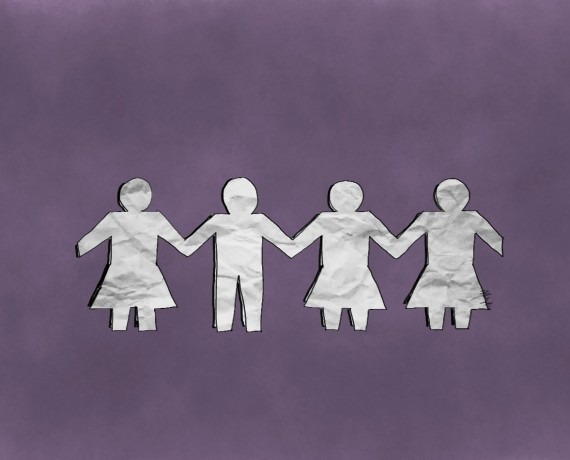
Sejujurnya saya tak tertarik untuk memikirkan pernikahan, tapi ntah kenapa, saya pernah berada di fase ketika saya merasa begitu menggebu untuk menikah dengan laki-laki beristri. Tunggu, sebelum terlalu absurd, atau disambar penghakiman, biarkan saya ceritakan bagaimana awal mulanya.
Rasa-rasanya, ungkapan “menikah adalah menuntaskan separuh dari perkara agama” mulai mendesak untuk diperhitungkan dan segera direalisasikan. Ini terjadi saat saya masih menjadi perempuan dengan girah ‘hijrah’ penuh.
Seperti kebanyakan orang, tentu bayangan pernikahan bagi saya adalah bersatunya sepasang kekasih lewat media ijab qabul. Namun, tak ada yang dapat menentukan ke mana arah angin.
Keinginan saya untuk menikah dengan hukum Islam yang begitu kental ini pun terfasilitasi dari beberapa kali saya mengikuti kajian pra-nikah yang kala itu cukup melimpah ruah. Informasi tentangnya, saya dapatkan dari media sosial, Instagram. Kebanyakan pembicara di dalamnya adalah pasangan nikah muda yang kemudian memutuskan menikah atas dasar agama.
Salah satu moment yang saya paling ingat adalah ketika Anisa Rahma (mantan personil Cherrycelle) menjadi pembicara bersama suaminya. Diceritakan, ia yang telah menempuh jalan hijrah kemudian bertemu dengan Dito dalam sebuah seminar pra-nikah. Sejurus kemudian, keduanya memutuskan ta’aruf. Amat mengharukan laksana film romansa komersil, pokoknya couple goals banget.
Lambat laun, semakin saya menekuni video ceramah keagamaan di Youtube, saya semakin terdorong untuk menjadi perempuan yang berbagi suami dengan orang lain. Sekali lagi, ini terjadi saat girah ‘hijrah’ saya sedang membuncah, apalagi dorongan untuk menerapkan ‘syariat Islam’ begitu lekat dan meledak-ledak dalam laku keseharian saya.
Lebih dari itu, pandangan saya perihal pernikahan ideal mulai bergeser ke konsep poligami, di mana seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari satu istri. Kala itu, saya cukup tersihir oleh narasi para penceramah yang bilang bahwa hukum poligami itu sunah karena Rasul juga poligami, lalu tentang ketimpangan jumlah perempuan dan laki-laki di dunia, hingga stereotipe nafsu laki-laki yang konon tak dapat dipenuhi hanya oleh seorang perempuan.
Telak, rentetan alasan yang disampaikan para penceramah itu memang terdengar masuk akal dan memiliki urgensi tingkat tinggi. Dengan pemahaman yang sekali jadi alias instan akan esensi poligami, saya pun secara mantap memutuskan ingin menjadi madu ataupun dimadu.
Meski begitu, apa yang sempat saya yakini sebagai jalan kemuliaan seorang perempuan itu sebetulnya memunggungi nurani saya. Ya, hati kecil seorang perempuan seperti saya tentu tak menampik bahwa akan ada luka yang senantiasa basah jika mengambil jalan poligami.
Membayangkan laki-laki yang dicinta membagi kasih dengan perempuan lain kok ya begitu getir terasa. Belum lagi membayangkan betapa sedihnya Bapak dan Ibu yang membesarkan saya sedari bayi dengan harapan bahwa suatu hari, anak perempuannya akan bahagia di masa depan, tapi berakhir dengan berbagi suami. Apakah anak-anakku kelak akan mendapat kasih sayang yang cukup dari seorang ayah? Ayah yang mesti membagi kasih pada anak di keluarga yang lain? Sungguh bukan hal mudah, gunungan luka begitu berat dalam bayangan.
Hanya saja, segenap jeritan hati itu seolah telah siap diberondong dengan bejibun dalil dan spekulasi tafsir, bahwa agar dapat menuju ridho-Nya, itulah harga yang mesti ditebus oleh seorang perempuan untuk sebuah jaminan surga. Lagi pula, setiap hal di dunia ini tidaklah diciptakan melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Jadi, saya pikir, begitulah tujuan dari sebuah pernikahan poligami.
Belakangan, jalan yang mengantarakan saya pada penerimaan poligami ternyata berbalik menjadi petunjuk yang membuat saya justru berhenti memimpikannya. Sebuah video berujudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga” menampilkan sebuah keluarga praktisi poligami dengan dua orang istri di dalamnya. Video itu juga menghadirkan seorang perempuan yang kontra terhadap poligami.
Kedua sudut pandang bersebrangan itu ditutup dengan penjelasan Nina Nurmalina, seorang akademisi Islam yang menghabiskan belasan tahun utnuk meneliti isu poligami. Dari penuturannya, dalam QS. An-Nisa ayat ke-3 yang banyak menjadi dalil rujukkan untuk berpoligami, justru merupakan bukti dari upaya Islam dalam merevolusi budaya poligami yang ugal-ugalan di era sebelum Islam.
Diceritakan, seorang laki-laki pada masa itu dapat memiliki puluhan Istri. Bahkan menurut Nina, Islam adalah agama yang menganjurkan monogami. Ini dapat dibuktikan dari penghujung ayat tersebut yang berbunyi “… jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja…”
Maka lalu saya renungkan lagi bagaimana para publik figur bisa berpoligami dan begitu tega menggunakan dalih bahwa poligami merupakan alternatif jika perempuan tak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis laki-laki.
Lebih dari itu, perempuan terasa seperti objek seksual yang jika sudah tak berfungsi dapat diganti. Perempuan seolah menjadi barang bukti maskulinitas laki-laki dengan segenap tuntutan tanggungjawab atas hidup sang perempuan.
Pertanyaannya, apakah seseorang laki-laki akan mampu berlaku adil, bahkan dalam tataran membagi perasaannya? Lalu jika mengatas namakan sunnah karena Rasul melakukannya, maka dapatkah laki-laki setia pada istri pertamannya hingga akhir hayat, seperti setianya Rasul pada Sayyidah Khadijah?
Wa ba’du, penentangan yang lahir dari buah pikir saya saat ini adalah bagian dari keresahan seorang perempuan. Bayangan kehidupan dalam konsep pernikahan dengan banyak sekali risiko dan luka batin yang rentan dialami perempuan membuat saya merasa begitu sedih. Jika poligami adalah harga yang mesti dibayar demi menebus surga, maka di mana letak wujud cinta itu?



