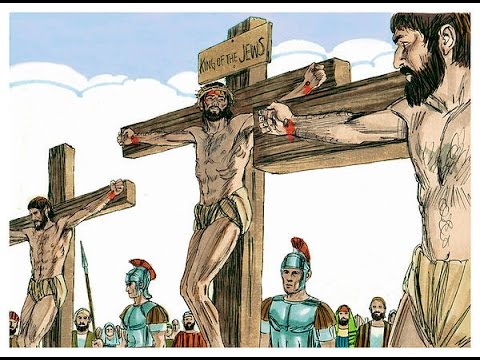
Mengulas dua sosok penting dalam agama lewat film bukan barang asing. Minggu lalu, saya menyempatkan dua film berkaitan dengan agama Katolik dan Protestan, yakni “Conclave” dan “Mary.”
Film terakhir ini menggambarkan kehidupan Bunda Maria, sedangkan Conclave mengulik prosesi pemilihan Paus di Vatikan.
Sepertinya kedua film sengaja dirilis berdekatan dengan perayaan Natal untuk menarik perhatian penganut kedua agama tersebut.
Kemunculan sosok-sosok penting dalam sebuah agama di sebuah film bukan barang asing.
Apalagi, tidak semua agama yang melarang visualisasi atau personifikasi sosok-sosok penting tersebut, seperti Nabi, orang suci, hingga Malaikat.
Saya kurang mengetahui bagaimana aturan dalam agama Katolik dan Protestan terkait penggambaran atau representasi utuh tokoh-tokoh penting mereka.
Sebab, jika kita berkaca kala film Majid Majidi rilis, kontroversi awal adalah soal personfikasi atau penggambaran utuh sosok Nabi Muhammad. Bahkan, hampir seluruh penolakan langsung mengabaikan banyak sisi atau nilai lain yang dihadirkan lewat film Film Muhammad: The Messenger of God.
***
Kedua film tentu bukan pengalaman pertama saya menyaksikan bagaimana sosok penting atau prosesi sakral dalam agama Katolik dan Protestan.
Terakhir, saya menyaksikan film “Two Popes.” Bahkan, beberapa film yang saya tonton juga mengulik hal-hal cukup kontroversi di kedua agama tersebut, seperti “Da Vinci Code.”
Awalnya, film Mary sebenarnya tidak terlalu spesial bagi saya yang Muslim, karna penggambaran sosok Bunda Maria masih standar. Namun, pasca saya menonton kembali, saya baru menyadari bahwa kalimat pengantar yang disampaikan lewat suara adalah kunci.
Film Mary menghadirkan interpretasi yang memukau tentang kehidupan Maria, ibu Yesus, melalui sudut pandang yang jarang diangkat.
Narasi utama yang ditonjolkan dalam film Mary adalah sosok Bunda Maria sendiri. Jadi pusat narasi film ini adalah perjalanan dari masa kecil Bunda Maria di Nazaret hingga momen monumental kelahiran Yesus, dengan menciptakan narasi yang mencoba menghidupkan kembali karakter historis dan spiritual yang berpengaruh ini.
Untuk itu, Mary adalah film yang tidak hanya menceritakan ulang kisah Bunda Maria yang telah dikenal, tetapi juga menggali lebih dalam aspek kemanusiaan sosok suci di Katolik dan Kristen.
Unsur kemanusiaan inilah yang memberikan pengalaman baru, di mana sosok utama, yakni Bunda Maria, seringkali hilang atau dilupakan dalam linimasa sejarah.
Dinamika sosial, politik, hingga urusan agama pun digambarkan hingga kita bisa “sedikit” memahami bagaimana kondisi kala Bunda Maria hidup dan melahirkan sosok Yesus.
Adapun film Conclave menawarkan pandangan mendalam ke dalam proses pemilihan paus, sebuah momen sakral dalam tradisi Katolik, namun dibalut dengan ketegangan politik, ambisi, dan konflik moral.
Conclave membawa kita sebagai penonton ke dalam dunia tertutup dan penuh rahasia di balik dinding Kapel Sistina. Bahkan, saya cukup terkejut kala menyaksikan plot twist di bagian akhir film ini.
Conclave tidak sekedar sebuah film drama religius, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pertautan antara kekuasaan, moralitas, dan iman.
Film ini menyoroti bagaimana ambisi manusia dapat bercampur dengan nilai-nilai spiritual dalam institusi yang seharusnya suci. Tema ini menjadi relevan di era modern, di mana Gereja Katolik sering menghadapi kritik terkait transparansi, politik internal, dan integritas moral.
Diadaptasi dari novel karya Robert Harris, film Conclave menyajikan gamblang bagaimana prosesi sakral di sebuah agama bisa berkelindan dengan sisi kemanusiaan, berisi dengan ketulusan, kejujuran, hingga kesalehan, namun juga penuh dengan intrik, tawar-menawar, hingga kesepakatan-kesepakatan.
***
Dari Conclave dan Mary, saya sebagai muslim adalah orang luar yang menyaksikan sisi (cukup) dalam di agama lain. Dengan kata lain, film ini, khususnya bagi penonton non Katolik dan Protestan, berkelindan dengan apa yang disebut dalam kajian sosial dengan “Yang Liyan.”
Istilah “Yang Liyan” biasa merujuk pada keberadaan individu atau entitas lain yang berbeda dari “diri” (subjek). Dalam konteks filsafat, “Yang Liyan” tidak hanya sekadar orang lain (individu), tetapi juga melambangkan keberbedaan, keasingan, atau yang berada di luar pusat identitas diri kita.
Dengan kata lain, sebagaimana disebut oleh Edward Said, “Yang Liyan” selalu tidak dipahami sebagaimana adanya, melainkan melalui kacamata stereotip yang diciptakan oleh subjek untuk menegaskan superioritasnya. Artinya, kita seringkali memandang atau menjelaskan
Film Mary dan Conclave memang menyimpan sisi kontroversinya, dengan beragam alasan dari kebebasan berkarya hingga urusan narasi agama. Namun, kita sebagai penonton tentu bisa sedikit menangkap narasi kemanusiaan yang berkelindan dengan sebuah agama, yang sering diklaim suci.
Padahal, prosesi paling suci pun selalu beririsan dengan sisi kita sebagai manusia.
Terlebih, kita bisa belajar bahwa agama juga menyimpan banyak hal yang seringkali luput kita perhatikan. Selain itu, di sisi lain, agama juga tidak boleh dikonstruksi sembarangan.
Pengalaman kita menonton kedua film kemanusiaan yang penuh alpa dan kelemahan dalam menghadirkan agama, tentu bukan membuka ruang untuk kita serampangan menuduh agama lain.
Emmanuel Levinas, filsuf, menggambarkan “Yang Liyan” sebagai yang melampaui diri kita, sebagai misteri yang tidak pernah selesai dipahami. Jadi, apa yang digambarkan dalam film Mary dan Conclave adalah misteri yang tidak akan pernah kita bisa pahami sepenuhnya. Untuk itu, kita seharusnya menghindari stereotipe atas agama lain. Begitu.
Fatahallahu alaina futuh al-arifin



