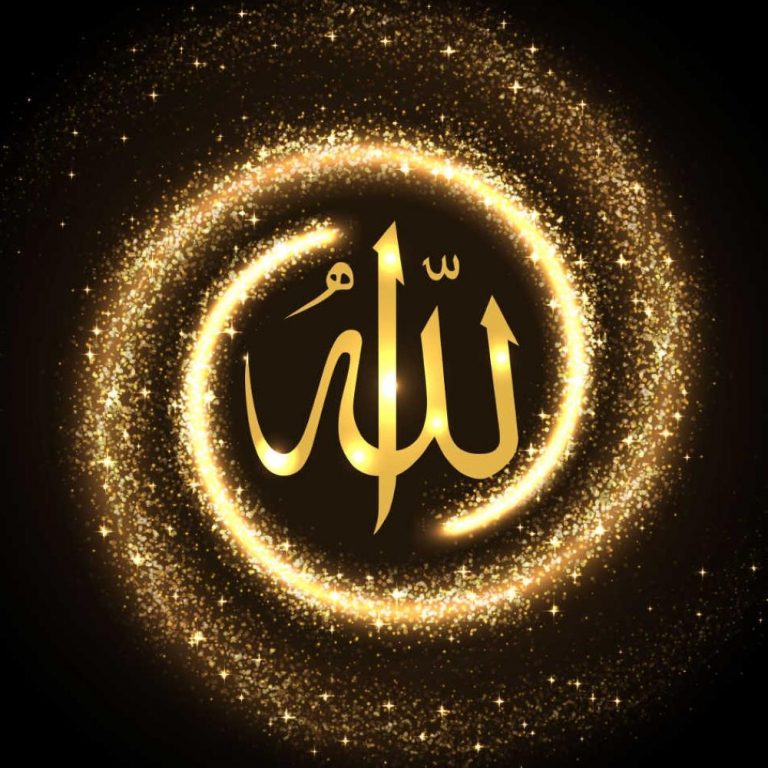
Dalam Asmaul Husna, sering kita temukan bahwa Allah memiliki wujud yang paradoksal; ada al-awwal dan al-akhir (yang Maha Awal dan yang Maha Akhir), ada al-Zahir dan al-Bathin (yang Maha Lahir dan Maha Bathin). Allah menyatakan dalam berbagai ayat Alquran bahwa Dia adalah Zat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang namun di sisi lain Allah juga menyebut dirinya sebagai Zat yang Maha Pedih azab-Nya.
Dalam Asmaul Husna disebutkan bahwa Allah itu Maha Pendendam. Ini artinya Allah itu tidak akan lupa dan tidak akan lalai dari kejahatan orang, sehingga Dia pasti akan membalas-Nya. Atas dasar ini, kita semestinya memahami Allah secara keseluruhan dan tidak boleh memahami-Nya secara parsial.
Jika kita memahami Allah SWT secara parsial, maka kita tidak akan memperoleh gambaran dan pemahaman yang tidak utuh dengan segenap konsekwensi yang ada.
Sebagai contoh, kalau kita hanya memahami Allah sebagai Zat Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kita akan mengalami kelembekan secara moral. Hal demikian karena kita selalu mempersepsi Allah sebagai yang Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita dan memaafkan semua kesalahan kita.
Demikian juga sebaliknya, kalau kita memahami dan mempersepsi Allah sebagai Pemberi azab yang pedih, Pendendam dan sebagainya, kita akan kehilangan harapan kepada Allah. Persepsi demikian akan berbahaya sekali padahal Allah adalah tempat kita bersandar. Hanya Allah sajalah tempat kita menggantungkan semua harapan. Kalau kita tidak menggantungkan harapan kepada Allah, kepada siapa lagi kita harus menggantungkan harapan.
Oleh karena itu, Ibnu Arabi mengajarkan kepada kita sifat-sifat paradoksal dari kebenaran dan kita harus melatih dari untuk melihatnya. Menurut Ibnu Arabi dengan adanya kemampuan menangkap kebenaran yang bersifat ilahi ini, kita menjadi parsial dan universal sekaligus.
Artinya, kita adalah individu dari berbagai individu al-mawjudat namun di saat yang bersamaan pula kita ini adalah mawjudat itu sendiri. Di satu sisi, kita menyadari hakikat diri kita sebagai individu namun di sisi lain kita menyadari bahwa individu ini lebur dalam keseluruhan. Tentu hal demikian tidaklah paradox. Oleh karena itu, Ibnu Arabi mengatakan bahwa tauhid ialah usaha untuk meniadakan dualisme. Ini artinya kalau kita masih melihat, mempersepsi, menilai sesuatu dengan dua unsur yang paradox itu, berarti sebetulnya kita belum benar-benar bertauhid.
Maksudnya kalau kita hanya memahami Allah hanya sebagai al-Ghafur ar-Rahim saja, kita masih belum bertauhid. Ini artinya sebenarnya kita memilih Tuhan sesuai dengan hasrat dan kehendak kita, atau sebaliknya, gaya hidup kita mempengaruhi persepsi kita terhadap Tuhan. Misalnya kalau dalam hidup ini orientasi kita sangat legal-formalistik (benar-salah), Tuhan akan kita persepsi sebagai Hakim yang kerjanya ialah mengetuk palu, menghukum benar atau salah:“ Kamu benar, masuk surga. Kamu salah, masuk neraka.” Akan tetapi kalau kita misalnya merasakan sulit sekali mencari rezeki mungkin kita akan memahami Allah sebagai Yang Maha Pemberi Rezeki dan kita meminta kepada-Nya uang atau meminta apa saja.
Oleh karena itu ajaran tasawwuf mengajarkan zikir kepada Allah melalui Asmaul Husna. Hal demikian karena dengan menyebut nama-nama Allah secara keseluruhan, kita diajarkan untuk mempersepsi Allah secara menyeluruh. Kalau kita hanya meniru Allah sebagai al-mutakabbir, kita akan terlaknat. Kita harus menggabungkannya dengan sifat lain, misalnya ar-rahim dan sebagainya. Unsur takabur kita gunakan untuk menolong harga diri. Kita tidak akan mempunyai harga diri kalau kita tidak mempunyai rasa sombong. Kendati demikian jika kelanjutannya itu betul-betul sombong, tentu sikap demikian sangatlah tidak terpuji. Inilah asma Allah yang kata Ibnu Arabi harus kita teladani secara menyeluruh dan tidak memahaminya secara setengah-setengah.



