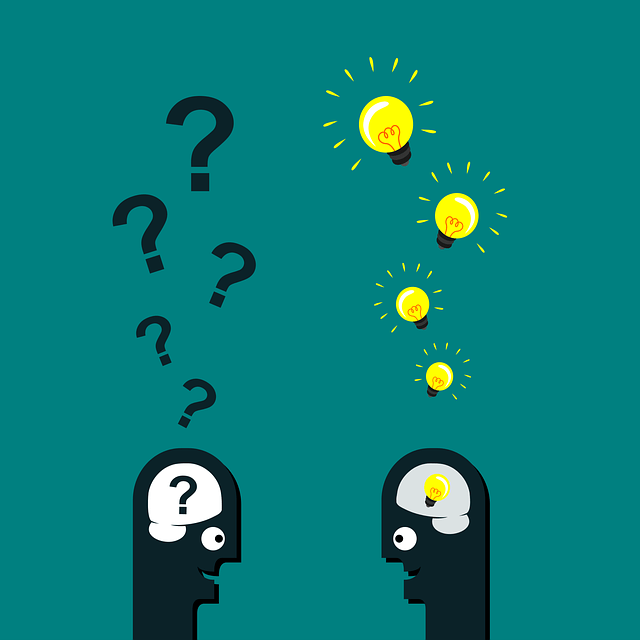
Semenjak ditinggalkan beliau Saw, tugas untuk “menghidupkan” nilai-nilai al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw diemban oleh para ulama. Karenanya, para ulama adalah pewaris para nabi. Begitu ya.
Di antara khittah manusia (termasuk para ulama) ialah berpikir. Adanya akal, pikiran, dan ilmu pada diri kita jelas merupakan karunia-Nya, untuk kita pergunakan dalam menjalankan kemaslahatan-kemaslahatan, termasuk untuk memahami dan menggali hukum-hukum Islam dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw tersebut.
Aktivitas berpikir manusia sudah pasti akan sangat majemuk tanpa batas. Banyak betul aspek yang mendasari, mempengaruhi, dan membentuknya. Mulai dari latar belakangnya, jangkauan ilmunya, kualitas pergaulannya, lingkungan hidup dan kebudayaannya, hingga kepentingan dan tujuannya.
Walhasil, alamiah belaka bila antar-orang, antar-ulama, lalu berbeda pemahaman, pendapat, pandangan, dan penyimpulan hukum terhadap ayat yang sama, hadis yang sama, bahkan kasus yang sama.
Kealamiahan ini bukanlah hal baru di era kita. Ia bahkan telah terjadi di antara para sahabat sendiri sejak Rasulullah Saw masih ada. Zaid bin Tsabit, umpamanya, bisa berbeda pendapat dengan Abdullah bin Mas’ud dalam memahami dan menyimpulkan maksud hukum dari kata “qur-un” dalam ayat 228 dari surat al-Baqarah. Zaid bin Tsabit mengartikannya “haid”, sedangkan Abdullah bin Mas’ud mengartikannya “suci”.
Dampak hukum dari dua pendapat tersebut sangat besar. Jika mengikuti pendapat “suci” (Abdullah bin Mas’ud), maka perempuan yang sedang menjalani masa iddah akan lebih pendek durasinya dibanding mengikuti pendapat “haid” (Zaid bin Tsabit). Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan suci, maka itu telah dihitung satu quru’ (suci). Sebaliknya, jika mengikuti pendapat kedua, satu quru’-nya baru dihitung setelah ia haid.
Riwayat sejenis masih sangat banyak untuk diuraikan. Bahkan, di antaranya juga pernah terjadi antara sahabat terkemuka, Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab yang masing-masing memiliki pendapat berbeda mengenai status tawanan Perang Badar. Lalu, Utsman bin Affan berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Thalib perihal apakah talak yang diucapkan tiga kali berturut-turut dianggap talak satu atau langsung talak tiga.
Seiring laju waktu, dinamika pemikiran dan keilmuan manusia (juga umat Islam) makin melimpas luas, meruah bagai bah. Dari disiplin-disiplin ilmu yang terkait langsung dengan urusan keislaman hingga tak terkait tetapi memberikan kontribusi besar bagi kekafahan penggalian hukum Islam.
Di antara disiplin umum yang menarik minat saya sejak tahun 2001 silam ialah filsafat Hermeneutika. Hermeneutika secara sederhana dimengerti sebagai filsafat penafsiran.
Pada pokoknya, ia relatif sebidang dengan metode ilmu tafsir dalam tradisi studi Islam. Di antara tokoh-tokoh besarnya adalah Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, hingga Paul Ricoeur. Sumbangsih filsafat ini kepada keilmuan studi Islam tak bisa dibantah keberadaannya—kendati cukup banyak cendekiawan muslim sendiri yang antipati.
Tentu lagi kita berutang perspektif kepada ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, kedokteran, teknologi, dan sebagainya. Artinya, studi Islam di masa kini dan depan musykil mampu menjawab tantangan zaman dan kahanan jika umat Islam sendiri tak membuka diri kepada khazanah keilmuan lain yang juga terus bergerak.
Berat sekali membayangkan pandangan Zhahiriyah (tekstualis-skripturalis) bisa menyelesaikan fenomena hidup umat Islam—bahkan akan rawan terus terbelenggu dalam klaim halal versus halal belaka tanpa kekayaan sudut lain yang lebih berspirit kerahmatan.
BACA JUGA Seluk Beluk Ushul Fiqih untuk Pemula (2): Sumber Utama Hukum Islam



