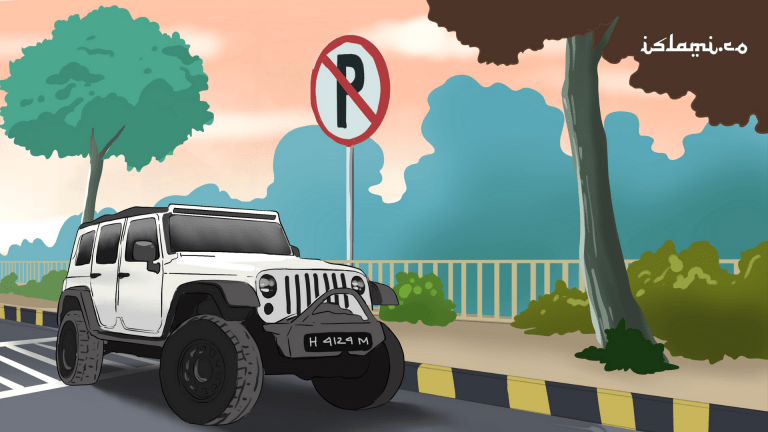
Tulisan fikih lalu lintas kali ini, akan saya mulai dengan mengutip satu kaidah populer:
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
Semua persyaratan bagi sebuah kewajiban, dengan sendirinya, juga berstatus kewajiban.
Kaidah tersebut, di dalam ranah fikih, dapat dirujuk contohnya pada status pengetahuan tentang tatacara haji bagi muslim mukalaf. Karena naik haji itu butuh ongkos, butuh jaminan kesehatan, dan harus tahu detil-detil syarat rukunnya, maka semua persyaratan di luar haji itu pun menjadi bagian yang juga wajib dilaksanakan dalam rangka pergi haji. Begitu pula dengan shalat: yang wajib itu adalah shalat, sedangkan wudu tidak. Akan tetapi, karena wudu itu menjadi bagian daripada sahnya shalat, maka status wudu pun adalah wajib.
Kaidah sederhana ini dapat dengan mudah diterapkan untuk aturan berlalu lintas di jalan raya, seperti syarat kecakapan mengemudi bagi sopir. Contohnya adalah sebagai berikut: seorang kru atau pembantu rumah tangga yang bertugas mengontrol kesiapan mesin mobil (baik itu oli atau elemen elektriknya) lalu mengeluarkannya dari garasi ke halaman rumah tidaklah wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Akan tetapi, saat ia hendak keluar dari pekarangan rumah dan masuk ke jalan raya, maka serta merta, pengetahuan tentang tertib berlalu lintas dan mengantongi SIM pun otomatis wajib diketahui oleh dirinya.
Dari mana semua pengetahuan itu ia peroleh? Melalui belajar, baik dengan cara ikut kursus maupun melalui lewat cara yang lain, seperti cara mengundang seseorang yang sudah kompatibel di bidangnya supaya membimbingnya (privat). Ia harus tahu dan paham teknik mengoperasikan kendaraan, termasuk kondisi-kondisi kedaruratan di dalam perjalanan ataupun di jalan raya, seperti cara parkir, cara menyalakan lampu sein, dlsb.
Di atas, dicantumkan syarat bahwa dia harus belajar ke lembaga kursus mengemudi atau kepada orang atau lembaga yang otoritatif (terutama di Indonesia, sebab di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, tanpa mempunyai sertifikat mengemudi dari lembaga tertentu, seseorang tidak serta merta boleh memiliki SIM atau mengemudi meskipun ia bisa. Alasannya adalah; dia tidak memenuhi kriteria umum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang di bidangnya). Syarat non-teknis dan praktis dalam mengemudi ini bukanlah mengemudi, melainkan kecakapan saja. Meskipun begitu statusnya, ia menjadi wajib diketahui karena tanpa pengetahuan tersebut, kecakapan mengemudinya dianggap batal.
Memang, antara teori dan praktiknya, di jalan raya, aturan akan menjadi lebih rumit. Kenyataan yang berlaku di lapangan acapkali tidak demikian. Seseorang cenderung abai pada hal-hal sepele sehingga menganggap bahwa mengemudi itu hanya sekadar bisa menjalankan mesin dan paham orientasi jalan. Akibatnya, banyak kita lihat seorang sopir yang terbiasa menyalakan hazard (disebut juga lampu segitiga; lampu sein yang menyala secara bersamaan, kanan dan kiri) saat melintas lurus di perempatan jalan, padahal aturannya tidak begitu. Lampu hazard hanya digunakan pada kondisi darurat, misalnya ketika parkir di tepi jalan dan separuh bodi kendaraan menginjak di atas aspal.
Mengapa kasus di atas itu banyak kita jumpai? Karena si sopir tersebut hanya melihat kebiasaan warga umum dan orang awam (yang kemampuan dan pengetahuannya tidak otoritatif) yang melakukannya begitu. Maka, dengan cara itulah ia meniru. Karena yang ditiru adalah hal yang keliru tapi dilakukan bersama-sama, bertahun-tahun, dan masif, maka kekeliruan pun seakan-akan menjadi sesuatu yang benar. Di sini berlaku lagi adagium (yang diduga bersumber kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, namun juga mengacu pada ungkapan Musthafa Sabri Afandi):
الحق بلا نظام يغلبه الباطل بالنظام
kebenaran yang tidak diorganisir akan kalah dari kebatilan yang terorganisir.
Akibatnya, sering kita (saya sendiri) melihat peristiwa (nyaris) tabrakan di perempatan jalan non-lampu-lalulintas gara-gara pengetahuan yang rumpang ini.
Nah, berdasarkan paparan di atas, mempunyai mobil atau sepeda motor tidak serta berarti boleh mengemudi/menyetir. Si empunya harus juga mempunyai kompetensi di bidang itu dengan berbagai syarat kelengkapan lainnya, seperti mengantongi Surat Izin Mengemudi yang diperoleh dari jalur yang benar, dengan maksud agar dia benar-benar memiliki kecakapan dan pengetahuan setelah lulus dari ujian/tes.
Maka, dengan demikian, jika ada anak di bawah umur yang mampu mengendalikan kendaraan dengan baik, bisa menjalankan dan mengendalikan kendaraan, status kemahirannya tetap dianggap batal, tidak sah secara payung hukum selagi dia tidak memiliki SIM dari Kepolisian karena hal itu adalah syarat pendamping yang menjadi pelengkap (seperti wudu) untuk sempurnanya syarat utama (seperti shalat). Secara teknis dia dianggap bisa, tapi secara hukum tidak. Sementara jika ada seorang pengemudi yang sudah dewasa, bisa menjalankan kendaraan sehingga dianggap cukup syarat untuk memiliki SIM dari Kepolisian, namun memiliki “cacat yang lain”, seperti kontrol emosinya jelek/temperamental, tidak paham rambu-rambu, dan berhasil mengantongi SIM lewat calo atau cara yang tidak benar, maka ia telah bersalah secara legal formal.
Fikih Lalu-Lintas: Begini Kaidah dan Dalil Bagi Pengguna Jalan Raya
Berdasarkan kenyataan yang kita lihat di lapangan (tentu saja ini tidak bersumber dari statistik), banyak orang yang mengemudi di jalan itu;
1) punya SIM, tapi tanpa pengetahuan berlalu-lintas
2) tidak punya SIM, tapi mengerti tata tertib lalu lintas dan karenanya dia hati-hati
3) punya SIM, berkompetensi, tapi serampangan dalam mengemudi
4) tidak punya SIM dan serampangan karena memang tanpa pengetahuan dan tanpa kompetensi mengemudi
Dampaknya akan fatal. Lihatlah data statistik kecelakaan di jalan raya. Kita punya angka yang sangat tinggi, masih berada di peringkat ketiga sebagai penyebab kematian. Tentu saja, penyebab kecelakaan itu—yang efek karambolnya menjadi penyebab kematian—tidak hanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan pengemudi terhadap aturan lalu lintas, melainkan juga disebabkan oleh, antara lain, kurangnya lampu penerangan jalan (dari Dinas Perhubungan), jalan rusak, kurangnya rambu-rambu, dan lain sebagainya. Mengapa semua itu terjadi? Kunci jawabannya mengerucut pada satu hal: kejujuran yang hilang.
Pengemudi tidak jujur; nyopir tidak punya SIM. Mungkin juga banyak (oknum) Kepolisian yang tidak jujur, memberikan SIM kepada orang yang tidak layak mendapatkannya; boleh jadi Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak jujur, lampu jalan yang mestinya dipasang di jalan, malah dipasang di rumah-rumah pribadi; atau jalan rusak yang mestinya ditambal sulam, dibiarkan rusak parah karena dananya disalurkan untuk kepentingan pribadi. Begitulah, meskipun kecelakaan lalu lintas adalah penyebab angka kematian terbesar, tapi hilangnya kejujuranlah yang menjadi hulu penyebabnya.



