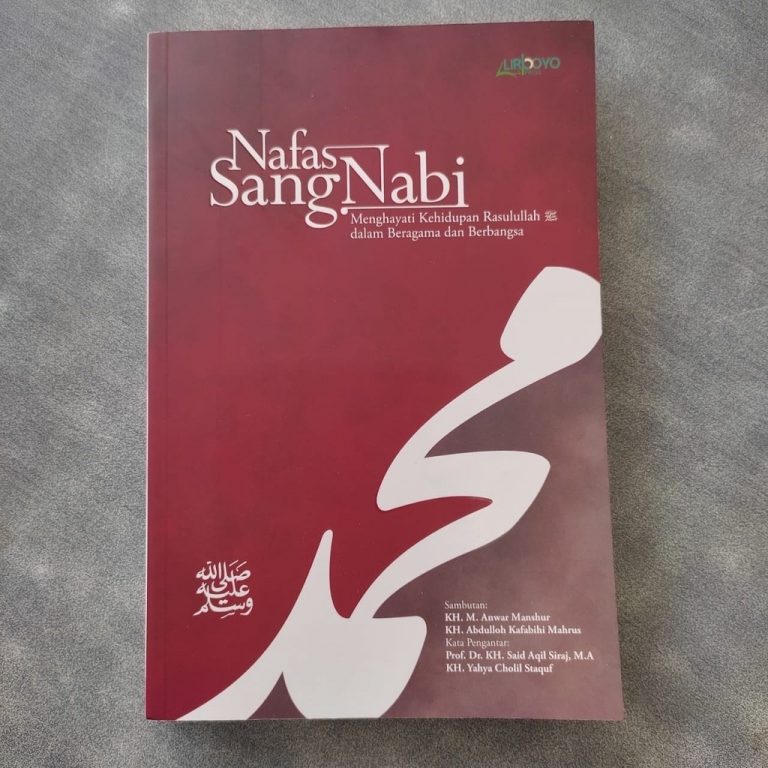
Nabi Muhammad merupakan sosok sempurna (insān kamīl) sebagai suri teladan dan idola bagi seluruh umat Islam lintas peradaban. Meski demikian, tak sedikit yang mempertanyakan, apakah figur Rasulullah masih relevan dijadikan panutan di zaman modern ini? Pertanyaan tersebut menjadi kerangka buku Nafas Sang Nabi; Menghayati Kehidupan Rasulullah dalam Beragama dan Berbangsa dalam membaca isu-isu kontemporer terkait kehidupan sosial keagamaan dan politik kebangsaan.
Buku Nafas Sang Nabi mengasumsikan bahwa sebagai manusia sempurna dan rahmat bagi alam semesta, nilai-nilai yang dibawa Nabi Muhammad tentu akan terus relevan dan tak lekang oleh waktu. Sekalipun di era modern ini, era ketika dunia sudah tersegregasi ke dalam negara-negara bangsa, era yang terpisah ratusan tahun bahkan ribuan tahun dari kehidupan Sang Rasul.
Sebagai tulisan pembuka, buku ini menegaskan kembali peran Rasulullah dalam konteksnya sebagai pembawa wahyu Tuhan. Kajian tentang misi profetik Nabi itu digambarkan secara komprehensif. Awal pembahasan tersebut melahirkan tesis tentang sosok Nabi yang bukan hanya sebagai pembawa risalah, melainkan juga sebagai rahmat untuk semesta dan sosok yang penuh cinta kasih kepada seluruh kalangan.
Nafas Sang Nabi dalam Berbangsa dan Bernegara
Buku ini mengurai setiap aspek kehidupan Nabi Muhammad dari kehidupan pribadi, sosial, hingga bernegara. Buku ini menampilkan dua perspektif ketatanegaraan melalui sosok Rasulullah; yaitu sikap Rasulullah sebagai rakyat sipil dalam konteks kehidupan Makkah dan sikap Rasulullah sebagai kepala negara dalam latar kehidupan Madinah. Dua sudut pandang ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan elemen-lemen kebangsaan dengan tetap mengacu pada perilaku luhur Nabi Muhammad.
Idealitas sikap Rasulullah sebagai rakyat sipil, misalnya, digambarkan melalui sifat Nabi yang selalu mengedepankan sikap luhur, tidak pernah menampakkan wajah yang keras dan koersif. Keluhuran Nabi itu tercermin dalam kehidupan sosial.
Misalnya, ketika Ka’bah berulangkali diterpa banjir dan mengakibatkan kerusakan parah, Nabi turut berkontribusi bersama para penduduk Makkah untuk bergotong-royong merenovasi bangunan mulia itu. Srawung-nya Nabi itu menunjukkan bahwa rakyat sipil hendaknya turut peduli dengan permasalahan yang ada di sekitarnya.
Tidak hanya sebagai rakyat sipil semata, jiwa luhur Nabi juga termanifestasikan dalam sikap-Nya sebagai pemimpin kekuasaan. Status ini diperoleh Rasulullah ketika beliau membangun negara di Madinah. Terdapat tiga agenda utama yang dilakukan Nabi sebagai kepala negara di Madinah.
Pertama, membangun masjid sebagai wadah perjumpaan umat Muslim. Kedua, mempersatukan masyarakat pendatang (muhājirīn) dan pribumi (anṣār). Ketiga, merumuskan konstitusi Negara Madinah untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda-beda.
Al-Farabi, sebagaimana yang dikutip Zuhairi Misrawi dalam bukunya, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW, mengatakan bahwa Madinah adalah kota yang dipimpin di atas perpaduan antara rasionalitas dan spiritualitas sejak dikelola oleh Rasulullah.
Refleksi Kemanusiaan Dalam Sosok Rasulullah
Prinsip kemanusiaan dalam diskursus modern sangat lekat dengan wacana Barat soal Hak Asasi Manusia. Meski ruang geraknya universal, konstruksi Barat tentang HAM kerap digunakan untuk “menghajar” Islam terutama jika berkaitan dengan kasus terorisme.
Buku Nafas Sang Nabi ini menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan sejatinya sudah menjadi titik berat dalam ajaran Islam. Hal ini tercermin dari nihilnya ajaran Rasulullah yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dalam buku ini, kajian tentang prinsip ini mengintisarikan empat sikap utama, yaitu: Mengedepankan sikap toleran; melindungi kalangan minoritas; anti diskriminasi; dan penebar perdamaian.
Prinsip perlindungan terhadap minoritas, misalnya, tercermin dari implementasi Piagam Madinah yang melindungi komunitas Yahudi Aus yang minoritas di Madinah. Sebagai penduduk Madinah, mereka tetap mendapatkan hak-hak warga negaranya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 46 Piagam Madinah.
Selain sebagai aktor utama dibalik tercetusnya Piagam Madinah, sosok inklusif Rasulullah juga dikaji dalam konteks relasi beliau dalam hal diplomasi dengan negara atau bangsa lain. Salah satu ayat yang dirujuk adalah QS. Al-Anfal [8]: 61.
Pada prinsipnya, Islam sangat menganjurkan perdamaian jika sedang berada dalam potensi konflik. Secara implisit, QS. Al-Anfal [8]: 61, menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili, seperti yang ditulis dalam buku, menjelaskan bahwa ayat tersebut menyerukan perintah untuk menerima akad perdamaian dengan pihak lawan. Dalam bahasa lain, Islam lebih memprioritaskan perdamaian ketimbang peperangan.
Persoalan Jihad dan Ketatanegaraan
Selaras dengan judul bukunya, isu keagamaan dan kebangsaan menjadi payung topik dalam kerangka kepenulisan. Segala sub-topik yang dikaji pada akhirnya akan bermuara kepada payung itu. Isu krusial lain yang mendapatkan perhatian dalam buku ini adalah tentang pemahaman jihad dan problematika idealisme khilafah.
Menariknya, buku ini tidak sedang mengeliminir sistem khilafah di era masa sepeninggal Nabi atau mengglorifikasi sistem pemerintahan di era modern, melainkan memberi gambaran tentang fakta historis khilafah dan mengulas kesalahpahaman beberapa kelompok Islam puritan.
Kedua pembahasan tersebut diuraikan dengan sangat artikulatif melalui legitimasi dalil para ahli tafsir dan ulama lintas disiplin. Kekayaan literatur membuat buku ini berbeda dari buku lain yang mengulas tema serupa. Tokoh otoritatif tafsir, misalnya, tidak hanya diambil dari era klasik saja, melainkan juga era pertengahan dan modern.
Dalam membincang persoalan khilafah, buku ini mengutip Imam ath-Thabari (w. 310 H/925 M) sebagai representasi mufassir klasik, menyadur Imam al-Mawardi (w. 1058 M) sebagai perwakilan era pertengahan, dan meminjam pendapat Wahbah az-Zuhaili (w. 2015 M) untuk mewakili perspektif modern.
Nilai-nilai yang diwariskan oleh Rasulullah tampak akan terus berkontestasi melalui patronnya masing-masing. Nilai itu bisa menjadi sangat rigid jika dipahami oleh kelompok Islam konservatif, namun ia juga bisa menjadi sangat lentur jika dipahami oleh kelompok Islam progresif.
Pertanyaan yang menjadi landasan kerangka buku, dan judul review, ini tentu sebuah pertanyaan retoris. Setelah membaca dan menelaah buku ini, kita baru tahu, apakah memang mengidolai Nabi Muhammad masih relevan di peradaban digital ini?
Wal-akhir, Terlepas dari perebutan tafsir yang terjadi, faktanya adalah bahwa umat Rasulullah bukan mereka yang hidup di abad ke-7 M saja, melainkan seluruh generasi manusia hingga hari akhir. Buku ini meyakini bahwa nafas sang Nabi akan membersamai seluruh umatnya hingga akhir zaman. [NH]



