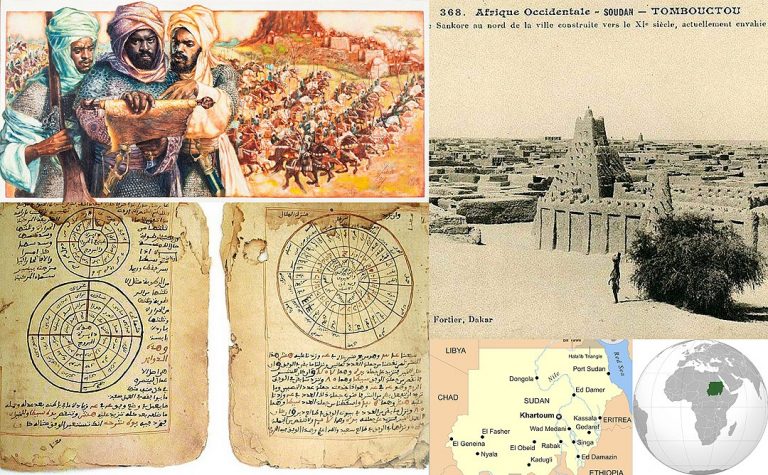
Bahkan tanpa harus mencari asal-usul dan makna awalnya, dalam khasanah pemahaman kita, kata puasa masih sangat jelas pengertiannya. Kita tahu persis bahwa puasa bermakna: menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kuasa dia lakukan. Pengertian ini sama sebangun dengan makna semantik dari kata shaum dalam bahasa Arab.
Ketika orang mengatakan bahwa dia sedang puasa bicara misalnya, tentu yang dimaksud adalah ia sedang menahan diri untuk tidak bicara. Atau, ketika orang mengatakan bahwa dia puasa berpolitik, tentu maksudnya adalah bahwa ia menahan diri untuk tidak berpolitik. Begitu seterusnya.
Tentu saja, ketika orang tidak melakukan sesuatu yang memang tidak kuasa dia lakukan, tidak akan bisa disebut sebagai puasa. Orang bisu tentu tidak bisa disebut melakukan puasa bicara, karena tanpa diminta alam sudah lebih dulu memuasakan mulutnya dari bicara. Rakyat kecil tentu tidak bisa mengatakan akan puasa berpolitik, karena posisi sosio-kulturalnya memang sudah memuasakan kemampuan berpolitiknya.
Ada banyak alasan yang membuat orang melakukan puasa-puasa semacam ini. Sayangnya, kebanyakan alasan ini muncul dari tekanan situasi dan kondisi tertentu, dan jarang muncul dari kesadaran akan pentingnya puasa itu sendiri dalam keseluruhan bangunan peradaban.
Orang yang puasa bicara atau berpolitik (atau lainnya) seperti disebut di atas, pasti melakukannya karena tekanan situasi sesaat. Tujuannya pun jelas: menghindari dampak-dampak yang lebih merugikan yang dia hitung bisa terjadi seandainya dia memilih tidak berpuasa. Jelas, dia tidak akan memilih berpuasa seandainya situasi dirinya tidak memaksanya.
Sementara pada sisi lain, kalau kita jeli mengamati, diam-diam semangat puasapun pada dasarnya sudah terintegrasi sedemikian rupa dalam pergaulan sosial-budaya kita. Meski ini terjadi secara lebih halus, sehingga sering tak terlalu disadari. Karena, tanpa puasa-puasa tertentu yang secara ajeg dan terus-menerus dilakukan, bisa kita bayangkan betapa amburadulnya tatanan sosial-budaya yang terbentuk.
Ambil saja contoh, kalau sebagian besar kita tidak ber’puasa marah’, misalnya, bisa kita bayangkan betapa gaduhnya ruang publik kita oleh suara makian. Betapa banyak hal yang bisa membuat orang marah, meski demikian lebih banyak lagi kesadaran untuk tidak membuat orang tiap saat melampiaskan kemarahannya.
Atau, kalau sebagian besar kita tak berpuasa terhadap naluri kekerasan, misalnya, bisa juga kita bayangkan betapa pusingnya kepala karena tiap saat harus melihat orang gontok-gontokan cuma demi memperebutkan tulang.
Atau, ketika orang yang punya senapan tidak berpuasa, misalnya, bisa kita bayangkan betapa bisingnya udara kita oleh bunyi letusan. Begitu seterusnya. Alhasil, harus diakui, puasa adalah landasan paling dasar bagi bangunan peradaban. Tanpa mau berpuasa, maka setiap orang, setiap pihak, bisa melakukan apa saja yang memang kuasa dia lakukan. Dan, akibatnya, pasti adalah sesuatu yang sudah terlalu akrab kita kenal sebagai anarki.
Sekarang, mari kita lihat: mengapa orang sukarela melakukan puasa-puasa semacam ini? Tentu jawaban sederhananya adalah: sebagian besar karena kesadaran tentang tatanan yang lebih tinggi. Tatanan yang dibutuhkan setiap orang untuk mengelola hidupnya masing-masing dalam jangka panjang. Dalam hal ini, sebuah tatanan moral dan etika sosial yang menjamin kepastian hidup bersama.
Sementara pada sisi lain, kesadaran puasa semacam ini, sebagian kecil bahkan harus dan sudah dilembagakan dalam bentuk hukum positif. Ancaman sanksi hukum ini pulalah yang mengondisikan orang untuk tidak bisa seenaknya mengumbar tindakan-tindakan yang sebenarnya kuasa dia lakukan. Orang dipaksa untuk puasa mencuri, memperkosa, membunuh dan seterusnya, karena ada ancaman hukum yang jelas bila dia tetap nekat melakukannya.
Sekali lagi, bisa kita tegaskan bahwa sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, puasa adalah landasan penting bagi pergaulan sosial manusia; pergaulan sosial yang menjadi landasan bagi bangunan sebuah peradaban.
Nah, bila puasa adalah realitas intrinsik dalam peradaban manusia, yang nota bene di dorong oleh kesadaran tentang kebutuhan adanya bangunan sosial yang kohesif; maka puasa seperti yang dikerjakan di bulan Ramadhan, justru digerakkan oleh kesadaran yang lebih tinggi dan lebih hakiki: kesadaran tentang Tuhan dan akhirat.
Kita tahu, ‘puasa-puasa’ yang dijadikan landasan bagi peradaban sering tampak rentan dan tidak stabil. Ini karena kesadaran dasar yang membentuknya -atau dalam istilah Jawa: pamrihnya- masih bersifat duniawi, sehingga gampang digoncangkan oleh pihak-pihak tertentu yang kebetulan mempunyai kekuasaan untuk itu.
Seperti biasa terjadi, selalu saja ada pihak-pihak yang bisa membongkar ‘puasa’ semacam ini dengan ‘mengatasi’ moral, etika dan -bahkan- hukum positif, tanpa seorang pun kuasa mencegah atau menghalanginya. Justru pihak lainlah yang malah harus menambah jumlah ‘puasa’nya, yakni harus mau dengan sabar terus menerus menonton pihak semacam ini mendemonstrasikan kekonyolannya, sampai Tuhan sendiri yang menghentikannya.
Puasa di bulan Ramadhan, tentu saja seharusnya melahirkan landasan yang lebih kokoh bagi ‘puasa-puasa’ lainnya, termasuk ‘puasa peradaban’. Karena dengan puasa di bulan ini, orang selalu digiring untuk menyadari kesementaraan segala sesuatu kecuali Dia, menyadari betapa tidak hakikinya segala sesuatu kecuali Dia, betapa sepelenya segala sesuatu kecuali Dia, betapa hidupnya sekedar seperti lintasan mimpi sekilas bila dibandingkan seluruh keberadaan yang akan dilaluinya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Kesadaran semacam inilah yang membuat orang untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri dalam pergaulan sosial dan peradabannya. Dan, dalam bahasa al-Qur’an, inilah makna operasional dari konsep taqwa; sesuatu yang seharusnya menjadi out put dan out come dari tindak ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadhan.
Apa boleh buat, mau tak mau kita harus kembali menerima bahwa kenyataan nyaris tidak pernah bisa sama dengan yang seharusnya. Meski tiap tahun kita memasuki Ramadhan, sesuatu yang nota bene seharusnya setapak demi setapak meningkatkan ketaqwaan, meningkatkan kualitas kehati-hatian dan penjagaan diri kita dalam pergaulan; tapi kenyataannya: peradaban yang kita bangun belum juga berubah, belum juga menampakkan kualitas dan kearifan seperti yang diharapkan sebagai out put dan out come puasa Ramadhan.
Jelas, ini artinya kita telah menyia-siakan Ramadhan, telah menyia-siakan uluran tanganNya. Jangan-jangan ini karena puasa Ramadhan kita -seperti yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW- hanya berhenti pada lapar dan dahaga belaka. Tak lebih dan tak kurang dari itu.
Anis Sholeh Ba’asyin, Pengasuh Suluk Maleman untuk selengkapnya, bisa dilihat di sini


