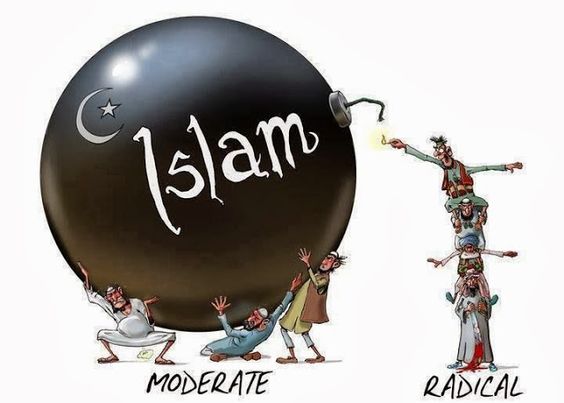
Tradisi pemikiran Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, dan Budha telah terbukti dapat disalahgunakan untuk memproduksi terorisme religius. Terorisme yang berbasis pada doktrin agama telah berumur tua, terutama pada era pra-modern di mana agama sering disalahgunakan sebagai justifikasi utama bagi terorisme. Dalam sejarah Yahudi terdapat sekte radikal bernama Sicarii yang membantai sekte lainnya. Di India dikenal kelompok radikal bernama Thuggee yang membantai warga sipil sebagai bentuk persembahan pada Kali, dewa perusak dalam keyakinan Hindu. Teror juga dilakukan oleh tentara Kristen (Crusaders) pada Perang Salib untuk membasmi populasi Yahudi dan Muslim di Jerusalem. Tujuan mereka adalah untuk mengembalikan Jerusalem menjadi kota Kristen.[1]
Di dalam sejarah Islam klasik, kelompok Khawarij dan Hasyasyiyin (Assassins) merupakan dua kelompok radikal yang menghalalkan pembunuhan terhadap kelompok Muslim lainnya. Khawarij melakukan penafsiran radikal atas al-Qur’an untuk membangun teologi radikal yang melegitimasi perang melawan musuh politik yang mereka tuduh telah mengabaikan al-Qur’an dalam pemecahan masalah kepemimpinan. Sementara Hasyasyiyin merupakan sempalan sekte Syiah yang dimotori oleh Hassan Sabbah. Mereka menganggap kelompoknya sebagai wakil Tuhan, sehingga halal bagi mereka untuk membunuh siapa saja yang berseberangan dalam hal keyakinan. Sementara saat ini, terdapat kelompok Wahabi yang senantiasa dikait-kaitkan dengan merebaknya terorisme global dimana pengikutnya gemar membid’ahkan dan mengkafirkan Muslim lain yang berbeda aliran.
Pada era modern, terutama pasca revolusi Prancis pada tahun 1789, terorisme yang dimotivasi oleh sentimen agama jarang ditemui. Pada abad ke-18 dan 19, ideologi-ideologi yang muncul adalah ideologi sekular seperti nasionalisme dan Marxisme. Nasionalisme dan Marxisme pun dapat mempengaruhi kemunculan terorisme yang dijustifikasi dengan term-term sekular, bukan religius. Namun pasca Perang Dingin antara Barat dengan Uni Soviet dan pasca revolusi Iran pada tahun 1979, terorisme atas nama agama muncul kembali ke permukaan. Belakangan ini terorisme religius secara massif dipertontonkan oleh Al-Qaeda dan ISIS yang berbasis pada doktrin Wahabi Jihadi.[2]
Pasca serangan Al-Qaeda pada 11 September 2001 di World Trade Center New York dan Pentagon, terorisme menjadi isu global yang hangat dibicarakan karena dinilai telah mengakibatkan konsekuensi yang luas, tidak hanya secara politis dan militer, tetapi juga secara ekonomis. Serangan 11 September kemudian diikuti oleh serangkaian bom bunuh diri (suicide bombing) di Bali pada tahun 2002, Madrid pada tahun 2004, London pada tahun 2005, New Delhi pada tahun 2005, dan Mumbai pada tahun 2006. Bom bunuh diri hingga saat ini juga sering terjadi di kawasan konflik seperti di Iraq, Israel-Palestina, dan negara-negera Timur Tengah terutama Suriah yang dikacaukan oleh aksi-aksi brutal ISIS. Di Indonesia, dari tahun 2000 hingga 2016 teror bom terus saja memakan korban. Bahkan pada tahun 2016 ini kita kembali dikejutkan oleh bom di jalan Tamrin dan gereja Oikumene di Samarinda baru-baru ini.
Ancaman terorisme global ini mendorong pentingnya identifikasi terhadap akar-akarnya (the roots of terrorism) dan cara penanggulangannya. Identifikasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengenali apa itu terorisme dan mengapa tindakan kekerasan dilakukan oleh para teroris. Kajian ini akan memperlihatkan bahwa selain dimotivasi oleh faktor politik, terorisme juga sering dipicu oleh doktrin Wahabi yang radikal. Terorisme religius yang didorong oleh doktrin radikal Wahabi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tipe-tipe terorisme lain. Teroris religius ala Wahabi selalu menganggap tergetnya sebagai kafir danmusyrik yang boleh dibunuh. Mereka menghalalkan penggunaan kekerasan sebagai aksi suci. Benarkan doktrin Wahabi adalah sumber terorisme global? Inilah pertanyaan yang akan dikaji jawabannya dalam tulisan ini.[3]
Wahabi dan Aliansinya
Doktrin Wahabi yang destruktif tersebut dengan mudah dimanfaatkan dan ditunggangi oleh Kerajaan Saud berserta aliansi-aliansi politik mereka yang selama ini senantiasa mensuplay dana dan persenjataan perang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi dalam sejumlah peperangan melawan Uni Soviet telah nyata-nyata beraliansi dengan Amerika dan Inggris kemudian menampakkan sikap arogansinya terhadap dunia Islam. Bahkan berdirinya Kerajaan Saudi setelah melepaskan diri dari Turki Utsmani juga karena mendapat dukungan dari Amerika dan Inggris, baik di bidang ekonomi, politik maupun militer. Inggris memiliki kepentingan mengamankan link via Canal Suez menuju India, sedangkan Amerika berkepentingan mengeksploitasi sumber daya minyak.
Anshumali Shukla, seorang peneliti dari Punjabi University, menggarisbawahi bahwa kemunculan Wahabi didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah keprihatinan Muhammad bin Abdul Wahab melihat perilaku bid’ah dan takhayul yang marak terjadi di Najd dan sekitarnya. Merespon fenomena itu, Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya menyerukan semangat pemurnian Islam sesuai dengan pemahaman tekstual dan kaku terhadap Al-Quran dan hadits. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dorongan kepentingan kolonialisme. Negara-negara kolonialis Barat sangat terusik dengan semakin meluasnya pengaruh Turki Utsmani dari kawasan Asia Barat, Afrika Utara, hingga sebagian kawasan Eropa. Untuk melemahkan kedigdayaan Turki Utsmani maka diperlukan strategi pecah belah dan adu domba antar kaum Muslimin. Inggris kemudian melihat bahwa Arab Saudi, yang memiliki doktrin Wahabi yang radikal, berpotensi digunakan untuk menciptakan konflik sesama Muslim melalui doktrin takfirnya. Arab Saudi sendiri—dengan dukungan Barat—berkepentingan untuk lepas dari hegemoni Turki Utsmani dan berdiri secara independen. Arab Saudi yang notabene merupakan daerah kemunculan Islam tidak selayaknya berada di bawah bayang-bayang hegemoni Turki Utsmani. Sebaliknya, Arab Saudi semestinya berada di depan memimpin negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Bertemunya kepentingan-kepentingan itulah yang mendorong kedua negara merancang agenda-agenda politiknya.[4]
Kuatnya hubungan Amerika dan Kerajaan Saudi semakin kuat pasca 18 Desember 2010 ketika gelombang revolusi pecah di Tunisia dan Mesir; perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, demonstrasi besar-besaran di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman, Kuwait dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dalam situasi tidak stabil tersebut, Amerika tampak melindungi kekuasaan monarkhi Kerajaan Saudi dari gelombang revolusi untuk melanggengkan hegemoni, intervensi, dan kepentingan kapitalisasi sumber daya alam di Timur Tengah.
Yang tak kalah menarik dibanding fakta di atas adalah pernyataan dari Garikai Chengu, seorang peneliti dari Harvard University, dalam artikelnya yang berjudul America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group. Menurutnya, Al-Qaeda dan ISIS tak lain hanyalah boneka buatan Amerika yang didesain untuk memecah-belah dengan strategi teror kemudian menguasai kekayaan kantong-kantong minyak di Timur Tengah di satu sisi, sedangkan di sisi lain adalah untuk menghambat berkembangnya pengaruh Iran di Timur Tengah. Pada era Perang Dingin, Amerika dengan kepentingan kapitalismenya menggunakan jasa Al-Qaeda Wahabi—yang didukung Arab Saudi dan dimentori oleh CIA—untuk melawan Uni Soviet di Afghanistan dengan dalih memerangi ideologi sosialisme yang dinilai atheis. Bahkan Amerika juga menndompleng gerakan Ikhwan Muslimin untuk menanggulangi semakin kuatnya pengaruh sosialisme di Mesir.
Sementara di Suriah saat ini, ISIS dengan doktrin Wahabi Jihadinya kembali ditunggangi oleh Amerika untuk menghadapi Basyar Asad dan sekutunya, yakni Iran dan Russia. Garikai Chengu menambahkan bahwa pada dasarnya ada tiga perang yang terjadi di Suriah: satu antara pemerintah dan pemberontak, yang lain antara Iran yang Syiah dan Arab Saudi yang Wahabi, dan yang lain lagi antara Amerika dan Russia. Ini adalah tiga pertempuan yang saling tumpang tindih. Inilah Perang Dingin Baru yang membuat Amerika mengambil risiko mempersenjatai pemberontak Wahabi di Suriah, karena Presiden Suriah, Bashar al-Assad, adalah sekutu utama Russia. Di sisi lain dan pada saat bersamaan, dukungan diam-diam Amerika pada ISIS bertujuan untuk menekan Iran. Dari situlah dapat dilihat sejauh mana doktrin radikal Wahabi yang dianut ISIS berperan dalam menciptakan konflik di Suriah.[5]
Kompleksitas konflik di Timur Tengah tersebut, menurut pandangan F. Gregory Gause, bukan semata-mata pertempuran tidak langsung antara Riyadh vis a vis Tehran. Jauh lebih komplek lagi, intervensi kepentingan ekonomi dan politik Amerika melawan Russia serta perebutan pengaruh antara Iran dan Arab Saudi atas negara-negara lemah di Timur Tengah menjadi muara Perang Dingin Baru di Suriah. Kaum militan yang mendasarkan aksi-aksi mereka pada doktrin agama hanyalah dijadikan alat perang kepentingan kelompok elit. Hal itu dapat terjadi sebab doktrin radikal rawan dipolitisasi oleh pihak-pihak elit yang berkepentingan. Amerika mendukung ISIS yang berbasis pada ideologi radikal Wahabi untuk melawan Basyar Asad, kemudian mengisolasi Iran, dan target berikutnya adalah Russia.[6]
Akar Terorisme dalam Doktrin Wahabi
Dalam kitab Fajar al-Shadiq fi al-Radd ‘ala al-Firqah al-Wahabiyah al-Mariqah, Jamil Sidqi al-Zahawi menuturkan sejarah kemunculan Wahabi di Najd pada tahun 1143 H yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan kemudian penyebarannya didukung oleh Dinasti Saudi yang beraliansi dengan Amerika dan Inggris. Sejak kemunculannya, para pengikut Wahabi mengkafirkan umat Islam yang berbeda pendapat, bahkan, lebih kejam lagi, mereka menghalalkan penjarahan harta serta pembunuhan terhadap kelompok lain yang dikafirkan. Dengan doktrin yang kaku dan sempit, pengikut Wahabi merusak bangunan-bangunan bersejarah Maqbaroh Baqi’ dan artifak-artifak keluarga Rasulullah.
Jamil Shidqi berpendapat bahwa doktrin radikal Wahabi menjadi biang keladi kerusuhan dan kekerasan atas nama Islam di Jazirah Arab. Doktrin Wahabi sangatlah eksklusif, tidak menerima dialog, dan secara serampangan mudah menyesatkan kelompok-kelompok lain. Inilah penyebab utama fitnah di kalangan kaum Muslimin saat ini.[7]
Dr. Ahmad Mahmud Shubhi juga berpendapat senada dalam bukunya yang berjudul Judzur al-Irhab fi al-Aqidah al-Wahabiyyah (Akar-akar Terorisme dalam Akidah Wahabiyah). Menurutnya, gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan Islam dan menggunakan kekerasan atas nama Islam sejatinya tidak bisa merepresentasikan Islam. Mereka hanya merepresentasikan kelompok Wahabi saja. Kelompok-kelompok teroris apapun namanya, baik itu Taliban, Al-Qaeda maupun ISIS, merupakan produk dari paham Wahabi yang ekstrem.
Ahmad Subhi Manshur, pakar sejarah al-Azhar University Cairo, pun sepakat bahwa akar kekerasan atas nama Islam belakangan ini adalah produk dari paham Wahabi yang rigid (al-mutazammid). Di Mesir, paham itu menemukan tempatnya dalam gerakan Ikhwan al-Muslimun, sebuah organisasi keagamaan di Mesir yang terpengaruh kuat oleh Wahabi Saudi. Para ulama al-Azhar senantiasa melawan pemikiran Ikhwan Muslimun yang keras dengan cara-cara dialogis, akan tetapi sering sekali mereka mengkafirkan dan menyesatkan ulama-ulama al-Azhar.[8]
Di Indonesia, Ikhwan Muslimun sangat kuat mempengaruhi gerakan-gerakan PKS. Salah satu bukti kuat adalah tingginya kebencian kader-kader PKS terhadap ulama-ulama moderat Al-Azhar. Saat Syaikh Ahmed Thayyib berkunjung ke Indonesia pada awal tahun 2016 dalam rangka menyebarkan pesan damai, para kader PKS beramai-ramai mencaci maki Grand Syaikh Al-Azhar tersebut dengan kata-kata yang keji. Fakta ini menunjukkan bahwa teologi kebencian ala Wahabi telah merasuk dalam pemikiran sebagian kader-kader PKS.
Selengkapnya, klik



