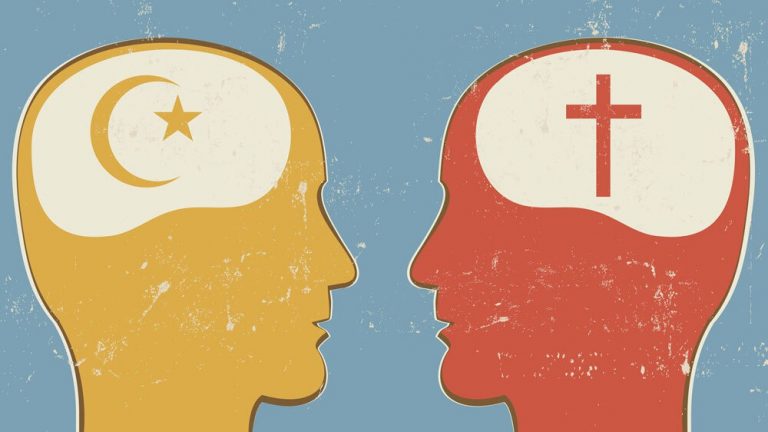
Selama ini, dampak dari kekerasan yang kita kenal adalah secara fisik, terlihat, dan konkret. Berbeda dengan kekerasan simbolik, di mana efeknya sama sekali tidak terlihat, laten, dan sangat lembut. Mudahnya, korban tidak akan merasakan jika dirinya berada dalam ruang kekerasan, korban justru menerima dan menyetujui posisinya, bahkan dia merasakan berada dalam posisi yang seharusnya dan sepantasnya.
Meminjam salah satu konsep kunci dari Pierre Bourdieu, prinsip simbolik ini disadari dan diterima baik oleh kedua belah pihak; pihak dominan yang menguasai dan pihak subdominan yang dikuasai. Prinsip simbolik ini menyerang dan menentukan cara berpikir, mindset, dan tindakan sebuah kelompok atas kelompok lainnya. Menurut Bourdieu, kekerasan simbolik muncul dari adanya struktur kelas dalam masyarakat.
Adanya struktur kelas dalam masyarakat adalah sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan, pemisahan, ketidaksamaan, ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan. Kekerasan simbolik berjalan dengan menggunakan sarana wacana. Wacana menjadi landasan pijakan efektif bagi keberlangsungan kekerasan simbolik.
Salah satu kekerasan simbolik yang mengakar dalam tradisi masyarakat kita adalah mengenai term mayoritas-minoritas. Tentu saja, istilah tersebut sangat lekat dengan kondisi sosial kita. Sudah jutaan wacana diproduksi tentang istilah itu. Namun, keseluruhan wacana itu pada akhirnya hanya mengendapkan satu kesimpulan yang sama, yaitu mayoritas yang dominan akan selalu menjadi penguasa terhadap minoritas yang didominasi.
Ambil contoh teman kita yang Kristen, misalnya, akan sepakat jika kaum mereka selalu mengalami subordinasi oleh kelompok mayoritas. Isu di Cilegon mengenai larangan pembangunan Gereja akan selalu disepakati oleh umat Kristen sebagai bentuk kuasa kaum dominan terhadap kaum sub-dominan seperti mereka.
Peran wacana sangat penting terhadap penegasan prinsip simbolik, termasuk term mayoritas-minoritas. Salah satu kontribusinya adalah penanaman dan pelanggengan nilai-nilai yang melekat kepada kedua posisi tersebut. Mudahnya begini, seperti yang barusan dibincang, wacana yang terus diproduksi jika membincang tentang mayoritas adalah perihal kekuasaan, dominasi, kontrol, superioritas. Sedangkan yang diproduksi ketika membicarakan minoritas adalah perihal korban, subordinasi, inferioritas, diskriminasi, dan marginalisasi. Kerja wacana secara efektif melanggengkan nilai-nilai itu dan semakin melekatkannya dalam masing-masing istilah.
Pada akhirnya, dikotomi mayoritas-minoritas bukan lagi masalah ketimpangan kuantitas, melainkan ketimpangan sosial. Jika membicarakan mayoritas-minoritas, yang menjadi titik fokus bukan lagi siapa yang lebih banyak dari pada siapa, namun siapa mendominasi siapa, siapa dikuasai siapa.
Celakanya, seperti yang dibincang di awal tulisan, kedua belah pihak mengafirmasi masing-masing posisinya. Bukan hanya mengafirmasi, kedua belah pihak seakan bersikap permisif terhadap kedudukannya. Dalam bahasa lain, umat Kristen di Cilegon, misalnya, akan menganggap diskriminasi yang sedang dihadapinya itu sebagai sebuah situasi yang lumrah. Pun, dengan umat Islam di sana yang menganggap bahwa perilaku diskriminatif yang mereka lakukan adalah sebuah kewajaran. Kedua situasi tersebut berangkat dari satu wacana, watak minoritas adalah tunduk, sedangkan habitus mayoritas adalah kontrol.
Saking sulitnya diidentifikasi karena kekerasannya tidak disadari, korban akhirnya akan terjebak dalam menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara melihat atau memandang sesuatu.
Sekali lagi, dikotomi mayoritas-minoritas pada akhirnya hanya melahirkan legitimasi moral semu yang berperan besar melanggengkan diskriminasi dan tirani mayoritas yang kerap terjadi belakangan ini. Termasuk dalam hal bertoleransi sekalipun. Toleransi memang akan selalu menjadi wacana milik mayoritas, hanya mayoritas yang memiliki hak istimewa untuk bertoleransi. Termasuk menentukan mana yang pantas dirangkul, mana yang tidak. Tidak perlu bingung melihat kasusnya, lihat saja bagaimana reaksi Muslim ketika disuruh memilih, berteman dengan seorang Kristen, atau dengan jemaat Ahmadiyah.
Bicara mengenai Ahmadiyah, saya minggu lalu menghadiri pembukaan dan peresmian masjid Ahmadiyah Kota Yogyakarta, di Kotabaru tepatnya. Ada pernyataan menarik dari aparatur desa setempat ketika melakukan sambutan, yaitu bahwa jemaat Ahmadiyah tidak perlu menutup diri. Masjid Ahmadiyah itu hendaknya bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh jemaat Ahmadiyah saja, namun juga bagi khalayak umum sebagai bagian dari proses membaur dengan masyarakat sekitar.
Wacana aparatur, yang kebetulan Muslim, tersebut menyiratkan sesuatu dalam benak saya. Mengapa justru kaum Ahmadiyah yang diberi “pr” untuk merangkul orang lain. Hal itu seolah mengindikasikan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap Ahmadiyah disebabkan karena mereka tidak mau berbaur dengan masyarakat. Mengapa aparatur itu tidak mengatakan bahwa masyarakat di sekitar masjid akan mendukung segala bentuk aktifitas yang akan dilaksanakan dalam masjid tersebut. Ini yang saya maksud kekerasan dalam sunyi. Mayoritas dalam posisi mengontrol, sedangkan minoritas hanya mendengar.
Tulisan ini seolah mempersoalkan dikotomi yang sebenarnya sudah mapan dan tidak perlu diotak-atik lagi. Namun, justru di situlah letak masalahnya. Banyak hal-hal mapan yang tidak kritisi sehingga menjadi hulu dari segala konflik.
Persoalan kekerasan simbolik, meski sulit diidentifikasi, bukan berarti tidak bisa diminimalisasi. Bourdieu pernah mengatakan bahwa kekerasan simbolik adalah kekerasan yang sudah tertanam dalam kebiasaan dan sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama sehingga tidak disadari adanya. Karena tak disadari adanya, maka kekerasan semacam ini sulit bahkan seakan-akan tidak pernah bisa dihilangkan. Oleh karena itu, upaya awal untuk meminimalisir dan membuka tabir kekerasan simbolik adalah kesadaran.
Jika masing-masing pihak sudah menyadari bahwa tindakannya merugikan orang lain, atau bahwa ia sedang dirugikan, maka upaya-upaya konkret lainnya baru bisa dilakukan. Sadar dan mengakui akan adanya kekerasan simbolik menjadi tahap awal memutus rantai kekerasan simbolik secara mutlak demi mewujudkan masyarakat yang setara, egaliter, dan sejahtera.



