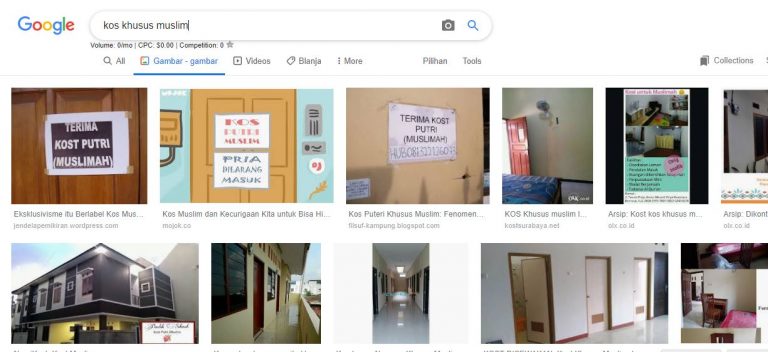
Belakangan ini di media massa sedang ramai memberitakan tentang fenomena kos-kosan balok di Jakarta. Apa itu kos-kosan balok? Sebuah kos-kosan yang berukuran tingginya kisaran satu meter, lebar sekitar setengah hingga satu meter, dan panjang kira-kira hanya pas panjang tubuh rata-rata orang Indonesia, kisaran dua meter. Karena bentuknya yang sangat sempit, pas ukuran tubuh, kotak, dan panjang itulah disebut sebagai kos-kosan balok. Karena bentuknya persis seperti balok.
Kos-kosan balok ramai dibicarakan karena unik berbeda dari kos-kosan pada umumnya yang lebarnya seukuran satu kamar yang cukup longgar dan cukup nyaman untuk istirahat. Tapi, kos-kosan balok sangat minimalis sekali, sempit, dan pengap. Sangat miris dan tak layak menjadi tempat tinggal seorang hamba tuhan.
Menurut pemberitaan berbagai media, kos-kosan balok yang super sempit tersebut disediakan untuk para penghuni yang memiliki kantong cekak di Jakarta. Harga sewanya kisaran 200 hingga 400 ribu rupiah perbulan. Mengingat, kata teman saya yang kini indekos di Jakarta, rata-rata kosan normal di ibukota itu kisaran 800 ribu ke atas. Semakin bagus fasilitasnya, semakin mahal harga sewanya.
Fenomena kaum berkantong cekak atau kaum mustad’afin seperti yang tampak dalam gejala fenomena kos-kosan balok ini bukanlah hal yang sama sekali baru di Jakarta. Kemiskinan adalah cerita lain yang sering ditutup-tutupi dari sisi gemerlapnya kehidupan metropolitan di Jakarta. Pembangunan kota modern seperti Jakarta tersebut, tak hanya berisi kisah-kisah orang yang sukses dan super kaya. Tapi di sisi lain, banyak juga kisah-kisah ketersingkiran kaum mustad’afin dari gemerlapnya pembangunan ibu kota.
Di televisi kita sering melihat orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, atau membangun gubuk-gubuk di tempat yang sering disebut oleh pembawa acara berita televisi sebagai perkampungan kumuh. Gubuk-gubuk reot tersebut seringkali menjadi bulan-bulanan Satpol PP untuk berulangkali digusur. Orang-orang yang bernasib tak baik itu jumlahnya tidak sedikit, jumlah mereka sangat besar sekali.
Fenomena kaum mustad’afin demikian itu pernah dituliskan oleh seorang antropolog asal Belanda, Roanne Van Voorst berjudul Tempat Terbaik di Dunia: Pengalaman Seorang Antropolog Tinggal di Kawasan Kumuh Jakarta (2018). Roanne menampakkan betapa hidup kaum lemah ini penuh dengan resiko: rawan banjir, kebakaran, dan juga penggusuran.
Kehidupan masyarakat kampung yang digambarkan Roanne sama sekali tak memiliki kelayakan. Sewaktu-waktu musim hujan mereka selalu kebanjiran, sering kebakaran, dan yang paling menyedihkan adalah mereka sering dihantui rasa takut oleh pemerintah kotanya sendiri yang akan menggusurnya. Dan memang benar, diakhir buku dikisahkan bahwa kampung mereka akhirnya digusur oleh pemerintah kota.
Kemiskinan dan Basis Islam Radikal
Fenomena kaum mustad’afin tersebut ternyata juga berkelit-kelindan dengan fenomena tumbuhnya islam radikal di Jakarta. Dalam buku hasil penelitiannya seorang peneliti Australia, Ian Douglas Wilson berjudul Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru (2018) memperlihatkan bagaimana kaum pinggiran Jakarta yang menjadi tumbal pembangunan ibukota mencari perlindungan dari ormas-ormas yang memiliki aspirasi politik yang reaksioner dan konservatif.
Para ormas islam radikal ini memanfaatkan kondisi ketersingkiran orang-orang pinggiran Jakarta untuk dijadikan sebagai basis massanya. Situasinya memang sangat pelik, para korban pembangunan ini memang tidak memiliki jaminan dan kepastian hukum sama sekali dari negara. Dalam kesulitan kehidupan sehari-harinya kaum pinggiran Jakarta ini, negara tak pernah hadir untuk membantu dan memberikan perlindungan kepadanya.
Dalam kesendirian masyarakat dalam menghadapi kesulitan hidup tersebut, yang datang dan mengulurkan bantuan adalah para ormas islam radikal yang tumbuh subur di daerah tersebut. Mereka memberikan jaminan keselamatan dari ancaman kejahatan dan sekaligus tak jarang memberikan pekerjaan kepada anak-anak muda di sana, melalui jaringan parkir di Jakarta.
Fenomena kesulitan ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh ormas yang pandangan keislamannya sangat primordialistik dan rasis. Oleh Ian D Wilson dalam tulisan yang lain menyebutkan bahwa besarnya gerakan 212 adalah keberhasilan ormas islam radikal dalam merekrut kaum mustadafin di sekitaran pinggiran ibukota.
Dalam kondisi kesulitan ekonomi dan fenomena uluran bantuan dari ormas islam radikal tersebut, mau tak mau memantik kesadaran kita untuk kembali memikirkan keislaman kita. Seharusnya, yang datang membantu kondisi kesulitan hidup para korban pembangunan kota tersbut adalah kita, kaum muslim yang memiliki aspirasi keislaman yang berbasis kemanusiaan.
Kemarin saya menyimak podcast dari teman-teman Seknas Gusdurian antara Buya Heru Prasetya dengan Roy Murtadho tentang Islam Progresif. Menurut Gus Roy, sapaan Roy Murtadho, bahwa seharusnya Islam seharusnya progresif, berpihak kepada kaum yang dilemahkan.
Dalam kasus keterpinggiran kaum mustad’afin di Jakarta, kehadiran Islam yang berpihak kepada mereka: penghuni kolong jembatan, rumah-rumah reot, pengemis, pemulung, dan tentu saja penghuni kos-kosan balok, sangat dibutuhkan. Karena jika saja yang datang mendahului kita adalah ormas islam radikal, semuanya akan menjadi sangat runyam, kemiskinannya tak tertangani, tapi kekerasan dan rasisme menjadi-jadi. Wallahua’lam.
M. Fakhru Riza, penulis adalah pegiat di komunitas Santri Gusdur Jogja.



