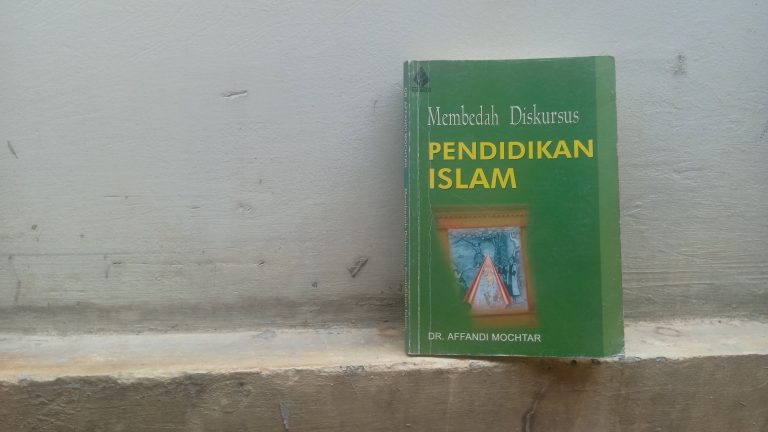
Udara pagi mengusap kulit kami, para alumni, yang sedang tergeletak di beranda gedung utama pondok. Waktu itu adalah 20 jam pasca reuni tahun 2017. Pondok Pesantren Ikhwanul Muslimin, walau namanya mirip kelompok kontroversial di Mesir, namun yang satu ini jauh berbeda, dan kini namanya telah berganti menjadi Madrasah Terpadu Tunas Cendekia.
Lokasinya di pojok area pesawahan desa Babakan, kecamatan Ciwaringin, Cirebon. Jadi, setiap pagi semburat matahari terbit bersama angin sawah selalu merayap di bangunan kotak tiga lantai warna hijau itu.
Matahari baru terbit. Wajah dan pakaian kami masih diselimuti lesu dan kusut. Dari kejauhan, sosok bersarung dengan pakaian rapih dan berwajah segar, perlahan mendekat ke arah kami. Sebagian dari kami yang sudah bangun bergegas mengucek mata. Sementara sebagian lain masih lelap tidur.
“ora keatisan tah? Turu e jeh pada ning jaba… (ga kedinginan? Tidurnya kok pada di luar…)” tanya beliau, KH. Affandi Mochtar.
“ora pak, bengen pas mondok biasa turu ning jaba… hehe (tidak pak, dulu pas mondok biasa tidur di luar)” jawab penulis.
Beliau masuk ke aula gedung utama, melihat-lihat sekitar tanpa satupun dari kami yang dibangunkan, lalu keluar dan duduk di taman depan gedung. Sebagian dari kami yang sudah bangun, walau dengan separuh nyawa, membangunkan kawan-kawan kami lain yang masih lelap.
8 hari lalu, figur itu telah berpulang. Dan kami baru tau ‘siapa’ beliau setelah beberapa taun pasca-reuni. Ketika acara tahlil 7 hari, disebutkan beberapa kontribusi beliau di Fahmina Institute, Kementrian Agama, dan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Maka terbayanglah kenangan memalukan tadi. Kini, kalau besok Covid-19 selesai dan kami bisa reuni kembali, tak ada lagi sosok itu.
Akan tetapi, tak ada yang terhubung dari seorang almarhum kecuali tiga hal: doa, sedekah jariah dan ilmu yang manfaat. Membedah Diskursus Pendidikan Islam adalah tulisan peninggalan beliau yang ditulis tahun 2001. Tebalnya 148 halaman, dengan substansi yang dapat dikatakan unik.
Sebagaimana judulnya yang memuat kata ‘diskursus’, kata ini sering identik dengan tradisi kritis, yang pada beberapa kesempatan analisis―di manapun dan oleh siapapun―sering dikaitkan dengan kata ‘kekuasaan’. Biasanya orang akan langsung terbayang nama Norman Fairclough atau Michel Foucault sebagai rujukan utama. Dua nama ini tak disebut sama sekali dalam daftar pustaka.
Kata ‘diskursus’ adalah tentang “pesan apa, untuk konteks seperti apa, bagaimana penyampaiannya, dan berpihak pada siapa.” Dengan kata lain, ‘diskursus’ adalah tentang sesuatu yang tersirat. Tepat pada pengertian inilah―walau tanpa Fairclough dan Foucault―buku yang terdiri dari tujuh bab ini mengambil sudut analisis.
Secara garis besar, Membedah Diskursus Pendidikan Islam membicarakan soal posisi dan peta kurikulum beserta desain institusional pendidikan Islam di Indonesia dibanding dengan disiplin besar asal Barat yang bernama Islamic Studies. Di sini, KH. Afandi memberikan analisa historis yang mengungkap bagaimana desain suatu ilmu beserta institusi keislaman tidak pernah netral dari kuasa tujuan.
Pengungkapan serupa―atau umumnya lebih dikenal dengan ‘analisa meta-teori’―di rumpun ilmu sosial umum sudah banyak. Namun dalam wacana keislaman-keindonesiaan, penulis baru menemukan di karya ini. Mungkin karena keterbatasan bacaan penulis dalam wacana studi Islam di Indonesia.
Di bagian pendahuluan, Islamic Studies diulas dan dievaluasi konstruksi bangunan keilmuannya, maksud dan tujuan studinya, dan nilai guna hasil studinya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dari abad pertengahan hingga pencerahan, Islamic Studies digunakan sebagai pembanding teologi Kristen yang lebih superior.
Di awal era modern, Islamic Studies digunakan untuk menunjang praktik kolonial dalam merumuskan kebijakan dan strategi politik yang lebih efektif. Akhir era modern, tujuannya masih sama. Hanya saja lebih diperkaya dengan perspektif kewilayahan. Keterbukaan dan tujuan yang lebih konstruktif baru mulai muncul di abad 20 ketika adanya kebutuhan dialog lintas agama dan pembangunan sesama.
Konsern buku ini sederhana: bagaimana posisi pendidikan Islam di Indonesia menentukan diskursus dan orientasinya di tengah arus besar Islamic Studies beserta institusinya yang telah mengglobal dan mapan sejak ratusan tahun? Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang, beserta kekhasan geografis dan kependudukan yang ada.
Afandi memulainya dengan pembahasan Kitab Kuning (sub-bab Mencari Akar Sejarah Kitab Kuning). Di sini, kecenderungan KH. Afandi terletak pada masalah genealogi intelektual dan akar tradisi akademik Islam yang termanifestasikan dalam kitab-kitab kuning sebagai pembanding Islamic Studies yang cenderung menggunakan tradisi keilmuan Barat dan belum tentu mengalami kontekstualisasi dari segi bahasa penyampaian.
Kitab Kuning dipandang sebagai elemen sentral karena, pertama, memiliki kekhasan dari segi etika transmisi, cara dan format penulisan; kedua, relevansinya telah terbukti sejak lama dan punya fleksibilitas dalam bentuk konteks penyampaian dan bahasanya; ketiga, kitab kuning adalah manifestasi dari diskursus yang menentukan corak keagamaan dan intelektual kalangan pesantren.
Masuknya pedagang dan ulama Timur Tengah ke Nusantara, di saat yang sama, juga membawa debat keagamaan di Nusantara sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah, yang intinya berpusar pada pilihan ortodoksi, sufisme dan rasionalitas. KH. Affandi mengkritik bahwa “akar intelektualisme islam di Indonesia adalah pemikiran sufisme yang, sayang sekali, tidak mencapai perkembangan terjauhnya dalam wujud wacana-wacana intelektual, melainkan lebih tentang wujud perilaku moral” (hlm.)
Dampaknya, sebagian besar proses pendidikan kitab kuning di pesantren berhenti pada hafalan dan pengulangan. Tradisi berkomentar, ataupun upaya penyegaran yang lebih kontekstual, tidak banyak dilakukan. Di lain pihak, implikasi ini diperkuat oleh kecondongan masyarakat pesantren pada bentuk ilmu yang ‘gaib’, ‘sakral’, dan termonopoli oleh figure tertentu (hlm.51). Diskursus dan corak intelektual menjadi statis.
Di sub-bab berikutnya, Tradisi Akademik Pesantren: Sisi yang Terabaikan, buku ini menunjukkan bahwa stagnansi di atas adalah sesuatu yang kebalikan dengan esensi pesantren. Dalam pandangan Kiai Affandi, pesantren adalah learning-society yang belajar 24 jam setiap hari dan terbiasa pada tradisi bahsul masail―gaya hidup intelektual yang sebenarnya dinamis, bukan statis.
Affandi menunjuk langsung pada karya Kiai Soleh Darat, Tarjamah Sabilul ‘Abid ‘ala Jawharat Tauhid, sebagai salah satu contoh bagaimana ketajaman nalar dan analisis yang berpadu dengan wawasan tasawuf dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Dalam contoh itu, dinukil salah satu bagian tentang: manakah yang lebih utama bagi orang yang didera kesulitan (khususnya ekonomi)? Kerja? Atau berserah diri?
Bagi Kiai Affandi, “tradisi akademik pesantren adalah suatu proses pembelajaran yang tuntas, yang dapat menampilkan satu sosok lulusan pesantren yang berwawasan luas, berkepribadian matang dan mahir melakukan rekayasa sosial … tanpa mengembangkan tradisi akademiknya, pesantren cenderung terasing dari lingkungan sekitar, sulit melebarkan pengaruh ke masyarakat, dan bahkan jatuh ke dalam fungsi instrumentalis sebagai sarana pendidikan semata” (hlm.81).
Akar klaim itu ia telusuri sampai periode Islam klasik. Dalam bab Tradisi Akademik Pendidikan Islam Klasik, diceritakan bahwa Skolastika Yunani memiliki pengaruh kuat terhadap tradisi akademik Islam. Madzhab-madzhab besar seperti Maliki, Syafi’I, dll. beserta murid-muridnya adalah penikmat munadharoh (forum debat terbuka untuk menguji sebuah argumen/teori kuat atau tidak).
Munadharoh merupakan tradisi yang disulam dari benang-benang skolastik seperti prinsip kesetaraan dan kebebasan berpendapat yang disertai tanggung jawab. Di lain pihak, Islam juga menekankan pentingnya ijtihad. Artinya, ada komitmen pemeriksaan atas kebenaran ajaran yang diterimanya.
Zaman bergulir, dan skolastika justru tumbuh subur di Eropa sampai menjadi tolak ukur utama bentuk pendidikan. Kemajuan yang dicapainya menarik negara-negara lain untuk mengadopsinya. Iran adalah salah satunya. Namun, sebagai bekas salah satu pusat peradaban klasik, apa yang dilakukan Iran tidak lain adalah memungut warisan peradabannya yang sudah lama terabaikan.
Sebagaimana yang dibahas dalam tiga bab terakhir buku ini, situasi pendidikan Islam Indonesia mengalami kompleksitas institusional dan diskursus. Awal abad 20, gerakan Islam modernis memberikan suara baru yang meresahkan pesantren sebagai institusi tertua di Indonesia.
Kompleksitas institusional semakin dinamis di era KH. Anwar Musadad, seorang Kyai sekaligus rektor pertama IAIN Bandung, yang mencetuskan integrasi tradisi pesantren ke dalam institusi modern. Menurutnya, IAIN perlu berjalan dalam dua unsur pendidikan, salafi dan modern. Akan tetapi, cita-cita ini pupus sebab tingginya beban politik institusi pendidikan Islam dalam percaturan politik nasional, yang kala itu, tahun 1980-an, kehadiran IAIN merupakan kompensasi bagi umat Islam atas berdirinya UGM.
Kompleksitas diskursus muncul ketika ‘kompensasi’ ini ditanya soal visi, orientasi dan luaran yang dikehendakinya. Tentu, pemenuhan tuntutan itu tidak dapat lepas dari kebutuhan yang muncul dari konteks kehidupan yang saat itu diwarnai devlopmentalisme Pak Harto, psikologi keterpinggiran umat Islam dari modernitas dan globalisasi, dan bargain posisi pendidikan Islam Indonesia dibanding negara-negara lain.
Tantangannya adalah bagaimana mencetak akhlak dan kesalehan, tapi disaat yang sama juga mencetak kompetensi modern. KH. Affandi melihat institusi pendidikan Islam di Indonesia, seperti IAIN, STAIN dan UIN perlu melakukan pembagian kerja atas tantangan yang ada.
Sepenggal pemikiran beliau kini telah berusia 20 tahun, tentu butuh beragam evaluasi dan pengembangan. Ada banyak hal yang bisa dijelajahi ketika peninggalan yang diwariskan berbentuk ‘peta’ desain wacana dan institusional, dibanding jika berbentuk doktrin ataupun apologetika. Karena dengan peta, kita bisa melakukan hitung-hitungan logis tentang tujuan, arah, titik mulai, strategi dan pengambilan sudut pandang.



