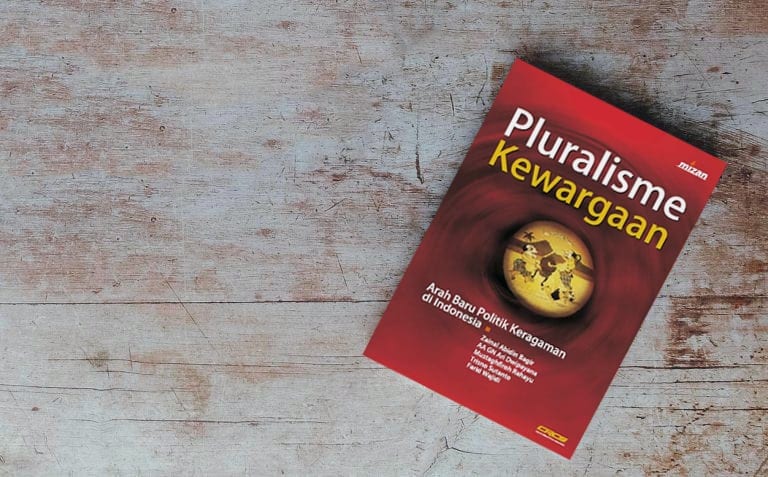
Telah banyak upaya yang dilakukan dalam mengelola keragaman di Indonesia. Melalui buku Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Zainal Abidin Bagir turut memberikan kontribusi dalam upaya tersebut.
Pengelolaan keragaman merupakan gerak krusial yang tidak boleh absen dalam negara berbasis pluralitas seperti Indonesia. Sebelum dikelola, keragaman perlu diakui karena ia melekat dalam demokrasi, sebuah sistem tata kelola politik yang menghargai otentisitas dan otoritas warga negara yang beragam.
Meski demikian, di samping sebagai bagian integral dari Indonesia, pengelolaan keragamaan juga harus diletakkan sebagai instrumen untuk memperjuangkan tujuan-tujuan komunal, yaitu kesetaraan dan keadilan sosial.
Zainal Abidin Bagir, dalam bukunya Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, memperkenalkan istilah “pluralisme kewargaan” untuk menunjukkan bahwa demokrasi, terutama di Indonesia, tidak semata mempromosikan sikap liberalism dalam berwarga-negara. Demokrasi juga bisa memberikan ruang yang lebih lebar bagi nilai-nilai publik dari identitas keragaman yang melingkupinya, seperti agama, adat, atau semacamnya.
Tiga Aspek Pluralisme Kewargaan
Prinsip “pluralisme kewargaan”, sekali lagi, ingin memberikan ruang sebesar-besarnya pada nilai-nilai berbasis identitas yang beragam sehingga kerja pengelolaan keragamaan itu bisa sekalian terpenuhi. Dalam eksekusinya, ada tiga aspek penting yang menjadi kerangka pengelolaan keragaman dalam bingkai pluralisme kewargaan, yaitu rekognisi, representasi, dan redistribusi sumber daya.
Kita mulai dari yang paling fundamental, rekognisi. Pengakuan (recognition) adalah dasar utama pluralisme kewargaan. Dalam tataran hidup keseharian, parameter rekognisi bisa dilihat dari sejauhmana berbagai identitas yang plural dalam masyarakat itu menghormati dan mengakui perbedaan dan keragaman satu sama lain. Pengakuan ini tak terbatas pada toleransi yang sekadar membiarkan identitas di luar dirinya hidup sendiri, melainkan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda dalam relasi antar kelompok.
Dalam konteks politik formal, rekognisi dilihat dari sejauh mana negara (pada tingkat nasional maupun daerah) menghormati dan mengakui berbagai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Juga, sejauh mana konstitusi mengekspresikan pengakuan itu, dan sejauh mana kebijakan-kebijakan negara merefleksikan jaminan konstitusi tersebut?
Rekognisi ini tentu bukan hanya dalam konteks hak-hak sipil dan politik, melainkan juga pada hak-hak sosial, ekonomi dan kultural. Termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional penghayat kepercayaan serta penghormatan pada identitas budaya dan kepercayaan di luar agama resmi negara.
Dalam bahasa lain, Indonesia memang sudah mempunyai instrumen hukum berbentuk UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 untuk mengakui keragaman kepercayaan dan membebaskan warganya untuk beragama. Namun, hal itu tidak cukup. Negara juga harus memenuhi hak-hak sosial kultural warga negara dari berbagai agama itu. Misalnya, pemenuhan soal fasilitas rumah ibadah yang layak bagi sebagian umat agama, atau jaminan perlindungan ketika beribadah. Dua hak dasar ini harus dipenuhi negara sebagai konsekuensi rekognisi negara terhadap keragaman.
Aspek kedua adalah representasi. Dalam mengelola keragaman, demokrasi menawarkan dua model keterlibatan, yakni jalur partisipasi dan kompetisi. Partisipasi berarti keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan tentang hidup bersama, dan setelah itu diikuti dengan kontestasi ide-ide yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
Sebaliknya, kompetisi memberikan ruang bagi warga negara untuk bertarung memenangkan gagasannya untuk jadikan landasan mengelola publik. Nah, representasi diperlukan untuk menghadirkan aspirasi warga negara dalam ranah publik melalui salah satu dari dua model tersebut.
Namun, representasi atau keterwakilan seringkali hanya merujuk pada fungsi lembaga perwakilan formal (parlemen) sebagai agensi penyalur kepentingan. Menyinggung pluralisme kewargaan dengan penekanan pada keragaman agama, di antara isu utama dalam representasi adalah, misalnya, apakah kelompok-kelompok keagamaan yang beragam bisa merepresentasikan aspirasi masing-masing dalam ruang publik? Siapa atau institusi apa yang digunakan untuk mewakilkan aspirasi mereka? Dengan cara apa? Bagaimana peta kekuatan dari intitusi representasi itu?
Isu soal representasi ini mungkin paling tepat dibincang dalam konteks permasalahan Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Kedua aliran Islam tersebut “digugat” sendiri olehsebagian umat Islam, sebagai payung akidahnya, bahkan hingga berdampak pada marginalisasi dan diskriminasi penganutnya. Kedua aliran tersebut tidak mempunyai cukup instrumen untuk merepresentasikan isu-isu yang dihadapi dalam internal komunitasnya.
Lagi-lagi, jika hanya mengandalkan representasi formal atau parlemen, maka fungsi keterwakilan itu tetap akan “prematur”. Karena pada dasarnya parlemen hanya akan mengakomodir suara yang dominan.
Pada akhirnya, jalur representasi alternatif yang diambil adalah melalui berbagai NGO’s atau komunitas aktivis semacamnya. Alternatif ini di satu sisi menjadi perdebatan terutama soal seberapa jauh para LSM yang notabene bukan milik Ahmadiyah atau Syiah itu bisa mewakili nilai-nilai perjuangan Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.
Aspek ketiga yang juga sangat esensial adalah tentang redistribusi sumber daya. Isu politik redistribusi dalam struktur ekonomi-politik yang terbangun dalam masyarakat lazim menyangkut tentang “siapa menguasai apa” atau “siapa memiliki apa” dan bagaimana pola hubungan produksi dalam masyakarat.
Pada ranah kebijakan, negara ditempatkan mewakili publik dalam melakukan fungsi redistribusi ini. Artinya, negara berperan mengelola keragaman melalui mekanisme kebijakan kesejahteraan, seperti perlindungan, kebijakan afirmatif pada warga miskin dan pemberian pelayanan publik.
Tujuan politis kesejahteraan negara adalah semata untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pertanyaan yang muncul adalah: apa saja yang telah atau seharusnya dilakukan oleh negara sebagai agensi publik dalam meredistribusikan sumber daya kesejahteraan? Apakah ada keberpihakan negara di sana? Dan, apakah itu bias keagamaan? Apakah kelompok-kelompok keagamaan memiliki mekanisme untuk mengatasi kegagalan negara dalam menjalankan fungsi redistribusi?
Pada dasarnya, pluralisme kewargaan bisa dilihat sebagai upaya negosiasi antara warga dan negara untuk mewujudkan kehidupan berbasis keragaman yang harmonis. Namun dalam konteks pengelolaan keragaman, mekanisme itu bersifat top-down. Negara seharusnya menjadi pihak yang aktif dalam mengawal kesejahteraan warga negara, dimulai dari aspek paling esensial yang menjadi identitas bangsa Indonesia, keragaman. [NH]



