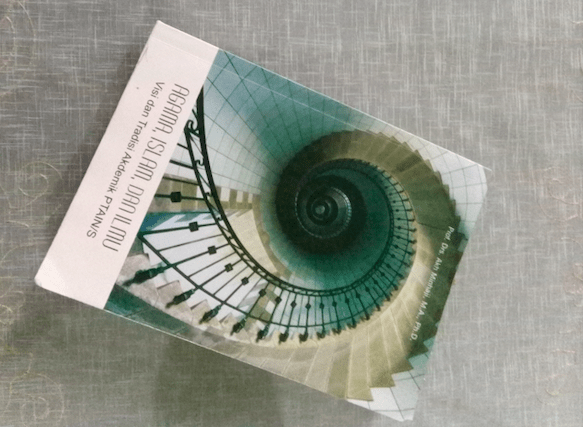
Menurut pandangan Minhaji, modernitas sebagai puncak prestasi bangunan ilmu ala Barat dinilai telah mendegradasi moral dan menjauhkan manusia dari agama, khususnya Islam. Sifat bangunan ilmu ala Barat yang melulu harus empiris, testable dan falsifiable telah menjadi standar akademik diberbagai kampus dan menjadi ‘cara pandang’ manusia modern di berbagai belahan dunia. Hal ini, menurut Minhaji, menggeser paradigma ilmu ala Islam yang bersifat ‘wahyu-plus-Allah-oriented’, yang cakupan dimensinya merentang dari mulai hal materil maupun non-materil.
Dengan kata lain, “paradigma ilmu tidak lagi dibangun atas dasar al-Qur’an dan Sunnah Nabi, tapi lebih merujuk pola pikir Barat-Modern-Sekuler” kata Minhaji (hlm.ix), “buku ini hadir untuk menggugah perhatian khalayak agar mencegah bangsa ini terjerumus pada lembah kesesatan yang lebih dalam” sambungnya (hlm.ix). Soal kesesatan, Minhaji menuding langsung pada maksim Karl Marx yang masyhur: “Agama adalah Candu” sebagai puncaknya.
Minhaji melihat bahwa, perguruan tinggi di Timur Tengah lebih berorientasi pada doktrin, sedangkan perguruan tinggi di Barat lebih pada metodologi. Dalam konteks inilah Minhaji menaruh harapan pada perguruan tinggi di Indonesia agar menjadi center of excellent, yang diprediksi dapat menjadi rujukan bagi masyarakat lokal dan internasional di kemudian hari bila mereka hendak mencari ‘doktrin sekaligus metode.’
Berangkat dari konteks itu, dan berdasar pada semangat ‘benturan peradaban Barat-Timur’ ala Hutington, Minhaji menyajikan analisis dan konsep pemikiran, baik filosofis maupun semi-praktis, soal bagaimana hal itu bisa dan seharusnya diterapkan pada kosmos keilmuan Islam umumnya, dan pada perguruan tinggi Islam khususnya.
***
Akan tetapi, buku terbitan SUKA Press tahun 2017 yang setebal 193 halaman ini memiliki beberapa masalah mendasar.
Pertama, buku ini belum memberikan evaluasi historis yang ketat soal dinamika atmosfer sosiologi pengetahuan di masing-masing daerah. Misalnya, Minhaji hanya berhenti pada klaim bahwa berpisahnya antara ilmu dan agama di Barat pada masa pencerahan (Aufklarung) adalah buruk, sedangkan integrasi ilmu dan agama di Timur (atau Islam) adalah baik―tanpa menguraikan implikasi di berbagai lapisan, baik itu lapisan teoritik, metodologis ataupun praktis dari sebuah bangunan ilmu yang disinggungnya.
Sementara itu, pertimbangan soal: mengapa scientific revolution terjadi di Barat; konteks masyarakat seperti apa yang melatar belakanginya; mengapa tragedi Galileo menjadi trauma tersendiri bagi Barat; apa implikasinya terhadap bangunan Ilmu ala Barat; dan bagaimana dinamika hubungan ilmu pengetahuan, masyarakat dan institusi agama di daerah Timur, tidak terasa dalam dialektika argumen dan analisa dalam buku ini. Sehingga, pada beberapa kesimpulan yang dibuatnya kurang bercorak sintesis.
Kedua, ‘Indonesia’ sebagai atmosfer sosiologi pengetahuan juga luput dari pertimbangan buku ini. Negara dunia ketiga umumnya punya corak dan sejarah ilmu pengetahuan yang berbeda dengan dunia Barat ataupun Timur Tengah. Di Indonesia, indigenous knowledge telah menjadi tulang punggung peradaban bagi berbagai suku dan etnis sejak lama. Namun saat kolonialisme hadir, indigenous knowledge terkubur dan tergantikan oleh bangunan ilmu modern Barat.
Baru kemudian di era presiden Soeharto, ilmu sosial modern ‘dijinakkan’ untuk melayani pembangunan ekonomi-industrialis dan mempertahankan kuasa politik rezim Orde Baru. Spektrum evaluasi ilmu sosial yang mulanya mencakup studi deskriptif-informatif, historis-interpretatif dan kritis-emansipatoris, disempitkan hanya sebatas deskriptif-informatif agar segala kebijakan Orde Baru mendapat ‘pembenaran’ yang seakan ilmiah dan terhindar dari kritik ataupun gonjang-ganjing akibat dua jenis studi di sampingnya.
Dampaknya, kampus-kampus umum di Indonesia pada masa itu cenderung berada di ketiak rezim Soeharto dan corak studinya lebih simpati terhadap studi deskriptif-informatif dibanding dua jenis studi lainnya. Hal ini masih terasa sampai sekarang, meski pengaruhnya kini semakin memudar, dan upaya untuk merestorasi rentang spektrum ilmu sosial telah digalakkan. Beberapa nama kunci dalam upaya ini misalnya, Ignas Kleden, Vedi Hadiz, Daniel Dhakidae, dan yang baru-baru ini naik panggung, Airlangga Pribadi Kusman.
Lalu, apakah perguruan tinggi agama Islam (PTAI) di Indonesia juga mengalami nasib intelektual yang serupa? Dan seperti apa posisi PTAI dalam relasi kuasa di masa Orde Baru dan di masa kini? Dua pertanyaan ini mendasar untuk dituntaskan lebih dulu sebelum merumuskan harapan dan formulasi PTAI di Indonesia sebagai ‘pusat doktrin dan metode’, agar bias-bias ideologis di belakangnya yang mungkin dapat menyebabkan distorsi metodologis dapat diinterogasi.
Namun diskusi dua soal itu kurang mendapat minat di lingkup PTAI umumnya, dan di kalangan intelektual profetik di Indonesia khususnya, dibanding diskusi soal integrasi Barat-Islam ataupun soal Islam-vs-Barat.
Dalam buku ini, sumber literatur Barat dan literatur Timur modern sangat dominan―dan nyaris tidak ada literatur Indonesia selain karya Kuntowijoyo, Nurcholis Madjid dan Harun Nasution yang dikutip. Terlebih lagi, sayangnya, di lokus literatur Barat, buku ini hanya bermain pada kutipan-kutipan yang bersifat testimonial dari beberapa komentator yang senada dengan semangat benturan peradaban ala Hutington, tanpa menunjukkan sejauh apa batas pengecualian yang dimaksud oleh komentator yang dikutipnya.
Sebaliknya, arsitek-arsitek utama bangunan Ilmu Barat, seperti Francis Bacon, Karl Popper, Lingkaran Wina ataupun Lingkaran Frankfurt justru tidak mendapat ulasan, evaluasi ataupun kritik sama sekali, karena memang tidak dikutip―kecuali Thomas Kuhn.
Di lokus literatur Timur, Kuntowijoyo (rasionalisasi teks agama) dan Ismail Raji Faruqi (islamisasi ilmu pengetahuan) memberikan warna yang dominan bagi corak gugatan buku ini terhadap bangunan Ilmu ala Barat―di samping pengaruh dari pemikir lain seperti Mohammad Arkoun dan Ali Syariati.
Komposisi literatur yang demikian, meninggalkan jejak bahwa argumen-argumen Barat dan Timur yang diimpor buku ini terputus dari pusaran debat ilmu sosial yang tengah berlangsung di Indonesia, dan nampak tak ada ruang bagi prospek perkembangan indigenous knowledge.
Ini agak paradoksal, sebab pada satu sisi, Islam di Indonesia dikenal sangat merawat kebinekaan hubungan sosial, namun di lain sisi, apakah telah dibarengi dengan merawat kebinekaan indigenous knowledge? Pertimbangan ini penting sebagai bentuk komitmen hidup di Indonesia.
Dari situ kemudian dapat ditanyakan, apakah rumusan integrasi ilmu dan agama ini juga sama-sama terjerembab pada proyek ‘dekolonisasi’ ilmu pengetahuan yang ahistoris sebagaimana yang dulu dialami oleh ilmu sosial di Indonesia saat baru diimpor dari Amerika di masa-masa awal Orde Baru? Biar waktu yang menjawabnya.
Masalah yang ketiga adalah, absennya kontekstualisasi pemikiran-pemikiran yang dikutip. Titik keberangkatan argumen yang menempatkan positivisme, empirisme dan rasionalisme Barat sebagai reduksi atas dimensi non-materil agama, sangat memikat untuk mengutip pemikir-pemikir kontroversial seperti Marx, Nietzsche, Camus, dan sejenisnya sebagai penegas antagoni Barat terhadap agama, tanpa secara proporsional menyebutkan pengaruh konteks pemikiran, irisan, kontribusi ataupun batas-batas pengecualian pemikiran mereka terhadap kehidupan manusia umumnya, dan terhadap bangunan ilmu pengetahuan khususnya.
Implikasinya, bangunan ilmu pengetahuan alternatif yang hendak dirancang oleh buku ini beresiko mengabaikan variasi-variasi fenomena empiris yang melibatkan unsur-unsur yang ditentang ataupun yang dibelanya. Misalnya, materialisme Marx dan nilai-nilai Islam. Kalau buku ini hanya mengakui bahwa materialisme adalah musuh Islam, maka, fenomena berkelindannya kapitalisme dengan agama di kasus Ahok-212, dan fenomena materialisasi agama Islam sebagai bentuk asuransi privilese sosial-ekonomi oleh kelompok Hijrah, akan tak terhimpun.
Pada titik ini, muncul peluang sikap yang inkonsisten, antara arsitektur bangunan yang telah didesainnya, dan klaim prestasi temuannya ketika berada di tataran praktik. Seseorang dapat mudah mengklaim atas signifikansi penelitian yang mengungkap, misalnya, bagaimana gerakan Islam transnasional bermain ekonomi politik dan hegemoni ideologi melalui kanal-kanal waralaba ataupun lewat kanal artefak kebudayaan seperti konten media sosial, hanya karena penelitian ini selaras dengan misi patriot Islam Nusantara yang dianutnya, meski di tataran konseptual ia tak bersepakat dengan teori ataupun paradigma yang digunakan penelitian itu.
Sementara itu, disaat yang sama, bangunan ilmu pengetahuan alternatif yang digagas buku ini juga mudah diretas. Seorang anggota gerakan Islam transnasional dapat dengan enteng mengatakan bahwa penelitian itu tidak Islami karena instrument yang digunakannya berasal dari materialisme Marx―sesuatu yang konon by design bertentangan dengan Islam. Dengan kata lain, apa yang digagas dalam buku ini punya potensi untuk menjadi bumerang.
Masalah yang keempat, ialah luputnya memperhitungkan sumbangan paradigma ataupun teori dari bangunan ilmu ala Barat yang digugatnya atas kehidupan manusia umumnya, dan kehidupan agama khususnya. Hal yang sangat terasa adalah adanya gugatan yang melompat dari positivism-empiris ala Barat ke dimensi ilahiyah agama. Dua aras tersebut semata dipertentangkan karena positivis-empiris ala Barat tak mengakui hal-hal yang gaib, tanpa melihat variasi-variasi paradigma yang ada di antara keduanya, dan bagaimana masing-masing dari itu membatasi diri satu-sama lain.
Teori kritis milik Madzhab Frankfurt misalnya. Karena asalnya yang merupakan turunan dari Marxisme, maka disebut oleh buku ini bahwa Teori kritis sebagai paradigma anti-kemapanan yang otomatis anti-agama (hlm. 144). Padahal, tanpa adanya teori kritis, atau paradigma kritis, manipulasi kesadaran yang mengatas-namakan agama tak mungkin bisa dibongkar. Manfaat teori kritis tentu semakin terasa di tengah situasi banjir pelintiran dan kebohongan di Internet.
***
Upaya membangun bangunan ilmu alternatif dapat terjerembab pada tendensi ‘mengukuhkan tirani mayoritas’ kalau nilai-nilai partisan yang dikedepankannya justru malah melonggarkan keketatan ilmiah, baik itu ketat dalam proses pembangunannya, proses penelaahan pemikiran terdahulu, ataupun proses perhitungan konsekuensi teoritik ataupun praktis atas bangunan yang hendak diciptanya. Resiko ini dapat semakin besar kalau kelahirannya hanya dibidani oleh iklim tautologis, sementara iklim keketatan berlogika masih belum mapan, dan iklim kritis/jujur terhadap pikiran sendiri masih belum diminati.
Di Islam, ada dua prinsip utama mencari ilmu: “lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan” dan “pungutlah hikmah (insight) di mana pun hikmah itu ditemukan.” Di Barat, orang kenalnya “saya bisa salah, anda mungkin bisa benar. Maka, mari diskusikan bersama.”



