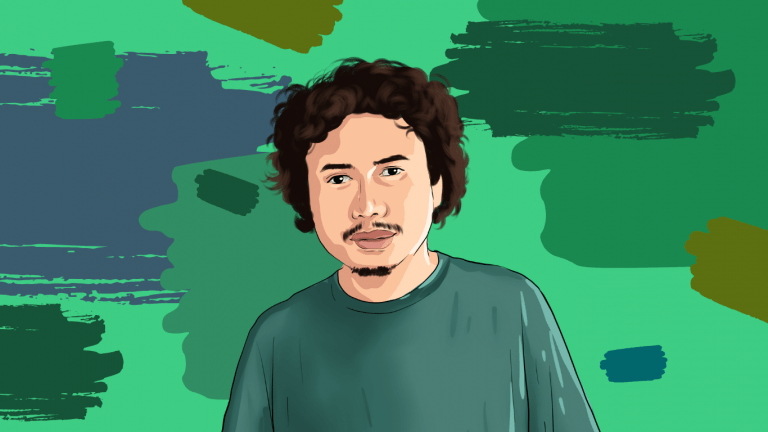
Salah satu episode sejarah yang seringkali saya baca dengan perasaan tak menentu adalah periode menjelang kekalahan umat Islam di Spanyol.
Ketika senjakala politik dan ekonomi Arab-Islam di Eropa tak terhindarkan, sebagian ulama (intelektual) pada masa itu menulis periode dalam keragaman yang penuh nuansa kegetiran. Beberapa di antaranya adalah soal pencapaian politik, ekonomi, dan tentu budaya yang sulit diselamatkan.
Mungkin banyak orang merasa senang tetapi sekaligus sedih ketika membaca novel Leo The African-nya Amin Malouf yang merekam sejarah Arab-Islam di Semanjung Iberia dari abad ke delapan sampai abad 13 Masehi.
Tetapi benarkah kehancuran, pasang-surut, kemaju-mundurannya semata karena ulah manusia? Di mana intervensi alam dan bagaimana dengan makar (muslihat) Tuhan dalam sejarah manusia? Benarkah semuanya terjadi karena umat Islam tidak rasional, tidak progressif dan liberal? Merosot secara politik, ekonomi dan intelektual?
Saya tertawa dengan kejangakan intelektual seperti yang dikampanyekan Mustafa Akyaol yang laris manis belakangan.
Sudah saatnya umat Islam melihat sejarah dalam nuansa yang lebih variatif. Sudah bukan masanya mempercayai wacana murahan seperti keterbelakangan intelektual, ketidak-terbukaan, ketidak-cakapan, dan ketidak-setaraan masyarakat muslim sehingga bernasib nahas seperti hari ini.
Sebagai llustrasi, berikut tanggapan dua ulama muslim yang hidup di masa senjakala kekuasaan Arab-Islam di Eropa, yakni Ibnu Khaldun dan Ibn Abbad dari wilayah Ronda.
Pada masa dinasti-dinasti atau kekhilafahan klan, dari Ummayah, Abbasiyah, Fatimiyah, Seljukiyah, Maridiniyah, dan banyak dinasti penguasa lain dalam lintasan sejarah Islam dikenal-lah istilah “pekerja budaya”. Hari ini mungkin bisa diistilahkan sebagai “intelektual-kantoran”, perseorangan atau klan (keluarga) yang mengabdi kepada para penguasa.
Salah satunya adalah, yang paling terkenal, Abdurrahman ibn Khaldun (1332-1406). Ia berasal dari keluarga pekerja budaya yang mengabdi dari satu dinasti ke dinasti lainnya.
Pada masa genting di Spanyol, menjelang inkuisisi, keluarga ini sedang berada di Spanyol, tepatnya di Sevilla. Tapi begitu kerajaan-kerajaan Katolik di Utara mulai berekspansi ke Selatan, keluarga ini kembali ke Tunisia.
Ibnu Khaldun (saya tidak memasukkan kajian akhir Syed Farid Al-Attas terhadap Ibn Khaldun) belajar tentang beragam fan atau disiplin pengetahuan dari ayahnya, dari para sarjana yang mengajar lembaga-lembaga skolastik dan humanistik (sebaiknya membaca kajian George Makadisi terkait ini).
Ibn Khaldun menulis catatan harian tentang matakuliah yang dipelajarinya, tidak saja menulis nama dari guru-gurunya, tetapi juga menggambarkan fisik, karakter dan (bahkan) bagaimana sebagian besar guru-gurunya meninggal akibat sampar “penyakit hitam” yang melanda dunia pada pertengahan abad ke-14.
Pada usia belasan tahun, Ibnu Khaldun mengabdi kepada penguasa Tunusia. Para penguasa Tunusia sebelumnya pernah membunuh kakeknya yang menyebabkan ayahnya lebih memilih kehidupan ‘pekerja budaya’ (intelektual) yang lebih sunyi, menjauh dari politik.
Pada usia 20 tahun ia telah mendapatkan jabatan politik yang lebih rumit dari para penguasa. Seperti halnya orang hari ini yang mengejar patronase politik, kedekatan dengan para penguasa dianggap sebagai keberuntungan.
Dari Tunisia ia melancong ke daerah Maghrib (Spanyol). Kecakapannya menarik perhatian para penguasa muslim dan mengutusnya sebagai seorang duta penguasa muslim kepada para penguasa Katolik di Spanyol.
Waktunya terasa sangat pendek. Sebagai seorang pekerja budaya, sebagian waktunya tersita oleh urusan politik dari pagi sampai sore hari (seperti ASN hari ini). Pada malam hari ia menyempatkan diri mengajar di masjid, yang saat itu menjadi salah satu pusat pengajaran skolastik Islam.
Antara tahun 1375 sampai 1379 (sekitar empat tahun) Ibnu Khaldun tinggal di sebuah kastel di pedesaan al-Jazair. Dengan berkurangnya kerja politiknya sebagai pekerja budaya, ia terbebas dari urusan-urusan dunia. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan oleh Ibn Khaldun untuk menulis sejarah para penguasa di Magrib.
Di Berber, Ibn Khaldun bertugas memastikan kesetiaan pada suku nomad yang menetapi padang rumput yang terpencar. Makanya dalam kitab Muqaddimah ia menulis bentuk-bentuk masyarakat sederhana berbasis kesukuan yang menjadi ciri masyarakat Arab.
Ibn Khaldun melihat energi alamiah dari masyarkaat kesukuan yang menempati pegunungan dan padang rumput dengan cara bertani, berternak, dan tanpa ada kepemimpinan yang teroganisir.
Dari titik inilah muncul kaidah tentang kelemahan bangsa Arab dalam membangun kota-kota, peradaban, dan budaya yang tinggi. Bagaimanapun, kitab Muqaddimah yang dielukan sebagai pengantar pertama sosiologi itu ditulis di masa “sekaratnya” sebuah peradaban”: kemenangan, keberuntungan, dan capaian intelektual, ekonomi dan politik yang sedang kehilangan enigma dan aura kerahmatannya. (Jadi jangan membayangkan peradaban kalau kita tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik, pakai aja istilah lain)
Kultur ashabiyah (dua arti harfiah dari kata ini: kesukuan dan juga bisa kultur perkotaan) dalam pengertian Ibnu Khaldun adalah ketika masyarakat pegunungan dan padang rumput ini berkembang menjadi satuan-satuan politik yang mengandalkan sentimen kesukuan dan kekerabatan yang diikuti oleh banyak kelompok masyarakat lain di sekitarnya. Dari situ tumbuhlah dinasti-dinasti kota yang cukup stabil dengan gaya hidup mewah dan budaya tinggi.
Namun kultur dasar pedesaan tetap kuat, sehingga dinasti-dinasti berbasis loyalitas kekerabatan memiliki hukum-hukum kelemahannya sendiri: gaya hidup mewah, tirani, dan kualitas pemerintahan politik yang cepat merosot.
Ketika stabilitas kekuasaan memudar, dinasti yang terdiri dari suku-suku ini akan kembali ke hukum semula kehidupan nomad: suku lain akan mengambil kekuasaan dari suku penguasa sebelumnya.
Ibnu Khaldun kalau secara blak-blakan ingin memberikan gambaran gamblang dari pertumbuhan dan kemerosotan dinasti-dinasti keislaman mungkin akan menjadi begini:
“Bagaimana agama dengan wahyu terkahir ini dikembangkan oleh elite dari suku-suku nomad Arab yang tidak memiliki kecakapan mencipatakan stabilitas politik karena kultur persaingan suku yang tidak ada ujungnya?”
Saya tidak sedang menceritakan kitab Muqaddimah yang kemungkinan diselesaikan ketika Ibn Khaldun kembali ke Masyriq (Arab Timur), di mana ia pertama kembali ke Tunisia dan kemudian ke Kairo karena kondisi politik di Maghrib sudah memasuki senjakala: sebuah peradaban yang seperti kehilangan rahmat dan tidak mungkin diselamatkan. Inilah yang sedang diratapi Ibn Khaldun.
Pada masa di Timur kedua inilah ia sempat bersama penguasa Tunisia ke Palestina dan di sana ia bertemu dengan Timur Lenk yang digambarkannya sebagai sosok yang memiliki persyarat sebagai pemimpin yang akan membawa kekuasaan kota, peradaban tinggi, karena bertumpu pada tantara dan rakyat. Kita melihat pendapatnya yang berubah-rubah seiring dengan perubahan kehidupannya yang getir.
Orang tuanya meninggal karena wabah Covid, sedangkan anaknya meninggal karena tenggelam di lautan. Dan, ini yang paling penting di masa akhir hayatnya, Ibnu Khaldun merenungi “getirnya takdir” perulangan dari keterlibatan Allah dalam kehidupan manusia.
Ketika Ibn Khaldun tiba di Mesir, perulangan itu seperti nyata, bagaimana ia merasa dikembalikan ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari asal semulanya sebelum ia ke Sevilla, dari titik berangkatnya pertama dengan suasana penuh perenungan.
Di masa akhir inilah Ibn Khaldun melihat banyak hal yang lebih penting daripada peristiwa peralihan kekuasaan dan peradaban. Melihat pesona bahasa Arab, melihat tempat-tempat suci yang tidak terganggu oleh peralihan kekuasaan, dan bagaimana iman kepada Allah menyelamatkannya dan memberinya makna di tengah permainan takdir.
Ketika Ibn Khaldun masih di daerah Maghrib, ada seorang ulama lain, seorang sufi dalam pengertian sejatinya, bernama Ibn Abbad dari Ronda (Ronda adalah sebuah wilayah di Spanyol di perbukitan yang sangat indah).
Jika Ibn Khaldun lebih melihat “senjakala peradaban Islam Eropa” dari sudut struktur politik yang terpecah-belah, merosotnya pertanian, lesunya ekonomi, dan pertahanan militer yang tidak memadai, maka Ibn Abbad di tengah “firasat malapteka” yang mengejar benak para pekerja budaya (ulama) di masa itu justru lebih terang-terangan menyandarkan harapannya kepada Allah.
Ibn Abbad meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhannya sejarah. Kekuatan ekonomi dan politik bukanlah segalanya. Para pengausa menyimpang, para kelas menengahnya jangak (cabul, tidak senonoh), dan moral tentaranya lemah.
Maka, selama ada iman di hati manusia, apa yang disebut “firasat malapetaka” hanyalah gambaran dari kelemahan iman manusia dalam menerima keterlibatan Allah SWT dalam kehidupannya.
Begitulah, garis sejarah selalu tentang kemungkinan dari perubahan. Sekali lagi kemungkinan. Perubahan terjadi bukan karena berlangsung-lurusnya tindakan dan rencana manusia dengan segala capaian pikiran dan ilmunya. Perubahan lebih sering disebabkan oleh campuran dari agregat tindakan manusia dalam hubungannya kelakar alam dan makar Tuhan.



