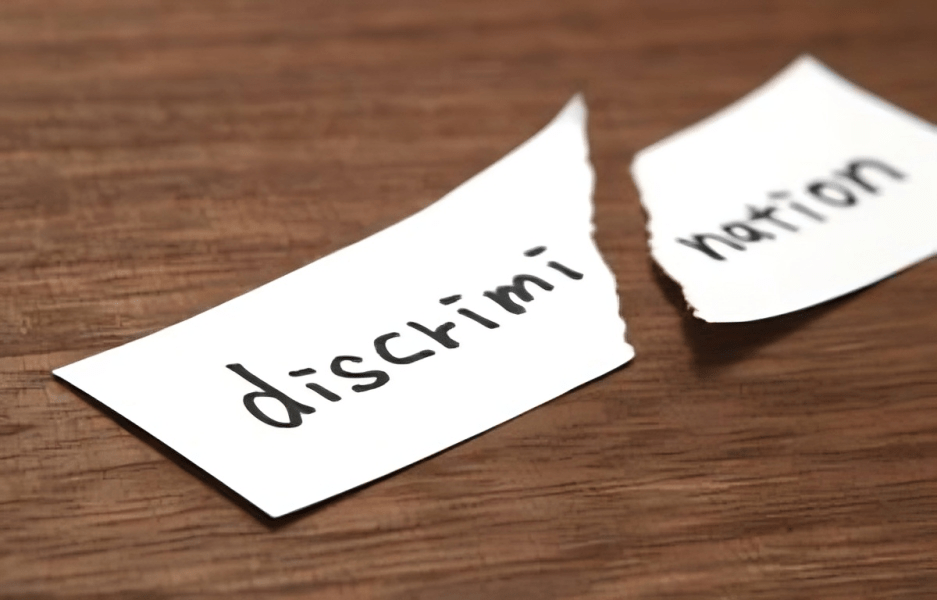
Jalan terjal masih harus ditempuh dalam penerapan nilai-nilai toleransi di Indonesia. Salah satu isu toleransi yang paling sering muncul ialah kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk dalam melaksanakan ibadah.
Sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (Unpam) yang sedang berdoa Rosario dibubarkan paksa oleh massa yang diduga diprovokasi oleh oknum RT 007 RW 002, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Gang Ampera Poncol, Tangerang Selatan, Senin (6/5/2024).
Dalam peristiwa itu, mahasiswa beragama Katolik yang menggelar Doa Rosario berjumlah 15 orang. Dua korban wanita mengalami luka sayatan senjata tajam dari masa penyerang dan satu orang lelaki mengalami luka usai dibacok saat berusaha melindungi para mahasiswa yang sedang beribadah.
Tragedi ini sepertinya bakal menambah daftar panjang kasus intoleransi berbasis kekerasan di Indonesia. Ironisnya, pihak yang seringkali bertanggungjawab atas persekusi semacam ini adalah mereka yang mengatasnamakan Islam. Namun berbeda dengan kasus kali ini. Tidak ada embel-embel ormas atau kelompok keagamaan tertentu di balik agenda pembubaran.
Kapolsek Cisauk Ajun Komisaris Dhady Arsya, mengutip Kompas, menuturkan, memang ada mahasiswa yang sedang berdoa di salah satu indekos. Namun, bukan karena mereka beribadah lalu diprotes warga. Sebelumnya, seperti yang dilaporkan, warga sudah memberikan teguran karena keramaian yang ditimbulkan oleh para mahasiswa yang kerap berkumpul hingga larut malam. Aktivitas itu mengganggu warga sekitar. Akan tetapi, teguran itu kerap tidak dihiraukan oleh sejumlah mahasiswa.
Puncaknya, pada Minggu malam, warga merasa perlu kembali menegur para mahasiswa itu agar tidak beraktivitas hingga larut malam lagi. Sayangnya teguran itu berakhir pada perselisihan hingga perkelahian antara warga dan kelompok mahasiswa. Ketua RW 002 Marat mengatakan warga tidak mempermasalahkan kegiatan ibadah. Hanya, dalam beberapa kegiatan mahasiswa kerap berkumpul setidaknya 10-20 orang. Ia menuturkan bahwa kejadian di Pamulang itu bukanlah isu SARA, melainkan persoalan etika sosial dan kesalahpahaman belaka.
Doa Rosario adalah penghormatan kepada Bunda Allah yang selalu dilakukan oleh umat Katolik setiap bulan Mei dan Oktober sebagai bulan Maria di Komunitas Basis Gerejani (KBG) dan dalam keluarga Katolik. Doa Rosario merupakan sarana bagi umat Katolik untuk mengimani Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Doa Rosario menjadi doa pemersatu dalam keluarga agar keluarga menjadi satu ikatan yang kuat.
Doa Rosario merupakan doa yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di kalangan umat Katolik yang dipahami sebagai doa yang dedikasikan kepada Bunda Maria sebagai penghormatan dan juga sebagai ungkapan kasih dari manusia kepada Bunda Maria. Ritual doa tersebut hanya dilakukan selama dua kali dalam setahun dan memang dilakukan di rumah-rumah pemeluknya, bukan di gereja.
Seperti yang dilaporkan, “mengganggu warga” menjadi dalih utama pembubaran. Dikutip Kompas, Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Tangerang Selatan, Asep Aziz Nasser, menjelaskan, konflik di Kelurahan Babakan tidak berkaitan dengan persoalan agama, tetapi terkait etika sosial. Namun demikian, sulit untuk tidak melihat irisan agama dalam kejadian tersebut.
Di satu sisi, persoalan etika sosial memang sah diutarakan. Sebagai umat beragama, mereka perlu memperhatikan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Ibadah berlebihan dan mengganggu ketertiban juga tak bisa dibenarkan. Tetapi di sisi lain, apakah kita sudah yakin ibadah kita tidak “merugikan” orang lain?
Tulisan ini tidak sedang menghakimi salah satu pihak, tetapi lebih pada evaluasi karakter beragama kita. Mengapa terjadi standar ganda terkait isu etika sosial ini. Mengapa kebisingan yang sama boleh dilakukan oleh kita, namun menjadi salah jika dilakukan komunitas agama lain. Tidak usah jauh-jauh, kasus Meiliana dan toa masjid adalah contoh konkretnya.
Dalam kasus toa masjid misalnya, saya sempat dicurhati oleh guru saya beragama Katolik bahwa ia mengeluhkan suara toa masjid yang ada di sebelah tempat tinggalnya di Yogyakarta yang begitu mengganggu, terutama ketika menjelang subuh. Saya sempat menyarankan untuk lapor kepada takmir masjid tersebut.
Namun, melihat pernah ada kasus pemidanaan terkait pelaporan seperti ini ini, nyali guru saya keburu ciut sehingga mengurungkan niatnya. Saya merasa bersalah akan hal ini. Betapa keegoisan umat Islam sangat berdampak pada psikologi umat non-Islam. Sikap eksklusivitas ini menyandera hak-hak suara minoritas yang harusnya bisa mereka ekspresikan.
Kekerasan juga menjadi catatan penting peristiwa pembubaran doa rosario di Pamulang. Kekerasan tidak dibenarkan dalam kondisi dan situasi apapun, terutama menyangkut sentimen keagamaan. Pelaku kekerasan dan penyerangan memang sudah diproses pihak kepolisian, tetapi alasan “etika sosial” kemudian menjadi tidak relevan karena kekerasan yang dilakukan justru menciderai “etika sosial” itu sendiri.
Saya khawatir standar ganda ini adalah salah satu sifat yang melekat pada umat beragama kita, yaitu egoisme beragama dan mayoritarianisme. Pertanyaannya adalah mengapa justru umat Islam yang menjadi momok bagi kesejahteraan kehidupan beragama di Indonesia? Pertanyaan retorik memang, namun penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama.
Sebagai refleksi, kita perlu menyadari bahwa status Islam sebagai agama mayoritas bukan semata selalu bernilai positif bagi masyarakat di sekitar kita. Hal itu karena superioritas ini rentan dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam untuk memecah belah masyarakat.
Eksploitasi tersebut tercermin salah satunya dari standar ganda ini. Perasaan ini lazim disebut logika mayoritarianisme. Perasaan ini muncul dari alam bawah sadar bahwa posisinya dominan sehingga merasa memiliki keleluasaan dalam bertindak.
Gus Dur pernah menyatakan, persekusi yang sering dilakukan oleh oknum keagamaan salah satunya disebabkan oleh pendangkalan agama dari kalangan umat itu sendiri, terutama angkatan mudanya. Umumnya mereka hanya memahami interpretasi keagamaan secara tekstual, namun pemahaman terhadap substansi ajaran masih lemah. Karena itu, mereka tertutup untuk mengenal kepercayaan dan ritual agama lain.
Sukar memang membedakan, pembubaran itu adalah murni karena norma sosial atau sedang memberi makan ego beragamanya. Tenggang rasa antar umat beragama adalah sarat mutlak untuk hidup berdampingan.
Kedua, kegagalan elemen negara, dalam konteks ini RT/RW sebagai unsur negara di lingkup terkecil, di ranah masyarakat untuk menjamin hak semua warga atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Karenanya, isu toleransi ini bukan hanya sekadar bottom up-policy, namun juga top down-policy. Di akar rumput, masyarakat perlu mengupayakan untuk menjadi umat beragama yang berintegritas dengan memperbanyak wacana yang mendamaikan, bukan meresahkan. Wacana untuk saling menghormati bukan menghakimi, wacana untuk saling mengayomi bukan mempersekusi. Di ranah elit, setiap sub-unsur pemerintahan harus memiliki visi kehidupan kebangsaan yang harmonis.
Apakah kita tidak lelah melihat masyarakat beragama yang dicitrakan penuh kekerasan dan intoleran. Siapa lagi yang akan mengukir citra umat beragama yang ramah dan penuh kasih kalau bukan kita sendiri?



