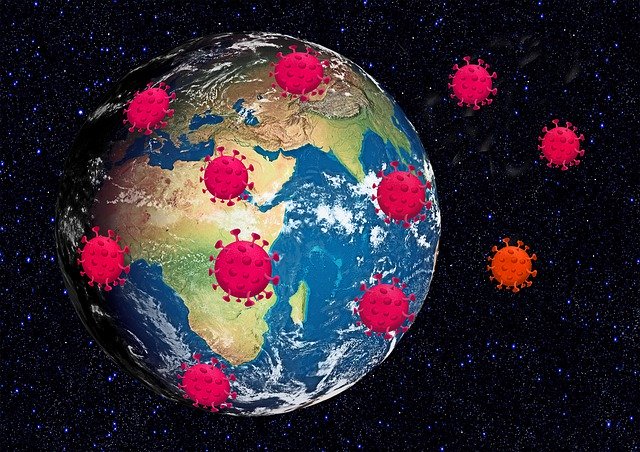
Beberapa waktu lalu, saat mengunjungi pasar dekat kontrakan untuk keperluan membeli kebutuhan stok bahan pangan masa karantina mandiri ini, saya melihat ada beberapa suasana yang berbeda. Pasar kecil itu kembali padat, padahal dua minggu belakangan ini jumlah pengunjungnya lumayan menyusut. Begitupun para pedagangnya, mereka mulai membuka lapak kembali setelah dua minggu tidak berjualan akibat teror pandemi Corona.
Serupa dengan itu, sebuah mini market yang biasa saya kunjungi untuk mengambil cuan di ATM-nya, pengunjungnya kembali padat. Antrean di meja kasir kembali berderet dan semuanya tampak normal kembali. Padahal kurang lebih dua minggu yang lalu, intensitas pengunjungnya sudah cukup surut.
Semuanya tampak sudah kembali normal. Tunggu dulu!! Ini bukanlah keadaan yang sebenar-benarnya normal. Melihat data dari pangkalan data perkembangan penularan wabah Covid-19 di Jogja mengabarkan terus adanya peningkatan. Kini, jumlah pasien positif sudah berjumlah sedikitnya tiga puluhan lebih, artinya ada peningkatan jumlah yang cukup signifikan dari sejak pertama kali infeksi dideteksi di kota pariwisata ini.
Jika data jumlah pasien yang terinfeksi Corona terus menanjak, mengapa banyak warga mulai kembali membanjiri jalanan, pasar-pasar dan ruang berkumpul yang telah dihimbau untuk dijauhi? Apakah mereka tak takut lagi dengan pandemi ini?
Nampaknya bukan sebab tak takut dengan pandemi pembunuh berdarah dingin ini. Sebaliknya, hal itu saya kira lebih disebabkan oleh alasan-alasan yang sifatnya kompleks, berkaitan dengan kebutuhan mencari penghidupan dan kebosanan setelah berdiam diri di rumah selama kurang lebih dua minggu ini.
Perihal kebutuhuan mencari penghidupan ekonomi, pemerintah beberapa waktu lalu sebetulnya telah memberikan berbagai paket kebijakan ekonomi dalam rangka menghadapi pandemi ini. Dari berbagai bentuk kebijakan ekonomi pemerintah itu, yang menjadi prioritas adalah masyarakat kelompok rentan dan miskin. Bantuan keuangan langsung, penggratisan dan diskon listrik, hingga relaksasi kredit kendaraan telah diberikan.
Namun, nampaknya pemerintah lupa satu hal: apakah kelompok kelas menengah kita yang tak tersentuh dari berbagai paket kebijakan pemerintah tersebut benar-benar mampu secara ekonomi untuk tidak bekerja selama masa isolasi diri yang tak tahu sampai kapan ini ?.
Ya, ada kekhawatiran bila mereka bakal tumbang juga pada minggu-minggu setelahnya, meskipun di minggu pertama hingga minggu kedua dapat bertahan hanya diam di rumah dan hidup dengan tabungan belaka.
Kelas menengah ini tak dapat benar-benar tenang melakukan karantina mandiri di rumah. Meskipun tak terlalu risau soal makan, namun bagaimana dengan tagihan perbankan untuk modal usahanya yang kini ditutup? Bagaimana nasib gaji ataupun tunjangan untuk karyawannya?
Kondisi itu ditambah rumit dengan kurang jelasnya strategi penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang dinilai masih setengah hati, tidak memberikan kejelasan kapan persisnya kita rampung untuk melakukan karantina mandiri dan dan dapat pulih bekerja. Sebulan? dua bulan? Atau berapa? Tidak jelas.
Kejelasan perihal waktu karantina mandiri ini penting bagi warga masyarakat. Masyarakat menjadikan kejelasan waktu karantina sebagai patokan untuk menghitung estimasi kebutuhan ekonomi selama masa itu dilakukan. Jika pemerintah tidak memberikan kejelasan waktu berapa lama hal ini akan dilakukan, warga masyarakat semakin berat memperiapkan perhitungan kebutuhan dan daya tahan tabungannya selama pandemi ini.
***
Perihal lain yang nampaknya melatari warga masyarakat kembali melakukan aktivitas normal di luar rumah adalah mereka merasa pandemi ini sebagai masalah yang nun jauh di sana. Terlebih lagi, informasi yang disampaikan pemerintah nampak ajeg dan lama kelamaan mudah kita tebak.
Ringkasnya, berbagai data laporan pemerintah, kini, dalam benak warga masyarakat hanya sebatas angka-angka yang tidak muncul di depan mata langsung. Informasi dan himbauan yang awalnya menakutkan itu, kini tampak menjadi biasa-biasa saja. Mara bahaya itu kini telah menjadi sebuah kenormalan.
Normalisasi yang terjadi dalam masyarakat ini sebetulnya sering terjadi dalam pengalaman hidup kita sebagai umat manusia. Kita sebagai manusia agaknya memiliki sebuah perasaan yang jika ditekan secara berulang-ulang, pada momen tekanan yang kesekian kalinya kita akan merasa bahwa tekanan tersebut menjadi sesuatu yang tidak membebani.
Perihal normalisasi ketakutan ini saya teringat kisah dari simbah saya. Saya selalu merinding ketika simbah bercerita pengalaman hidupnya bersama beberapa temannya membuka rimba hutan Sumatera untuk dijadikan wilayah perumahan penduduk. Saya membayangkan begitu menakutkan sekali membabat hutan yang masih banyak hewan buas dan makhluk astral itu.
Namun, ketakutan itu nampaknya hanya imaji saya semata yang tidak mengalami masa sulit itu secara langsung. Padahal, nampaknya simbah menceritakan pengalaman itu secara biasa-biasa saja. Agaknya, pengalaman yang bagi saya cukup mengerikan itu, baginya hanya momen yang dianggap biasa-biasa saja. Mungkin karena sudah terlalu terbiasa dengan kegetiran hidup, menghadapi berbagai peristiwa yang mengerikan itu bagi simbah akhirnya (dianggap) menjadi biasa-biasa saja.
Sebagaimana yang dialami simbah saya, kebanyakan warga masyarakat kini menjadi terbiasa dengan keadaan yang menakutkan seperti pandemi Corona ini. Wabah itu kini telah dinormalisasi. Situasi ini di satu sisi adalah sebuah kabar baik, warga masyarakat tidak mengalami kekhawatiran yang berlebih. Namun, di sisi yang lain adalah sebuah bencana. Kini terjadi keacuhan terhadap pandemi ini.
Dan tentu saja ini sangat berbahaya. Namun, harus bagaimana lagi. Di tengah kebijakan penanganan pandemi dari pemerintah yang serba setengah hati seperti saat ini, mau tak mau mengharuskan banyak warga masyarakat harus punya inisiatif mandiri untuk menyelamatkan dapur keluarganya. Sebab perihal dapur ini tak bisa dianggap tak kalah berbahaya bukan?
BACA JUGA Pandemi Covid-19, Rahmat atau Azab? ATAU Artikel-artikel Menarik Lainnya



