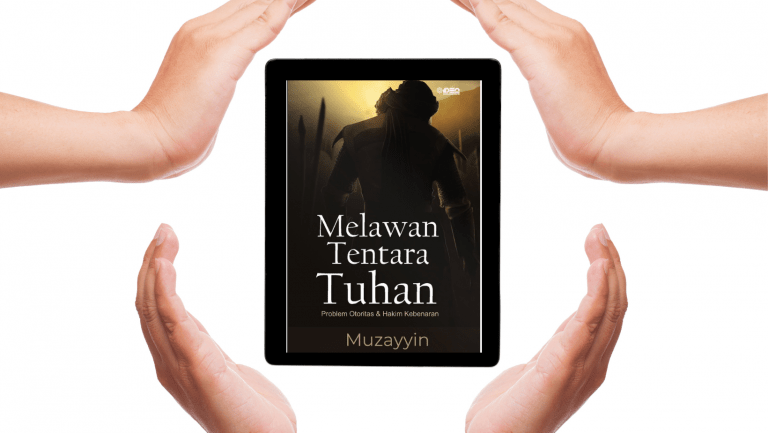
Beberapa waktu lalu, salah seorang rekan di universitas tempat saya mengajar mengungkit sebuah pertanyaan lawas mengenai apakah agama justru menghambat kemajuan pola pikir bangsa Indonesia?
Pertanyaan tersebut ia lontarkan usai membicarakan sejumlah permasalahan dalam konteks umat Islam di negara kita yang sampai sekarang masih kerap diwarnai isu-isu intoleransi.
Menurutnya, alih-alih melihat gagasan-gagasan besar dalam Islam yang dikaji menggunakan beragam perspektif keilmuan dan menjadi motor bagi gerakan sosial yang progresif, kita justru lebih sering disuguhi ormas Islam A membubarkan pengajian karena penceramahnya dari Kelompok B yang, mungkin secara sepihak, dianggap berseberangan dalam ideologi atau dinilai radikal serta berbahaya; kemudian, para penceramah yang kerap membid’ahkan atau bahkan memberi label kafir kepada orang-orang di luar kelompoknya.
Pendeknya, antar-kelompok muslim di Indonesia seakan-akan senantiasa memendam ketegangan-ketegangan yang serupa bom waktu, dan ia bisa meledak setiap saat dan melukai banyak pihak.
Sekitar seminggu setelah obrolan tersebut, saya berkesempatan membaca buku karya intelektual muda asal Jember, Muzayyin. Judulnya adalah Melawan Tentara Tuhan: Problem Otoritas dan Hakim Kebenaran (2023).
Saya pikir buku ini akan ‘menggelisahkan’ bagi sebagian kaum muslim di Indonesia. Sejak dari judul saja, buku ini cukup provokatif, alias ngajak gelut.
Bagaimanapun, diksi seperti “melawan”, “problem otoritas”, dan “kebenaran”, merupakan kata kunci yang kerap saya dapati sebagai jargon dalam studi-studi yang menawarkan paradigma kritis. Dan memang, melalui bukunya, Muzayyin hendak memberi kita semacam pengantar untuk merespons secara kritis kemunculan aktor-aktor yang merasa paling memiliki otoritas dalam menafsirkan firman-firman Tuhan dan menjadikan tafsirnya sebagai kebenaran mutlak, seakan-akan ia paling mengerti Tuhan, kemudian menyingkirkan otoritas tafsir pemikir lainnya.
Pertarungan berebut klaim otoritas, menurut yang saya tangkap dari buku ini, merupakan salah satu permasalahan mendasar yang kerap memercikkan api perseteruan di kalangan umat Islam dari waktu ke waktu.
Secara khusus, buku Melawan Tentara Tuhan berusaha mendialogkan gagasan teori interpretasi Al-Qur’an dari Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd, dengan menelusuri pesan ideologis maupun muatan kepentingan di baliknya, serta menguji argumen-argumen teologis atau filosofis dari kedunya melalui pembacaan kritik ideologi dan analisis wacana kritis.
Menurut argumen Muzayyin, baik Al-Ghazali maupun Ibnu Rusyd adalah sama-sama memiliki standar atau kualifikasi interpreter masing-masing. Dengan kualifikasi tersebut, keduanya lantas “menyingkirkan” pihak-pihak yang tak sejalan dengan ideologi yang diusungnya dan, sebaliknya, “mengangkat” pihak-pihak yang se-ideologi dengannya.
Melalui buku ini, sang penulis menyinggung pemikiran Al-Ghazali yang cenderung menempatkan pakar bahasa, hadis, mufasir, hukum, teolog muslim, dan filsuf sebagai masyarakat awam yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menakwilkan ayat-ayat yang samar atau sulit dipahami.
Ia pun mengangkat sufi ahli hakekat sebagai kategori masyarakat terpelajar yang berperan aktif mengungkap makna batin di balik teks. Secara kualifikasi, masyarakat sufi memenuhi standar Al-Ghazali, terutama karena mereka menggeluti metode iluminasi atau intuisi mistik dalam menangkap misteri di balik suatu teks.
Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Rusyd memandang para filsuf adalah kelompok masyarakat yang paling berhak dan wajib melakukan penakwilan terhadap Al-Qur’an.
Menurut Ibnu Rusyd, para filsuf menggunakan metode demonstratif yang akan membawa mereka menuju kebenaran sesuai syariat. Selain itu, metode tersebut dipandang lebih meyakinkan karena berpegang pada rasionalitas dan mengandalkan daya analitis.
Muzayyin mendudukkan perbedaan cara pandang kedua pemikir tersebut sebagai fenomena yang menunjukkan bahwa proses penggalian makna atas teks kitab suci pun tidak bisa dilepaskan begitu saja dari ideologisasi sang interpreter.
Dan, dalam proses ideologisasi tersebut, selalu ada pihak yang disingkirkan, dan pihak yang dijadikan rujukan. Sementara itu, kualifikasi atau standar siapa yang boleh dianut, siapa yang tidak, itu bergantung pada orang-orang yang dianggap memegang otoritas memaknai firman-firman Tuhan. Masalah kemudian muncul ketika pernyataan-pernyataan dari si pemegang otoritas ini mengalami sakralisasi.
Sebagai refleksi, fenomena sakralisasi pernyataan atau pemikiran dari orang-orang yang dipandang memegang otoritas dalam memahami agama sangat mewarnai corak dinamika masyarakat kita hari ini.
Masyarakat kita cenderung dengan mudah akan melaksanakan apa pun pernyataan dari ulama yang dianutnya karena mereka menganggap petuah ulama tersebut sakral, termasuk melakukan kekerasan. Mulai dari kekerasan verbal, seperti menuding kelompok yang tak sejalan dengannya sebagai kafir atau sesat, sampai kekerasan fisik yang barangkali dapat membahayakan nyawa.
Dalam menyoal sakralisasi, Muzayyin juga menghadirkan pandangan-pandangan yang cukup menantang pemahaman masyarakat kita mengenai yang suci dan yang profan, dengan mendialogkan pemikiran muslim puritan dengan muslim progresif.
Para muslim puritan cenderung menundukkan akal budi di bawah teks-teks kitab suci. Dampaknya, mereka akan memaknai teks secara taken for granted atau diterima apa adanya. Makna dalam Al-Qur’an, dalam perspektif ini, dianggap final karena ia bersumber dari Tuhan dan bukan produk manusia. Pemaknaan atas ayat-ayat dalam teks Al-Qur’an hanya bisa dilakukan otoritas tertentu yang kerap disakralkan dan pandangannya tidak boleh dibantah.
Sebaliknya, muslim progresif berusaha menundukkan teks-teks kitab suci di bawah akal budinya. Pemaknaan terhadap Al-Qur’an harus dilandaskan pada rasionalitas, sehingga mungkin bagi kita mengkritik atau melengkapi pandangan-pandangan pemikir terdahulu yang telah menafsirkannya dan menyesuaikan moral dalam kitab suci tersebut untuk masa sekarang.
Jadi, tidak ada sakralitas dalam hal ini: Al-Qur’an adalah teks, yang di darinya kita dituntut menegosiasikan pemaknaan kita dan itu bisa sangat tidak terbatas sejauh dinamika kehidupan terus berlangsung.
Buku ini, selain mendialogkan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd serta bagaimana sakralitas menjadi bagian darinya, juga merangkum berbagai isu perdebatan yang menarik, menyangkut otentisitas, historisitas, dan pendekatan tekstualis-kontekstualis, dalam membaca Al-Qur’an.
Oleh karenanya, saya mengatakan buku ini bisa sangat meresahkan bagi sebagian kamu muslim negara kita, terutama yang belum berkenalan dengan pandangan-pandangan liberal (dalam arti akademis) dan yang masih belum berani memandang Al-Qur’an atau wahyu kenabian dalam pertikaian intelektual yang relatif terbuka.
Namun demikian, perdebatan-perdebatan itulah yang justru membuat buku Melawan Tentara Tuhan menjadi penting untuk kita baca. Muzayyin, agaknya, berhasil merangkum berbagai pertikaian akademik dalam studi Islam dan itu bisa menjadi bekal awal kita untuk senantiasa mendialogkan berbagai kebenaran yang kita peroleh dari beragam sumber, alih-alih meyakininya secara buta dan bertingkah seakan-akan paling mewakili Tuhan di muka bumi ini.



