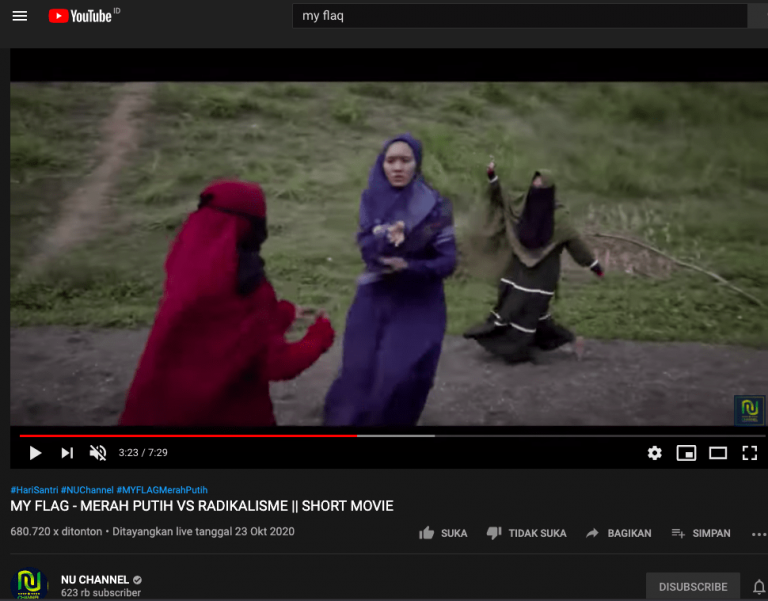
Film My Flag justru menjauhkan pengetahuan kita tentang arti radikalisme maupun ekstremisme. Film itu seolah menyempitkan term yang jadi perbincangan umat Islam belakangan ini, bukan justru menjernihkannya.
Sebuah pesan masuk ke WA saya. Intinya, sang pengirim pesan bingung karena mendapat banyak pertanyaan dari rekannya terkait film yang viral di youtube dan banyak orang mengira, film itu adalah representasi ormas NU–padahal setelah ditelusuri ternyata bukan– Kebetulan film yang sedang dibahas itu adalah film yang ramai dikritik karena membuat gaduh, khususnya terkait distorsi Islam dan kaitannya dengan radikalisme yang ditafsirkan sempit.
Judul film itu My Flag: Merah Putih vs Radikalisme. Per 28 Oktober, film yang mulai tayang tanggal 23 Oktober sudah ditonton lebih dari 600.000 kali. Satu pencapaian bagus kalau dihitung dari angka. Film itu juga mendapatkan dislike yang cukup besar.
Di beberapa grup kasus yang sama muncul. Banyak kecaman yang ditujukan pada film pendek berdurasi 7:29 menit itu. Karena penasaran saya pun menontonnya.
Tidak diragukan bahwa teknik pengambilan gambar film ini sangat baik bin artistik. Sudah seperti film-film berkualitas. Pesan awal yang muncul pun menggungah karena sebagai warga negara kita tentu harus punya identitas kebangsaan. Film ini mengeksplorasi simbol mencitai negara dalam bentuk bendera. Sebuah awalan yang bagus, pikirku.
Namun semakin panjang durasi alur cerita kian tidak terarah. Pengambilan gambar yang baik tidak disertai dengan story telling yang bisa untuk dinikmati. Hasilnya, film ini ngglambreh ke sana ke sini. Durasi 7 menit terasa sangat panjang dan kita dipaksa untuk menyaksikan banyak scene tidak penting.
Saya pernah terlibat dalam penjurian sebuah festival film yang diikuti para pelajar dengan durasi yang sama. Dari ratusan film, saya bisa tonton sampai habis karena kekurangan para filmaker biasanya hanya terletak pada aspek teknis seperti kualitas audio dan kamera. Tapi itu masih termaafkan karena substansi filmnya dapat.
Namun film My Flag kebalikan dari itu. Satu film saja rasanya sudah melelahkan. Teknik audio dan gambar yang baik harus terkubur dengan substansi yang entah mau dibawa ke mana.
Film ini terlalu menonjolkan simbol yang terstigmatisasi. Misalnya di menit 3:01 saat sekelompok orang bersarung dan berjilbab bertemu dengan kelompok berjubah dan bercadar. Kedua kelompok itu langsung bentrok.
Ada kalimat yang diucapkan oleh seorang berjilbab non-cadar:
Sejauh mana imanmu, sejauh itu cintamu pada Negerimu
Setelah itu, gedebuk! Gelut. Saya waktu nonton pun langsung mbatin. ‘Heh, maksute opo to iki?’
Film My Flag tersebut menempatkan orang yang bersarung dan berjilbab sebagai kelompok yang mencintai bendera. Sementara pihak yang bercadar dianggap kelompok radikal. Aspek penonjolan yang sangat tidak penting dan terkesan sangat memaksakan. Dan tentu saja tidak relevan.
Saya tidak tahu sejauh mana si pembuat film melihat realitas keberislaman di Indonesia atau bahkan dunia. Barangkali para pembuat film memiliki pengalaman hidup dengan kelompok yang ditonjolkan. Kalaupun iya, itu bukan alasan yang tepat untuk mengasosiasikan cadar dan cingkrang ke kelompok radikal.
baca juga: perempuan dalam film Islami
Yang mengherankan mengapa stigmatisasi ini justru dimunculkan di Indonesia, negeri dengan sejuta keberagaman? Sementara di Eropa dan Amerika, banyak negara sudah mulai terbuka dengan model berpakaian, termasuk bercadar.
Cadar adalah pilihan yang tidak bisa diasosiasikan dengan pemikiran. Sebagian menganggapnya sebagai gaya berpakaian. Sebagian lagi menganggapnya ajaran agama. Tak masalah sudut pandang mana yang diambil selama tidak memaksakan jalan iman orang lain.
Sama seperti ketika orang enggan bersalaman dengan lawan jenis bukan berarti memiliki pikiran yang intoleran, bukan? Di pesantren saya pun tidak ada santri yang berkenan untuk bersalaman dengan lawan jenis.
Toh, yang namanya beragama memang harus radikal sebagaimana arti kata radic yang berarti sampai ke akar-akarnya. Bukankah kita memang diajarkan untuk beragama secara radikal untuk diri sendiri dan terbuka dalam hubungan yang sifatnya sosial?
Yang harus ditolak adalah sikap intoleran dan merasa benar sendiri. Apalagi sampai melakukan tindakan persekusi. Sayangnya, di film tersebut orang yang bercadar jadi kelompok yang dipersekusi karena cadarnya dilepas secara paksa.
Saya teringat posting-an Facebook Budi Irwanto, salah seorang dosen dan peneliti film Indonesia saat mengomentari film pendek Tilik. Sebagian kalangan menyebut film tersebut sarat stereotype dan misoginis karena menampilkan perempuan sebagai kelompok yang suka gosip. Namun bagi Irwanto film tersebut hanyalah melakukan typing, bukan stereotyping.
Sederhananya, typing adalah metode penceritaan atas realitas sehari-hari. Menceritakan sebuah keluarga di mana ibu berperan sebagai ibu rumah tangga dan bapak sebagai orang kantoran, kalau memang mengambil latar keluarga yang demikian, itulah typing.
Bagi orang-orang desa yang menonton film Tilik pasti juga mengamini apa yang terjadi sehingga film itu terasa ‘aku banget’. Menontonnya bahkan bisa tertawa karena tokoh-tokoh di dalamnya seperti mengamini karakter di kehidupan sehari-hari.
Lalu bagaimana dengan film My Flag? Sebagai orang yang pernah tinggal di desa dan kini di perkotaan apa yang ditampilkan sama sekali bukan bentuk penceritaan sebagaimana kehidupan sehari-hari. Khususnya adegan cadar itu merupakan bentuk membangun narasi yang tergolong stereotype dan bentuk simplifikasi dari bercadar adalah radikal sehingga harus dilawan.
Sayangnya kita tidak tahu siapa orang-orang yang ada di balik pembuatan film ini karena sepanjang 7:29 menit tidak dimunculkan nama-nama krunya. Padahal memunculkan nama bisa jadi bentuk apresiasi bagi orang-orang yang terlibat di belakang layarnya. Selain itu dengan memunculkan nama kita bisa juga memberi kritik yang membangun terhadap para sineas. Bukankah kritik menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah film?
Meski demikian saya berharap agar para pembuat film ini tidak berhenti belajar. Ada potensi di dunia sinematografi yang tidak banyak ditekuni oleh kalangan santri (barangkali yang membuat adalah santri). Setelah bisa menguasai skill, tahap selanjutnya adalah mempelajari realitas masyarakat agar film yang diproduksi layak dijadikan tuntunan, bukan sekadar tontonan. Agar memberi manfaat, bukan sekadar menjadi keringat. Wallahua’lam.



