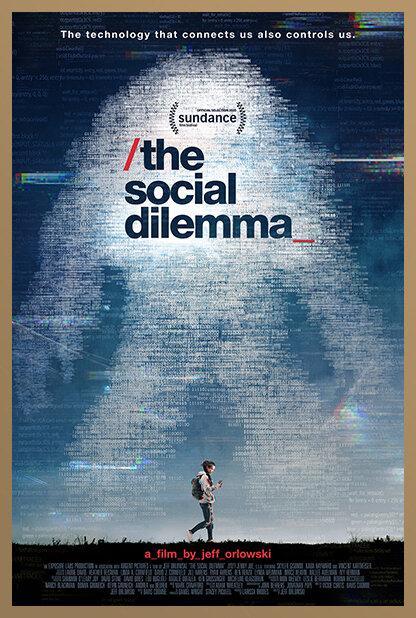
Bagaimana media sosial berperan besar dalam fanatisme politik, atau memang ia tercipta dari relung terdalam manusia dan teknologi cuma memanfaatkanya?
Sejak tahun 2009, terjadi kenaikan sebesar 62% anak perempuan di usia 15-19 mengalami kekerasan tidak fatal. Tingkat bunuh diri anak perempuan usia 15-19 tahun di AS , sejak tahun 2009 mengalami kenaikan 70%. Begitupun bunuh diri anak perempuan usia 10-14 mengalami kenaikan 151%. Tidak ada yang bisa memprediksi secara tepat kapan dan bagaimana seorang anak sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun Media sosial dan ponsel pintar berperan besar dalam peningkatan ini (Washingtonpost, 15/5/2019).
Soal utamanya: Media sosial menciptakan realitas sendiri bagi setiap orang. Pencarian google tidak akan menunjukan hasil yang sama bagi setiap orang. Lokasi, profile, dan IP menentukan informasi apa saja yang akan mesin pencari dan sosial media berikan pada anda. Maka wajar kalau kemudian sosial media seringkali menghilangkan teman-teman anda daripada mempereratnya. Model ini mirip gravitasi yang akan menarik benda-benda sekitarnya saja. Semakin terkumpul minat ideal anda, maka anda hanya akan berotasi pada hal-hal tersebut.
Masalah utamanya, selama berotasi dengan dunianya masing-masing, sosial media bisa secara halus menyelipkan pesan-pesan tertentu, seperti iklan dalam minat kita di dalam jejaring sosial media. Menurut investor teknologi, McName, seiring waktu kita memiliki kesan palsu bahwa semua orang setuju dengan kita karena semua orang di umpan berita (newsfeed) tampak seperti kita. Dalam keadaan demikian kita mudah dimanipulasi, apalagi urusan fanatisme politik.
Rashida Richardson, asisten Profesor di NYU School of Law dan menjabat sebagai direktur A.I.Now Institute menyatakan, kita hanya menerima dunia yang tidak bertentangan dengan kita. Menurutnya kita bukan lagi individu objektif yang objektif dan konstruktif. Hal ini berlaku juga di politik. Polarisasi politik semakin menguat akibat sosial media. Setiap pendukung semakin fanatik dengan pilihannya.
Guillaume Chaslot (Pejabat Teknik Youtube, CEO IntuitiveAI, Pendiri AlgoTransparancy) orang dibalik ‘rekomenasi Youtube.’ Ia membenarkan Algoritma yang diciptakannya malah memperkuat polarisasi masyarakat. Ia mengklarifikasi bahwa Algoritma tidak merekomendasikan hal yang baik untuk anda, mereka mencarikan perangkap yang sangat sesuai dengan minat kita. Youtube akan merekomendasikan salah satu video lain berulang kali. Hal paling buruk dari rekomendasi semacam ini adalah ketika banyak publik figur akhirnya percaya—misal—bumi datar. Kemampuan logaritma dalam merekomendasikan ‘konten’ semakin baik. Bahkan sebuah perkumpulan informasi (grup) yang tidak berkaitan kata kuncinya dengan pengguna (user) bisa direkomendasikan karena grup tersebut sangat kuat.
Studi yang dilakukan MIT menyebutkan bahwa fake news (berita palsu) di twitter menyebar enam kali lebih cepat daripada berita aslinya. Hal ini bisa berakibat pada perubahan neraca prilaku manusia. Mengapa berita palsu sulit diberantas secara internal oleh perusahaan teknologi? Kenyataannya, berita palsu yang membuat sosial media seperti Facebook, Twitter, Youtube mendapatkan banyak keuntungan.
Ketika Covid-19 merebak, sosial media membuat orang-orang tidak tahu mana yang benar. Padahal kini virus tersebut telah menjadi persoalan hidup dan mati. Media sosial memperkuat gosip, desas-desus dan juga fanatisme politik yang sungguh berlebiha dan terkadang di luar nalar.
Dengan demikian Media sosial seperti Facebook adalah alat persuasi yang paling hebat yang pernah dibuat. Renee Diresta, Manajer peneliti di Stanford Internet Observatory menyayangkan saat negara atau seorang diktator memanfaatkan kemampuan Media sosial. Seperti di Myanmar saat pemerintahannya sendiri justru mengobarkan kebencian terhadap Muslim Rohingya.
Ironinya: media sosial yang dilahirkan kebebasan berpendapat ternyata mengancam demokrasi. Polarisasi politik meneguhkan berita palsu sebagai senjata utama politik. Inilah soal utamanya, media sosial menyemai fanatisme. Persuasi halus dengan cara mendekatkan semua yang berada disekitar minat anda, dan semua yang anda sukai mengelilingi anda justru menjauhkan kita dari sikap berimbang dalam menilai suatu konten sosial media.
EDUKASI
Institusi pendidikan dianggap paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut. Edukasi berkali-kali soal berita hoax dan mengajak masyarakat untuk tidak mudah membagikan ‘konten’ yang belum jelas asal usulnya bukan perkara mudah. Justru banyak dosen, guru dan kaum akademis yang justru ikut terlibat dalam beberapa kasus penyebaran berita bohong. Artinya, institusi pendidikan sendiri kurang mampu menahan laju berita hoax.
Sikap ilmiah dan terbuka dianggap sebagai berperan besar dalam menentukan sejauh mana seseorang mudah mempercayai berita bohong atau bukan. Namun hasil PISA 2018 menunjukan bahwa tes Sains anak Indonesia begitu rendah. Meskipun angka ini tidak selalu bisa jadi acuan, namun kita memiliki gambaran utuh bahwa menyelamatkan masyarakat dari berita hoax adalah jalan terjal yang begitu panjang.
Soal lainnya, pemerintah juga mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Umum diketahui bahwa propaganda preventif yang halus media sosial diakomodasi oleh para ‘influencer.’ Mereka umumnya adalah akun sosial media berpengaruh dengan jumlah follower yang tinggi dan opininya bisa mempengaruhi banyak orang. ICW menyebut bahwa Pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana sekitar 90 Miliar untuk sewa jasa Influencer (Tempo, 20/8/2020). Namun diluar itu, cara lama beriklan dengan membayar media cetak atau berada pada halaman-halaman paling depan dari laman berita online dinilai kurang efektif dibandingkan dengan beriklan menggunakan jasa influencer.
Dilema ini dirasakan oleh para arsitek berita online yang jauh tertinggal oleh pada influencer mengenai tingkat efektifitas dan sasaran sesuai permintaan pelanggan (pembayar iklan). Meskipun berita online mengalami goncangan etika untuk meniru para influencer yang sebenarnya menyisipkan iklan / pesanan dalam informasi atau opini mereka. Walhasil, tradisi menghebohkan judul berita dipakai beberapa kantor berita minim etika jurnalistik. Masyarakat internet Indonesia (Netizen) tidak memiliki pilihan lain selain menyerap bias-bias informasi yang berisi dorongan halus agar pesan-pesan penyedia jasa iklan influencer tersampaikan.
Bagi kita yang berusaha untuk terus objektif dalam memahami informasi, tentu saja berada pada ekosistem informasi sosial media yang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Oleh sebab itu lebih mudah tersungkur dalam fanatisme sebab hal tersebut melayani hasrat-hasrat yang telah dibentuk daripada melawan diri sendiri dengan cara menahan diri.
Seolah-olah internet yang memberikan banyak informasi gratis memagari ‘informasi yang benar’ dengan ilalang kebohongan sebagai cara mengembalikan tradisi lama bahwa pencarian kebenaran bukanlah jalan yang mudah.



