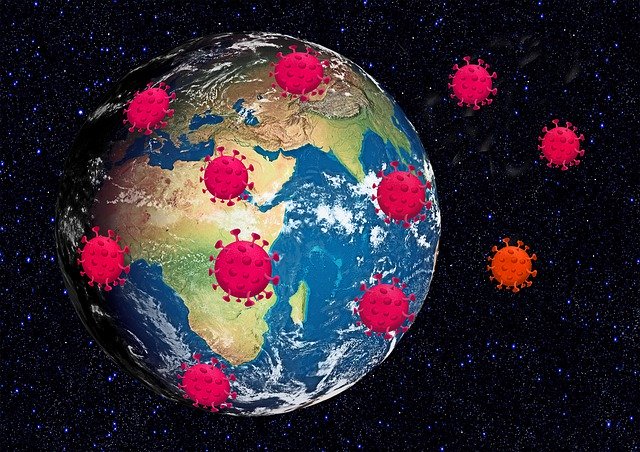
Bulan keempat tahun 2020 umat manusia dihantui dua kegetiran. Pertama, dapatkah vaksin wabah virus Corona atau COovid-19 ditemukan dalam waktu dekat? Kedua, seperti apa masa depan dunia setelahnya? Masa depan, mulai menjadi sebuah kajian yang belakangan disebut Futurologi. Tokoh utamanya Alvin Toffler (yang beberapa prediksinya dianggap cukup akurat), Sardar (Futurolog Islam) dan Robert Malthus (bukan hanya memberikan prediksi kebutuhan pangan dan pertumbuhan penduduk planet bumi, ia berhasil mengintervensi sejarah masa depan; melahirkan konsep Revolusi Hijau yang dipakai Indonesia pada masa Swasembada pangan tahun 1984).
Masa depan seringkali dikisahkan dalam karya fiksi seperti Hunger Games, 1984 (1949), The Handmaid’s Tale (1985), Divergent (2011) dan Ghost Fleet (2015). Meskipun tidak cukup popular, novel yang terakhir sempat mewarnai perdebatan Pilpres di Indonesia tahun 2019 karena menyebut Indonesia sudah bubar di masa depan (2030). Industri film lebih menggila, seperti A Space Odyssey (2001), Star Trek (1979), Terminator (1984), Back To the Future Part I-III (1989) dan banyak lagi. Salahsatu film yang ciri-cirinya paling mendekati wabah Covid-19 adalah Contagion (2010).
Filsuf Sejarah
Karya Novel maupun film fiksi tersebut sangat penting dalam kajian sejarah, meskipun kalangan ini paling keras mengkritik keduanya, sebagian dari kalangan tersebut, yakni para filsuf sejarah membutuhkan daya imajinatif fiksi untuk melangkah lebih jauh dari batas-batas penelitian sejarah.
Peristiwa sejarah dengan Filsafat sejarah merupakan hal yang berbeda. Peristiwa sejarah adalah apa yang mungkin kita ketahui tentang masa lalu. Kemudian–singkat kata–filsafat sejarah adalah bagaimana caranya membentuk pemahaman tentang masa lalu baik objeknya, subjeknya maupun keseluruhan diantara keduanya. Sejarawan yang memikirkan masa depan tentu keluar dari pakem mereka yang selalu memikirkan masa lalu, maka mereka yang tertarik mengkaji masa depan disebut filsuf Sejarah. Filsuf sejarah tidak selalu berarti mereka seorang sejarawan. Sebagai contoh, pertanyaan paling mendasar mengenai sejarah masa depan pernah ditanyakan oleh Stephen Hawking, dalam buku ‘A Brief History of Time’ ia bertanya:
‘… mengapa kita mengingat masa lalu tapi tidak mengingat masa depan. Waktu dianggap ibarat rel lurus dimana kita hanya bisa bergerak kesatu arah dan sebaliknya. Tapi bagaimana bila rel itu punya jalur melingkar dan cabang sehingga kereta yang berjalan di atasnya bisa terus bergerak maju tapi kembali ke stasiun yang sudah dilewatinya? Dengan kata lain bisakah kita bepergian ke masa depan atau masa lalu? (Hawking, 2018:222)”
Pertanyaan Hawking memicu para filsuf sejarah untuk menjelajahi masa depan dengan pengetahuan masa lalu. Oleh sebab itu menjadi masuk akal mengapa seorang sejarawan kini mampu mengisi kolom artikel di sebuah surat kabar ekonomi seperti Financial Times dan memberikan nasehat-nasehat proyektif dengan bahan sejarah.
WABAH: Optimisme dan Lupa
Ketika ilmuwan kedokteran bersusah payah menanggulangi dan terus berupaya mencari cara mengatasi Covid-19, para filsuf sejarah memetakan masa depan dengan cara membuka catatan masa lalu. Sejarawan kondang Yuval Noah Harari, setelah bukunya menjadi best seller karena untuk pertama kali mengajukan sejarah sebagai bahan optimisme tatanan dunia, segera ditegur oleh keadaan dunia yang belum siap menanggulangi wabah Covid-19.
Harari berharap umat manusia perlu bergandengan disaat wabah covid-19 berlangsung. Disaat yang sama justru beberapa negara mengambil sikap oportunis dan anti-solidaritas. Baru-baru ini Jerman mengeluhkan tindakan Amerika Serikat mencegat produksi Masker yang dibuat untuk Jerman di pabrik Thailand dan Cina, kemudian mengambil untuk negaranya sendiri (RusianToday, 4/4/2020). Apakah tindakan negara seperti ini merupakan hal yang lumrah dalam sejarah?
Wabah selalu membuat negara-bangsa berbuat gegabah, boleh jadi karena mereka tidak memiliki pengalaman untuk melakukan mitigasi wabah atau mereka tidak memiliki skenario simulasi wabah dimasa mendatang. Wabah Covid-19 rupanya memiliki ciri-ciri yang sama dengan wabah yang diceritakan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah ratusan tahun silam, ia menulis:
“Udara rusak oleh ledakan penduduk, pembusukan serta uap lembab buruk bercampur baur dalam daerah yang sesak penduduk. … Jika kerusakan udara bertambah parah, paru-paru akan sakit. … akibatnya banyak timbul penyakit demam … tubuh akan sakit dan binasa. … karenanya pula, wabah yang terdapat dikota-kota yang banyak penduduknya lebih banyak daripada yang terdapat ditempat lain… (Khaldun, 385-6)”
Catatan Khaldun mengenai ciri-ciri wabah ‘paru-paru sakit, demam dan kota-kota padat’ memberikan gambaran bagaimana sistem kota sejak ratusan tahun silam menyimpan potensi pandemik. Meskipun dalam hal ini Khaldun lebih memusatkan perhatian kepada ‘kerusakan udara yang parah’. Sangat menarik bahwa fenomena wabah disebut Khaldun sebagai fase ‘akhir negara’.
Diksi ‘Akhir negara’ sepertinya mirip dengan apa yang sering dikutip dari Karl Marx, yakni tahapan sebelum menuju fase masyarakat sosialis. Dalam hal ini tidak disebut sebagai ‘akhir sejarah’ sebagaimana judul buku Fukuyama yang cukup ambisius. Menjelang puncak wabah covid-19 justru sebaliknya, banyak ramalan tentang akhir kapitalisme global dengan merujuk pada situasi pasar global yang semakin menderita.
Salah satunya artikel Martin Surajaya yang merekomendasikan model sosialisme negara (yang belakangan direvisi). Menurutnya, diambang Kapitalisme dan ancaman barbarisme, hanya ada pilihan sosialisme negara (Surajaya, 30/3/2020). Kekhawatiran akan kapitalisme—tidak hanya oleh Marx–diutarakan oleh Albert Einstein artikelnya berjudul ‘Why Socialism?’ pada tahun 1949 Ia menganggap kapitalis merupakan sumber kejahatan. Sebab dalam sistem kapitalis teknologi seringkali menyebabkan lebih banyak pengangguran daripada meringankan beban pekerjaan (Einstein, 1949).”
Ramalan Einstein tentang pengangguran karena teknologi lebih banyak terbukti, berbeda jauh dengan kaum optimistik seperti Harari yang melihat ‘perkembangan biotech’ sebagai masa depan yang harus diberikan porsi investasi lebih besar. Menghadapi perkembangan teknologi industri yang ganas terhadap nilai-nilai kemanusiaan—bukannya mempertanyakan teknologi industri—Harari malah membuka peluang perubahan radikal aspek-aspek kemanusiaan sehingga diksi negatif seperti ketidakadilan, penindasan, hingga rasa sakit dapat dimediasi melalui bioteknologi.
Ia membela perkembangan teknologi secara penuh yang didukung sistem kapitalisme melalui pendanaan riset-riset strategis, kemudian mempersiapkan bagaimana ‘manusia’ mulai melampaui kemanusiaanya menuju Homo Deus (Harari, 2018).
Harari membandingkan sikap Amerika terhadap Ebola dan Covid-19. Ia menganggap sikap Amerika Serikat terhadap Ebola harusnya dicontoh oleh Amerika Serikat ketika menghadapi Covid-19 (Harari, 20/2/2020). Walhasil, Ebola sukses dihentikan. Namun perbedaannya cukup signifikan, virus Ebola lebih dekat dengan kemiskinan dan kebersihan sanitasi.
Sedangkan Covid-19 menyerang kelas atas dan menengah terlebih dahulu, melalui bilik-bilik privat transportasi ber-AC tertutup; ruang kerja, kamar lobi, mobilisasi keagamaan dan pertemuan-pertemuan pejabat penting. Tentu ini perkembangan awal saja, sebab apabila sudah menyebar ke lingkungan padat, masyarakat kelas bawah akan menghadapinya lebih parah mengingat bagaimana akses pelayanan kesehatan mereka.
Meskipun tingkat kematian Covid-19 dibawah 10% lebih rendah dari SARS dan MERS, namun virus ini telah menjadi ‘selebriti global’ bukan hanya karena menular pada kalangan selebriti, tapi mempengaruhi aktivitas manusia secara global yang didominasi oleh pesawat terbang.
Tahun 1918 pada waktu pesawat komersil berpenumpang massal belum ditemukan, kematian akibat wabah virus Influenza berada di angka 50-100 juta jiwa. Namun buku sejarah pada periode tersebut lebih memberi porsi besar pada Revolusi Bolsevik, Perang Dunia I, dan krisis Malaise. Terbukti buku Garis besar sejarah Amerika Serikat sama sekali tidak menyinggungnya.
Alfred W Crosby mengemukakan bahwa dampak yang luar biasa yang ditimbulkan oleh pandemi Influenza tidak membekas sama sekali pada rakyat AS padahal tentara mereka paling banyak terjangkit (Wibowo, 2009:52). Artinya ingatan manusia akan wabah cukup pendek, selain itu mekanisme pengkaburan peristiwa-peristiwa sejarah gelap seperti wabah dianggap membantu masa-masa sulit penyembuhan global melalui peristiwa-peristiwa lainnya demi memudahkan mobilisasi masyarakat dan membentuk masa depan baru pasca-wabah.
Sejarah Masa Depan
Ibun Khaldun mengamati sejarah ramalan-ramalan masa depan yang dimulai sejak penerjemahan pembicaraan pada astrolog/ Filsuf Yunani yang mempengaruhi Astrolog Muslim Seperti Harun Ibn Sa’id Al-Ajali, Jarras bin Ahmad Al Hasib, dan Ya’kub bin Ishaq Al-Kind. Ia mengkritik karena kebanyakan kitab-kitab ramalan tokoh tersebut dimanfaatkan ahli nujum yang penuh kebohongan dan manipulatif (Khaldun, 2017: 391-3). Khaldun juga dengan kesal menyatakan bahwa ramalan kedatangan ‘Mahdi’ atau Imam Mahdi, diamini oleh ‘orang-orang bodoh, tidak mengetahui hakikat masalah, dan kebanyakan dari mereka berasumsi (Khaldun, 2017:388).
Khaldun sangat kritis terhadap fenomena ‘ramalan’ oleh sebab itu ia sangat rasional ketika memprediksi masa depan atau akhir negara diawali oleh wabah dan kelaparan (Khaldun, 2017: 383-4). Satu-satunya pemetaan masa depan Khaldun adalah upayanya dalam menjelaskan siklus kelahiran dan kehancuran peradaban dalam pola kota-kota (2017:481). Upaya filsuf sejarah memetakan masa depan tetap merupakan pekerjaan intelektual ambisius sejarah dalam menembus masa lalu, kini dan masa depan.
Namun satu hal yang pasti, bepergian ke masa lalu selalu dihantui kemungkinan perubahan pada ‘masa kini’. Oleh Sebab itu Alfred Anyer segera menyanggah dengan menyatakan bahwa meskipun kita benar-benar hadir dimasa lalu menyaksikan—katakanlah—ketika Pangeran diponegoro ditangkap oleh pihak Belanda, apa yang kita alami dan rasakan tidak bisa mewakili apa yang dialami dan dirasakan oleh zaman tersebut ataupun orang yang hadir dalam sejarah tersebut—pelaku sejarah. Kita selalu membawa bias masa kini dalam tafsiran masa lalu (angkersmith, 92-23).
Peristiwa sejarah juga menunjukan bagaimana sejarah masa depan di masa lalu. Sebagai contoh gambaran optimis terhadap sistem kapitalisme Global mulai mendapatkan banyak pertanyaan. Proyek Neoliberalisme yang terkenal setelah Margaret Thatcher- Reagan menyatakan ‘there is no such as society’ diwakili oleh poster masa depan tahun 1980 bahwa pada awal milenium tahun 2000 manusia akan mencapai ‘mobil terbang’. Bukannya mobil melayang, dunia justru dipenuhi konflik atas kebutuhan bahan bakar mobil. Sementara terkonologi informasi semakin maju, nyatanya nasehat terbaik agar tetap hidup sampai tahun 2020 adalah dengan mencuci tangan dengan sabun seperti era pertama kuman ditemukan (Diamond, 1997).
Gambaran lainnya yakni keberhasilan internet dalam menyelenggarakan Open Society. Menurut Kampanye tersebut, dengan internet semua orang akan ‘terkoneksi’–nyatanya telah mengecewakan. Selain disinformasi, perubahan paling fundamental web 3.0 adalah ketika Logaritma newsfeed sosial media tidak lagi kronologis sesuai dengan kebiasaan sejarah, namun mengutamakan interaksi tertinggi. Sehingga dimensi waktu dalam sosial media lebih mirip gravitasi antar planet. Anda tidak akan terhubung secara bebas, logaritma akan merekomendasikan newsfeed yang paling tertinggi disekitar anda. Kisah Utopia bahwa manusia akan semakin terhubung melalui globalisasi menghadapi kiamatnya justru bukan karena wabah atau tindakan negara yang mengisolasi dirinya, namun dimulai sejak tahun 2018 ketika logaritma internet berubah.
PASCA-DISTOPIA: Tanpa Kapitalisme?
Belakangan ruang imajinasi dan fiksi menghadapi tantangan baru ketika tren film anak berubah dari Utopia (Cinderela) menjadi Distopia (Despicable). Kata Utopia sendiri ditemukan tahun 1516 oleh Thomas More yang diartikan sebagai tempat imajiner dengan sistem sosial politik sempurna (Coverley, 2010:9). Kebalikan dari Utopia, distopia merujuk pada masa depan yang kelam. Keduanya hadir dalam sejarah.
Merlin Coverley menunjukan empat kecenderungan Utopia dari Golden Ages (seperti kisah Atlantis & City of God), Early Mordern Era (On Cannibals & New Atlantis), The Imaginary Voyage (Candide & Voyage Around The World), dan Socialism Utopia ( An New View of Society & The Communist Manifesto). Selain itu terdapat dua kecenderungan Distopia, pertama Totalitarian Nightmares (kisah 1984 George Orwell) dan kedua The Cold War Era (The Handmaid’s Tale karya Margaret Atwood) (Coverley, 2010: 9-14).
Utopia sebagai tujuan dari pemetaan masa depan disebut oleh Angkersmith sebagai sistem filsafat sejarah Spekulatif. Pemikiran ini berlanjut dari Khaldun, Darwin, O Spengler, Toynbee, Hegel, Marx hingga Harari. Para filsuf sejarah melalui pemikiran sejarah berani menyatakan bahwa gerak dan arah masa depan bisa dibayangkan melalui sistem filsafat sejarah mereka. Belakangan, Rutger Bregman, Sejarawan berkebangsaan Belanda mengklaim bahwa tidak hanya penganut Idealisme atau Materialisme dialektik saja yang memiliki Utopia. Seorang Realistis masih memiliki kesempatan ber-utopia.
Dalam bukunya berjudul Utopia for Realists (2016), Bregman memberikan gambaran bagaimana peningkatan basic income disebuah distrik kecil di Canada bisa menaikan taraf pengangguran hingga angka nol. Hal ini diperkuat dengan penelitian tingkat IQ seorang petani ketika sebelum dan setelah panen. Hasilnya seorang Petani rata-rata memiliki IQ tinggi setelah panen dan ber-IQ rendah ketika belum panen.
Hal ini menunjukan bagaimana kecerdasan orang bisa berubah sesuai dengan ‘rasa’ jaminan kelangsungan hidupnya. Berkaitan dengan Utopia, ia menyarankan bahwa meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui basic income masyarakat bukanlah Utopia. Sebab di era yang sangat kapitalistik, jaminan basic income dari pemerintah dianggap Utopia. Padahal sistem kapitalisme sendiri didorong oleh Utopia Fundamentalisme Pasar.
Apabila kita membentuk Utopia baru, tentu saja hal tersebut adalah thesis yang harus dipertentangkan, dibenturkan dan diuji coba. Ambil contoh, seringkali dikatakan bahwa pembela kapitalis lebih rajin membaca das Capital untuk membaca pengaruh politik dalam bursa saham. Bahkan dikatakan Spekulan saham ternama, George Soros, mengoleksi karya Marx tersebut. Berbeda dengan kaum sosialis yang menjadikannya sebagai dogma politik.
Menghadapi kaum merah pada era Perang Dingin, negara-negara barat membangun serangkaian kampanye melawan Utopia sosialis dengan menyediakan kisah-kisah fiksi revolusi yang gagal. Sehingga hasil sejarah yang diharapkan seperti ‘kapitalisme hamil tua’ dan prestasi negara sosialis terkubur oleh kisah-kisah gelap yang diproduksi Hollywood. Dalam hal ini sejarah pikiran dalam sistem spekulatif menjadi benar-benar Utopis karena didorong untuk menjauhi kenyataan sejarah. Namun gambaran masyarakat sosialis yang telah kehilangan pamornya selalu muncul secara periodik dan dramatis seperti pada krisis ekonomi Global tahun 2008 silam. Kate Connolly memperhatikan tren tersebut pada tahun 2008 dengan menyatakan “Karl Marx is Back” (The Guardian, 12/10/2008)
Hal tersebut hanyalah contoh bagaimana nasib spekulasi-spekulasi sejarah. Untuk pertama kalinya orang yang mampu mengkritik itu adalah Karl Popper. Ia menyebut spekulan sejarah sebagai Historisisme’ (Angkersmith, 1987:50). Ia keberatan dengan ramalan masa depan melalui ‘hukum sejarah.’
Tetapi perlu ditegaskan, tanpa filsafat sejarah spekulatif tidak akan tersedia narasi-narasi sejarah yang mampu merangkul semua peristiwa-peristiwa sejarah termasuk memetakan rangkaian penemuan ilmiah demi keberlangsungan keilmuan itu sendiri. Contohnya, sebagai fakta sejarah, tulisan Harari dalam Sapiens dan Homo Deus tidaklah baru bagi para pengkaji sejarah. Namun gambaran besar mengenai sistem sejarah spekulatif yang ditulis Harari telah membuka popularitas sejarah diera teknologi dan informasi. Selain itu Harari berhasil menyediakan narasi sejarah bagi kaum optimis.
Artinya, harus diberikan ruang bagi spekulasi-spekulasi sejarah dan Utopia yang akan menyeimbangkan narasi Distopia, sehingga masyarakat memahami (atau mungkin mempertanyakan!) fungsi utama mereka sebagai manusia. Namun Paul Mason yang menulis ‘The End of Capitalism has Begun’ mengkhawatirkan Utopia yang tidak sesuai ‘sejarah.’ Ia menyatakan ‘kita membutuhkan lebih dari sekedar impian utopis dan proyek horizontal skala kecil. Kita membutuhkan proyek berdasarkan alasan, bukti dan desain yang dapat diuji, yang sesuai dengan sejarah dan kelanjutan planet ini’ (The Guardian, 17/7/2015).
Kelanjutan sejarah sebenarnya ditentukan pula oleh faktor non-manusia. Mungkin ketidakhadiran dunia objektif (Hegel) yang bersifat ‘alamiah’ seperti bencana alam dan wabah sebagai fakta yang konstan dalam setiap penulisan sejarah akan mengakibatkan ketidaksesuaian ‘sejarah.’ Sebagai contoh diperlukan ketekunan membentuk sejarah pikiran yang lebih ramah lingkungan untuk menandingi sejarah pikiran yang ramah industri. Catatan sejarah mengenai prestasi industri dalam merubah kehidupan manusia harus diletakan sebagai prestasi negatif ketika kerusakan lingkungan yang diakibatkannya melampaui masa lalu dan masih terasa hingga sekarang.
Kebebasan untuk membentuk Utopia ditopang oleh kesempatan bereksperimen Filsuf sejarah untuk menulis masa depan. Pembukaan kesempatan ini bukan hanya berbentuk demokrasi politik. Kebebasan yang dimaksud adalah memecah pesimisme terhadap Utopia yang selalu saja memberikan apologi terhadap sistem ekonomi-politik yang sedang berlaku. Slavo Zizek pernah berkelakar, mengapa orang-orang yang mampu membayangkan tidak ada surga dan neraka, justru kesulitan untuk membayangkan dunia tanpa kapitalisme? Sebagai langkah awal, manusia perlu diberi kesempatan untuk membayangkan dunia yang melampaui Utopia kapitalisme global—sistem ekonomi politik yang dominan saat ini. Tentu saja artinya kita tidak kembali pada Utopia–yang terbukti dalam sejarah–sudah gagal.
Sumber:
Angkersmith, F.R. 1987. Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Coverley, Merlin. 2016. Utopia. Harpenden: Pocket Essentials
Einstein, Albert. 1949. Why Socialism? —
Harari, Yuval Noah. 2018. Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia. Ciputat: Alvabeth
Harari, Yuval Noah. 2020. The World after Coronavirus. Financial Times
Khaldun, Ibn. 2000. Mukaddimah Ibn Chaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Stephen Hawking. 2018. A Brief History of Time. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Surajaya, Martin. Membayangkan Politik Dunia setelah Korona. 30 Maret 2020. Martinsurajaya.com
Wibowo, Priyanto dkk. 2009. Pandemik Influenza 1918 di Hindia Belanda. Depok: FBPI-UNICEF
Bregman, Rutger. 2016. Utopia for Realists: The Case for A Universal Basic Income, Open Borders, and a 15-Hour Workweek (Trans: Manton, Elizabeth). The Correspondent.



