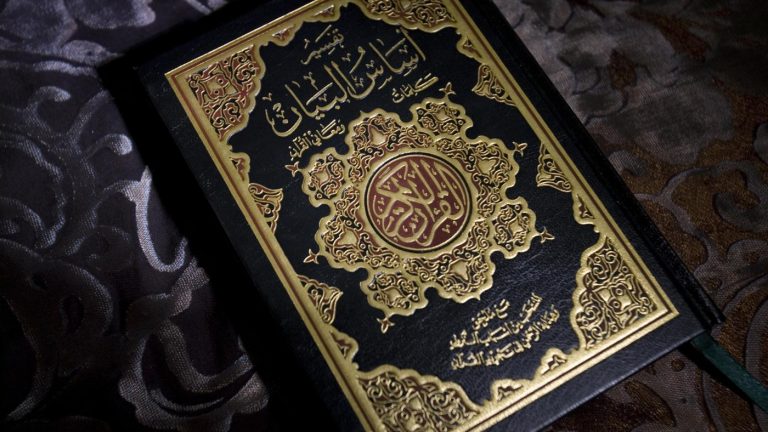
Setelah penaklukan Irak dan Syam pada masa kekhalifahan Saydina Umar ibn Khattab, para sahabat dihadapkan dengan persoalan apakah yang harus mereka lakukan terhadap tanah hasil rampasan perang tersebut. Jika merujuk kepada apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah di masa hidupnya, maka empat perlima dari tanah tersebut harus dibagikan kepada mereka yang ikut berperang dan seperlimanya digunakan untuk kemaslahatan umum.
Sayyidina Umar mempunyai pandangan yang berbeda, ia tidak lagi membagikan harta rampasan perang tersebut seperti aturan yang pernah berlaku. Malahan ia memutuskan untuk membiarkan tanah tersebut tetap berada di tangan pemiliknya, hanya saja mereka dikenakan pajak dan hasilnya diberdayakan untuk kepentingan umat Islam dan pemerintahan.
Sepintas apa yang dilakukan oleh Umar pada kasus di atas adalah suatu hal yang menyalahi aturan baku yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt menyebutkan dalam surat al-Anfal, ayat ke-41, bahwa seperlima harta rampasan perang dialokasikan buat kepentingan kaum muslimin dan sisanya dibagi-bagikan kepada prajurit muslim yang ikut serta dalam berperang. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah kenapa ijtihad (sebut fatwa) dari Saydina Umar terkait kasus di atas bisa berbeda? Apa dasar hukum serta alasan beliau mengubah hukum tersebut? Tidak khawatirkah beliau kalau nantinya dianggap sebagai orang yang berani menentang ataupun bahkan merubah hukum Allah dan Rasul-Nya?
Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, para ulama Ushul Fikih telah merumuskan sebuah kaedah bahwa fatwa terhadap sebuah kasus tertentu bisa saja berubah disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, orientasi, situasi dan kondisi lingkungan di mana fatwa itu disampaikan.
Hal ini pernah diulas secara panjang lebar oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya I’lam al-Muwaqqi’in. Sementara itu Syekh Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan setidaknya ada sepuluh faktor penyebab perubahan fatwa ulama. Selain lima faktor di atas, beliau menambahkan lima faktor lainnya, seperti faktor tradisi (‘uruf), perubahan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan manusia, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik, perubahan pemikiran serta musibah/bencana.
Berdasarkan kaedah tersebut, maka dapat dipahami bahwa perubahan kebijakan/fatwa yang dikeluarkan oleh Saydina Umar terkait masalah di atas sudah pasti dilatarbelakangi oleh suatu faktor tertentu. Ali Hasan menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh Saydina Umar karena ia melihat kepentingan masa depan umat Islam secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya kewajiban pajak terhadap tanah-tanah rampasan perang tersebut maka Islam akan semakin kuat karena ditopang oleh perekonomian yang mapan serta pemerintahan yang solid. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Ahmad Raisuni menyebutkan bahwa kemaslahatan merupakan dasar pijakan utama dalam pemutusan sebuah hukum.
Selain itu, Syekh Ali Jum’ah dalam karyanya ‘Ilm Ushul al-Fiqh wa ‘Alaqatuhu bi al-Falsafah al-Islamiyyah juga menggarisbawahi bahwa fatwa merupakan elemen terpenting dalam hukum Islam yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak (sebut masyarakat).
Oleh sebab itu, fatwa seharusnya dibangun berdasarkan realitas yang terjadi dengan menekankan prinsip kemaslahatan serta keadilan sosial. Ia juga menekankan bahwa seorang mufti seyogyanya harus memahami persis perihal kasus yang sedang ia tangani, jika perlu seandainya kasus tersebut berkaitan dengan bidang keilmuan yang tidak ia kuasai misalnya, maka sang mufti harus memusyawarahkan persoalan tersebut kepada para pakar yang menguasai bidang tersebut sebelum akhirnya mengeluarkan fatwa.
Kesembronoan dalam berfatwa bisa saja membawa dampak negatif terhadap orang yang meminta fatwa (baca mustafti), karena hal tersebut mungkin saja berakibat kebinasaan ataupun bahkan perpecahan kalau fatwa tersebut berkaitan dengan relasi antar masyarakat. Sebagai contoh misalnya, pada masa Rasulullah ada seorang yang terluka dalam sebuah perjalanan, tanpa disengaja pada malam harinya dia junub.
Lalu ia bertanya kepada teman-temannya -yang serombongan dengannya- terkait apakah ia boleh bertayamum saja sebagai ganti dari mandi wajib. Tanpa berpikir panjang teman-temannya menjawab bahwa ia tetap harus mandi. Akhirnya karena infeksi, laki-laki tersebut meninggal dunia.
Ketika berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah, beliau pun marah terhadap teman-temannya dan menyebut mereka sebagai “pembunuh” sahabatnya yang meninggal tersebut.
Begitu juga dengan fatwa yang berisi pencapan kafir terhadap suatu golongan atau kelompok tertentu sebelum menelitinya secara mendalam nan akurat juga dapat mengakibatkan kehebohan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Tidak sedikit fatwa-fatwa seperti ini mengundang amarah serta tindakan radikal dari sekelompok orang yang merasa benar karena dilegitimasi oleh fatwa sembrono dari muftinya. Imam Ahmad ibn Hambal, sebagai dikutip oleh Ali Hasaballah, mensyaratkan seorang mufti harus paham dengan hal ihwal masyarakat dan tipologi mereka. Hal ini supaya sang mufti tidak terjebak oleh kepicikan serta memutuskan perkara dengan hasil yang jauh dari standar-standar kemaslahatan yang ada.
Berdasarkan penjabaran di atas, perlu rasanya semua pihak untuk saling introspeksi diri agar tidak lantas langsung menyalahkan tindakan orang lain yang secara lahiriah berbeda dengan apa yang ia lakukan. Karena mungkin saja kondisi atau situasi yang ia hadapi berbeda dengan apa yang orang lain hadapi. Fatwa ulama di pedesaan yang masyarakatnya homogen (seideologi) pasti akan berbeda dengan fatwa mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang cenderung heterogen (multietnis dan beragam).
Begitu juga fatwa ulama yang hidup di daerah minoritas Islam tentunya akan berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan begitu seterusnya. Sehingga dengan demikian, saling memahami kondisi sangat dibutuhkan dalam persoalan ini. []



