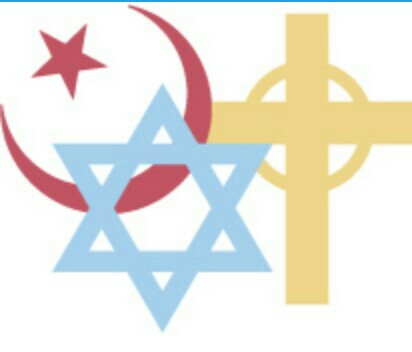
Terlepas dari asosiasi politis di abad ke-21, bagi saya “pelangi” merupakan merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang paling indah di alam semesta. Corak ragam warna berpola itu menjadi satu identitas yang membuat kita betah berlama-lama menikmatinya. Keindahan pelangi merupakan perpaduan dari varian warna yang berbeda-beda, tidak ada warna yang saling mendominasi, semua sesuai dengan dengan kadarnya, pas, dan proporsional. Warna-warna itu seakan sudah saling sepakat untuk tinggal berdampingan tanpa saling mempengaruhi.
Seorang sarjana relasi lintas agama, Leonard Swidler, membuat perumpamaan semesta sebagai sebuah kosmik dialog. Jika kita keluar malam hari dan menatap langit, cahaya bulan akan terlihat syahdu diiringi dengan kerlip bintang-bintang di sekitarnya. Apalagi saat bulan purnama, sinar bulan tampak menembus daun-daun pepohonan sembari bergoyang diterpa angin.
Dalam bayangan Swidler, bulan, bintang, daun-daun, angin, bahkan manusia sekalipun adalah elemen-elemen kosmik yang berdialog satu sama lain dan bersepakat untuk menciptakan semesta yang indah. Dalam bahasa lain, semesta yang elok ini tak lain adalah hasil dialog dan interaksi berbagai materi dan energi, proton dan elektron, tubuh dan spirit, individu dan kelompok, dan seterusnya.
Di masa lalu, mungkin sebuah komunitas, misalnya suku kecil tertentu, bisa membatasi dirinya untuk tidak banyak berinteraksi dengan komunitas lain. Paradigma kesukuan yang hidup sebelum Islam, misalnya, akan sengaja untuk menutup diri demi melindungi sukunya dari suku lain yang potensial membawa ancaman. Akan tetapi, kondisi itu hampir tidak mungkin berlaku bagi sebagian besar manusia di muka bumi saat ini.
Terutama sejak hadirnya internet, saat ini yang terjadi justru sebaliknya, pertemuan kita dengan orang-orang yang berbeda kian intensif. Perbedaan tersebut bisa meliputi banyak aspek, bisa saja mereka dari daerah, negara, agama, keyakinan, jenjang pendidikan, kelas sosial atau gaya hidup yang berlainan dari kita. Apalagi di era media baru, kita tidak mungkin lagi mengisolasi diri dari keragaman. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang elegan untuk hidup di era plural ini adalah menerima keragaman dengan sebagai kenyataan.
Tentu saja, naif rasanya jika menuntut seluruh manusia untuk bersikap elegan. Seperti yang baru saja kita singgung, keragaman itu juga mewujud dalam berbagai cara manusia merefleksikan sesuatu. Dalam konteks kehidupan beragama, ada manusia yang lapang menerima keragaman keyakinan yang ada di sekitarnya. Namun, tidak sedikit orang yang nyinyir kok bisa tetangga sebelah meyakini kalau Yesus itu Tuhan, misalnya.
Jika nyinyir itu tidak berdampak pada perlakuan diskriminatif dan kekerasan, menurut saya aman-aman saja. Sama halnya ketika kita berniat melakukan kejahatan. Ya gak masalah selagi itu tidak direalisasikan. Namun, jika sikap resistensi terhadap keragaman itu berlanjut kepada tindakan ekstrem, maka rasanya perlu ada upaya untuk menyadarkan bahwa keragaman itu niscaya.
Jalan paling efektif, menurut saya, untuk membentuk komunitas keberagaman yang minim konflik adalah dengan dialog. Dialog bukanlah debat. Banyak dialog lintas agama gagal memperbaiki sikap sosial mereka karena mereka terjebak pada perasaan bahwa mereka sedang melakukan dialog, padahal mereka sedang berdebat. Bedanya jelas sangat ekstrem. Dalam perdebatan, orang bertujuan untuk membuktikan kepada yang lain tentang kebenaran ideologinya dengan berbagai argumen yang meyakinkan dan untuk menolak pandangan yang berbeda. Sementara itu, tujuan dialog bukan untuk meyakinkan lawan bicara kita, tetapi untuk belajar secara terbuka dari seseorang. Di dalam dialog tak ada dominasi dan monopoli pandangan satu pihak terhadap pihak lain.
Yang paling penting, dialog memuat dimensi relasional. Dalam dialog, kita tidak hanya mengenal pendapat orang lain, tetapi sekaligus mengenal manusia yang lain. Kita sebagai manusia mengungkapkan pandangan kita, sementara partisipan dialog yang lain juga mengungkapkan keyakinannya sebagai manusia. Aspek manusia bertemu manusia inilah yang menjadikan dialog mengandung unsur relasional. Melalui dialog kita memiliki kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Pelan-pelan kita akan menyadari bahwa eksistensi kita berarti bagi orang lain, demikian juga sebaliknya.
Namun, dialog bukan semata soal bertukar gagasan saja. Dialog bukan hanya soal perbincangan teologis di atas meja. Saripati aktivitas dialog adalah untuk saling memahami satu sama lain. Untuk mengambil saripati itu, banyak cara dialog yang bisa dilakukan. Dialog, misalnya, dapat dilakukan dalam bentuk festival budaya. Dalam festival, kita akan saling mengetahui karakteristik budaya satu sama lain.
Dialog juga bisa dilakukan dengan pendekatan progresif dengan mendiskusikan satu isu penting. Contohnya, perwakilan umat Islam dan Kristen membahas soal isu ekologi di dunia modern. Komunitas Kristen akan mengenal bagaimana perspektif Islam mengenai kerusakan lingkungan. Sebaliknya, umat Islam akan mengenal bagaimana doktrin Kristen soal menjaga lingkungan. Seperti yang telah dibincang tadi, selain aspek percakapannya, relasi antar manusia menjadi penting dalam konteks ini.
Kembali ke soal pelangi, Tuhan tidak menciptakan pelangi hanya dengan satu warna. Kita juga tentu tidak akan menikmati keindahannya jika pelangi bertema monokrom. Keragaman yang diciptakan Tuhan salah satunya adalah untuk membuat alam semesta ini tetap estetik. Rumah akan terlihat indah jika genteng tidak memaksakan keramik untuk menutup atap. Umat manusia akan hidup damai jika keragaman itu terorganisir dengan baik melalui dialog. Tidak ada dominasi, tidak ada marginalisasi, tidak ada diskriminasi. Manusia saling menyadari porsinya dan saling memahami satu sama lain.



