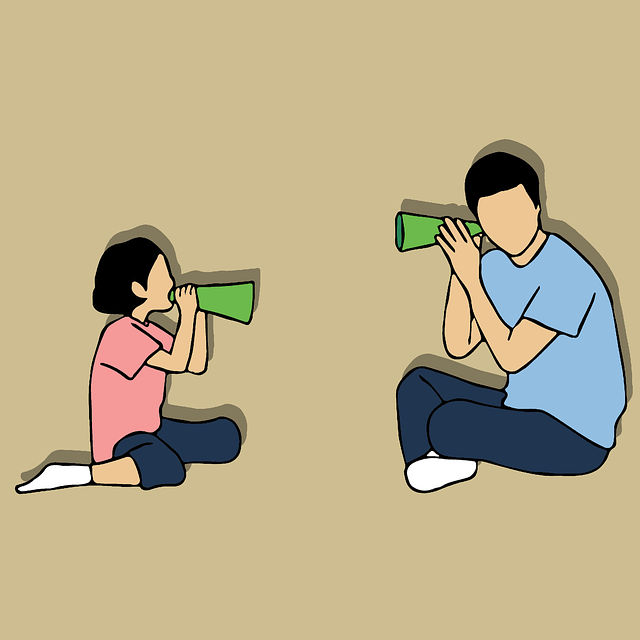
Ada banyak nuansa yang terdapat di dalam tafsir hadist ataupun Al-Qur’an soal negara-bangsa. Mudah untuk menemukan detail konteks sosial beserta evolusi historis bahkan untuk teks dengan redaksi seliteral apapun, sampai redaksi literal tersebut bisa ditawar untuk konteks Indonesia.
Di lain pihak, gejolak sosial-politik Indonesia masa kini juga memengaruhi tidak hanya tingkat popularitas, melainkan juga kecenderungan bentuk tafsir tertentu untuk tujuan tertentu.
Begitu juga dengan tafsir teks suci mengenai relasi gender. Cendekiawan, komunitas, kampus, individu, hingga influencer ikut berkontribusi menyajikan nuansa-nuansa tambahan soal teks-teks relasi gender agar akar partriarkisnya netral.
Hasilnya, muncul kekayaan khazanah dari mulai filosofis sampai aplikatif tentang seluk-beluk relasi gender di Indonesia, yang dari segi intelektual dapat dibedakan dengan kerabatnya di Barat sana ataupun di Timur Tengah, dan dari segi manfaat sosial jelas indikator serta dampaknya.
Akan tetapi, hal serupa belum terjadi pada tafsir teks tentang parenting atau relasi orang tua dan anak. Alhasil, banyaknya produksi tafsir tentang relasi orang tua-anak di ruang populer seperti mimbar, televisi, keseharian dan bahkan institusi pendidikan agama, cenderung miskin makna.
Dalam tema negara-bangsa dan tema relasi gender, mudah untuk menemukan uraian yang tuntas dari jejalin benang kusut antara: mana masalah bias-kognitif, mana masalah konteks sosial, mana budaya Arab, Asia Tenggara, mana kontruk budaya Indonesia, mana Jawa, warisan feodalisme,mana pengaruh modernisme, dan mana pengaruh kapitalisme ataupun urbanisme, secara kongkrit dan terang.
Dengan kata lain, ada pengecualian-pengecualian rigit untuk menjelaskan seberapa jauh otoritas teks agama dapat berlaku dalam aneka kasus negara-bangsa ataupun kasus relasi gender. Pengecualian-pengecualian serupa nyaris tidak pernah muncul dalam penjelasan tafsir teks tentang relasi orang-tua anak. Pandangan bahwa suara orang tua adalah suara Tuhan masih populer.
Hari ini, bila ada seseorang menyatakan bahwa feodalisme ala kekhalifahan adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah (karena raja adalah orang pilihan Tuhan), atau menyatakan bahwa suara laki-laki adalah suara Tuhan, maka ia bisa diprotes banyak orang―sekalipun banyak teks agama menyatakannya dengan redaksi literal.
Tapi tak ada telinga yang memerah bila mendengar seseorang mengklaim suaranya adalah Tuhan ketika memarahi anak, dan dengan ringan akan mengambil justifikasi dari redaksi literal teks tentang hierarki dan posisi orang tua-anak beserta dengan seabreg kutipan reward and punishment-nya.
Bukankah hanya nabi yang memiliki sifat maksum (terjaga dari kesalahan)? Namun, banyak orang tua mengklaim titahnya adalah kebenaran mutlak ketika memarahi anak. Masalah menjadi rumit sejak kita belum memiliki ukuran yang akurat tentang makna akhlak, makna durhaka, dan makna berbakti.
Tiga istilah kunci tersebut cenderung diterima apa adanya, dan nyaris tidak pernah melibatkan kajian sosial-historis atas perbedaan maupun perubahan makna di satu tempat dan waktu atau lainnya. Implikasinya, hubungan orang tua-anak cenderung dibingkai dengan ukuran-ukuran permukaan, seperti tingkat pitch suara dan jumlah materi yang diberikan.
Hal-hal lain yang lebih mendasar, seperti cara komunikasi, praktik diskursif, tekanan sosial, dinamika lingkungan sekitar, dinamika psikologi, dan perbedaan konstruk sosial antara orang tua dan anak, luput dari pertimbangan. Problem ini muncul, salah satunya, dari kecenderungan populer dalam menafsirkan teks tentang relasi orang tua-anak melalui pendekatan testimonial: mengidealkan apa yang pernah direkam oleh Nabi, namun mengabaikan diversitas bentuk relasi orang tua anak lainnya, baik yang tersedia pada masa itu ataupun masa kini.
Romantisme kemudian timbul di antara proses produksi tafsir dan praktik implementasi tuntunan agama (dari mulai keseharian, narasi televisi, sinetron, khutbah, dll). Hal prinsipil seperti mutual-respect, praktik diskursif yang sehat, kebebasan dari filial-piety, dan hal puitik seperti penderitaan hidup, jumlah pengorbanan, dan tinggi-rendah intonasi suara, keduanya dikaburkan oleh romantisme mengakar.
Dua tema dominan dalam romantisme ini adalah, anak durhaka vs anak berbakti. Selain neraka, kedurkahaan sering dikaitkan dengan nasib malang seorang anak secara ekonomi dan mental (eksistensial) di masa depan. Tapi, tak ada yang pernah mempertanyakan, kenapa jumlah orang tua yang hari ini tidak mujur secara ekonomi―padahal telah berbakti pada generasi kakek―juga cenderung banyak?
Selain surga, keberbaktian sering dihubungkan dengan nasib mujur dan ajaib seorang anak di bidang ekonomi dan mental di masa depan. Puncak tertingginya biasanya berupa keberuntungan yang tak terduga, atas hasil keberbaktian heroik penuh pengorbanan. Di sinetron, baik tema durhaka ataupun tema keberbaktian, banyak. Namun berapa jumlah yang sebenarnya terjadi di dunia nyata?
Proses tafsir teks agama, konstruk budaya, representasi sosial (baik di jagat hiburan ataupun narasi), dan aplikasi sehari-hari hubungan orang tua-anak adalah saling berjejalin: satu hal memengaruhi hal lainnya. Tinggal menentukan mana yang berusaha paling dominan.
Masalah intinya adalah, dominasi dari salah satu faktor tersebut menentukan apakah seseorang atau suatu masyarakat akan fokus pada hal-hal ajaib? Atau hal-hal yang realistis? Kecenderungan pada salah satu tendensi akan menentukan banyak hal.
Buku Ilmu Sosial di Asia Tenggara (1996), salah satunya, merekam bagaimana pada tahun 1980-an, Kementerian Agama pernah mengadakan seminar hasil riset pra-perumusan kebijakan. Dihadirkanlah ilmuan sosial dan pemuka agama. Hasil penelitiannya menyatakan harus melakukan A, sementara pemuka agama (sebagai pembahas) berpendapat B. Keputusan yang diambil sebagai dasar kebijakan kemudian adalah B, meskipun hasil riset menyatakan A.
Taufik Abdullah, Kepala LEKNAS-LIPI pada masa itu, hadir sebagai pembahas undangan, dan mengatakan dalam buku tersebut, “apa yang dikatakan oleh pemuka agama lebih dianggap sebagai kenyataan daripada apa yang sebenarnya nyata.”
Tahun 2022, KH Faqihuddin Abdul Qodir pernah memberikan testimoni dalam webinar INFID bulan April kemarin, bahwa “banyak orang yang berpendapat kalau KDRT dan kekerasan seksual mustahil terjadi di rumah tangga, semata karena ‘sudah menikah’, padahal data Kementrian PPPA dan Komnas Perempuan menyatakan jumlah kasusnya sekian dan terus meningkat.”
Kiai Faqih mungkin adalah generasi baru pemuka agama yang mulai memberikan ruang peran ilmu sosial adalam proses advokasi keagamaan. Namun, dalam kasus tafsir teks relasi orang tua-anak, banyak orang yang masih melihat bahwa relasi orang tua-anak adalah sepenuhnya soal langit, meskipun dinamika keduanya sangat manusiawi: unsur keserakahan, pelintiran, ambisi, ekspektasi, kekerasan, dan kebohongan tidak mustahil terjadi.
Di daerah miskin-urban (poor-urban), mudah untuk menemukan bagaimana kemiskinan mendorong tindak kekerasan pada anak. Di daerah, miskin-pedesaan (poor-rural), mudah untuk menemukan bagaimana ekspektasi materil dan marital orang tua terhadap anak mendorong tekanan mental dan konflik antar generasi. Di kalangan wealthy-urban, mudah menemukan bagaimana anak ditelantarkan karena status kelahiran non-marital. Di kalangan wealthy-rural, sebagian anak tertekan karena perbedaan visi hidup.
Konteks sosial tersebut terbangun dari aneka faktor dan nuansa yang tak bisa disimplifikasi dengan indikator intonasi suara, kuantitas pengorbanan, ataupun tindakan simbolik tertentu. Pencarian makna atas nuansa-nuansa di balik dinamika, perubahan, dan struktur sosial penting untuk dilakukan agar tafsir tentang relasi orang tua-anak dapat mengejar keterbelakangan dari dua tema lain (negara-bangsa dan relasi gender) yang lebih mapan.
Teks agama tentang relasi orang tua-anak perlu berhenti ditafsirkan secara literal dan testimonial, agar makna akhlak, makna durhaka, dan makna berbakti, dapat diklasifikasi secara kultural (baik regional ataupun kesukuan), ideologis (mana makna pra-kapitalisme dan pasca-kapitalisme), periodik (mana makna pra-modern, modern, dan pasca-modern), dan secara politik (mana yang merupakan peninggalan rezim terdahulu, dan mana makna yang baru).



