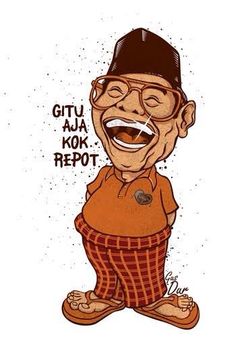
Suatu ketika, di bulan Ramadhan, Gus Dur bersama kiai lain, diundang oleh mantan presiden Soeharto untuk buka bersama. Gus Dur tiba di sore yang cerah, untuk menepati janji hadir ke undangan Pak Harto. Ketika adzan tiba, tuan rumah mempersilakan tamu untuk berbuka, disusul kemudian shalat maghrib berjamaah.
Shalat maghrib pun usai, yang dilanjut dengan ngobrol santai ngalor-ngidul antara tamu dan tuan rumah. Suguhan makanan ringan, kopi dan teh terhidang di meja. Terjadilah dialog antara Soeharto dan Gus Dur.
Soeharto : Gus Dur sampai malam di sini?
Gus Dur : Enggak pak, saya harus segera pergi ke tempat lain.
Soeharto : Oh iya, iya, silahken.. Tapi kiainya, kan ditinggal di sini, ya?
Gus Dur : Oh iya pak! Tapi harus ada penjelasan.
Soeharto : Penjelasan apa?
Gus Dur : Shalat tarawihnya nanti ngikutin NU lama, atau NU baru?
Soeharto bertambah bingung, ia baru kali ini mendengar ada istilah NU lama dan NU baru. Ia lalu bertanya kepada Gus Dur, untuk menghilangkan keraguan.
Soeharto : Lho, NU lama dan NU baru apa bedanya?
Gus Dur : Kalau NU lama, tarawih dan witirnya itu 23 rakaat.
Soeharto : Oh, iya, iya iya.. Ndak apa apa..
Gus Dur sementara diam, memberi jeda pak Harto untuk melempar tanya.
Soeharto : Lha kalau NU baru?
Gus Dur : Diskon 60 %!
Semua terbahak, hahahahaha… Gus Dur, Soeharto dan orang-orang yang mendengar percakapan ini, tertawa.
Gus Dur :Ya, jadi shalat tarawih dan witirnya cuma tinggal 11 rakaat.
Soeharto : Ya sudah, saya ikut NU baru saja. Pinggang saya sakit.
Kisah di atas memberi gambaran bagaimana sosok Gus Dur memberi teladan bagaimana menyikapi perbedaan tanpa menjadi permusuhan. Bahasa komunikasi menjadi kunci bagi Gus Dur untuk menjebol perbedaan tradisi, ideologi maupun kekuasaan politik. Gus Dur, di hadapan Soeharto, tidak lekas tunduk dalam lingkaran politik yang menjadi benteng kekuasaan penguasa Orde Baru.
Justru, Gus Dur dengan gesit keluar dari penjara ideologi, untuk membedakan NU dan Muhammadiyah, menjebol perbedaan tradisi dan ritual ibadah dengan guyonan yang mencairkan ketegangan komunikasi. Coba, bayangkan jika Gus Dur tidak mengungkapkan perbedaan dengan guyonan, yang timbul adalah jurang perbedaan ideologi.
Maaf, Belajar dari Gus Dur
Pesan penting dari Gus Dur bagi umat manusia—tidak hanya warga Indonesia, namun juga warga dunia—adalah menjaga nilai kemanusiaan. Bagi Gus Dur, kemanusiaan menjadi kunci untuk menghormati sesama: memandang manusia sebagai manusia. Inilah pesan Gus Dur yang dijabarkan dalam prinsip dan tindakan hidupnya, dengan perjuangan sebagai pelaksanaan kata-kata.
Dalam ungkapan Gus Mus, Gus Dur itu merupakan pemimpin yang memiliki keberanian luar biasa. “Ada kiai sepuh yang bilang, Gus Dur tetap dianggap keramat hingga selepas meninggal karena mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kiai manapun,” terang Gus Mus.
Gus Dur, dalam seluruh narasi hidupnya, sangat berani untuk memperjuangkan keadilan, membela mereka yang lemah dan terdiskriminasi. Tidak jarang, sikap Gus Dur membahayakan dirinya sendiri dan keluarga. Namun, Gus Dur terus bergerak dengan prinsipnya, dengan nuraninya.
Dalam sepak terjangnya, Gus Dur sangat berani untuk memperjuangkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi Gus Dur, jika sudah menyangkut HAM, sebagai hak dasar umat manusia, maka siapapun harus berani. Gus Dur berani menyampaikan permohonan maaf atas tragedi 1965, yang melibatkan warga NU dan Banser di berbagai daerah. Meski arus besar tokoh NU menolak sikap Gus Dur, ia terus teguh dengan sikapnya, dengan keberaniannya. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur mengusulkan untuk mencabut TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966.
“…, membuat TAP MPRS (XXV/1966) itu keliru mengenai tadi itu, tentang hak hukum seseorang. Karena itu, saya minta TAP ini dicabut, bukan mencabut hak politiknya, tetapi jangan sampai hak hukum orang kita langgar karena kita jengkel,” ungkap Gus Dur yang dikutip Kompas, 1 April 2000. TAP MPRS No 25 tahun 1966 berisi tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Kebijakan ini, juga menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia, serta larangan untuk menyebarkan faham atau ajaran komunisme.
Bagi Gus Dur, maaf merupakan kunci. Ungkapan maaf yang dimaksud Gus Dur bukan maaf politik yang didengungkan penguasa. Namun maaf yang disertai jalan lempang untuk menjemput keadilan, menjernihkan gelap sejarah yang terjadi di masa lalu. Dengan maaf, Gus Dur ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu kembali, memikirkan masa depan negeri.
Gus Dur juga mengajak orang Indonesia untuk memberi maaf. Ketika etnis Tionghoa mendapatkan perlakukan diskiriminatif, pada 1998, Gus Dur mengajak untuk mencari jalan terang. Gus Dur membela orang-orang Tionghoa Indonesia, sebagai etnis yang terus menerus mendapatkan diskriminasi politik. Orang Tionghoa di negeri ini dijadikan sapi perah masa kolonial Belanda, hingga perlakuan diskriminatif pada masa Orde Baru.
Ketika menjadi presiden, Gus Dur mencabut Inpres no 14 tahun 1967. Kebijakan ini, memberi ruang bagi orang Tionghoa untuk mengekspresikan ritual, tradisi dan kebudayaannya di ruang publik. Gus Dur menetapakan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2000, dengan menjadikan Imlek sebagai Hari libur nasional. Komunitas Tionghoa di negeri ini berterima kasih kepada Gus Dur. Pada 10 Maret 2004, Gus Dur mendapat gelar sebagai Bapak Tionghoa Indonesia, oleh komunitas Tionghoa di klenteng Tay Kek Sie, Semarang.
Kisah perjuangan Gus Dur terhadap warga Papua, Aceh dan beberapa komunitas yang terdiskriminasi, sejatinya merupakan cermin bagi kita untuk melihat pesan damai yang disampaikan Gus Dur. Dari seluruh pesan cinta yang diungkap Gus Dur, maaf adalah kunci.
Ramadhan bersama Gus Dur, adalah melepaskan seluruh energi kebencian dan menggantinya dengan keindahan maaf. []
Munawir Aziz, esais dan peneliti, penulis beberapa buku kajian Islam Nusantara, twitter: @MunawirAziz



