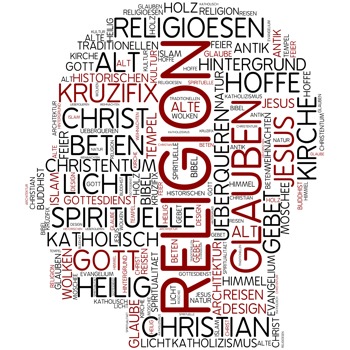
Jutaan umat Islam dari berbagai Ormas Islam berasal dari beberapa daerah di Indonesia datang ke Jakarta berdemonstrasi menuntut agar Basuki Tjahya Purnama, Gubernur Jakarta, segera diperoses hukum karena dianggap telah menista agama.
Dalam kunjungan ke Kepulauan Seribu, Ahok — begitu ia biasa disapa — berpidato di depan masyarakat Kepualuan Seribu mensosialisasikan salah satu program pemerintahannya. Dalam pidatonya itu, terselip kata-kata seperti ini:
“Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu gak pilih saya, karena dibohongin pakai al-Maidah 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya”
Video potongan pidato Ahok ini diunggah ke media sosial, kemudian menuai tanggapan, reaksi, juga kontroversi di kalangan umat Islam. Hingga akhirnya isu ini menggelinding membesar seperti bola salju (snow ball). Percakapan di media sosial — terutama FB dan twitter — hampir semuanya tersedot mengikuti arus ini, baik pro maupun kontra.
Mengapa kasus Ahok begitu menyita perhatian publik dan begitu banyak menghabiskan energi pemuka bangsa ini? Sampai-sampai menjelang pecah demonstrasi 4 November Presiden memanggil pimpinan Ormas keagamaan terbesar negeri ini, NU-Muhamadiyyah, untuk dilibatkan sebagai “pemadam kebakaran” api kemarahan umat Islam.
Apakah karena ia Tionghoa? Atau ia non muslim? Atau karena ia calon gubernur? Dalam konteks demokrasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah pentung alias mubadzir alias sia-sia belaka. Mengapa? Karena konstitusi negara tak menyoal etnisitas atau pun agama sebagai kriteria pemimpin.
Lantas, kenapa persoalan Ahok ini seolah begitu penting menghiasi ruang publik? Apakah aksi 4 November ini bisa disebut peristiwa agama? Atau ini hanyalah sebuah peristiwa politik “berjubah” agama? Bukankah ini terjadi bersamaan dengan momentum Pilkada Jakarta, yang secara kebetulan Ahok sebagai salah satu kontestannya?
Setidaknya isu Ahok ini menjadi menarik karena dua hal. Pertama, ini isu agama (SARA). Agama berada di dalam ruang batin setiap individu dan paling sensitif menerima “ancaman” dari luar. kesadaran keberagamaan seseorang akan mudah terprovokasi jika disulut oleh pihak lain (out group).
Kasus “kartun Nabi” beberapa kali memanitik kemarahan umat Islam dunia. Sebagaimana al-Quran, Nabi Muhammad SAW adalah orang suci, diagungkan, sakral, dan merupakan “kitab suci” kedua bagi umat Islam.
Orang Islam tak melihat kartun Nabi sebagai karya seni, melainkan karena yang dijadikan objek karya seni itu adalah orang yang selama ini dianggap suci dan sakral untuk divisualisasikan. Terlebih ketika karya seni tiu ditunjukkan sebagai bahan olok-olok dan ejekan (mockering)
Begitu pula dengan kasus surat al-Maidahnya Ahok. Boleh jadi Ahok tak bermaksud menyebut al-Maidah sebagai ayat untuk menipu umat (maksudnya ayat yang sering dijadikan legitimasi untuk tidak memilih pemimpin non muslim). Isi kandungan ayatnya benar, tapi penafsirannya seringkali dimanipulasi untuk tujuan politik tertentu.
Terlepas maksud Ahok seperti apa, Ahok sudah memasuki “kamar pribadi” orang lain. Dalam menyikapi al-Maidah 51 umat Islam berbeda pemahaman dan penafsiran. Masing-masing pemahaman dan penafsiran itu hidup dalam keyakinan umat Islam.
Kedua, ini isu politik. Suhu politik Jakarta sedang tinggi. Aktor-aktor politik tingkat tinggi terlibat dalam perebutan kekuasaan di Jakarta. Isu ini mencuat di saat tepat. Dalam politik, isu agama paling potensial dijadikan komoditas politik untuk memengaruhi bahkan menjatuhkan lawan politik. Bagi sebagian orang, dalam menjatuhkan pilihan politik, pertimbangan-pertimbangan keagamaan menjadi sebuah rujukan.
Meskipun Ahok secara resmi sudah meminta maaf, namun persoalannya tak berhenti sampai di situ. Lawan-lawan politik Ahok tampaknya memanfaatkan betul isu ini. Sehingga, tak aneh, jika isu ini semakin hari semakin liar dan membesar. Mereka menunggang kuda agama dalam permainan politik mereka: politik praktis, politik perebutan kekuasaan dan kepentingan.
Lantas, dalam demonstrasi 4 November kemarin, siapa menunggangi siapa? Semua saling membutuhkan, saling berkepentingan dan ditemukan dalam momentum yang sama. Tanpa ada momentum Pilkada sekalipun, orang seperti Riziek Syihab pasti akan bereaksi menanggapi pernyataan kontroversial Ahok. Sama seperti reaksi Riziek menanggapi pernyataan Gus Dur “al-Qura kitab suci porno”.
Apakah Ahok dan Gus Dur menghina al-Quran? Jika statement keduanya dimakan mentah-mentah dengan melepas peristiwa atau konteks pembicaraannya, bisa jadi keduanya menghina al-Quran. Namun, siapakah yang berhak menilai atau memvonis maksud pernyataan seseorang? Sejak dulu agama rawan dibajak dan tak lepas dari pertarungan oleh kelompok kepentingan tertentu.
Oleh karena itu, penyelesaian kasus Ahok tak bisa diselesaikan dengan penyelesaian keagamaan, melainkan harus melalui penyelesaian politik dan hukum. Negara harus hadir di sini. Wallahu’alam bi sawab. []
Jamaluddin Mohammad, peneliti Rumah Kitab, wakil sekretaris LAKPESDAM PBNU



