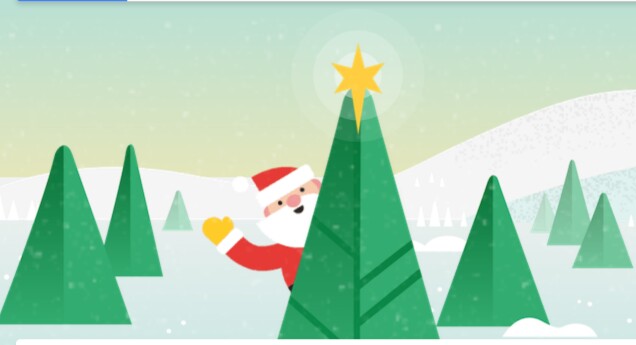
Ada satu hadis yang belakangan kerap dikutip sekalangan muslim sebagai dalil untuk mengharamkan orang Islam memakai topi Santa Claus. Hadis yang lazim disebut hadis tasyabbuh (penyerupaan) itu berbunyi: “Barang siapa menyerupai suatu kaum, ia termasuk kaum itu.” Bagi mereka, pakaian santa adalah bagian dari ikon Natal yang khas Kristen. Karena itu, mengenakan topi santa bagi muslim adalah tindakan menyerupai kaum Kristen, yang dilarang oleh Nabi.
Sebenarnya, hadis tasyabbuh itu tidak secara khusus merujuk pada perayaan hari besar agama non-Islam. Hanya, Ibnu Taimiyyah (1263-1368), dalam kitab Iqtidha’u al-Shirath Al Mustaqim, menggunakannya sebagai dasar utama fatwanya yang melarang umat Islam terlibat dalam perayaan hari besar Nasrani atau agama lain.
Bagi Ibnu Taimiyyah, keterlibatan semacam itu sama halnya dengan turut menyemarakkan syiar Kristen, yang bisa diartikan sebagai persetujuan terhadap ajaran Kristen itu sendiri. Karena itulah, tindakan tasyabbuh ini diharamkan karena bisa menjurus pada kekafiran. Fatwa Ibnu Taimiyyah itulah yang dijadikan sebagai salah satu rujukan pengharaman atribut Natal, bahkan juga ucapan selamat Natal.
Tapi betulkah tasyabbuh serta-merta diharamkan? Bagaimana dengan syar’u man qablana, ajaran umat sebelumnya yang oleh Allah dinyatakan sebagai berlaku bagi umat Islam. Misalnya, puasa Ramadan, yang oleh Al-Quran diwajibkan “sebagaimana orang-orang sebelum kamu”. Ahli tafsir generasi pertama, seperti Muqatil bin Sulaeman, memaknai “orang-orang sebelum kamu” sebagai ahlul injil alias kaum Nasrani. Sedangkan Mujahid bin Jabar mengartikannya sebagai ahli kitab secara umum. Contoh lain, keharaman daging babi yang juga berlaku untuk kaum Yahudi. Yang ingin saya katakan, syar’u man qablana, yang lalu diadopsi menjadi ajaran Islam, bukan saja menyerupai, melainkan justru merupakan kelanjutan dari agama para Rasul sebelumnya.
Di samping itu, keniscayaan haramnya tasyabbuh juga bermasalah ketika dihadapkan pada hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan, betapa dalam hal gaya rambut, Nabi lebih suka menyerupai model rambut kalangan ahli kitab ketimbang kaum kafir Quraisy (HR Muslim). Yang menarik, ada juga hadis lain yang berbunyi: “Berbedalah kalian dari Yahudi. Mereka beribadah dengan tidak memakai sepatu atau sandal.” (HR Abu Daud). Namun dalam hadis lain dinyatakan bahwa Nabi sendiri pernah salat tanpa sepatu atau sandal. Jadi, ketika kaum muslim salat tanpa alas kaki, sejatinya itu meniru cara peribadatan Yahudi. Tapi toh tak berarti haram, bukan?
Karena itu, hadis tasyabbuh di atas jangan kita pahami secara sempit dan saklek sebagai pengharaman segala bentuk penyerupaan terhadap golongan agama lain. Tak sesederhana itu.
Ketika Ibnu Taimiyyah memfatwakan haramnya memakai atribut perayaan hari besar Nasrani, kekuatan politik Islam saat itu berada dalam krisis akut: runtuhnya khilafah Abbasiyah, invasi pasukan Mongol, dan ancaman Perang Salib. “Kegalakan” fatwa Ibnu Taimiyyah lahir dari situasi perang agama yang akut antara Islam dan Kristen. Nah, ketika Perang Salib sudah tak ada lagi, relevansi fatwa Ibnu Taimiyyah di atas layak dipertanyakan.
Perlu dicatat, tak semua yang secara lahiriah tampil sebagai penyerupaan bisa dikategorikan sebagai tasyabbuh yang diharamkan. Bukankah menurut hadis segala tindakan bergantung pada niatnya? Setidaknya itu disadari oleh para Ulama NU yang pada 1927 menyatakan bahwa berpakaian ala penjajah Belanda yang Kristen tak lantas identik dengan tasyabbuh yang haram. Kalau niatnya sekadar berpakaian saja, ya tidak masalah. Bahkan, tindakan penyerupaan bisa diniatkan sebagai perlawanan. Para pendiri republik, misalnya, mengadopsi pendidikan dan teknologi Belanda justru untuk mensubversi penjajahannya.
Hal lain, benarkah topi santa identik dengan ikon perayaan Natal yang khas Kristen? Ikonisasi terhadap sosok santa tak bisa dilepaskan dari komodifikasi kapitalisme. Kostumnya yang merah putih adalah kreasi Coca-Cola pada 1940-an. Bahkan perayaan Natal itu sendiri juga bertaut erat dengan kapitalisme. Dan kapitalisme, kata Marx dalam Manifesto Komunis, mengubah apa pun yang dianggap sakral menjadi profan: semua disulap jadi komoditas.
Tak mengherankan bila kaum Kristen Puritan di Eropa dan Amerika, yang tak suka terhadap gebyar Natal yang duniawi, pernah mengharamkannya pada abad ke-17. Menariknya, sikap kaum Puritan ini sejalan dengan sebagian kaum muslim yang mengharamkan atribut Natal dengan dalil tasyabbuh. Tapi, jangan-jangan, dengan begitu mereka tanpa sadar justru menyerupai kaum Kristen Puritan.
Sekarang era globalisasi, bukan Perang Salib. Penyerupaan tak serta-merta identik dengan tasyabbuh yang diharamkan. Karena itu, topi santa tak perlu dilihat secara paranoid sebagai sesuatu yang serta-merta mengancam akidah. Orang bisa menikmati kegembiraan Natal (misalnya untuk liburan) tanpa harus menjadi Kristen, sebagaimana orang bisa menikmati kegembiraan Idul Fitri tanpa harus menjadi muslim.[]
NB: Artikel ini hasil kerjasama islami.co dan INFID



