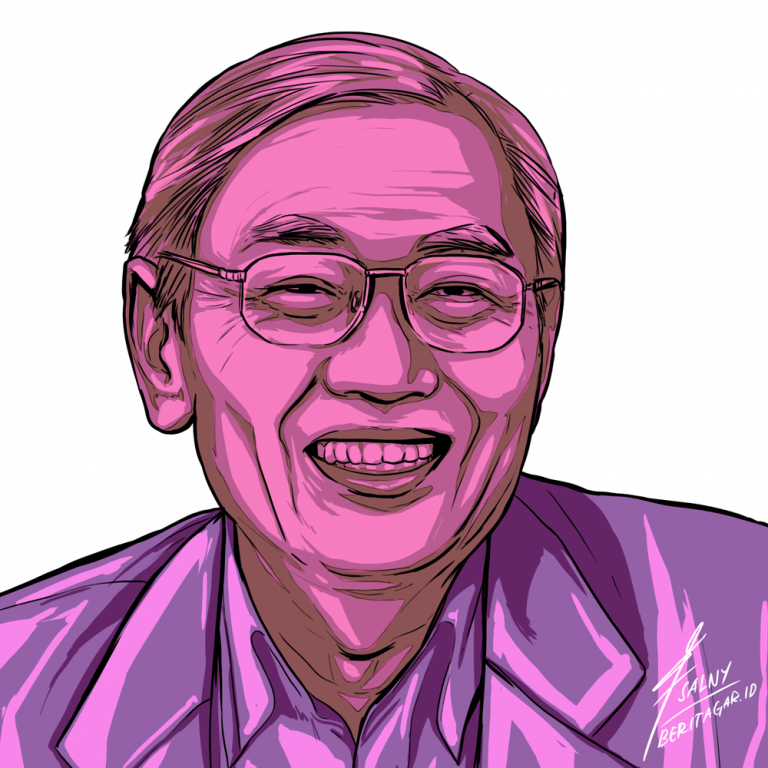
Muslim kota memiliki dua kecenderungan gairah ke-Islaman yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi marak penggunaan busana muslim dan banyaknya majelis, serta diskusi agama. Namun di sisi lain berpeluang negatif, berpotensi dimanfaatkan kelompok intoleran. Nurcholis Madjid (1939-2005) memilih segmen dakwah kepada muslim kota ini dalam menyebarkan pemikirannya tentang islam, humanisme dan ke-Indonesiaan.
Terkait pilihan ini, Wahyu Nafis, salah satu muridnya, pernah menyebut Cak Nur sebagai sopir taksi. Apa maksudnya? Ini metafora, di mana penumpang taksi umumnya merupakan masyarakat kalangan menegah ke atas dengan akses kesehatan, pendidikan dan penghasilan yang baik. Untuk itulah, Cak Nur juga turut bergabung dengan Klub Kajian Agama (KKA).
Forum ini dimulai sejak 28 November 1986 dan memungkinkan bertemunya para sarjana Islam dengan kemampuan teks-teks keislaman klasik, sekaligus mengalami pertemuan dengan budaya modern–yang saat itu dilekatkan kepada Barat–dengan muslim kota rasional, pengetahuan agama yang tidak mendalam tapi memiliki gairah belajar Islam yang tinggi.
Klub ini sendiri menyajikan Islam yang modern, inklusif, dan santai. KKA diselenggarakan di hotel berbintang, ditingkahi dengan denting piano musik klasik Mozart & Beethoven. Model pengajian ini, menurut laman resmi Paramadina, tidak melulu normatif namun kontekstual–ia juga dikaitkan dengan aspek peradaban Islam yang terkait. Dengan metode semacam ini, maka “tali hubungan dengan Allah” diterjemahkan menjadi “tali hubungan dengan sesama manusia”.
Perspektif paling penting pengajian ini adalah penekanan bahwa agama tetap bersifat kemanusiaan, sebab ia ditujukan untuk menuntun manusia mencapai kebahagiaan yang memancar dari Ketuhanan. Dengan demikian, agama merupakan sesuatu yang tidak berjarak dengan manusia. Pola pikir semacam ini nampaknya sesuai dengan masyarakat perkotaan yang cenderung logis dalam mengambil kesimpulan, namun memiliki semangat tinggi dalam beragama.
KKA ini menjadi sangat penting sehingga disebut Cak Nur sebagai gua garba Paramadina (baca: rahim) komunitas kajian Islam Paramadina. Pada tahun berikutnya, Cak Nur mewujudkan sebuah yayasan bersama dengan Sudwikatmono, seorang pengusaha Muslim, bernama Yayasan Paramadina-Mulya.
Yayasan ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Wakaf Paramadina milik Cak Nur dengan Yayasan Pondok Mulya milik pengusaha yang sering mengundang Cak Nur dalam pengajian di rumahnya. Bersama dengan para kolega termasuk sahabatnya, Utomo Dananjaya, mereka mendirikan Universitas Paramadina-Mulya pada 10 Januari 1998 dan akhirnya berubah menjadi Universitas Paramadina.
Sebelumnya, Cak Nur mendirikan Yayasan Samanhudi pada tahun 1971–nama ini nampaknya merujuk pada Haji Samanhudi yang mendirikan Sarekat Islam yang merupakan organisasi massa Islam berbasis pedagang batik yang visioner sekaligus progresif.
Di tempat ini, alumnus sastra Arab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bertemu dan berdiskusi secara internsif dengan para intelektual seperti Djohan Efendi, M. Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Syu’bah Asa sebagaimana ditulis Greg Barton bertajuk Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid(1999).
Universitas ini, mengutip Budhi Munawar Rahman dalam Ensiklopedi Nucholish Madjid(2006), memiliki misi khusus yakni untuk melakukan kerja-kerja ijtihad dan pembaruan yang akan mengubah masyarakat ke arah peradaban [baru]. Kerja semacam ini memerlukan, bagi Cak Nur, pekerjaan kalangan elit dan kaum terpelajar.
Cak Nur, Jejak Buku dan Keteguhan
Ide dan pemikiran Cak Nur dapat dibaca dalam Doktrin Islam dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan yang terbit pertama kali pada 1992. Buku ini cetak berkali-kali dan merupakan materi ceramah Cak Nur dalam KKA. Ada berisi 4 (empat) bagian besar dalam buku ini: tauhid dan emansipasi harkat manusia, disiplin ilmu tradisional, membangun masyarakat etika, dan universalisme Islam dan kemodernan.
Bila bagian kedua dan ketiga lebih umum membicarakan agama dan manusia, maka bagian kedua membicarakan disiplin ilmu yang lazim diterapkan dalam pemikiran Islam arus utama di Indonesia, serta unsur-unsur yang mungkin masuk di dalamnya sekaligus kritik. Bagian keempat membicarakan Islam dan modernitas, termasuk unsur-unsur modern seperti kemajuan teknologi yang banyak diakses masyarakat kota. Adapun pribadi Cak Nur dapat diteropong melalui Hidupku Bersama Cak Nur; Catatan Omi Komaria Madjid (2015).
Buku ini membahas sisi personal Cak Nur yang nampaknya tidak banyak disorot orang kebanyakan. Jika kita membayangkan nafas panjang Cak Nur dalam sesuatu yang disebutnya sebagai “menyegarkan pemahaman Islam”, maka kita akan menemukan sebagian besar jawabannya. Ibu Omi, isteri Cak Nur terkasih, adalah teman sedih dan gembira bersama Cak Nur dan seorang kawan setia sejak di Indonesia hingga menjamah berbagai belahan dunia termasuk kuliah jenjang magister dan doktoral di Amerika Serikat.
Kita semua mengetahui bahwa Cak Nur dikritik keras–sekaligus dipuji banyak orang– menyusul populernya slogan “Islam Yes Partai Islam No” di tahun 70-an. Bagi Cak Nur, ini sebagai bagian dari ide sekularisasi yang mempromosikan pemisahan antara yang profan dan sakral, yang transendetal dan yang duniawi, serta hal lain yang sejenis. Termasuk isu agama dan wewenang negara di dalamnya.
Kritik keras datang HM. Rasjidi, senior Cak Nur di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), organisasi yang menempa dan membesarkan namanya. Tentu saja bukan sesuatu yang mudah, selain pengkritik lain yang terkadang menyerang sisi personal. Sekularisasi yang digulirkan Cak Nur oleh Rasjidi disebut merupakan interpretasi semena-mena dari makna aslinya. Selain itu, sekularisasi selalu akan berujung pada sekularisme, di mana agama dipisahkan dari negara bahkan bisa jatuh dalam relasi benci agama yang merugikan umat Islam.
Pada aras ini, Omi adalah “tipikal” pendamping yang ditakdirkan menemani perjuangan seorang pemikir besar. Mereka merupakan perempuan dengan stok kesabaran di atas rata-rata, pantang menyerah, dan tidak hobi mengeluh. Sebagaimana Gus Dur ditemani oleh Sinta Nuriyah Wahid.
Omi setia ada bersama Cak Nur menghadapi sejumlah kesulitan sejak kesulitan ekonomi hingga serangan yang “ideologis” karena pemikiran Cak Nur yang berbeda dari arus utama. Ketika kesulitan ekonomi membuat kita beradaptasi terhadap kelaparan dan kehausan yang sifatnya fisik, maka kritisisme pada Cak Nur mengukur bagaimana emosi dikelola.
Cak Nur sendiri diuji keteguhannya untuk terus bertahan, tanpa perlu membalas beberapa seruan yang sudah keterlaluan seperti menyeret manusia ke comberan atheismeatau gagasannya paralel dengan sikap iblis. Cap ini rasanya belum lengkap, sehingga Cak Nur dilekati dengan cap paripurna bernama agen zionis–Yayasan Paramadina yang didirikan Cak Nur sendiri justru pernah menolak bantuan George Soros yang jutawan Yahudi dalam pembangunan gedung Universitas Paramadina.
Jangan lupa, Cak Nur juga dilabeli liberal. Mungkin julukan ini terbukti mengingat pola pendidikan liberal Cak Nur dalam mendidik sekaligus membebaskan kedua anaknya dalam bekerja dan berkarir, yakni Nadia Madjid dan Ahmad Mikail Madjid. Nadia bekerja VoA (Voice of America) dan Ahmad berkarir di sebuah bank internasional cabang Jakarta.
Cak Nur pada kenyataannya bertahan dan konsisten sejak pidatonya bertajuk Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia di TIM (Taman Ismail Marzuki) pada tahun 1972 hingga menjadi tim penulis buku Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (2004) dan akhirnya berpulang pada 29 Agustus 2005.
Selama masa perawatan, Cak Nur sempat dikunjungi sejumlah tokoh dari Pesantren Gontor selaku almamaternya dan negara meminta jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta setelah ia meninggal dunia. Ia adalah segelintir orang dari sipil yang mendapatkan kehormatan ini karena jasanya yang begitu banyak bagi umat, bagi Indonesia.
Lantas, apa kemudian?
Jasad Cak Nur mungkin pergi namun pemikirannya masih terpatri hingga kini. Murid-murid Cak Nur masih giat menyebarluaskan gagasannya seperti usaha yang dilakukan Budhi dan kawan-kawan di lingkungan Yayasan Paramadina melalui Ensiklopedia Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban (2006) yang sudah terbit sebanyak 4 (empat) jilid. Di sisi lain, Omi beserta murid Cak Nur yang lain seperti Wahyuni Nafis mendirikan Nurcholish Madjid Society (NMS) untuk merawat dan melanjutkan gagasan dan ide alumni University of Chicago ini.
Universitas Paramadina yang pernah digadang-gadang Cak Nur beserta koleganya untuk menjadi laboratorium pengkajian Islam yang modern kini sudah tidak lagi menjadi titik pusat seperti dahulu. Dalam situasi ini, ingatan penulis segera melayang pada pidato seorang pejabat Universitas Paramadina yang mengaku sudah memadamkan api di depan kelompok yang secara idelogis berseberangan dengan pemikiran Cak Nur.
Sejatinya api ini tidak pernah padam. Lebih banyak cinta dan kepedulian yang terus disebarkan oleh orang-orang di lingkaran dalam Cak Nur itu dan kita semua ketimbang semangat pemadaman itu sendiri. Mereka inilah yang akan melanjutkan perjuangannya untuk menangkap Islam sebagai api, mengutip Ashmad Gaus dalam buku Api Islam Cak Nur: Jalan Hidup Seorang Visioner (2015), bukan arang atau abu. Wallahu A’lam…
Penulis: Nurun Nisa’, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta konsentrasi Agama dan Politik. Aktivis Gusdurian Jakarta.



