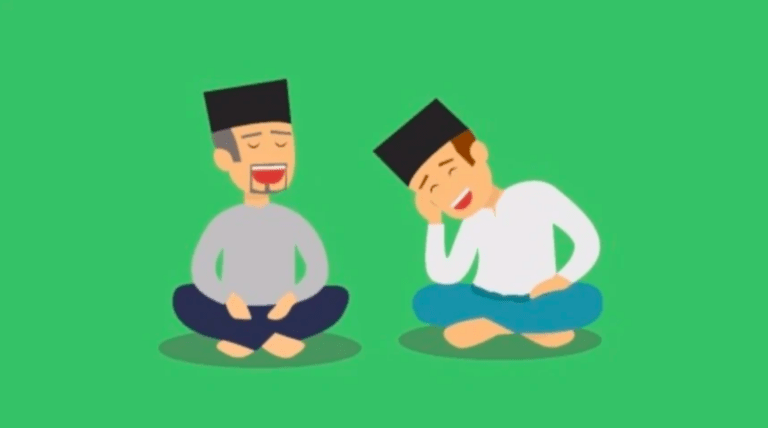
Pada 7 Maret 1942, Jepang telah membentuk Gunseikanbu (Pemerintahan Militer) di Pulau Jawa. Pembentukan organisasi pemerintah itu dimulai beberapa saat setelah pendudukan Jepang di Banten, Indramayu, Rembang, Tuban hingga penyerahan tanpa syarat dari Panglima Angkatan Perang Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten kepada Panglima Tentara ke-16 Jepang Letnan Jenderal Hitoshi di Kalijati.
Kebijakan Jepang dimulai dengan mengeluarkan Maklumat No. 1 dan menyebarkan ke masyarakat. Maklumat itu berbunyi:
“Karena bala tantara Dai Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon, dan juga hendak mendirikan ketentraman yang Tangguh untuk hidup makmur bersama-sama dengan rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Raya bersama-sama, maka dari itu bala tantara Dai Nippon melangsungkan pemerintahan militer bagi sementara waktu di daerah yang telah ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.” [Pemerintah Militer/Gunseikanbu] Di Jakarta.
Sontak saja, setelah mendapatkan selebaran Pemerintah Dai Nippon Jepang, muncul komentar dan sikap beragam di masyarakat, hal itu secara unik digambarkan Saifuddin Zuhri dalam Berangkat Dari Pesantren (2013, Hal 242).
Nippon dan Saudara “Keturunan”
“Bagaimana pendapat saudara mengenai maklumat balatentara Dai Nippon ini. Saudara seorang wartawan, biasanya bermata jeli, tanya R.H. Konsul NU ke Saifuddin Zuhri dalam satu rapat.
“Waaah, kalimatnya panjang sekali. Mesti baca secara saksama”, jawabnya
Di tangan masing-masing ada selembar maklumat Gunseikanbu, mereka mulai kembali membaca.
“Di sini ada kata-kata ‘memperbaiki nasib rakyat Indonesia’, ‘yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Dai Nippon’, ‘mendirikan ketenteraman yang teguh’, ‘makmur bersama-sama’, mempertahankan Asia Raya’. Sementara waktu, kalimat-kalimat itu mengandung berbagai pertanyaan”, ulas Saifuddin.
“Pendapat saudara saya dukung”, sela Ustadz Mursyid. “Kalimat memperbaiki nasib rakyat Indonesia saya kira cuma bujuk rayu kalau bukan kata-kata tipuan. Apalagi kalimat, “yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon’, rasa-rasanya kok baru sekarang ini saya mendengarnya… itu cuma sebuah tipu muslihat. Jangan lupa : Al-kharbu khidah, perang itu tipu muslihat’.
“Mungkin yang dimaksud Niipon itu bahwa kita dari satu keturunan dengan mereka, artinya sama-sama berasal dari Nabi Adam…! sela Kiai Syatibi membuat semua yang hadir tertawa.
‘Meski pun sama-sama keturunan dari Nabi Adam, kita dari keturunan Habil sedang mereka dari keturunan qabil,’’ sahut Kiai Halimi memecah gelak tawa hadirin.
Tak syak lagi, usaha penyebaran maklumat melalui strategi intensif, massif dan mendesak ala Pemerintah Jepang itu untuk ditujukan merebut simpati masyarakat dengan segera, khususnya muslim sebagai penduduk terbesar di Indonesia.
Kiai dan Nomor Urut
Suatu hari di awal tahun 1943 warga berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jawa Timur. Sungguhpun itu waktu para warga NU sedang berada dalam suasana tayakkur, seiring telah keluarnya Hadlratusy Syaikh dari penjara Dai Nippon, namun tetap menjaga kewaspadaan agar tidak kendor.
Perjuangan masih panjang, ujian-ujian dihadapi dengan ketabahan dan tawakkal. Para muballigh mendapat petunjuk dan bimbingan dalam perjuangan Izul Islam wal Muslimin di tengah-tengah suasana perang ‘Asia Timur Raya’, tulis Saifuddin Zuhri (2013).
Abdul Wahab Hasbullah menggembleng ketabalan iman dan ketakwaan mereka yang hadir. Dan yang paling membekas, para Muballigh NU memperoleh ijazah wirid bernama Selawat Kamilah dan Hizbur Rifa’i, yang harus dibaca di saat-saat tertentu.
“Setan ora doyan, dhemit ora ndulit”, ucap Kiai Wahab Hasbullah dengan nada jenaka, tapi tetap membuat pasukan makin berani berjuang.
Lewat beberapa hari, ada kabar akan kedatangan Shuchokan (Residen) Surabaya dan pembesar Nipoon ke Pesantren Tebuireng. Kedatangan itu mempunyai makna penting. Nippon hendak memperbaiki hubungannya dengan umat Islam, setelah peristiwa fitnah dan penahanan terhadap Hadlratus Syaikh selama 5 bulan.
“Kiai Hasyim Asy’ari ini nomor satu, betulkah?, pertanyaan Shuchokan kepada Kiai Abdulmanaf Murtadlo (Kepala Jawatan Agama Karesidenan Surabaya, yang mendampingi KH. Hasyim Asyari) melalui juru bahasa.
“Betul!”
“Kiai Wahab yang bertubuh kecil itu, kiai nomor duakah?” pertanyaan berikutnya.
“Betul”
“Tuan sendiri kiai nomor berapa?” pertanyaan Shuchokan sambal mengamati orang yang ditanyai yang juga bertubuh kecil.
“Nomor tiga!” jawab Kiai Abdulmanaf Murdtadlo dengan tegas. Orang-orang Nippon itu manggut-manggut.
Dlaah habis, begitulah Nippon. Suka aneh-aneh. Biarlah saya berlaku aneh terhadap mereka. Orang-orang yang biasa berbuat aneh tidak akan memandang aneh-aneh hal yang sebenarnya aneh. Memangnya kiai itu apa? Dikasih nomor segala…”. Demikian Kiai Abdulmanaf Murtadlo bercerita sebagaimana dituturkan ulang oleh Saifuddin Zuhri.
Sejak itu aku sekali tempo memanggilnya dengan “kiai nomor tiga, ia membalas dengan tawa terkekeh, ungkap Saifuddin Zuhri.
Demikian dua riwayat unik yang sedikit menggambarkan suasana dalam masa awal penduduk Jepang di tanah air. Hal tersebut sangat unik jika dilihat dari kacamata psikologi massa yang dalam menghadapi kepedihan era Jepang, tetap dapat mengimbangi dengan sikap-sikap satir sekaligus jenaka. Sungguhpun ketika membandingkan era Kolonial Belanda dengan Dai Nippon Jepang, maka fase yang terakhir 3,5 tahun ini tidak kalah berat-menyengsarakannya bagi rakyat Indonesia.
Dan kelak, di daerah yang lain, sikap satir dan jenaka dari masyarakat Indonesia tersebut konon bermunculan dengan model yang beragam, mulai dari pantun, lirik hingga sindiran-sindiran rakyat. Seperti halnya Utomo Priyambudi (2012) pernah mencatat lagu “Wak-wak Gung, Nasinya-nasi Jagung” yang muncul di masa Jepang, lahir dari masyarakat Betawi yang tak tahan karena kehabisan beras hingga orang-orang makan jagung.



