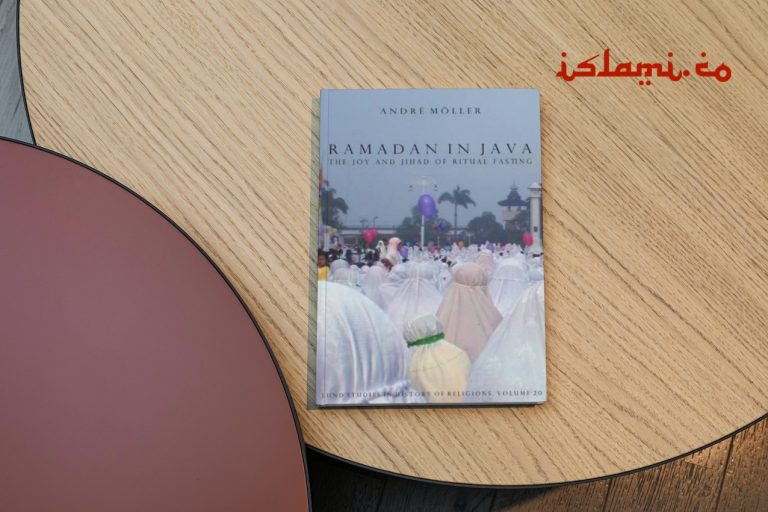
Bulan Ramadhan telah tiba, masyarakat muslim di seluruh dunia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengisi aktivitas di bulan puasa ini. Ramadhan adalah bulan Al Quran, seperti yang disebutkan beragam hadis Nabi, dan bulan istimewa di mana berbagai ibadah dilipatgandakan balasannya di sisi Tuhan.
Gaung Ramadhan ini telah hadir di bulan sebelumnya, di masa Sya’ban bahkan Rajab, yang tergambar dari doa: “Allahumma baarik lanaa fi rajaba wa sya’bana, wa ballighnaa ramadlan.” Begitu pula semarak bulan Ramadhan mulai masuk ke segala aspek kehidupan muslim: mulai sahur, penyesuaian jam kerja, penambahan materi di kelas-kelas sekolah, iklan sarung dan sirup, juga aktivitas tarawih dan tadarus.
Semarak Ramadhan itu memang begitu nyata di tengah-tengah kita, khususnya bagi saya yang tinggal di kampung kota, maupun masyarakat desa. Namun, pernahkah kita mengambil jarak sedikit saja untuk memotret bagaimana Ramadhan itu hadir di tengah kita, dan memahaminya secara lebih manusiawi sebagai bagian dari tradisi?
Saya kira, salah satu karya menarik yang menyajikan kehidupan Ramadhan secara komprehensif, khususnya di Jawa, adalah yang ditulis oleh Andre Möller dalam bukunya Ramadan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting (dahulu diterjemahkan dengan judul Ramadan di Jawa: Pandangan dari Luar).
Buku tersebut adalah disertasi Andre Möller saat studi di Lund University, Swedia, yang merekam hiruk pikuk Ramadhan di Jawa – dalam konteks buku ini, Ramadhan yang ia alami di Yogyakarta dan Blora, Jawa Tengah – sebagai tradisi yang hidup, tidak hanya berasaskan Islam yang normatif dalam teks dan nash, serta berdialektika dengan zamannya. Atau dalam bahasa kajian akademik hari ini, Andre Möller berusaha menyajikan apa yang disebut Living Islam.
Ada tujuh bab dalam buku Ramadan in Java ini, yang tiap babnya saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab yang lebih awal adalah basis informasi yang menunjang pembahasan bab-bab selanjutnya. Pada bab pertama, sang penulis menyajikan mengapa ia mengambil menelaah kehidupan Islam di Blora dan Yogyakarta.
Menurut catatan Möller, Jawa bukanlah entitas tunggal, dan Blora sebagai salah satu entitas kota-kota pantai utara (Pantura) memiliki tradisi berislam yang berbeda dengan Islamnya keraton-keraton Jawa di Yogyakarta yang lebih kosmopolit, maupun Islam di daerah-daerah pesisir Jawa yang lebih “islami” karena para pendakwah lebih dahulu hidup di sana.
Keunikan keberislaman daerah Blora pedesaan bisa dibilang dalam bahasa Möller: “…has no affiliation with any wali and is, as always, rather anonymous and discreet”. Kendati banyak pernyataan bahwa Wali Songo telah “mengislamkan Jawa”, tapi Blora tidak populer dengan kisah para wali, dan juga bukanlah daerah yang terkenal keislamannya. Pada bab pertama buku ini juga, Möller meletakkan konteks penelitiannya pada puasa sebagai ritual dan kaitannya dengan agama-agama lain.
Di bab kedua, Möller memaparkan perkembangan Islam di Jawa dan kelindan para pihak – mulai dari ormas keagamaan sampai pemerintah – yang memiliki pengaruh pada keberislaman orang Indonesia, lebih spesifiknya orang Jawa. Ia mengomparasikan bagaimana ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, sampai Islam Liberal dan Radikal, punya andil memengaruhi lanskap berislam masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.
Hanya saja, Möller mencatat bahwa urusan-urusan liberal dan radikal itu – di masa ia meneliti, kurun 2000-an awal – tidak punya banyak tempat dibicarakan orang-orang desa. Departemen Agama dan MUI juga penting, tapi keduanya tidak pernah menunjukkan sikap ingin menyeragamkan Islam masyarakat khususnya dalam urusan ibadah Ramadhan.
Selanjutnya, peneliti asal Swedia ini memaparkan beragam pandangan tentang syariat puasa dari Al Quran, hadis, juga amalan-amalan terkait. Pada bab ketiga itu juga, ia menjelaskan bagaimana penerimaan masyarakat Jawa terhadap aturan-aturan normatif ibadah Ramadhan.
Dalam syariat Islam, mudah saja menemukan dalil maupun kalam ulama mengenai betapa istimewanya bulan Ramadlan ini – baik dalil itu dari hadis shahih sampai hadis yang palsu. Möller tidak mengkritik adanya dalil-dalil yang bisa jadi bermasalah tersebut, namun ia menunjukkan bahwa otoritas teks tetap dipegang oleh Islam Jawa dalam laku berislamnya.
Lebih jauh, di bab keempat Written Ramadan, Möller memotret secara mendalam pengaruh otoritas ulama, ceramah, dan meningkatnya minat mengaji masyarakat di bulan Ramadhan. Ini seperti gambaran kita yang lebih bersemangat “menambah ilmu agama” dari berbagai medium di bulan Ramadhan. Möller juga tentu tidak melewatkan berkembangnya musik religi dan tren media massa mengisi rubrik mereka secara khusus untuk Ramadhan, dengan memberikan porsi lebih kepada para ulama.
Bab paling seru menurut saya dari buku ini, adalah di bab Lived Ramadan. Hal-hal yang dicatat oleh Möller sebenarnya adalah persoalan yang sudah sangat biasa bagi kebanyakan muslim Jawa rural, dan telah diamalkan tiap tahunnya. Möller dengan mengesankan menjelaskan bahwa konteks bulan Ruwah dan Syawal tidak bisa dilepaskan dari kemeriahan Ramadhan setiap tahunnya. Ia menjelaskan juga persoalan munggahan, nyekar, kupatan, sungkeman, mudik, sampai pasar malam pasca lebaran yang ia ikuti di Blora.
Para peneliti boleh berpikir bahwa Ramadhan adalah bulan yang menyengsarakan dengan berpuasa sepanjang hari. Tapi dari amatan Möller, Ramadhan itu dirayakan – “I need to stress the latter verb here: enjoy.”
Dalam bab Compared Ramadan, Möller membandingkan persoalan-persoalan yang ia rekam dari semarak Ramadhan di Blora, dengan aktivitas Ramadhan di Yogyakarta, juga problem-problem rutinan tiap tahun seperti hisab rukyat, jumlah tarawih, serta bagaimana Ramadhan di belahan dunia seperti Arab Saudi, Maroko dan Turki dilakukan. Media massa, yang dipandang sebagai cultural broker oleh publik, rupanya juga tidak sepenuhnya berhasil memengaruhi pandangan muslim tentang puasa. Pengaruh otoritas keulamaan dan pesantren lebih besar dalam membentuk perayaan Ramadhan di masyarakat.
Islam di Jawa dengan berbagai nuansa festivalnya mungkin hari-hari ini lebih mudah kita temui di pedesaan dibanding perkotaan. Budaya Islam di Jawa, memang selalu mengalami benturan dengan nilai dan ajaran baru. Perkembangan tersebut bisa dibilang adaptif, kendati menurut Möller ”…that the history of Javanese Islam generally has been one of slow—but increasingly fast—and steady movement towards an Islamic ‘orthodoxy’.”
Sejarah Islam Jawa secara umum bergerak lambat – meskipun mulai lebih cepat – menuju Islam yang ortodoks, atau lebih “sesuai syariat”. Tentu komentar ini bisa diamini, melihat bahwa geliat konten dan penampilan islami semakin mendapat perhatian masyarakat luas.
Möller sadar bahwa penelitian Islam Jawa secara antropologis, kerap membenturkan Islam Jawa dengan ajaran Islam yang normatif dan “lebih murni” dalam syariat fikih serta amaliah orang-orang di Timur Tengah. Kekurangan penelitian yang demikian menimbulkan kesan bahwa Islam di Jawa adalah Islam yang “kurang Islami”. Padahal, kacamata biner dalam meneliti laku Islam Jawa apalagi di lingkup pedesaan, akan mengurangi kesadaran betapa dinamisnya pergulatan muslim dengan kedaerahannya.
Pada akhirnya, buku ini adalah salah satu buku ulasan ibadah Ramadhan yang asyik, menyenangkan lagi komplet. Di tengah geliat perbenturan antara ortodoksi Islam dan tradisi lokal dewasa ini, Ramadan in Java adalah buku yang terasa sangat akrab dalam menjelaskan amaliah Islam dengan segala pernak-perniknya, yang mungkin saya atau Anda alami juga di kampung halaman.
Puasa Ramadhan memang jihad memerangi hawa nafsu, tapi ia juga membawa joy, kesenangan, yang seperti itulah kurang lebihnya orang Jawa dan mungkin juga Indonesia merayakan bulan tersebut: sebagai festival dan perayaan tahunan yang selalu berusaha disemarakkan. (AN)



