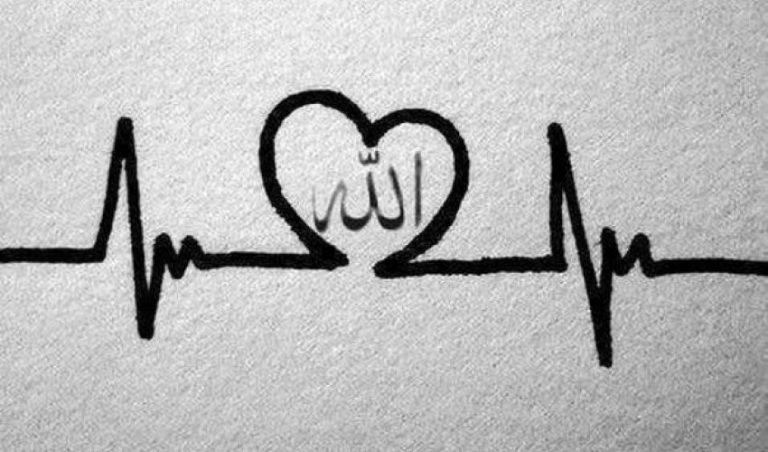
Banyaknya bencana yang menimpa negeri kita ini, konon, akibat makin sedikitnya orang beriman. Tapi kita tahu, hari ini, kian banyak saja orang yang menyebut asma Tuhan, kian sering saja orang mengucap “Allah, Allah, Allah”. Tidak hanya karena masjid-masjid semakin massif dibangun, lalu azan jadi gencar dikumandangkan. Tidak juga lantaran kian gampang umat “disemangati”, lalu sebentar-sebentar berteriak “Allahu Akbar”. Atau karena kian marak peminta sumbangan di jalan-jalan, yang selalu mewiridkan lafadz jalalah itu demi memperoleh simpati pemberi sedekah. Tidak cuma itu. Hari ini, mudahlah kita simak ucapan “Allah” yang muncul seiring dengan obat flu, sampo, sabun colek, atau bahkan pembalut wanita.
Di layar elektronik, yang bisa menerobos kamar paling terkucil sekalipun itu, kita hampir selalu disuguhi kisah yang bertabur ucapan “Allah”. Kisah-kisah itu mudah dinamai religius, berwatak agama. Tapi apa itu yang berwatak agama? Kita tahu akhirnya, yang religius adalah ketika ucapan “Allah” menjadi penetap garis, mana tokoh pahlawan dan mana sosok begundal. Untuk mengetahui mana tokoh pahlawan, cukuplah kita lihat mana yang rajin melafadzkan “Allah”, dari astaghfirullah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, hingga yang paling biasa, dan paling sering, bismillah dan alhamdulillah. Sudah bisa dipastikan, dalam kisah-kisah itu, tokoh-tokoh yang kerap mengucap demikian tak bakal berakhir dengan mata terbelalak, tubuh gosong, atau kulit melepuh.
Tapi kata “Allah” juga merupakan penanda sebuah keadaan. Dan, kebetulan tapi anehnya terus berlangsung, ucapan “Allah” menjadi ekspresi kondisi sedih dan nelangsa. Ketika ada seorang istri mendapati suami berkelakuan meyakitkan, tiba-tiba kata “Allah” menjadi mantera wajib yang sebentar-sebentar terucap. Saat seorang menantu mengalami perlakuan serba tega dari mertua perempuan, wiridan ”Allah” menjadi adegan reguler.
Begitupun, tatkala ada anak kecil disia-siakan ibu tiri, bebunyian “Allah” macam hendak dipantulkan di tiap sudut. Sepertinya, kalau pun kita tak merasa teryakinkan oleh lakon para pemeran dalam menciptakan situasi pedih, cukup kita simak gencarnya lafadz “Allah” maka kita bisa tahu bahwa tragedi sedang berlangsung.
Kita mungkin tak pernah bertanya, apa sebenarnya yang ada di benak para pembuat cerita itu. Tapi barangkali juga tak mudah menjawab jika ada yang tanya, Allah itu siapa? sebuah pertanyaan sederhana, namun membutuhkan jawaban yang tak gegabah. Sebab jangan-jangan, si penutur pun tak sepenuhnya mengerti apa yang dilafadzkannya sendiri. Bisa jadi, satu-satunya yang diresapi adalah bahwa jika ada kata “Allah” di sebuah cerita maka ia menjadi “berwatak agama”. Lain tidak. Seperti juga ketika, dalam cerita lain yang “berwatak remaja”, selipan kosa kata Inggris menentukan sebuah cerita masuk kategori “gaul” atau tidak.
Singkatnya, jangan-jangan, pemahaman yang tertanam adalah, kata “Allah” tak ubahnya kata sisipan macam by the way, basically, at least, it’s ok, dan seabgrek lainnya. Bedanya, yang pertama menjadi pengabsah sebuah status “religius”, sedangkan yang kedua menjadi stempel merek “gaul”.
Apa boleh buat, semua itu memenuhi ruang-ruang kita, setiap hari, berselang-seling dengan klip video jualan obat, makanan ringan, perangkat kecantikan, dan lain-lain. Hingga, ketika ada yang memanggil Allah dengan sebutan lain, kita sulit memasukkannya dalam kotak religius. Kita tahu, dalam hidup sehari-hari, orang lebih akrab menyebut Allah dengan istilah “Yang di Atas”. Sangat tidak religius? Tidak dari bahasa Arab? Kurang islami? Mungkin iya, jika kita cuma berpatokan pada kata, dan melupakan pengalaman, dan penghayatan.
Bagi yang akrab dengan sebutan itu, Allah hadir tidak dalam pengalaman kosong, melainkan dari kenyataan sehari-hari bahwa mereka tak selalu mampu mengendalikan hidup, menyetir hal-ihwal. Lalu timbul kesadaran bahwa ada “Yang di Atas”, yang melampaui segala, yang menguasai seluruh hal-ihwal. Apakah ini bukan religius?
Ada juga yang lebih suka menyebut Sing Nggawe Urip, yang mencipta hidup. Sangat tidak Arab tentu saja. Tapi dengan sebutan itu, kehadiran Allah terasa lebih nyata. Menyebut Allah saja mungkin terasa “biasa”, namun ketika menyebut Sing Nggawe Urip, kehadiran Allah terasa merasuk di setiap pengalaman, yang paling sepele sekalipun. Yang mencipta hidup, yang menggerakan nafas, yang mengalirkan darah, yang menggeser malam—dan seterusnya. Dan mereka merasa kurang religius jika cuma menyebut “Allah” begitu saja. Buat mereka, banyak pintu nama yang bisa mengekspresikan hakikat Allah. Dan bukankah Allah memiliki nama-nama indah, al-Asma al-Husna?
Allah juga disebut al-Rahman, pengasih, dan al-Rahim, penyayang. Tapi Allah sekaligus al-‘Aliyy, yang Mahatinggi. Bukankah ini yang diistilahkan “Yang di Atas” tadi? Allah juga memiliki nama lain, al-Khaliq, yang Menciptakan, , yang Menghidupkan, al-Mumit, yang Mematikan. Bukankah ini terekspresikan dalam bahasa Sing Nggawe Urip? “Allah memiliki nama-nama indah,” kata Rasulullah, “dengan nama apapun kalian memanggil-Nya, sesungguhnya kalian sedang memanggil hakikat yang satu. Dia punya nama-nama indah, al-Asma al-Husna.”
Syir’ah 62



