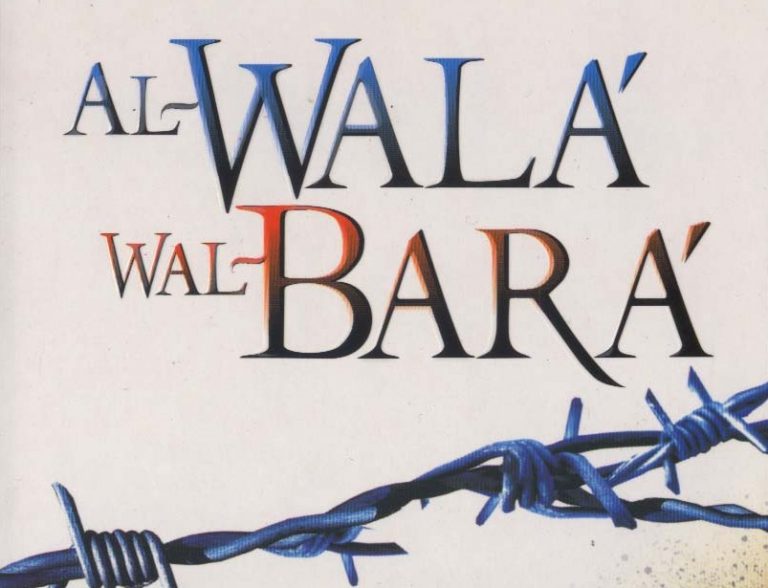
Dalam pembahasan mengenai tauhid, kelompok jihadis memasukkan pembahasan bernama al-Wala’ wa al-Bara’ sebagai syarat keimanan. Pensyaratan ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali oleh kelompok jihadis. Pasalnya prinsip ini dipahami sebagai loyal kepada orang beriman dan tidak loyal kepada sebaliknya, orang kafir.
Menurut mereka orang beriman tidak boleh wala’ (loyal) dengan keimanan orang kafir, karena seharusnya mereka bara’ (berlepas diri) dari kekafiran mereka. Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kata tauhid menunjukkan secara bersamaan al-Wala’ kepada yang mempercayai dan menyembah Allah sekaligus al-Bara’ dari mereka yang mengingkari dan kafir kepada-Nya.
Ada ulama yang memasukkan al-Wala’ wa al-Bara’ sebagai syarat keabsahan keimanan, yaitu Ibn Taymiyyah kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya, jika seseorang masih memiliki sikap al-Wala’ terhadap non-muslim misalnya, maka keimanannya tidak sah. Ekses dari cara berpikir demikian adalah munculnya gerakan yang menyatakan jamaahnya mesti al-Bara’ kepada orang yang berbeda pendapat meski dalam persoalan khilafiyah. Praktiknya ini dilakukan oleh kelompok terorisme seperti ISIS untuk melakukan pengeboman di negara-negara barat, bahkan di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim sekalipun seperti Indonesia.
Salah satu ayat Quran yang dijadikan dalil yang digunakan adalah surah al-Mumtanah: 4,
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
“Dan kalian sudah memiliki contoh yang baik, yaitu Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika itu mereka berkata kepada kaumnya, “sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami telah kafir (berbeda agama) dengan kalian, dan antara kami dan kalian akan ada permusuhan dan kemurkaan selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata”. Kecuali, perkataan Ibrahim kepada ayahnya (agar ayahnya tidak mengikuti kaumnya) “sungguh aku sekuat tenaga memintakan ampun bagi engkau dengan segenap kemampuan yang aku miliki dari sisi Allah. Tuhan Kami !, kepada Engkaulah kami berserah diri, bertaubat, dan hanya kepada Engkau kami kembali !.”
Untuk memahami sebuat ayat, kita tidak bisa semerta-merta mengambil makna tekstual dari satu ayat kemudian menyimpulkannya tanpa membandingkan dengan ayat-ayat lain atau sumber lain. Paling tidak, tugas pertama kita adalah memeriksa sebab turunnya ayat (sabab al-nuzul). Menurut al-Qasimi dalam tafsirnya yang berjudul Mahasin al-Ta’wil, ia mengutip riwayat dalam tafsir Ibn Katsir bahwa ayat ini memang menjadi perintah bagi orang-orang beriman untuk tidak mendukung apalagi mencintai orang musyrik yang mengusir mereka dari kota Mekkah.
Maka dengan melihat tiga ayat sebelumnya (1-3) dari surah ini, kita mengetahui bahwa perintah diatas konteksnya adalah bagi para sahabat yang mendapatkan tekanan di Mekkah, sehingga sangat wajar kalau Allah berfirman bahwa mereka adalah musuh Allah. Betapa pedihnya perselisihan tersebut hingga Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya,
لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“istri dan anak-anak kalian tidak akan mendapatkan manfaat di hari kiamat, pada hari kiamat kiamat kalian akan terpisah. Dan Allah Maha Melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.”
Sebab turunnya ayat ini adalah, ketika akan dilakukan Fathu Makkah Nabi Saw. memerintahkan agar kaum muslimin bersiapan menghadapi mereka. Ternyata, salah seorang tawanan Utsman bin Affan yang telah masuk Islam, bernama Hathib bin Abi Balta’ah tidak siap denga keputusan itu karena di Mekkah ia masih memiliki harta dan anak-anak yang ditinggal di Mekkah. Maka, ia mengirimkan surat ke Mekkah agar penduduk Mekkah siap menghadapi serangan dari Madinah. Sayang, perilakunya terdengar oleh Nabi Saw. Hathib pun memohon ampun kepada Rasulullah Saw. atas perbuatannya dan beliau memaafkannya.
Dengan demikian, untuk memahami ayat ke-4 dari surah al-Mumtahanah, kita dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut disampaikan dalam kondisi konflik antara kaum musyrikin di Mekkah dan umat muslim di Madinah, bukan dalam kondisi perdamaian. Sehingga, berdalil dengan ayat tersebut untuk menyatakan bahwa orang muslim yang tidak sependapat dengan kelompok tertentu menyebabkan mereka tidak loyal kepada muslimin, cara memahami yang benar-benar keliru. Justru Rasulullah memperluas kategori orang beriman. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Saw. pernah bersabda,
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ
Dari Anas bin Malik: Rasulullah Saw. bersabda: “Keluarlah dari neraka orang yang berkata “Laa Ila Illa Allah”, orang tersebut memiliki kebaikan dalam hatinya.”
Untuk orang yang berbeda agama dengan kita, kita memang bersikap bara’ dalam persoalan peribadatan agama mereka. Misalkan, kita tidak meyakini kebenaran agama di luar agama Islam dan diwujudkan dalam bentuk tidak ikut serta dalam ritual peribadatan. Namun, ini tidak menjadi dalil terlarangnya kita mu’asyarah bi al-ma’ruf (bergaul dengan baik) dengan penganut agama lain, bahkan dianjurkan untuk terus bersilaturahmi. Ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw. dengan tetap berbuat baik kepada pamannya, Abu Thalib meski beliau tidak beragama Islam sampai akhir hayatnya. Lebih dari itu, salah seorang mertua Nabi Saw. sendiri dari istri bernama Shofiyyah, Huyay adalah seorang Yahudi.



