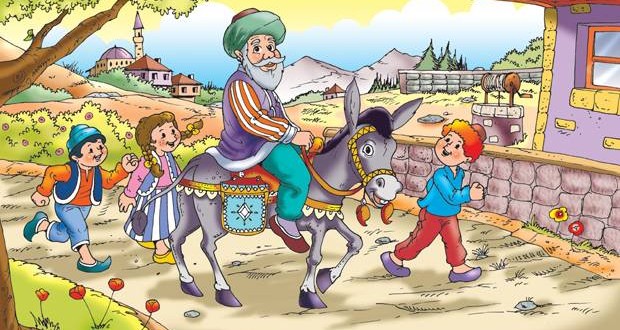
Pada satu kesempatan, Savic Ali pernah bercerita tentang pengalamannya kuliah di kampus Katolik. Aktivis yang lama bergelut di dunia media dan Islam moderat itu menyampaikannya saat mengisi kelas berpikir kritis di acara Temu Nasional (Tunas) Jaringan GUSDURian di Yogyakarta.
Sebagai muslim, dia kagum pada pada teman-teman Katoliknya di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, kampusnya dulu. Banyak di antara mahasiswa STF Driyarkara adalah frater, calon pastur yang kelak menjadi pemimpin umat Katolik.
“Teman-teman saya, para calon pastur itu, belajar filsafat untuk menguji kebenaran agama Katolik. Mereka tidak takut menggempur agamanya dengan keilmuan lain. Karena mereka tahu, semakin agama mereka digempur, semakin kokoh pula kebenaran dan keimanan mereka,” kata Savic. “Kalau di Islam, jangankan digempur, disenggol dikit aja udah sakit hati,” lanjutnya.
Para peserta kelas tertawa serempak.
Kami menyadari, di tengah tensi politik menjelang pilpres yang sedang tinggi saat itu, cerita tersebut terasa sangat relevan. Rasanya itulah saat yang tepat untuk menertawakan diri sendiri sekaligus melakukan otokritik.
Kita semua tahu, pasca kasus Ahok, Islam beserta umatnya telah menjadi komoditas politik yang dipertimbangkan di skala nasional. Semua mata tertuju pada Islam. Tidak hanya pada kekuatan massa yang besar dan mudah digerakkan, tapi juga betapa mudah tersinggung dan tersulutnya massa tersebut dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di meja musyawarah.
Fenomena seperti ini, barangkali bisa kita lacak melalui sejarah ketersinggungan umat Islam di Indonesia. Setidaknya sejak tahun 1918, saat sebuah tulisan di surat kabar Djawi Hiswara dianggap menista agama dan membuat HOS Tjokroaminoto mengumpulkan massa untuk berdemonstarsi. Pun dengan kasus di penghujung Orde Baru, saat Arswendo Atmowiloto dikecam keras oleh umat Islam karena majalahnya Monitor telah membuat angket yang hasilnya menempatkan nama Nabi Muhammad SAW di urutan ke-11.
Lalu, satu dekade ke belakang kita disuguhi kasus tuduhan penistaan agama oleh gubernur Basuki Tjahaja Purnama karena menyinggung ayat al-Qur’an. Kemudian muncul kasus serupa yang dibebankan pada punggung Sukmawati Soekarnoputri karena puisinya, juga kasus tuduhan penistaan agama oleh Meliana gara-gara mengkritik volume adzan.
Kasus demi kasus yang terjadi sampai detik ini seakan hanya mempertebal cap “baperan” yang dilekatkan pada umat Islam.
Jangankan politisi yang diserang karena sarat kepentingan politik, atau kelompok minoritas yang tidak mendapatkan perlindungan kuat, banyak juga komedian yang terkena dampak baper umat Islam ini. Iya, komedian! Profesi yang tugasnya menghibur, membuat lelucon berdasarkan fakta sosial dan kegelisahannya sehari-hari.
Di Indonesia, setidaknya sudah ada enam komedian yang sempat merasakan dirundung hingga dilaporkan ke polisi karena dituduh menistakan agama. Dimulai dari komika Uus yang diancam, dikecam, hingga berujung diberhentikan dari pekerjaannya karena dituduh menghina Rizieq Shihab. Disusul perundungan kepada Ernest Prakasa di media sosial karena ia menyinggung Zakir Naik dalam tweet-nya.
Lalu pada awal tahun 2018, dua kasus tuduhan penistaan agama ditujukan pada Joshua Suherman dan Ge Pamungkas pada waktu hampir berdekatan. Joshua dan Ge dituduh menistakan Islam lewat salah satu bit komedi yang dibawakannya di atas panggung. Estafet penistaan itu kemudian dioper pada duo komika Coki-Muslim karena membuat video mencampur daging babi dengan sari kurma di Youtube. Mereka berdua sempat mengundurkan diri dari dunia komedi lantaran berbagai ancaman fisik yang diterimanya. Terakhir, nama Andre Taulany juga sempat dilaporkan karena dituduh menghina Nabi Muhammad SAW.
Sebenarnya, saya melihat dari rentetan kasus di atas tidak ada tendensi untuk memperburuk citra Islam. Sebagian memang reflek slengean mereka sebagai komedian, sebagian lagi adalah keisengan dan ketidaktelitian. Siapa pun memang berhak tersinggung pada level ini. Tapi bagaimana pun, reaksi-reaksi seperti perundungan, hujatan dengan kata-kata kasar, ancaman kekerasan hingga “halal darah”, atau bahkan pelaporan memakai pasal karet penodaan agama sekalipun bukanlah tindakan tepat.
Selalu ada ruang untuk berdialog bagi siapa pun yang mengaku beradab. Selalu ada kesempatan untuk berbicara baik-baik bagi siapa pun yang mengaku beragama. Begitulah cara untuk memuliakan agama dan derajat kita sebagai manusia.
Namun di sisi lain, kita juga tak bisa asal tersinggung pada apa pun yang berbau agama. Kita perlu berpikir, mencerna, dan menahan emosi sesaat sebelum memutuskan segala sesuatu. Kenapa? Karena komedi sering kali juga menjadi sarana kritik yang ampuh di masyarakat. Kritik sangat dibutuhkan oleh siapa saja untuk terus berbenah diri.
Dalam sejarah awal teater Prancis, penampilan comédie ditujukan untuk menghibur dan mengkritik dengan memperolok sifat dan cacat-cela manusia, keadaan, atau situasi yang konyol. Di Inggris, Charlie Chaplin menghadirkan satire atas Hitler dan fasisme Nazi Jerman. Sedangkan di Indonesia, Warkop DKI pernah cukup lantang dan berani mengkritik kekuasan Orde Baru pada masanya. Saat ini, saat banyak negara mengakomodir demokrasi dan kebebasan berpendapat, komedi menjadi lebih cair dan menyuarakan kritiknya pada siapa dan apa pun yang membuat gelisah.
Di Indonesia, kita punya masalah serius pada mayoritarianisme dan konservatisme agama. Maka dari itu, sebagian komedian Indonesia mencoba mengangkat kegelisahan mereka terkait hal ini. Tapi sayangnya, kritik dan kegelisahan itu membuat mereka dalam masalah.
Sebut saja duo komika Coki-Muslim. Jika kita mau jeli, pesan yang mereka sampaikan sebenarnya bukanlah melulu soal kurma dan babi. Itu hanya permukaannya. Mereka menyampaikan pesan melalui satire atas fanatisme dan kakunya pemahaman umat Islam pada teks. Saking kakunya, terkadang kita sulit memahami mana bahasa Arab dan mana ayat al-Qur’an. Kita juga terlampau terpaku pada makna kata halal dan haram tanpa melihat konteksnya. Sampai-sampai kita mudah terjebak pada produk-produk non-makanan yang melabeli diri “halal” atau “syariah” meski telah menyimpang dari maknanya.
Pun dengan materi lawakan Joshua. Ketika ia membercandai Cherly (mantan Cherrybelle) untuk masuk Islam supaya bisa sepopuler Annisa yang muslim, sebenarnya ia sedang mengkritik mayoritarianisme Islam yang superior di Indonesia. Mayoritarianisme ini selalu menjadi momok bagi kelompok minoritas karena sikap totaliternya dan sewenang-wenangnya. Entah itu Mayoritarianisme Islam di Indonesia, Hindu di India, atau Buddha di Myanmar.
Kita akhirnya melihat, bahwa kritik dan kegelisahan lewat komedi sekali pun gagal masuk secara halus ke hati terdalam kita sebagai manusia. Artinya, ketika kita tidak mampu menerima kritik, kita tidak punya bahan refleksi diri untuk menjadi umat yang tumbuh menjadi lebih baik.
Kita tidak sedang membicarakan agama, tapi kita membicarakan bagaimana menjalani hidup berdasarkan pemahaman kita pada ajaran agama. Kita tak sedang menggugat kebenaran mutlak-ilahiah, tapi kita membicarakan potensi kesalahan kita sebagai manusia dalam memahami kebenaran-Nya. Maka dari itu kita butuh kritik. Dan komedi adalah medium yang segar untuk mendapatkannya.



