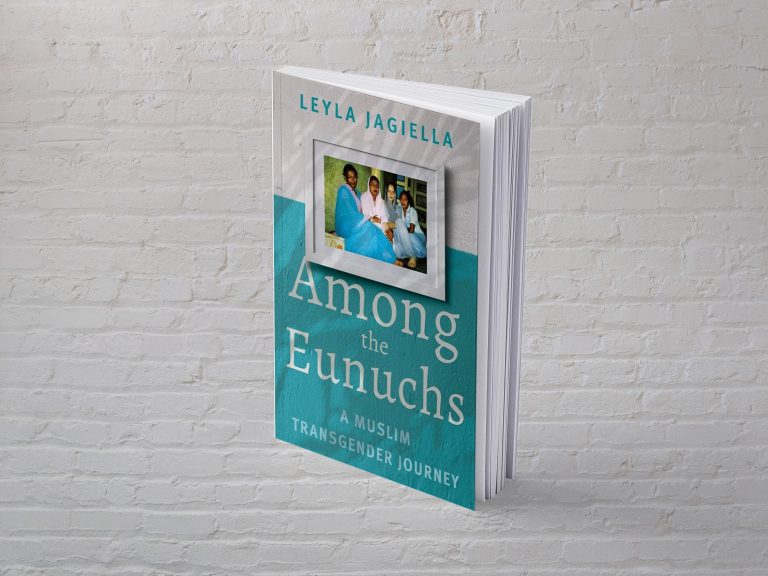
Di tengah sesaknya narasi agama yang meminggirkan dan menolak minoritas gender dan seksualitas, mungkinkah seorang transgender bisa menemukan dirinya sebagai bagian dari suatu agama sembari tetap menerima identitas gendernya yang berbeda? Mungkinkah ada titik perjumpaan; muara yang mengantarkan seorang transgender untuk menegosiasikan identitas gender dan keagamaannya secara merdeka?
Buku berjudul Among the Eunuchs: A Muslim Transgender Journey yang ditulis oleh seorang transgender perempuan (transpuan) berdarah Jerman yang memutuskan untuk mualaf menjadi Muslim, barangkali satu buku yang mampu menyajikan diskusi dan realitas mencerahkan atas dua pertanyaan —sekaligus kegelisahan dan kerumitan— itu.
Leyla Jagiella mencoba mengurai benang kusut kompleksitas konsep, teori, dan pemahaman tentang gender dan seksualitas melalui pergumulan pribadinya sebagai transpuan, dan perjumpaannya di tengah-tengah komunitas hijra dan khwajasara, dua istilah dan identitas lokal di Asia Selatan yang merujuk pada konsep ketubuhan yang non-conforming, yang kerap juga dilabeli dengan ‘gender ketiga’ meskipun konsep ini pun tak selalu seutuhnya mencakup dan sepenuhnya diterima bahkan oleh kelompok hijra/khwajasara sendiri. Seringkali, mereka juga tak mau disebut sebagai transgender.
Inilah salah satu kerumitan yang coba diungkap oleh Leyla, bahwa konsep tentang gender dan seksualitas yang ditawarkan oleh Barat dan modernitas tak selalu mampu memberikan jawaban atas ‘misteri’ tubuh dan ketubuhan yang beragam, malah bisa jadi menambah persoalan dan kerumitan lain. Dalam konstelasi ideologis ‘Timur vis-a-vis Barat’, Leyla meletakkan isu dan realitas keragaman gender sebagai lokus untuk mengkritik bineritas dogmatik yang lahir dari keduanya, juga superioritas yang diproduksi oleh berbagai pihak, baik atas nama Barat maupun atas nama mereka yang menolak Barat.
Melalui pengalamannya tinggal bersama komunitas hijra di India, dan komunitas khwajasara di Pakistan, selama dua puluh tahun sejak 2000, Leyla mengungkapkan bagaimana masyarakat Muslim hidup berdampingan secara hangat dengan kelompok minoritas gender. Di rumah bersama, disebut juga dengan dera atau gharana, yang biasa menjadi tempat tinggal hijra di India, dan khawajasara di Pakistan, seringkali bersebelahan dengan masjid dan madrasa tempat warga sekitar belajar mengaji Al-Quran, pemandangan seperti ini adalah hal yang biasa dijumpai di beberapa titik dan daerah di sana. Bahkan di Islamabad, terdapat pula khawaja sira quran school, mungkin mirip dengan Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta.
Pengalaman tumbuh besar di Eropa di masa ketika visibilitas transgender masih sangat rendah kala itu, Leyla terkesima oleh nuansa penerimaan komunitas hijra saat pertama kali dia menginjakkan kaki di Delhi. Tanpa meminggirkan fakta bahwa diskriminasi dan marginalisasi juga terjadi di masyarakat India, Leyla seketika menyadari betapa dibandingkan dengan Eropa, masyarakat India justru jauh lebih akrab dengan visibilitas hijra bahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tahun 2009, Pakistan mengesahkan status gender ketiga, ‘third gender’, diikuti oleh India pada tahun 2011, dan Bangladesh di tahun 2013. Menariknya, Pakistan, negara dengan populasi lebih dari 90% Muslim, bahkan memiliki undang-undang anti-diskriminasi terhadap transgender yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 2018. Meskipun pada level law enforcement masih jauh panggang dari api. Di sisi lain, Leyla juga menyadari betapa isu minoritas gender dan seksualitas (queer) secara luas seringkali hanya menjadi alat pemicu dan penanda culture war antara dunia Barat yang memposisikan diri sebagai suar pelindung kelompok queer, dan dunia non-Barat, terutama Muslim, yang mencitrakan diri sebagai garda terdepan nilai-nilai tradisional. Konsekuensinya, kelompok queer hanya menjadi marker, dikorbankan dalam culture war sengit ini.
Islam dan Pergumulan tentang Yang Ilahi
Jauh sebelum memutuskan untuk mendatangi India dan Pakistan, Leyla kecil selalu mengalami kegelisahan tentang dirinya, tentang kultur dan dunia tempat dia dibesarkan. Terlahir dari keluarga migran yang masih memiliki garis keturunan Polandia-Turki, yang memutuskan berpindah ke Jerman, Leyla terbentur berkali-kali oleh identitas ‘the other’, yang liyan. Di satu sisi dia merasa tak seutuhnya laki-laki seperti yang orang selalu katakan tentang dirinya, di sisi lain dia merasa tak seutuhnya Jerman. Melihat bagaimana rasisme juga membudaya di Jerman, Leyla semakin tersudut di pinggiran, mencari dan menggali makna kehidupan di balik kerimutan identitas ‘liyan’. Dalam kegelisahan itu, dia belajar tentang Islam.
I started to wonder what the final truth was behind all of this…what the truth was behind my life. Why are some human beings born different? And why does that cause them so much suffering? Was there a meaning behind all of this? Somehow, Islam appeared to be the best answer to my questions… Islam gave me a philosophy with which to understand my reality. The idea that there is a Divine Unity at the centre of existence, one that nevertheless manifests in the multiplicity of human expression, appealed to me and gave me a framework to understand my experiences of non-belonging and otherness…. Nothing essential but Him. Everything else is just the endless diversity that His boundless unity expresses itself in. (hlm. 33-34)
Aku mulai bertanya-tanya tentang kebenaran abadi tentang semua ini, tentang kehidupanku. Mengapa ada orang-orang yang terlahir berbeda? Dan mengapa kenyataan itu justru menimbulkan begitu banyak penderitaan? Adakah makna di balik semua ini? Entah mengapa, Islam hadir sebagai jawaban dari semua pertanyaanku… Islam mengantarkanku pada filosofi untuk memahami realitas. Gagasan bahwa ada Yang Ilahi sebagai pusat segala eksistensi, yang termanifestasi dalam segala kekayaan keragaman ekspresi manusia, adalah gagasan yang mempesona, ia memberikanku cara pandang untuk memahami pengalamanku tentang yang liyan…Tak ada yang penting selain Dia. Segala hal hanyalah keragaman yang tak berujung, ejawantah dari kesatuan tentang-Nya.
Sejak itu, Leyla mulai mencari dan berjumpa dengan kolektif Muslim queer (keragaman gender dan seksualitas) yang ada di beberapa negara. Ia juga menghabiskan bertahun-tahun mendalami Al-Quran di Muslim Insititute di London. Dari perjumpaan-perjumpaannya dengan berbagai kelompok Muslim progresif, Leyla mencari tahu tentang ragam identitas gender di berbagai masyarakat Muslim, dan memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual dan komunal sebagai transpuan, ke India dan Pakistan.
Pengalaman bergabung dan hidup selama dua puluh tahun di tengah-tengah komunitas hijra dan khwajasara di Asia Selatan membuatnya menyadari bahwa konsep tentang tubuh, ketubuhan, gender dan seksualitas tak bisa dilihat hanya melalui satu sudut pandang yang dogmatik semata. Penghayatan tentang identitas hijra dan khwajasara yang telah sekian abad menjadi bagian kultur dan keagamaan di Asia Selatan itu sangat berbeda dengan apa yang diasumsikan banyak orang hanya dalam satu kotak transgender. Leyla secara tegas menyatakan bahwa setiap orang mengalami pergumulan dan penghayatan yang berbeda-beda tentang berbagai hal, termasuk dalam soal agama, gender, dan seksualitas. Baginya, memperdebatkan bahwa satu cara dan pemahaman tentang gender dan seksualitas sebagai satu-satunya yang paling benar (baik dari sudut pandang Barat maupun non-Barat), adalah ilusi besar. Baginya, yang paling utama adalah bagaimana masyarakat memastikan tidak adanya diskriminasi dan kekerasan atas dasar perbedaan apapun.
Karenanya, Leyla begitu detail dan komprehensif ketika menuliskan satu bab khusus: ‘the genders of Islam’. Mengutip berbagai pemikir Muslim klasik hingga kontemporer, dari kalangan Sunni maupun Syiah, dari ‘Abd al-Wahhab al-Thaqafi, Ibn ‘Arabi, al-Nawawi, Syakih Muhammad al-Tantawi. ‘Abd al-Wahhab al-Subki, Shahab Ahmad, Adil Salahi, Ayatollah Khomeini dan sebagainya, Leyla menjabarkan secara sangat luas sekaligus rinci tentang bagaimana keragaman gender dalam Islam sesungguhnya tak sekaku dan tak serigid yang dibayangkan orang, tak semonolitik yang diyakini oleh sebagian Muslim sendiri, dan tak sekeras yang seringkali dipotret oleh media-media secara sensasional. Tentu tanpa menolak fakta bahwa ada sebagian kelompok Muslim yang memang secara begitu obsesif mendiskriminasi dan berupaya mengkriminalisasi kelompok queer melalui dalih agama.
Buku Leyla ini menjadi salah satu catatan menarik untuk mendudukkan kesalahpahaman Muslim terhadap minoritas gender dan seksualitas, sekaligus membuka kesadaran dan khazanah yang sangat luas namun sekaligus pelik tentang teror-teror ketakutan yang diciptakan untuk semakin meminggirkan yang berbeda, baik yang dilakukan oleh dunia Barat terhadap non-Barat dan Muslim, maupun Muslim terhadap identitas-identitas lain di negerinya sendiri.
Buku ini sekaligus mengajak pembaca merenungi kembali esensi-esensi kehidupan yang beragam sebagai cara Yang Ilahi mengajarkan umat manusia tentang cinta dan penghormatan. Sebab pada akhirnya, kita bisa tidak sepakat tentang banyak hal, tapi itulah barangkali cara Tuhan mendidik kita untuk tetap saling menghormati di tengah segala ketidaksepakatan dan perbedaan yang kita miliki.
(AN)



