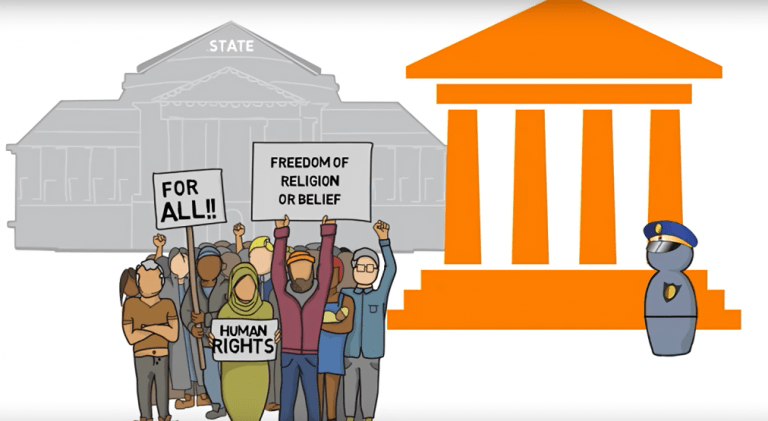
Membayangkan Indonesia benar senyap dari tumpukan kasus pelanggaran kebebasan beragama & berkeyakinan (KBB) tidaklah mudah. Tahun berganti tahun, Setara Institute for Democracy and Peace dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies/CRCS UGM sebagai misal, terus melaporkan kondisi kebebasan beragama di negara kita, yang kian hari frekuensinya kian akut, bising, dan hingga hari ini belum ada indikasi akan membaik.
Gangguan atau perusakan tempat ibadah, masifnya delik penodaan agama, dan penolakan ceramah adalah beberapa contoh dari tren pelanggaran KBB yang dominan terjadi dalam setiap tahunnya. Teranyar, kasus pelanggaran yang disebut terakhir kembali mengemuka, tepatnya berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
Ada apa sebenarnya dengan relasi sosial keberagamaan kita? Mengapa konflik kelompok keagamaan tak kunjung selesai? Kenapa kita yang berikrar atas nama Tuhan yang sama harus memusuhi kelompok yang sebenarnya hanya berbeda paham soal Islam? Kenapa kita harus saling sikut untuk berebut label “yang benar” dan “yang salah”; “yang moderat” dan “yang ekstrem”; “yang persuasif” dan “yang permisif”; “yang memakai kerangka dalil, ibarat, atau sebagainya” dan “yang tak memakai kerangka itu sama sekali?
Jika retorika kontradiktif dan paradoksal ini dipakai, maka seinklusif apapun cara kita beragama, jalan akhirnya selalu mengarah kepada rel sektarian yang bersifat fragmentatif; menganggap yang lain sebagai liyan dan memposisikan yang liyan sebagai musuh. Alih-alih solutif dan menawarkan jalan keluar, kerangka fragmentatif yang cenderung menyesuaikan pada afiliasi masing-masing kelompok ini justru membuat cara kita bersosial dan beragama semakin runyam dan runcing. Memprihatinkan.
Forum Internum dan Eksternum Beragama
Mengacu pada problem sebelumnya, tampaknya kita perlu memahami kembali landasan pijak bagaimana seharusnya menghargai keberagaman dalam beragama, termasuk ketika hendak mengekspresikan pemahaman keagamaan kita pada ruang publik. Salah satu nomenklatur yang dapat dirujuk untuk itu ialah Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan dengan jaminan KBB.
Ringkasnya, KBB menjamin setiap individu untuk memilih agama, berpindah agama, bahkan tidak beragama sekalipun. Artinya, melalui kerangka kebebasan ini, tidak seorangpun berhak untuk mengintervensi pilihan keagamaan seseorang. Tidak berhenti di situ, jaminan tersebut juga meniscayakan bahwa seseorang diperkenankan menginterpretasikan atau menafsirkan ajaran agama—baik radikal, moderat, atau bahkan liberal sekalipun—sesuai dengan pemahaman masing-masing individu. Kebebasan yang tidak dapat dibatasi inilah yang dimaksud dengan forum internum.
Oleh karenanya, jika terdapat individu atau institusi, baik dengan disengaja ataupun tidak, membatasi hak bebas individu untuk memilih agama sesuai dengan pilihannya, maka pembatasan tersebut dapat melanggar hak seseorang dalam memilih agama. Sebab, sebagaimana dijelaskan di muka, forum internum beragama merupakan hak individu yang tak dapat ditunda pemenuhannya (non-derogable rights). Titik.
Namun, KBB sendiri pun harus dipahami bukan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ada batasan-batasan tertentu di mana umat beragama tidak dapat secara serampangan mengekspresikan pemahaman keagamaannya, misalnya jika kebebasan itu berlawanan dengan undang-undang. Pada saat yang sama, negara (bukan yang lain) dapat membatasi kebebasan ekspresi keagamaan seseorang (forum eksternum), sepanjang hal itu diperlukan (necessary) dan memenuhi syarat-syarat pembatasan yang absah berdasarkan pada apa yang dimuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), misalnya untuk menjaga ketertiban umum.
Problemnya, dalam konteks di Indonesia, definisi “ketertiban umum” tampaknya ditafsirkan secara berlebihan dan seringkali dipakai untuk merestriksi kelompok minoritas. Kasus pembatasan terhadap Ahmadiyah adalah contoh interpretasi yang luas terhadap konsep “ketertiban umum”. Mereka dianggap pemerintah sebagai pihak yang mengganggu ketertiban umum karena ajarannya berbeda dengan Islam mayoritas. Dus, dengan alasan itu ekspresi keagamaan mereka dinilai layak dibatasi.
Dalam ranah lebih luas, jika ada konflik keagamaan seperti yang terjadi pada Ahmadiyah yang disalahkan bukanlah mereka yang menyulut kekerasan melainkan mereka yang menjadi korban, dan rasa-rasanya pola serupa juga terjadi di Surabaya.
Klaim yang Bias
Kasus pembubaran pengajian di Surabaya dapat dibaca dalam beragam perspektif. Misalnya, kubu pro akan memandang kasus ini sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi tindakan radikal. Di pihak lain, tuduhan “radikal?” yang dilabelkan kepada mereka nyatanya tidak sepenuhnya akurat bahkan cenderung bias. Tuduhan tersebut lebih tampak sebagai klaim-klaim kasuistis dan hanya berkaitan dengan perbedaan penafsiran. Terlebih, dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia ini, kehadiran kelompok “radikal” dan intoleran dapat dipandang sebagai fakta sosiologis yang absah dan tidak mengurangi status mereka sebagai warga negara yang juga berhak dan bebas untuk mengekspresikan forum eksternum keberagamaan mereka ke ruang publik.
Masalahnya, apakah menoleransi model keberagamaan yang cenderung intoleran tersebut dalam kualifikasi tertentu masih dikategorikan sebagai toleran? Dan sejauh mana tindakan intoleran dapat ditoleransi?
Di sinilah konsep zero tolerance Sidney Jones (2015) berbicara. Bagi Jones, tindakan intoleransi yang mengarah pada tindakan kekerasan sama sekali tidak dapat ditoleransi, apapun alasannya. Setiap kekerasan, intimidasi, dan tindakan serupa lainnya merupakan kejahatan yang harus dijerat dengan hukuman maksimal. Dan jika kasus itu terjadi yang berhak untuk menangani kasus ini, bahkan dengan cara kekerasan sekalipun, adalah negara bukan ormas keagamaan.
Nahasnya, kehadiran pemerintah untuk bersikap dan mengantisipasi agar tidak ada kekerasan malah absen dan justru diambil alih ormas. Walhasil, kasus semacam itu dianggap sebagai masalah yang sangat kompleks dan digeneralisasi sebagai masalah ideologis, padahal intinya adalah perdebatan dalam memberikan penilaian terhadap kelompok mengenai tindakan apa yang cocok dan apa yang tidak. Kegagalan untuk menempatkan masalah ini ke dalam problem sesungguhnya membuat masalah semakin pelik dan pada saat yang sama melanggar kebebasan beragama.
Tanpa ada pretensi untuk berpihak kepada siapapun, tampaknya, meskipun kita berpikir bahwa tindakan pembubaran kelompok yang dianggap garis-keras, provokatif, dan dapat memecah kerukunan umat Islam secara inheren adalah upaya untuk menciptakan kebaikan (maslahat) bersama, nyatanya apa yang dimaksud “kebaikan bersama” masih dapat diperdebatkan. Misalnya, kelompok “garis-keras” itu tidak sedikit atau bahkan bisa jadi lebih yakin bahwa kajian mereka dapat membentuk masyarakat yang lebih baik dibanding dengan ormas keagamaan yang memakai argumen kerukunan tersebut.
Terlebih, seandainya kita secara proporsional melihat bahwa kelompok itu juga menaruh perhatian yang sama terhadap apa yang terjadi di Palestina, memberikan peringatan yang lebih humanis dan nir-kekerasan tentu akan lebih arif daripada apa yang sudah terjadi.
Barangkali, misinterpretasi paling fundamental dalam kehidupan keberagamaan kita yang terus memandang yang lain sebagai liyan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Gus Muhammad Al-Fayyadl, yaitu terletak pada akar ideologinya. Seringkali dengan alasan “ideologi”, kita semakin represif, over-religious, dan pada saat bersamaan menggunakan alasan ideologi itu sebagai upaya untuk melakukan kekerasan terhadap mereka.
Menyelesaikan problem ideologis suatu kelompok dengan ideologi, seperti dialegorikan Gus Fayyadl, justru sama seperti menetralisasi pasien overdosis obat dengan obat. Sama sekali tidak solutif. Lebih penting daripada itu, yang dibutuhkan hari ini adalah melepaskan batas demerkasi ideologis keberagamaan kita, terutama di kalangan umat Islam, sekaligus menggesernya pada kerangka keberislaman yang mampu menjawab masalah akar sosial umat Islam yang jauh lebih besar, seperti praktik kapitalisme dan politik nepotisme yang hari ini sedang menceracam.



