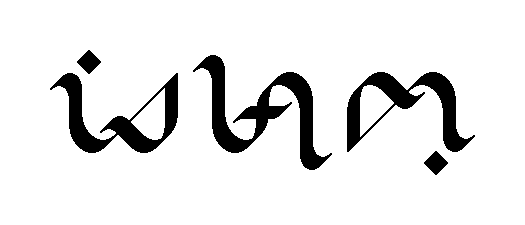
KEPERCAYAAN atau keimanan meniscayakan adanya ketulusan, kesadaran, dan cinta. Ketulusan artinya komitmen hati tanpa disertai tekanan atau paksaan. Sebab keimanan merupakan pilihan, dan pilihan hanya dapat diambil oleh seseorang yang dalam kondisi bebas berkehendak; merdeka.
Keimanan juga harus dilandasi cinta. Karena kepercayaan dan cinta merupakan dua hal yang saling berkait-kelindan dan tak bisa dipisahkan; kepercayaan adalah bukti cinta, begitupun cinta juga adalah bukti kepercayaan. Bukan kepercayaan jika tanpa cinta. Sebaliknya, tidak ada cinta tanpa kepercayaan. Ini bisa dilihat dari cara pandang para sufi yang melandaskan keberagamaannya dengan cinta. Kepercayaan dan cinta tidak bisa dipaksakan.
Sufi besar muslim, Abu Manshur al-Hallaj, suatu hari di Pasar Kota Baghdad menyampaikan keberatannya ketika saat melihat seorang lelaki muslim sedang memaksakan kehendak dan membentak orang Yahudi. Ia berkata kepada lelaki itu, “Perbedaan agama itu adalah kehendak Allah. Maka janganlah mengingkari kehendak Allah yang sudah ditetapkan.”
Keimanan menjadi absurd ketika berada dalam tekanan dan paksaan. Dikatakan dalam satu ayat, “Lâ ikrâh fî al-dîn,” (tidak ada paksaan dalam beragama atau memeluk agama). Huruf “lâ” dalam ayat ini adalah huruf negasi, yang menurut gramatika Arab berfungsi sebagai nafy al-jins (menegasikan segala bentuk dan jenis yang dinegasikan). Sehingga ayat ini mengandung arti bahwa tidak boleh ada paksaan sama sekali dalam bentuk apapun dalam beragama. Kita tahu bahwa ada banyak bentuk, motif, dan jenis paksaan, misalnya paksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, paksaan dengan cara-cara persuasif-lunak, paksaan dengan memanfaatkan kelemahan posisi seseorang atau golongan tertentu secara ekonomi atau politik dalam bingkai relasi mayoritas-minoritas, atau paksaan dengan memanfaatkan relasi patronase, dan bahkan paksaan atas ‘nama cinta’. Dan semua bentuk paksaan tersebut dilarang keras dalam al-Qur`an.
Keimanan bisa berpijar di dalam hati seseorang oleh sebuah hidayah (petunjuk) yang bisa diusahakan dengan adanya ketertarikan yang muncul secara alamiah akibat pergolakan batin yang serius dari akselerasi pembelajaran, pengalaman hidup, atau pencarian kebenaran, atau terpikat dengan sendirinya pada ajakan (dakwah) yang elegan, bukan oleh sebuah paksaan. Paksaan dalam beriman dilarang, karena bertentangan dengan karakter keimanan yang meniscayakan adanya pilihan bebas dan cinta.
Dalam menyerukan ajarannya Islam selalu mengedepankan suri tauladan yang baik dari Nabi, tutur kata yang baik, nasihat yang baik, dakwah dan dialog dengan cara-cara paling baik. Itu pun dilakukan kepada para penganut paganisme, yang ketika Islam pertama kali diproklamirkan sebagai agama disebut sebagai penyembah berhala. Akan tetapi Islam tetap menghargai setiap keyakinan sebagaimana terlihat dalam sejarah ketika Islam masuk ke Mesir, di para sahabat Nabi tetap mempertahankan patung-patung, piramida, dan tempat peribadatan agama-agama pagan yang ada. Demikian juga ketika Islam masuk ke Persia, orang-orang Majusi yang menyembah api dihormati dan bahkan filosofinya dicoba diakulturasikan dengan tasawuf dan menghasilkan teori al-isyrâq (illuminasi).
Sedangkan kepada para pemeluk agama samawi, yang disebut sebagai Ahlul Kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, Islam hanya mengajak untuk mencari titik temu, kalimatun sawâ, tidak mengajak untuk mencari titik perbedaan yang berujung pada konflik horizontal dan perang atas nama agama [QS. Ali ‘Imran: 64]. Bahkan, Islam mensyaratkan secara mutlak bahwa keabsahan iman seorang muslim adalah dengan mengimani dan meyakini kitab-kitab suci yang diturunkan kepada umat sebelumnya, yaitu Taurat bagi umat Yahudi dan Injil bagi umat Nasrani [QS. al-Baqarah: 4], mengharuskan umat Muslim untuk bergaul dengan baik, dan boleh saling memberi hadiah makanan [QS. al-Ma`idah: 5].
Islam yang begitu indah dan mesra perlu dirawat, dengan mendudukkan ayat-ayat perang dan ‘terkesan’ intoleran pada konteksnya. Sebab, jika tidak maka akan berpotensi ditafsirkan secara harfiyah dan dipaksakan untuk diterapkan pada masa kini yang konteksnya berbeda. Di antaranya adalah ayat-ayat peperangan yang mewajibkan orang kafir yang kalah perang untuk membayar jizyah. Menurut Fahmi Huwaidi, seorang pemikir Mesir, dalam bukunya “Muwâthinun lâ Dzimmiyun”, bahwa pembayaran jizyah bukan aturan yang pertama kali diterapkan oleh Islam dan dunia Arab. Pembayaran jizyah oleh pihak yang kalah berperang atau daerah yang diduduki merupakan aturan perang internasional pada masa Sebelum Masehi dan berlangsung sampai Nabi Muhammad Saw. diutus. Kaisar Anusyirwan, raja Persia, abad ke-5 SM., dianggap sebagai raja yang pertama kali menetapkan undang-undang pembayaran jizyah pada negara yang diduduki. Ia menerapkan undang-undang itu pada saat Persia menguasai Asia Kecil dan Athena. Begitu juga Romawi yang menerapkan undang-undang pembayaran jizyah terhadap negara yang sekarang termasuk negara Prancis.
Jadi, persoalan pembayaran jizyah bukan persoalan teologis Islam vis-a-vis non-Islam. Akan tetapi murni persoalan politik dan undang-undang perang yang berlaku pada masanya, dan sekarang itu dianggap sudah tidak relevan, karena termasuk pelanggaran HAM. Islam sendiri akan selalu merelevankan dirinya dalam konteks tempat dan masanya, shâlih li kull zamân wa makân. Islam bersifat adaptif sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah fikih, “Taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azminah wal al-amkinah,” (hukum bergerak dinamis sesuai dengan perubahan kondisi masa dan tempat).
Demikian juga ayat-ayat yang mengesankan disharmonisasi relasi antara umat Muslim dan non-Muslim itu turun dilatarbelakangi posisi defensif umat Muslim yang membela diri dari serangan non-Muslim, bukan ofensif. Karena misi Islam sejak awal adalah sebagai agama penebar kasih sayang, rahmatan li al-‘âlamîn. Islam membela dirinya demi tegaknya cinta kasih.[]



