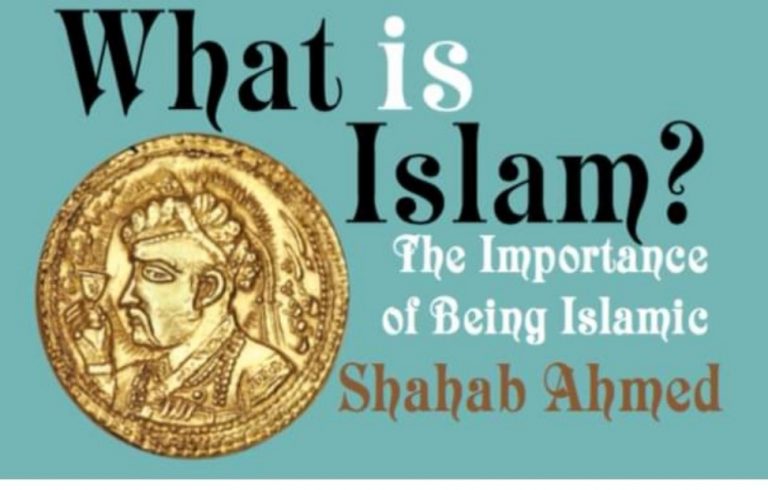
Seperti pepatah “gajah mati meninggalkan gading,” buku yang sangat tebal ini, sekitar 600an halaman, adalah “gading” yang akan awet dan menjadi warisan Ahmed bagi kesarjanaan di Amerika dan dunia. Dengan segala kontroversinya, bukunya ini diterima oleh kalangan kesarjanaan sebagai sumbangan yang penting dan unik bagi studi pemikiran Islam.
What Is Islam adalah buku yang sangat detail dan kaya, juga panjang dan mendalam. Di beberapa tempat saya mendapatkan kesan Ahmed mengulang-ngulang beberapa hal yang sebenarnya sudah jelas, setidaknya bagi para sarjana.
Pertanyaan utama buku ini, jika disederhanakan, mungkin begini: bagaimana kita mengatasi kontradiksi dan ketegangan antara Islam yang universal dan lokal, yang tekstual dan kontekstual, yang ortodoks dan heterodoks. Apakah ada definisi koheren tentang apa itu Islam? Upaya mendefinisikan Islam yang ketika di pesantren seperti usaha sederhana, karena cukup dengan jawaban rukun Islam, di tangan akademisi seperti Ahmed menjadi sangat canggih, dalam, panjang dan ensiklopedik.
Bukunya dibuka dengan elaborasi 6 contoh yang diambil dari tradisi Islam untuk menunjukan ketegangan dan bahkan kontradiski. Ia misalnya bertanya: apa yang Islami dari Filsafat Islam jika sebagian besar pandangan filsafat itu berakar dari tradisi Yunani dan dielaborasi oleh orang-orang yang bahkan non-Muslim (banyak filsuf dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tumbuh pada masa kejayaan Islam). Apa yang Islam dari tradisi spiritualisme dan sufisme Islam jika pandangan-pandangan itu bahkan seolah-olah bertolak belakangan dengan ‘doktrin Islam”? Misalnya, dalam tradisi sufisme, ketika sekat-sekat formal agama melebur dan seolah menjadi tidak bermakna, lantas bagaimana kita masih menganggap itu tradisi Islam? Cotoh lain adalah tentang wine atau minuman anggur. Meski secara jelas teks Al-Qur’an dan hadith melarang minum anggur, dalam tradisi dan sejarah Islam minuman ini dirayakan bahkan dalam kegiatan keagamaan para sufi sebagaimana direkam dalam banyak karya sastra dan puisi. Apa yang Islami (atau tidak Islami) dari anggur itu?
Dengan mengambil pengalaman dari apa yang dia sebut sebagai “wilayah Balkan-Benggali” (Balkan-To-Bengal Complex), Ahmed ingin menyodorkan Islam “yang lain” yang elaboratif sekaligus akomodatif, dan bukan Islam yang berkutat semata-mata dengan urusan penerapan aturan dan batasan (Islam perskriptif). Wilayah itu adalah wilayah di mana sufisme, seni dan filsafat tumbuh subur sampai pada titik dimana banyak manifestasinya yang daanggap “kurang” atau “tidak” Islami. Persis disinilah pertanyaannya menjadi relevan: apa ukuran kita menilai sesuatu itu Islami? Apa itu Islam?
Jika Islam itu semata dilihat dari pendekatan legalistik, maka akan banyak masalah yang muncul, menurut Ahmed. Pendekatan ini melihat Islami atau tidak sebuah ekspresi budaya atau prilaku dilihat dan diukur dari sejauh mata hal tersebut bersesuaian dengan aturan dan norma hukum Islam.
Ahmed bertanya, jika yang Islami itu yang sesuai dengan aturan formal-legalistik, lantas bagaimana kita memberlakukan semua contoh yang tadi disebutkan yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan formal itu (wine, iluminasi, filsafat dan lain-lain)? Apakah kita mengaggap mereka sebagai semata ekspresi sekular dalam tradisi masyarakt Muslim? Atau kita menganggapnya sebagai tradisi pinggiran, marjinal, yang tidak diakui karena dianggap sebagai penyimpangan?
Sayangnya, menurut saya, ketika Ahmed mengatakan “legal-supremacist” sebagai tidak lengkap dan bermasalah sebagai ukuran ke-islaman, ia seolah melupakan dinamika hukum itu sendiri yang begitu dinamis dan beragam. Hukum sendiri tidak tunggal dan beragam, bahkan sampai pada titik dimana apa-apa yang sangat kontroversial diakui. Beberapa minggu lalu, misalnya, saya membaca teks fikih klasik terkait perdebatan apakah najis bisa berubah menjadi halal dengan proses istihālat. Madzhab Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa proses itu hanya boleh terjadi secara alamiyah. Madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa proses itu bisa saja melalui usaha manusia seperti proses pembakaran. Dalam diskusi tentang ini, muncul pandangan yang mengatakan bahwa bahkan jika anjing sekalipun jatuh ke tungku pembakaran pembuatan garam (malāhah) dan menjadi mengerak dan menyatu dengan garam (milh), maka hal tersebut menjadi halal karena zat (ain) dari najis itu telah berubah!
Tapi karena buku ini bukanlah buku hukum, simplifikasi Ahmed perlu kita maklumi karena hal utama yang ingin disampaikannya adalah bahwa ukuran hukum tidaklah cukup untuk menakar ke-islam-an.
Cara lain yang biasa digunakan untuk melihat apa itu Islam adalah dengan mengukurnya dari apa yang disebut ortodoksi. Ortodoksi tentu saja terkait dengan otoritas karena ialah yang mempunyai kewenangan untuk mengukur bagaimana prilaku dan ekspresi budaya bersesuaian atau bertentangan dengan aturan-aturan ortodoksi. Ortodoksi pada dirinya selalu memiliki ciri membatasi, mengatur dan mengukur (prescriptive and restrictive). Tepat di titik inilah Ahmed tidak terlalu setuju dengan pendekatan yang selama ini mengemuka, terutama setelah diajukan oleh antropolog kenamaan, Talal Asad.
Jika Islam difahami sebagai sebuah tradisi wacana (discursive tradition), maka, menurut Ahmed, selain berpaku pada aturan dan ukuran, otoritas juga mestinya mengedepankan penerokaan dan penjelajahan yang kreatif (explorative authority). Jika pemangku otoritas yang bersifat mengatur selama ini melihat kewenangannya sebagai cara untuk membatasi dan mengatur pihak lain di luar dirinya, maka otoritas eksploratif ala Ahmed melihat dirinya sebagai pemberi izin, setidaknya bagi dirinya sendiri, bagi upaya penerokaan wilayah-wilayah yang belum terjamah dan tak diketahui.
Dus, bagi Ahmed, alih-alih dilihat sebagai aturan dan pembatas berdasar ortodoksi (prescriptive and restrictive), Islam adalah pembebas bagi setiap kemungkinan tindakan penerokaan yang kreatif (explorative and creative). Tepat pula disinilah kita bisa menempatkan ekspresi dan eksplorasi seni, puisi, filsafat dan spiritualitas (sufisme) ajeg berdiri meski terkadang melewati batas-batas ortodoksi. Dengan begitu, kontradiski dan ambiguitas dalam Islam tidak lagi dilihat sebagai yang “lian” dan terpinggirkan. Dua hal tersebut menjadi bagian inti dari Islam.
Sampai di sini kita mungkin sudah mendekati pada upaya kita memahami apa yang disodorkan Ahmed terkait pertanyaan “Apa itu Islam” dan bagaimana sesuatu disebut “Islami”. Jika anda membaca bukunya, jawaban itu baru ditemukan di dua bab akhir, tepatnya setelah anda membaca sekitar 400an halaman. Bagian tiga dari bukunya, tepatnya pada bab 5 dan 6, Ahmed mencoba menyodorkan gagasannya untuk mencoba melengkapi usaha menjawab pertanyaan terkait apa itu Islam yang selama ini ada (pendekatan legalistik dan ortodoksi agama).
Baginya, yang Islami atau Islam adalah segala upaya penafsiran yang bermakna dalam interaksi manusia dengan keseluruhan totalitas pewahyuan Muhammad. Istilah “Totalitas Pewahyuan” adalah bahasa yang saya gunakan untuk menggungkapkan teori yang dipakai Ahmed yang melihat Pewahyuan sebagai sesuatu yang meliputi “Pre-Text,” “Text,” dan “Con-Text”. Bagi Ahmed, text yang tertulis ibarat puncak gunung es Kebenaran: ia penanda bagi adanya entitas yang tak terlihat. Pre-Text itu kurang lebih gunung es di bawah permukaan laut yang tak nampak dari permukaan air. Text (Qur’an dan Hadith), adalah tanda bahwa ia tidak sendiri. Sejak dulu, tradisi Islam dipenuhi perdebatan apakah manusia bisa mengetahui apa yang tidak nampak itu (pre-text) atau tidak. Jika bisa, apakah harus mengaksesnya melalui perantara teks atau tidak.
“Con-Text,” lebih lanjut, bagi Ahmed adalah keseluruhan “gudang” makna dari hasil upaya penafsiran teks yang dilakukan sepanjang sejarah sebelumnya. Con-text adaleh text atau wahyu yang telah menyejarah. Ketiga unsur inilah yang saya sebut sebagai totalitas pewahyuan.
Dengan membaca Islam sebagai upaya pembentukan makna dari hasil interaksi penafsiran manusia dengan totalitas pewahyuan itu, maka Islam tidak melulu diukur dari teks, aturan formal dan ortodoksi. Dengan begitu, apa yang nampak bertentangan dan heterodoks dilihat sebagai bagian dari inti-Islam dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang “lian”. Islam sedari awal dipenuhi oleh pertentangan yang bertalian dan berkelindan secara logis karena Pewahyuan adalah totalitas pre-text, text dan con-text.
Jika ortodoksi dan hukum menyandarkan pada teks yang nampak, usaha ekplorasi kreatif adalah upaya untuk mengetahui apa yang tidak terlihat sekaligus mengapresiasi apa yang menyejarah itu. Jika demikian, maka variasi yang sepertinya bertolak belakang, yang universal dan yang lokal, yang abadi dan temporal, ortodoks dan heterodoks, menjadi secara masuk akal dipahami. Islam meciptakan Muslim yang kemudian mendefinisakan kembali Islam.
Meski panjang, mendalam dan ensiklopedik, tesisi dasar Ahmed di akhir bukunya, menurut saya, terkesan sederhana: bahwa Islam adalah penafsiran manusia (self) terhadap pewahyuan yang menyejarah dalam pengalaman manusia. Islam adalah apa yang dirasakan, dialami dan diakui oleh manusia sebagai keberislaman, terlepas dari apakah ukuran tersebut dianggap sesuai atau tidak dengan hukum atau ortodoksi.
Akirnya, hanya Allahlah yang maha tahu.
Catatan: Buku yang dibaca berjudul What is Islam, The Importance of Being Islamic, (Princeton University Press, 2016)



