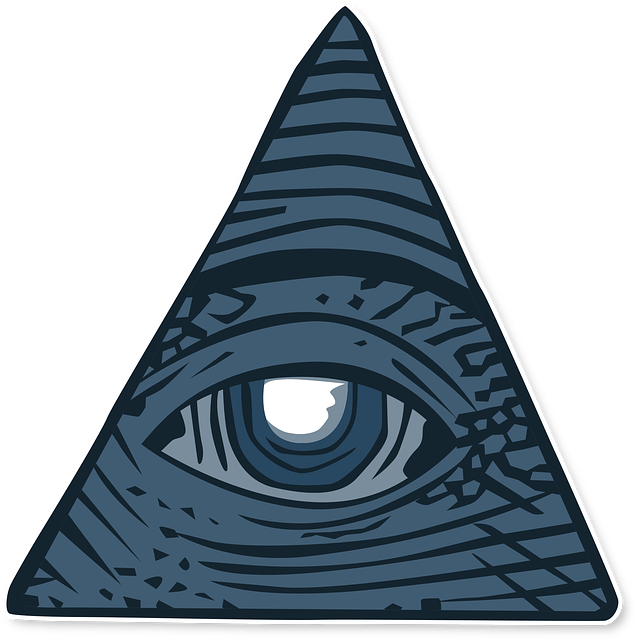
Enaknya menjadi umat akhir zaman adalah, bisa melihat jejaring percakapan dan jejaring relasi pada skala yang tak terbayangkan sebelumnya. Privilese ini, selain bisa digunakan untuk memanipulasi kesadaran politik seseorang secara masif, juga bisa digunakan untuk ‘muhasabah diri’.
Privilese tersebut tentu tak dimiliki zaman Kartosuwiryo, atau bahkan zaman Nabi sekalipun―kecuali jika anda adalah seorang cenayang tingkat tinggi yang dekat dengan kekuasaan atau dipungut oleh gerakan revolusioner keagamaan.
Tetapi di akhir zaman, anda tidak perlu menjadi cenayang dengan segala perjanjian Gelap demi menggapai pengetahuan makro ataupun futuris, karena jenis pengetahuan ini sekarang dipegang oleh Data Scientist.
Minggu lalu, saya dan Anwar Kurniawan mewawancarai Data Scientist, Ismail Fahmi. Poin-poinnya menarik. Ternyata, sepanjang pantauannya soal jejaring sosial dan wacana umat Islam di jagat media sosial Indonesia―khususnya dari periode menjelang Ahok 2016 hingga PPKM 2021―emosi yang paling dominan dari umat Islam adalah distrust, yang mulanya berasal dari distrust terhadap pemerintah, kemudian seiring berjalannya waktu dan dinamika kehidupan, menjalar kemana-kemana. Itu adalah poin pertama.
Kemudian poin kedua adalah, dalam konteks pandemi, ternyata terjadi tren ‘islamisasi teori konspirasi’ yang menyebabkan kalahnya narasi keagamaan berbasis sains di kalangan umat islam. Dan sangat disayangkan pula, bahwa korban atau bahkan penyebarnya tidak hanya berasal dari kalangan islam non-mainstream, tetapi juga sebagian berasal dari kalangan Islam mainstream.
Poin ketiga, menjamurnya teori konspirasi beserta proses islamisasinya, ternyata juga dirangsang oleh motif ekonomi. Peluang monetisasi Youtube dan tingginya kecemasan di kalangan umat islam, adalah dua faktor utama yang membuat bisnis konten konspirasi islamik laku.
Selain peluang ekonomi digital, konten-konten konspirasi islamik juga memperbesar peluang ekonomi luring. Berkatnya, herbal Timur Tengah, ataupun obat-obatan lain yang bungkusnya berbahasa zaman Nabi, bisa bersaing lebih kompetitif dengan obat produk ‘sains sekuler’.
Tiga poin tadi adalah pucuk dari gunung es yang kalau disingkap badannya akan ditemukan berbagai benang saling-silang sejak bertahun-tahun lalu.
Masalah kecemasan sebagai emosi dominan umat islam yang kemudian melahirkan distrust terhadap berbagai hal, khususnya apa-apa yang berkaitan dengan status quo, bermula ketika model keimanan modern disemai di kalangan muda-mudi muslim di tahun 70-80an silam.
Model keimanan ini mengusung basis keimanan gaib nan ajaib―dibanding basis kognitif―sebagai modal utama untuk menaklukan kehidupan material, yang pada giliranya justru melemahkan basis kognitif mereka secara berkelanjutan dalam membaca ataupun memahami tantangan zaman.
Karena tak ada modal lain selain basis keimanan, maka materialisasi agama sebagai asuransi hidup atas keterpinggiran mereka secara ekonomi dan sosial menjadi bagian tak terpisah dari motivasi maupun perilaku beragama.
Karakter itulah yang menyebabkan mereka lemah dalam merancang strategi kolektif untuk menaklukan kenyataan sosial ekonomi, selain membuntut pada patron mereka, yang kadang sangat setia tapi kadang juga berpaling dari umat. Dan karakter itu juga yang membuat iman mudah dibajak oleh aktor konspiratif.
Narasi Cina dan depopulasi misalnya. Dua narasi ini telah melawati proses evolusi berkali-kali. Dari yang mulanya sebatas sentimen terhadap kroni konglomerat Cina di lingkaran Pak Harto (90-2000an), lalu muncul tuduhan ‘Cina-Cina antek PKI’ (nyaris di setiap momen pilpres), hingga menjadi narasi ‘Covid adalah buatan Cina untuk menurunkan populasi umat Islam,’ atau ‘vaksin akan mengubah genetik seseorang menjadi Cina.’
Seiring berkelindannya teks agama dengan teori konspirasi, dan seiring terakumulasinya kecemasan umat, iman mereka mengalami mutasi: pahala dan keselamatan dunia-akhirat bisa diperoleh lewat laku-laku kebencian rasial dan sikap anti-sains, meski jalur ini membahayakan orang lain.
Sialnya, mereka hidup dalam iklim dunia yang kental logika kapitalistik. Mereka bingung bagaimana menakklukan roda ekonomi dan menjinakkan realitas sosial, maka jadilah bisnis herbal ala Nabi, travel haji bersama ustadz selebriti, layanan wallpaper, ringtone Islami, dsb. Dan jadilah islamisasi kegiatan sosial, dari fashion hingga festival Jazz di masjid. “Usaha yang diridhoi Allah,” kata beberapa ustadz, meski tak sesukses rival konglomerat mereka.
Pada konstelasi tersebut, kaum islamis akhirnya berada pada posisi yang tanggung. Tajir-melintir seperti kongklomerat Cina, tidak. Revolusioner juga tidak. Mereka terjebak pada, kalau bukan kelas menengah, maka kelas prekariat, yang dua-duanya adalah jalan hidup penuh kecemasan atas kehidupan yang tak pasti.
Kelas menengah cemas kalau pekerjaan, gaji, dan privise-nya yang tak seluas konglomerat itu direbut si liyan (orang Cina, rezim ‘anti-Islam’, dst), tapi terutama, kelas menengah sangat mencemaskan nasib di akhirat karena mereka sadar sehari-hari berkecimpung pada urusan duniawi. Kelas prekariat cemas karena sepiring nasi untuk esok hari, jodoh untuk di kemudian hari, dan penunjang hidup lainnya, juga tak pasti.
Tanggungnya posisi kaum islamis akhirnya menempatkan mereka pada status yang juga tanggung: menjadi the powerful of small ala rival konglomerat mereka, tidak; menjadi the well-organized mass ala gerakan buruh atau petani, juga tidak. Status mereka jatuh pada the floating mass, atau ‘kerumunan mengambang’, membuat kaum islamis mudah diretas atau bahkan di uyak-uyak oleh siapapun berjubah ‘kharismatik,’ meski yang palsu sekalipun.
Cukup sentil saja kecemasan mereka lewat narasi-narasi menjanjikan dan cerita-cerita yang menenangkan psikologi mereka (walau yang konspiratif sekalipun), syahdan, anda bisa memukul telak demokrasi parlementer lewat gerakan tirani mayoritas.
Di momen politik, posisi pendirian mereka jelas: tolak dan jangan percaya apapun selain model sosial, ekonomi, dan politik Islam. Namun setelah momen politik itu hilang, mereka juga kehilangan ‘patron’. Tak ada lagi agenda yang bisa diusung selain kembali melanjutkan ibadah sambil membalut kecemasan psikologis mereka dengan iman yang diunduh dari internet dan media sosial.
Ketika pandemi datang, walaupun sudah diperban dengan iman, tapi kecemasan mereka masih atau bahkan semakin terasa sakit. Patron mereka yang dulu di momen politik merangkap agamawan sekaligus makelar politik, kini berubah menjadi agamawan sekaligus konten-kreator.
Mereka sadar, umatnya butuh kepastian hidup, dan mereka juga sadar perlu mencari sumber pendapatan lain selain bisnis konvensional karena terdampak pandemi. Sebagian patron ada yang meningkatkan intensitas doa dan anjuran 3M beserta prokes sekaligus vaksin. Sementara sebagian lain dari patron itu ada yang mutuskan untuk menjaja konten dosis tinggi dengan melakukan islamisasi teori konspirasi.
Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Dengan menjual teori konspirasi di media sosial, maka, (1) jumlah viewers di Youtube bisa dimonetisasi, (2) umat merasa mendapat kepastian dan ustadz juga bisa memelihara kesetiaan umat, (3) bisnis herbal akan diuntungkan berkat ketidak-percayaan umat pada otoritas kesehatan ataupun obat yang disepakati.
‘Muhasabah diri’ di era akhir zaman mungkin lebih menukik kalbu jika menggunakan temuan-temuan yang diungkap ilmuan data, dibanding menggunakan ayat ataupun hadist yang dijaja ustadz konspiratif. Karena dengan temuannya, kita bisa langsung fokus pada apa dan bagaimana perbuatan kita, sehingga kontradiksi antara lisan dan tindakan bisa langsung diidentifikasi.
Kita harus berhati-hati, boleh jadi, momen pandemi dengan pengentalan praktik islamisasi teori konspirasi adalah raport merah yang menandakan fase lanjutan dari semakin tenggelamnya basis kognitif umat Islam.
Pertanyaannya, bentuk kehidupan seperti apa yang mungkin terjadi dari ketidak-singkronan antara kondisi keimanan dan kualitas kognitif? Masihkah kita dibolehkan mengutip ayat atau hadist bila hanya membuat lebih banyak membawa kerusakan dan kematian? Apakah kita telah resmi memeluk iman jalur konspirasi?



