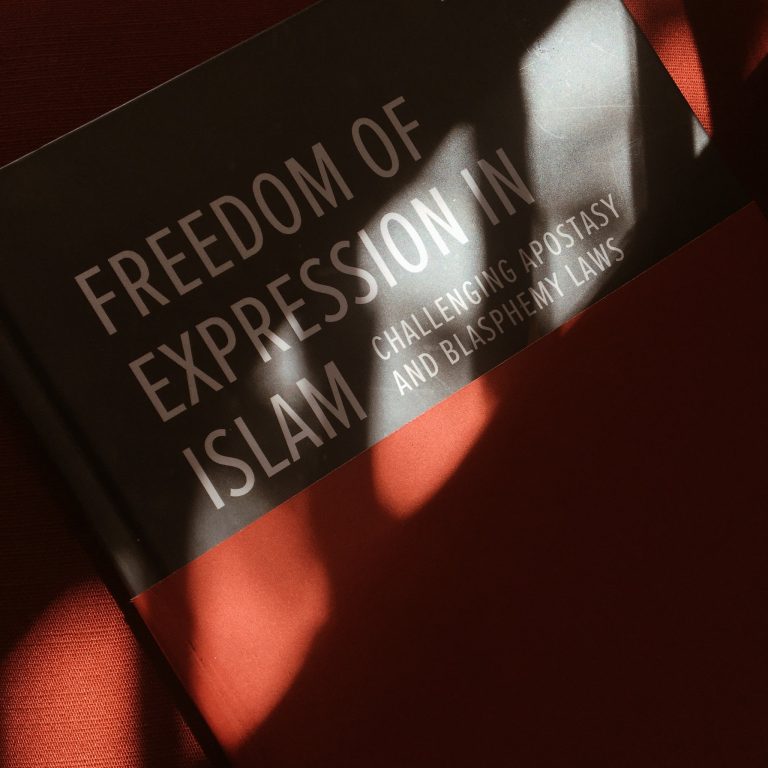
Keberadaan regulasi penodaan agama (blasphemy) dan kemurtadan (riddah) tidak pernah absen dari kritik. Alih-alih mulia dan melindungi agama, nyatanya tidak semua Muslim seiya dengan regulasi tersebut. Buktinya, sekelompok cendekiawan Muslim internasional yang menulis antologi Freedom of Expression in Islam: Challenging Apostasy and Blasphemy Laws mengorkestrasikan penilaian yang berbeda.
Buku ini memuat kompilasi artikel tentang konsekuensi hukum penodaan agama dan kemurtadan yang diterapkan di negara-negara Islam. Para penulisnya memberikan pijakan bahwa hukum penodaan agama dan kemurtadan seringkali dilandaskan pada norma-norma agama yang sarat dengan kepentingan berjangka. Bahkan, regulasi yang dominan diterapkan di negara-negara berbasis Islam — seperti Iran, Pakistan, Mesir, termasuk Indonesia — juga tidak mendapatkan pendasaran yang kokoh, khususnya dalam sumber-sumber primer Islam.
Buku ini telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kebebasan Berekspresi dalam Islam: Menggugat Hukum Kemurtadan dan Penodaan Agama (2023). Lebih dari sekadar konversi bahasa, ia diproyeksikan untuk mengevaluasi tumpukan masalah yang mengekor pada keduanya; mulai dari kuasa yang tak seimbang, doktrin ideologis yang bias minoritas, serta konstruksi hukum yang serba paradoksal. Sebagai gantinya, buku ini lebih memilih untuk mempromosikan semangat kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi yang juga tidak kalah islaminya.
Sengkarut Penodaan dan Kemurtadan
Pada bagian pertama, Abdullah Saeed dalam “Hukum Penodaan Agama dalam Islam: Ke Arah Peninjauan Ulang?” menyodorkan bagaimana hukum penodaan dan kemurtadan dalam Islam digunakan sebagai alat yang efektif untuk merestriksi banyak hal; mulai dari pengerdilan oposisi politik, medium untuk memobilisasi massa, serta alat untuk membatasi kebebasan berfikir dan berekspresi internal umat Islam.
Salah satu contohnya adalah larangan untuk menghina Sahabat Nabi. Saeed mencatat pantangan itu sebagai upaya ahli fikih (fukahā’’) beraliran Sunni untuk menganeksasi tumbuh kembangnya kelompok Syiah dan Khawarij. Atau dalam tujuan lain, penisbatan tindakan menodai agama (termasuk juga murtad) sebagai dosa dan pelanggaran yang harus dihukum hanyalah produk normatif para ahli fikih yang diformulasi untuk mempolarisasi sekte yang satu dengan yang lain, tidak kurang apalagi lebih. Teks Al-Qur’an ataupun hadis sahih yang secara eksplisit memperbolehkan menghakimi pelakunya, terutama dengan hukuman mati, justru absen.
Penilaian Saeed menjadi penting terutama untuk menimbang seberapa penting mempertahankan hukum tersebut. Ia secara asertif menekankan bahwa selain tak ada dalilnya, hukuman mati sebagai akibat menodai dan murtad juga berlawanan dengan semangat kebebasan beragama yang diusung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang, justru berlimpah dalil dan sarat dengan nilai-nilai islami. Pertimbangan itulah yang membuat Saeed berargumen bahwa penodaan agama berikut dengan konsekuesi yang melekat padanya tidak penting dipertahankan.
Tulisan Omaima Abou-Bakr bertajuk “Kebebasan Beragama dalam Tafsir al-Quran” memperkuat argumen Saeed. Dengan berpacu pada ayat QS 2:256 Abou-Bakr berupaya mempromosikan kebebasan beragama yang bernuansa islami. Di bagian ini, Abou-Bakr banyak merujuk kepada Khaled Abou El Fadl. Bagi El Fadl, wacana al-Qur’an tentang dukungan terhadap kebebasan beragama sangat berlimpah. Contohnya dapat dikonfirmasi pada QS 2:256, 10: 99, 18:29, dan 109:6. Ia menguraikan bahwa al-Qur’an sama sekali tidak mendikte seseorang untuk menganut agama tertentu. Urusan murtad-memurtadkan tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, pesan moral di dalamnya lebih mendorong kebebasan individu dalam memilih agama.
Sayangnya, inisiatif-inisiatif inklusif seperti yang ditawarkan Saeed dan Abou Bakr tidak terlalu digubris. Represi atas pilihan beragama dan tidak segan untuk menghukum mereka yang melanggar terus begulir, bahkan tidak sedikit yang disponsori oleh kekuatan rezim.
Penodaan Agama dan Kemurtadan di Negara-Negara Islam
Selain mengupas tentang sengkarut konsep penodaan agama dan kemurtadan, buku ini juga menyodorkan kasus-kasus relevan yang berhubungan dengan delik penodaan dan kemurtadan yang terjadi di negara-negara Islam. Masing-masing negara memiliki karakter dan pendasarannya masing-masing. Di Iran, proses identifikasi kasus penodaan dan kemurtadan dilandaskan pada beberapa hal, seperti KUHP 2012 dan hukum pers, serta hukum yang tidak terkodifikasi (mekanisme fikih). Isinya meregulasi tentang larangan menghina nabi, para imam Syiah, dan Fatimah.
Sementara itu, regulasi di Pakistan diduga kuat banyak dipijakkan pada hukum Islam beraliran mazhab Hanafi. Lewat Pasal 295-C KUHP, negara ini secara represif akan mengategorikan pelaku penodaan sebagai pelanggaran ḥadd yang wajib dihukum mati. Menghina Nabi Muhammad adalah satu contohnya. Tanpa memandang apakah yang menghina beridentitas muslim ataupun non-muslim, pelaku penodaan dinilai tidak dapat ditolerir.
Tidak kalah represif dari Iran dan Pakistan, Mesir juga meregulasi penodaan dan kemurtadan. Namun, perihal apa dan bagaimana sesuatu bisa disebut menodai ia tidak mendapatkan definisi yang jelas. Pendukung undang-undang ini dominan dimobilisasi oleh mereka yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi. Misalnya dalam kasus pemberlakuan hukum kemurtadan. Di Mesir, seorang muslim dapat divonis dengan jerat kemurtadan, jika mereka berani mengeskpresikan perbuatan yang diduga menodai agama atau memiliki pemahaman yang diferensiatif dengan kelompok Islam arus-utama. Contohnya adalah vonis terhadap akademikus Nasr Hamid Abu Zayd. Meski Zayd tidak pernah mendeklarasikan diri keluar dari Islam, namun akibat kajian ilmiahnya terhadap Al-Qur’an yang kritis, ia harus menanggung hukum perdata yang dikejam; pengadilan Mesir secara paksa membatalkan status pernikahan Zayd dengan pedusi sahnya.
Fatwa MUI: Sumber Konflik Penodaan Agama di Indonesia?
Indonesia juga masuk dalam sorotan buku ini. Tulisan Syafiq Hasyim pada bab kedelapan mencoba menyelidiki bagaimana fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut bertanggung jawab atas meningkatnya kasus-kasus penodaan agama. Hasyim menilai bahwa institusi ini tidak hanya memproduksi fatwa yang diorientasikan untuk mempertegas dominasi kelompok mayoritas, tetapi juga ikut bermain terutama untuk merestriksi keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang dituduh menyimpang dan sesat. Ahmadiyah dan Syiah adalah dua contoh komunitas yang diposisikan Hasyim sebagai sasaran utama viktimisasi fatwa MUI.
Secara legal, benar bahwa fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam banyak kasus, Hasyim mencatat bahwa aparatur negara kerap terintervensi dan menjadikan fatwa sebagai referensi untuk menghakimi kelompok yang dituduh menyimpang. Tidak cukup di situ, MUI turut mencari pembenaran fatwanya dengan berlindung di balik ketiak UU No.1/PNPS/1965 atau populer dengan UU anti-penodaan agama. Lewat piranti hukum inilah, MUI mulai memainkan peran politisnya.
Dalam pembacaannya terhadap kasus kelompok menyimpang, Hasyim mencatat bahwa MUI seringkali berhasil mempengaruhi negara untuk meningkatkan level fatwa mereka sebagai delik aduan penodaan agama. Keberhasilan ini juga tidak lepas terutama karena kesinambungan antara fatwa MUI dan UU penodaan agama, yang sama-sama memiliki visi ingin memberangus eksistensi kelompok non-ortodoks. Dengan kata lain, meskipun sama-sama Islam, terdapat kelompok tertentu yang haknya tidak terfasilitasi secara proporsional. Salah satu penyebab utamanya adalah pengaruh fatwa-fatwa MUI yang serba parsial tersebut.
Problem regulasi penodaan agama yang terjadi di lingkungan negara-negara Islam hakikatnya tidak murni berkaitan dengan sesat atau tidaknya suatu kelompok, juga tak berhubungan dengan berkurangnya nilai-nilai kesakralan Islam. Lebih jauh daripada itu, ia berkorelasi dengan upaya mempengaruhi wacana hukum di ruang publik dengan nilai-nilai normativitas Islam yang telah disesuaikan dengan kriteria rezim tertentu.
Buku ini berkontribusi terutama untuk mengevaluasi implikasi buruk hukum penodaan terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas. Hukum penodaan agama tidak mendapat dukungan yang kokoh dalam teks-teks Islam. Alih-alih memuliakan, ia justru merendahkan.
Apa yang disuguhkan buku ini menjadi tamparan keras bagi negara-negara yang memberlakukan hukum penodaan agama. Sayangnya, dalam konteks Indonesia hari ini, regulasi penodaan agama tampaknya masih suluh dan terus berkembang biak. Beberapa kelompok tengah rajin menghakimi kelompok lain dengan alasan melindungi doktrin agama dari penodaan. Pemidanaan Panji Gumilang adalah salah satu contohnya. Para pengusungnya berdalih dengan dalil hukum yang jelas-jelas bermasalah dan jauh dari nilai-nilai keislaman. Setelah ini, dalih model apalagi yang akan mereka gunakan?



