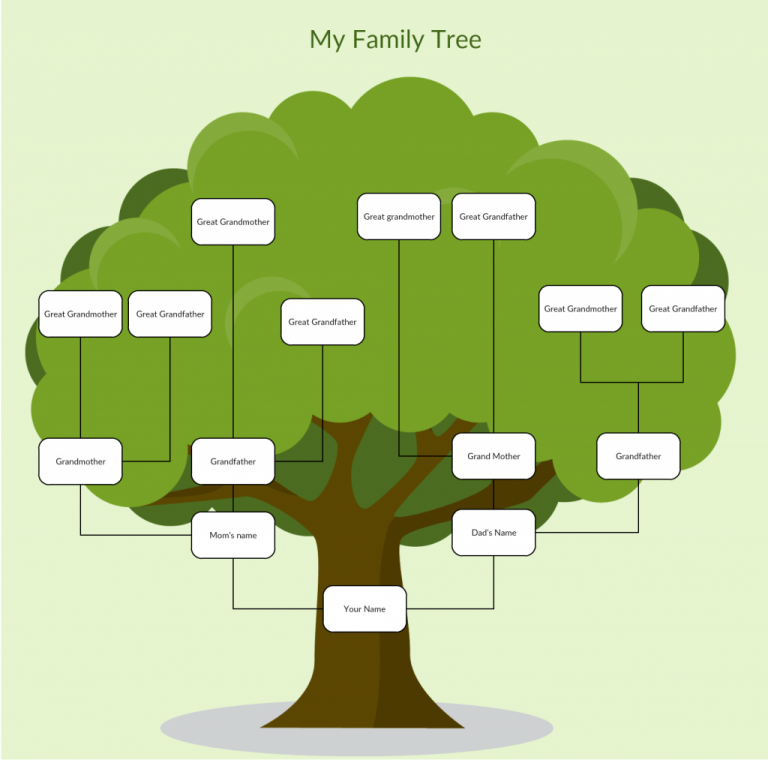
Anak pertama saya baru bisa berjalan di usia 14 bulan, anak kedua malah 22 bulan. Terlambat. Mereka juga baru bisa mengucapkan kata-kata pertama pada usia kurang lebih dua tahun. Lagi-lagi, terlambat.Apakah sebagai orangtua kami tidak khawatir? Sangat.
Pada awalnya, sebagai orangtua baru, kami kerap dihantui pertanyaan: apakah ada yang salah? Apakah kami kurang memberi makan? Atau kurang mencukupi gizi mereka? Atau kurang memberi stimulasi? Atau cinta kasih? Atau gen yang bagus?
Sejak dulu hingga sekarang kecepatan menjadi sesuatu yang dipuja dan dirayakan. Pada semua bidang. Anak-anak (dengan orangtua sebagai ikutannya) dipuji jika sudah bisa tengkurap pada usia 3 bulan (atau kurang dari itu), dihujani tepuk tangan ketika bisa berjalan dan bicara pada usia yang belum mencapai satu tahun, membaca di usia sedini mungkin, kalau bisa barangkali pada usia 3 bulan seperti si genius Mathilda, tokoh ciptaan penulis buku anak-anak Roald Dahl.
Memangnya, siapa yang tidak bangga kalau anaknya sudah bisa membaca dan menulis di usia 4 tahun? Sudah bisa meraih gelar S1 di usia 18 tahun? Sudah bisa entah apa lagi di usia yang entah berapa lagi lebih dini daripada bapak-ibunya, tetangga-tetangganya, atau entah siapa yang kita baca atau dengar di media massa.
Bagi orangtua dengan anak-anak yang tidak seperti itu, situasinya jadi agak kurang menyenangkan. Padahal, saya yakin tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak-anak dengan kecerdasan berbeda atau laju perkembangan yang berbeda.
Pohon-pohon di halaman rumah mengingatkan saya akan hal itu. Ada dua pohon buah di halaman kami, pohon mangga dan pohon jambu biji. Kedua pohon ini kami tanam pada waktu yang hampir sama, tetapi laju perkembangan keduanya berbeda. Tinggi si pohon mangga sudah kalah telak dari si pohon jambu biji. Padahal ketika ditanam, si pohon mangga jauh lebih tinggi daripada si jambu biji. Jumlah daun pohon jambu biji juga lebih banyak. Sekarang si jambu biji, sudah mulai berbuah pula. Padahal perlakuan kami pada kedua pohon itu sama (sama-sama tidak kami urus maksudnya haha). Oh, apakah pohon mangga sedemikian bodohnya sampai dia tidak bisa meninggikan badan, memperbanyak daun, memunculkan buahnya?
Pada titik ini mungkin ada sebagian orang yang mulai menganggap sayalah yang bodoh (“ya iyalah beda. Pohon mangga dan jambu biji kan memang beda gitu loh!”).Nah, persis itulah inti celotehan saya di sini. Pohon mangga dan jambu biji memang berbeda. Anak-anak juga berbeda. Ada yang akan tumbuh menjadi pohon jambu biji, ups, maksud saya atlet, atau guru olah raga, ada juga yang tumbuh menjadi penulis misalnya, atau computer geek yang, sungguh, tidak memerlukan kemampuan motorik kasar atau bahkan kemampuan bicara yang terlalu super.
Masih ingat Einstein? Dia sempat dianggap anak bodoh oleh gurunya. Seingat saya dia juga terlambat bisa membaca. Kita tahu sekarang orang akan senang sekali bila dibilang “seperti Einstein” karena Einstein sudah menjadi kata lain dari genius.
Padahal jangan-jangan teman Einstein sewaktu masih SD dulu tidak suka bila dikatai “seperti Einstein.” Tentu,tentu,tentu, saya tidak bilang anak saya akan menjadi seperti Einstein (walau saya juga tidak keberatan bila itu terjadi), saya hanya ingin mengatakan: anak punya takdirnya masing-masing. Saatnya kita terima mereka apa adanya. Kita tidak pernah tahu, hendak menjadi apa mereka nanti.
Omong-omong, saya lebih suka mangga daripada jambu biji..



