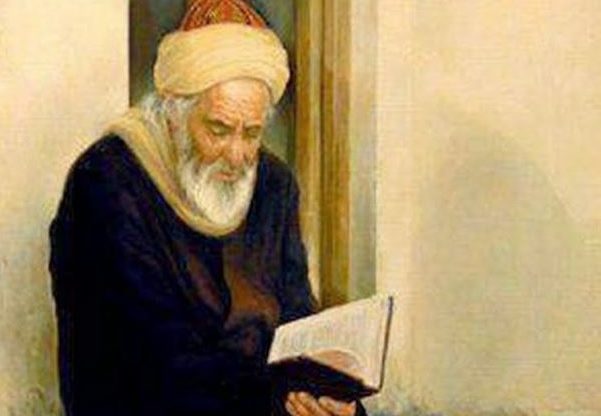
Ada hal yang menggelitik saat pandemi covid-19 menyesaki ruang-ruang keseharian masyarakat Muslim Indonesia, yaitu seteru ideologis antara teologi tekstualis Islam dan sains.
Pandemi covid-19 telah membuat dunia sains begitu terbuka. Beragam temuan sains yang berkaitan dengan pandemi covid-19 dipublikasikan secara terbuka dan menyentuh berbagai kalangan dari yang alim hingga yang awam. Temuan-temuan sains seperti kecepatan penularan virus korona, pentinya cuci tangan, penjarakan sosial, penjarakan fisik, dst. menjadi topik keseharian khalayak ramai.
Segaris dengan itu, resistensi teologis atas temuan-temuan sains juga ditemukan di lingkup publik. Beberapa temuan sains yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi covid-19 membentur secara keras ritual-ritual komunal yang selama ini mewarnai kehidupan sehari-hari umat Islam.
Benturan ini pada gilirannya, membuat umat Islam menjadi dilema, antara mempertahankan tradisi ibadah komunal yang diperintahkan Tuhan atau menghentikannya sebagaimana dianjurkan oleh temuan sains. Akibatnya, muncul dua kelompok yang berseteru menyoal dua pilihan pahit itu.
Yang pertama memilih mempertahankan tradisi ibadah komunal dengan alasan ketakutan kepada Allah itu lebih utama daripada ketakutan pada Korona. Sementara yang kedua memilih untuk menghentikan atau membatasi tradisi ibadah komunal dengan mempertimbangkan temuan-temuan sains.
Berhubung selama pandemi covid-19, informasi temuan-temuan sains mengalir deras di ruang publik dan diadopsi oleh pihak-pihak otoritatif (pemerintah), maka dalam seteru keduanya, kelompok pertama sering kali terpinggirkan. Ungkapan-ungkapan seperti “Takutlah kepada Allah dan jangan takut pada korona!” segera akan terlabel sebagai ungkapan “ngenyel”, bandel, atau tidak taat aturan.
Sepintas, keterpinggiran kelompok pertama ini memang merupakan kabar baik, karena tidak dapat dimungkiri bahwa pilihan kelompok kedua itu lebih mendukung pada kebijakan pemutusan mata rantai pandemi covid-19. Namun, secara teologis, peminggiran atau peremehan atas argumentasi kelompok pertama ini dapat berakibat cukup fatal.
Secara perlahan, orang-orang akan lebih teryakinkan oleh argumen-argumen sains dari pada argumen-argumen teologis. Argumen-argumen teologis tentang pandemi covid-19 akan menjadi bahan tertawaan dan dicemo’oh sedemikian rupa, karena untuk urusan ini argumen-argumen sains masih jauh lebih otoritatif.
Sinisme terhadap argumen-argumen teologis ini jelas merupakan kabar buruk. Bukan tidak mungkin, benturan sains dan teologi di Eropa masa lalu juga akan dialami oleh tradisi teologi Islam di Indonesia. Perlahan tapi pasti, kepercayaan-kepercayaan teologis akan tergantikan oleh kepercayaan-kepercayaan sains. Sains menjadi agama baru masyarakat Muslim Indonesia menggantikan teologi Islam.
Untuk menghindari ini, agaknya kita perlu banyak belajar pada al-Ghazali. Sang Hujjatul Islam ini pada masanya juga pernah mengalami hal yang kurang lebih serupa dengan yang terjadi saat ini. Semasa hidupnya, perseteruan antara okasionalisme dan kausalitas tengah mewarnai diskusus teologis Islam. Perseteruan ini nyaris serupa dengan benturan sains dan teologi di masa pandemi covid-19. Okasionalisme diwakili oleh teolog Muslim Asy’ariyah sementara kausalitas diwakili oleh para filsuf Islam peripatetik (Ibn Sina, al Farabi, dkk.).
Al-Ghazali cenderung memilih jalur tengah saat dihadapkan pada dua pilihan itu. Berdiri di antara kutub okasionalisme Asy’ariyah dan kausalitas filsuf muslim (terutama Ibn Sina), al-Ghazali kemudian mengembangkan kosmologinya sendiri. Melalui analisisnya, dia menemukan sebuah lorong kecil yang sangat menarik ke arah pengadopsian determinisme kosmologi Ibn Sina sembari tetap menjadi seorang teolog muslim yang berharap akan mempertahankan pilihan bebas Tuhan atas tindakan-Nya.
Al-Ghazali menerima statemen kausalitas bahwa hubungan sebab akibat itu niscaya. Ini misalnya terlihat dalam bukunya yang berjudul Ihya’ Ulum al-Din. Dalam kitab tersebut ia mengatakan, “Apabila Anda mengharap Allah akan membuat Anda kenyang tanpa roti, atau membuat roti bergerak kepada Anda, atau memerintahkan malaikat untuk mengunyahkannya untuk Anda dan menyaksikannya pindah ke perut Anda—itu hanya akan memperlihatkan kebodohan Anda tentang tindakan-Nya” (Ghazali: 1982, 249).
Namun, meskipun ia memiliki pandangan determinis tentang alam semesta, al-Ghazali tanpa letih memelihara pandangan bahwa tindakan Tuhan itu bebas dan Dia adalah satu-satunya “pencipta” atau causa efisien di seluruh alam semesta. Setiap kejadian, bahkan kepakan sayap seekor nyamuk pun dikehendaki dan diciptakan oleh-Nya.
Begitulah al-Ghazali mendamaikan seteru antara teori okasionalisme dan kausalitas. Tak ayal, atas prestasi al-Ghazali ini Frank Griffel, peneliti al-Ghazali dari Jerman, kemudian menyebut teologi al-Ghazali tersebut sebagai teologi filosofis.
Gaya teologi filosofis ini agaknya perlu direnungkan kembali di tengah maraknya benturan ideologis antara sains dan teologi Islam tekstualis selama masa pandemi Covid-19 ini. Agar setiap kalangan tidak terjebak dalam ektrimisme masing-masing kutub ideologisnya, mereka harus berani belajar pada model penyikapan al-Ghazali atas teori okasionalisme dan kausalitas.
Seperti al-Ghazali, masyarakat Muslim saat ini semestinya harus menghargai temuan-temuan sains terkait pandemi covid-19. Namun, sembari memberikan apresiasi atas temuan sains itu, masyarakat Muslim harus tetap berusaha memelihara pandangan bahwa tindakan dan kehendak Tuhan itu senantiasa menyertai setiap upaya sains dalam menanggulangi pandemi covid-19. Dengan demikian, masyarakat Muslim tidak akan terjebak pada pengkultusan berlebihan terhadap tradisi keilmuan sains serta tidak tergelincir pada kepercayaan teologis buta. (AN)



