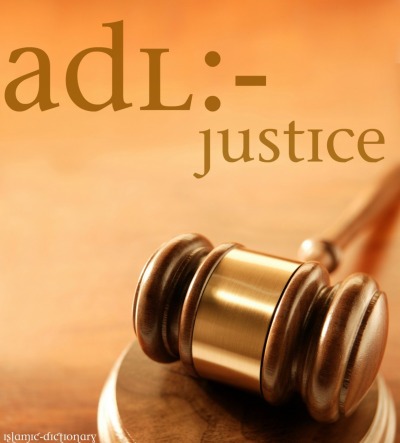
Ki Ageng Suryomentaram, filsuf nusantara yang menjadikan dirinya sendiri sebagai laboratorium penelitian nyaris di sepanjang hidupnya, telah mewariskan konsep yang sangat menarik tentang manusia. Menurutnya, sebelum manusia dilekati oleh rasa yang berhubungan dengan namanya masing-masing (kramadangsa), belum ada rasa suka atau tidak suka (dhemen-sengit) di dalam dirinya.
Namun begitu manusia diberi nama, dimana si A tidak akan menoleh saat dipanggil dengan panggilan B, dan hanya akan menengok jika dipanggil sebagai A yang menjadi namanya, maka mulailah ada kemelekatan di sana. Awalnya yang melekat di dalam kramadangsa setiap manusia adalah namanya sendiri itu tadi yaitu namaku. Lalu berkembang pada identifikasi ini ibuku, ini ayahku, ini mainanku, dan seterusnya dengan pelekatan “-ku” atas segala sesuatu yang disenangi (didhemeni), termasuk agamaku. Adapun terhadap segala sesuatu yang tidak disukai (disengiti), si kramadangsa tidak mau meng-aku-kannya, sekalipun sesuatu yang tidak disenangi itu juga ada di dalam dirinya.
Jadi, yang membuat manusia tak bisa bersikap adil saat memandang atau memperlakukan segala sesuatu adalah karena si kramadangsa di dalam dirinya hanya mau mengakui hal-hal yang disenanginya saja. Sementara terhadap segala sesuatu yang tidak disukainya, si kramadangsa merasa bahwa hal itu tidaklah bagian dari dirinya (dudu aku) meskipun jelas-jelas ada padanya.
Pangawikan pribadi adalah metode agar seseorang bisa bersikap adil
Menurut Ki Ageng, manusia seringkali kebingungan, galau, karena tidak mampu melihat dirinya sendiri secara apa adanya. Mengetahui diri sendiri secara apa adanya itulah yang distilahkannya dengan pangawikan pribadi, dan ditegaskan bahwa objek pangawikan pribadi adalah pelbagai rasa di dalam diri dari mulai yang dangkal hingga yang paling dalam (Pribadi, awakipun piyambak, punika kadadosan saking raos-raos kathah sanget lan raos-raos wau wonten ingkang cethek, wonten ingkang lebet, lan wonten ingkang lebet sanget), yang disederhanakannya sebagai jiwa. Artinya objek pangawikan pribadi lebih dititikberatkan pada batin dan bukan lahir.
Tentu saja yang paling mudah diketahui adalah rasa terdangkal, lalu perlahan-lahan meningkat pada rasa dalam, dan kemudian rasa yang sangat dalam. Contoh mengetahui rasa dangkal adalah menyadari bahwa diri sendiri memiliki kecenderungan untuk merekam segala sesuatu. Misalnya saat kita melihat meja, maka wujud meja itu pun akan terekam dalam ruang rasa kita. Namun rekaman wujud meja di ruang rasa kita, dengan meja yang wujudnya kita rekam pasti berbeda bukan?
Tidak hanya merekam apa-apa yang terlihat, kita juga dapat merekam apa-apa yang pernah kita dengar, cium, kecap, dan rasakan. Misalnya saat kita merasa haus, lalu rasa haus itu pun kita rekam di dalam ruang rasa. Dan jelas sekali perbedaannya antara rasa haus yang tengah kita rasakan dan rasa haus yang berada dalam rekaman kita bukan?
Selain merekam, rasa kita juga bisa mengimajinasikan pelbagai hal. Misalnya kita dapat mengimajinasikan adanya seekor kuda yang berkepala manusia. Imajinasi itu tidak ada wujudnya di alam nyata, ia hanya merupakan kombinasi dari rekaman kita tentang wujud kuda dan wujud manusia pada awalnya. Begitulah, di dalam ruang rasa kita juga terdapat ruang imajinasi yang luasnya tak terbatas selain adanya ruang luas yang bisa menampung pelbagai rekaman.
Kemampuan lain manusia dalam ruang rasanya adalah melahirkan ide. Misalnya ide untuk membuat payung. Awalnya manusia berpikir bagaimana supaya badannya bisa terlindungi dari hujan atau panas matahari saat berjalan di ruang terbuka, lalu terlahirlah ide itu, berusaha diwujudkan melalui berbagai percobaan, dan berhasil. Karena bermanfaat, maka si payung yang semula hanya merupakan gagasan tersebut pun terus dikembangkan sesuai kebutuhan dari masa ke masa hingga wujud mutakhirnya sekarang ini.
Baik ide maupun imajinasi, keduanya sama-sama terlahir dari sebuah gagasan. Hanya saja, ide probabilitasnya untuk diwujudkan lebih tinggi ketimbang imajinasi. Pada wilayah ruang rasa dari mulai penyimpan rekaman, imajinasi, dan ide itulah kramadangsa setiap manusia hidup dan mati secara silih berganti dan terus menerus berlandaskan dhemen (rasa suka) atau sengit (rasa benci), di sepanjang hidupnya.
Nah, keberhasilan seseorang di dalam mendidik kramadangsa-nya menjadi luhurlah yang membuat dirinya akan dapat bersikap adil di dalam memandang segala sesuatu dan peristiwa secara apa adanya. Ya, karena sifat dasar kramadangsa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Yaitu hanya mau mengakui hal-hal yang disenanginya saja, sementara terhadap segala sesuatu yang tidak disukainya, si kramadangsa merasa bahwa hal itu tidaklah bagian dari dirinya (dudu aku) meskipun jelas-jelas ada padanya. Kramadangsa yang belum atau tidak terdidik, oleh Ki Ageng disebut sebagai kramadangsa asor.
Wallahu a’lamu bishshawaab.



