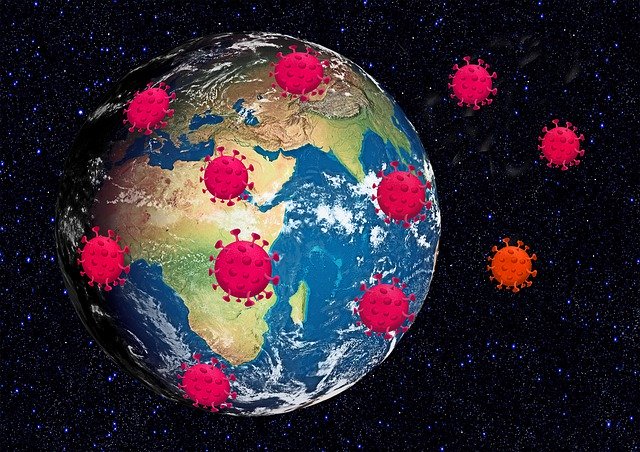
Ada yang menarik kita simak dan amati di masyarakat terkait Covid -19, yaitu respon masyarakat atas imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing atau physical distancing (menghindari kontak fisik) hingga pada ritual keagamaan, seperti shalat di rumah dan shalat Jum’at diganti dengan shalat Dzuhur
Imbauan tersebut, tak serta merta jadi bahan uji coba atau sebatas spekulasi, ia berangkat dari analisis dan kajian atas dasar ilmu pengetahuan bagi mereka yang kompeten dibidangnya, tentu dalam hal ini para ahli atau medis, bukan wewenang agamawan atau ustadz.
Tak pelak sebagian masyarakat merespon dengan mempertentangkan antara ilmu pengetahuan dengan pemahaman keagamaan (bukan agama). Ada kesan bahwa ilmu pengetahuan bukanlah bagian dari nilai agama dan nilai agama berbeda dari dasar ilmu pengetahuan. Sebab itu, nilai agama tak boleh diganggu-gugat oleh ajaran ilmu pengetahuan. Artinya imbauan dokter atau medis tak menjadi halangan untuk tidak shalat berjamaah dan Jumatan.
Maka tak heran, imbauan berdasar pijakan ilmu pengetahuan ini justru dianggap sangat bertentangan dgn nilai paham keagamaan dengan dalih teologis bahwa Corona tak kuasa Yang Kuasa adalah Allah, semestinya mari kita ramaikan Mesjid untuk melawan virus ini atau Allah sudah mengatur nyawa manusia jadi tak perlu khawatir. Bahkan kekhawatiran mereka jika mesjid ditutup dan meniadakan shalat Jum’at dapat mengancam akidahnya, juga dianggap sbagai tanda tanda kiamat.
Pertanyaannya, apakah dengan mematuhi imbauan berbasis ilmu pengetahuan berarti mengabaikan nilai ajaran agama? atau bagi mereka yang mengabaikan imbuan medis atas dalih nilai ajaran agama justru melawan ajaran agama sendiri?
Pertama, sebab ini menyangkut kesehatan dan pencegahannya, maka yang berhak dan paling patut didengar dan dipertimbangkan adalah dokter atau tenaga medis bukan agamawan, ustad atau masyarakat biasa (Baca QS: al-Nahl ayat 43). Covid-19 menyangkut nyawa, nasib dan taraf hidup orang banyak. Jika dihubungkan dengan ajaran agama, maka kehadiran Islam memberi perlindungan dan jaminan hidup bagi pemeluknya yaitu menjaga nyawa manusia (hifdz nafs).
Sebab itu, tugas ulama ikut mempertimbangkan saran dokter, karena mereka sadar itu bukan ranah dan kompetensi mereka. Maka meniadakan shalat berjamaah dan shalat Jum’at adalah hubungan yang selaras antara pandangan ilmu pengetahuan dengan nilai ajaran agama yaitu hifdz nafs (memelihara jiwa). Mengutip seduran ulama “mengutamakan keselamatan jasmani didahulukan atas keberlangsungan ritual agama jika ibadah itu justru mengancam”.
Kedua, mereka yang mendahulukan keyakinan mengabaikan imbauan medis (pijakan ilmu pengetahuan). Tak sepenuhnya salah jika ada anggapan Allah Yang Kuasa dan menentukan matinya seseorang. Akan tetapi jauh lebih benar dan dibenarkan secara agama pun ilmu pengetahuan jika keyakinan itu berbanding lurus dengan ikhtiar untuk menghindari ancaman dan yang mengancam jiwa
Mendahulukan teologis seolah membabi buta dan pasrah sepenuhnya bagian dari menafikan posisi dan peran akal bagi dirinya. Padahal Tuhan membuka ruang bagi kita untuk iqra’ dan iqra’ (bacalah) tentu dengan sandaran bismirabbika (menyebut Nama Tuhan). Nah imbauan atas dalih ilmu pengetahuan bagian dari wujud bismirabbika dengan mengutamakan keselamatan.
Sebab itu, imbauan untuk meniadakan shalat Jum’at/berjamaah diganti shalat Dzuhur sementara waktu adalah cara untuk menjaga keyakinan di satu sisi, karena orang yang beriman kewajiban bagi dirinya adalah menjaga hak tubuh atau keselamatannya (hifdz nafs). Karena ibadah tak menuntut jika seseroang akan mengancam keselamatannya terlebih shalat tak mengandaikan harus di Mesjid.
Terakhir, biarlah ulama atau MUI yang lebih banyak berbicara sebab mereka yang lebih paham bagaimana seharusnya. Semoga ujian ini segera berakhir, setiap kesulitan selalu ada kemudahan.



